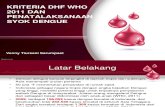referat DHF
description
Transcript of referat DHF

REFERAT
DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER
Diajukan untuk Memenuhi PersyaratanPendidikan Program Profesi Dokter Stase Penyakit DAlamFakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh:
Yohana Pandora, S. Ked (J510155073)
Pembimbing:
Dr. Bambang Wuri Atmodjo, Sp. PD
KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT DALAM
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

REFERAT
DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER
Yang diajukan oleh :
Yohana Pandora, S. Ked, S. Ked
J510155073
Telah disetujui dan disahkanoleh bagian Program Pendidikan Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Pada hari Kamis, tanggal
Pembimbing :
Dr. Bambang Wuri Atmodjo, Sp. PD (………………….)
Dipresentasikan dihadapan :
Dr. Bambang Wuri Atmodjo, Sp. PD (………………….)
Disahkan Ka. Program Profesi :
dr. D. Dewi Nilawati (………………….)
KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT DALAM
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyakit virus dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue
tipe I,II III dan IV golongan arthropod borne virus group B (arbovirus) yang
ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albocpitus. Sejak tahun 1968
penyakit ini ditemukan di Surabaya dan Jakarta, selanjutnya sering terjadi
kejadian luar biasa dan meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu
penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang awalnya banyak
menyerang anak tetapi akhir-akhir ini menunjukkan pergeseran menyerang
dewasa.1
Perjalanan penyakit infeksi dengue sulit diramalkan. Pasien yang pada
waktu masuk keadaan umumnya tampak baik, dalam waktu singkat dapat
memburuk dan tidak tertolong (Dengue Shock Syndrome / DSS). Sampai saat ini
masih sering dijumpai penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang semula
tidak tampak berat secara klinis dan laboratoris, namun mendadak syok sampai
meninggal dunia. Sebaliknya banyak pula penderita DBD yang klinis maupun
laboratoris nampak berat namun ternyata selamat dan sembuh dari penyakitnya.
Kenyataan di atas membuktikan bahwa sesungguhnya masih banyak misteri di
dalam imunopatogenesis infeksi dengue yang belum terungkap1
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia cenderung
meningkat, mulai 0,05 insiden per 100.000 penduduk di tahun 1968 menjadi
35,19 insiden per 100.000 penduduk di tahun 1998, dan pada saat ini DBD di
banyak negara kawasan Asia Tenggara merupakan penyebab utama perawatan
anak di rumah sakit. Mengingat infeksi dengue termasuk dalam 10 jenis penyakit
infeksi akut endemis di Indonesia maka seharusnya tidak boleh lagi dijumpai
misdiagnosis atau kegagalan pengobatan. Menegakkan diagnosis DBD pada
stadium dini sangatlah sulit karena tidak adanya satupun pemeriksaan diagnostik
yang dapat memastikan diagnosis DBD dengan sekali periksa, oleh sebab itu perlu
dilakukan pengawasan berkala baik klinis maupun laboratoris.3

BAB II
DEMAM BERDARAH DENGUE
A. Definisi
Demam Berdarah Dengue/DBD (dengue haemorrhagic fever/DHF) adalah
penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis
demam, nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang disertai lekopenia, ruam,
limfadenopati, trombositopenia dan diatesis hemoragik. Pada DBD terjadi
perembesan plasma yang ditandai oleh hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit)
atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom renjatan dengue (dengue shock
syndrome) adalah demam berdarah dengue yang ditandai oleh renjatan/syok..2
B. Epidemiologi
Di Indonesia, demam berdarah dengue (DBD) pertama kali dicurigai di
Surabaya pada tahun 1968, tetapi konfirmasi virologis baru diperoleh pada tahun
1970. Di Jakarta, kasus pertama di laporkan pada tahun 1968. Sejak
dilaporkannya kasus demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 1968 terjadi
kecenderungan peningkatan insiden. Sejak tahun 1994, seluruh propinsi di
Indonesia telah melaporkan kasus DBD dan daerah tingkat II yang melaporkan
kasus DBD juga meningkat, namun angka kematian menurun tajam dari 41,3%
pada tahun 1968, menjadi 3% pada tahun 1984 dan menjadi <3% pada tahun
19913
Morbiditas dan mortalitas DBD yang dilaporkan berbagai negara
bervariasi disebabkan beberapa faktor, antara lain status umur penduduk,
kepadatan vektor, tingkat penyebaran virus dengue, prevalensi serotipe virus
dengue dan kondisi meteorologis. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan
antara jenis kelamin, tetapi kematian ditemukan lebih banyak terjadi pada anak
perempuan daripada anak laki-laki. Pada awal terjadinya wabah di sebuah negara,
pola distribusi umur memperlihatkan proporsi kasus terbanyak berasal dari
golongan anak berumur <15 tahun (86-95%). Namun pada wabah selanjutnya,
jumlah kasus golongan usia dewasa muda meningkat. Di Indonesia pengaruh

musim terhadap DBD tidak begitu jelas, namun secara garis besar jumlah kasus
meningkat antara September sampai Februari dengan mencapai puncaknya pada
bulan Januari3
Gambar 1.1 Negara dengan resiko transmisi dengue (WHO, 2011)
Beberapa faktor resiko yang dikaitkan dengan demam dengue dan demam
berdarah dengue antara lain : demografi dan perubahan sosial, suplai air,
manejemen sampah padat, infrastruktur pengontrol nyamuk, consumerism,
peningkatan aliran udara dan globalisasi, serta mikroevolusi virus. Indonesia
berada di wilayah endemis untuk demam dengue dan demam berdarah dengue.
Hal tersebut berdasarkan penelitian WHO yang menyimpulkan demam dengue
dan demam berdarah dengue di Indonesia menjadi masalah kesehatan mayor,
tingginya angka kematian anak, endemis yang sangat tinggi untuk keempat
serotype, dan tersebar di seluruh area.3
Selama 5 tahun terakhir, insiden DBD meningkat setiap tahun. Insiden
tertinggi pada tahun 2007 yakni 71,78 per 100.000 pddk, namun pada tahun 2008
menurun menjadi 59,02 per 100.000 penduduk. Walaupun angka kesakitan sudah
dapat ditekan namun belum mencapai target yang diinginkan yakni <20 per
100.000 penduduk.

Gambar 1.2 Angka kesakitan dan kematian demam berdarah dengue di Indonesia
(Depkes, 2008)
Epidemic sering terjadi di Americas, Europe, Australia, dan Asia hingga
awal abad 20. Sekarang demam dengue endemic pada Asia Tropis, Kepulauan di
Asia Pasifik, Australia bagian utara, Afrika Tropis, Karibia, Amerika selatan dan
Amerika tengah. Demam dengue sering terjadi pada orang yang bepergian ke
daerah ini. Pada daerah endemic dengue, orang dewasa seringkali menjadi imun,
sehingga anak-anak dan pendatang lebih rentan untuk terkena infeksi virus ini.5
Gambar 2. Distribusi Dengue di Dunia. CDC 2009.7
Keterangan : Biru : area infestasi Aedes aegypti.Merah : area infestasi Aedes
aegyptidan epidemic dengue
DHF/ DSS lebih sering terjadi pada daerah endemis virus dengue dengan
beberapa serotype.Penyakit ini biasanya menjadi epidemic tiap 2-5 tahun.

DHF/DSS paling banyak terjadi pada anak di bawah 15 tahun, biasanya pada
umur 4-6 tahun. Frekuensi kejadian DSS paling tinggi pada dua kelompok
penderita : a. anak-anak yang sebelumnya terkena infeksi virus dengue, b. bayi
yang darah ibunya mengandung anti dengue antibody. Transmisi penyakit
biasanya meningkat pada musim hujan. Suhu yang dingin memungkinkan waktu
survival nyamuk dewasa lebih panjang sehingga derajat tranmisi meningkat.2
Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penyebaran kasus
DBD sangat kompleks, yaitu (1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi, (2)
Urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali, (3) Tidak adanya kontrol
vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis, dan (4) Peningkatan sarana
transportasi.1
Morbiditas dan mortalitas infeksi virus dengue dipengaruhi berbagai faktor
antara lain status imunitas pejamu, kepadatan vektor nyamuk, transmisi virus
dengue, keganasan (virulensi) virus dengue, dan kondisi geografis setempat.
Dalam kurun waktu 30 tahun sejak ditemukan virus dengue di Surabaya dan
Jakarta, baik dalam jumlah penderita maupun daerah penyebaran penyakit terjadi
peningkatan yang pesat. Sampai saat ini DBD telah ditemukan di seluruh propinsi
di Indonesia, dan 200 kota telah melaporkan adanya kejadian luar biasa. Incidence
rate meningkat dari 0,005 per 100,000 penduduk pada tahun 1968 menjadi
berkisar antara 6-27 per 100,000 penduduk. Pola berjangkit infeksi virus dengue
dipengaruhi oleh iklim dan kelembaban udara. Pada suhu yang panas (28-32°C)
dengan kelembaban yang tinggi, nyamuk Aedes akan tetap bertahan hidup untuk
jangka waktu lama. Di Indonesia, karena suhu udara dan kelembaban tidak sama
di setiap tempat, maka pola waktu terjadinya penyakit agak berbeda untuk setiap
tempat. Di Jawa pada umumnya infeksi virus dengue terjadi mulai awal Januari,
meningkat terus sehingga kasus terbanyak terdapat pada sekitar bulan April-Mei
setiap tahun.1
C. Etiologi

Demam dengue dan demam berdarah dengue disebabkan oleh virus
dengue, yang termasuk dalam group B arthropod borne virus (arbovirus) dan
sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Flavivirus
merupakan virus dengan diameter 30 nm terdiri dari asam ribonukleat rantai
tunggal dengan berat molekul 4x106 .
Gambar 1.3 Virus Dengue (Smith, 2002)
Terdapat 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4 yang
semuanya dapat menyebabkan demam dengue atau demam berdarah dengue.
Keempat serotype ditemukan di Indonesia dengan DEN-3 merupakan serotype
terbanyak. Infeksi dengan salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi seumur
hidup terhadap serotipe yang bersangkutan tetapi tidak ada perlindungnan
terhadap serotipe yang lain. Seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue
dapat terinfeksi dengan 3 atau bahkan 4 serotipe selama hidupnya. Keempat jenis
serotipe virus dengue dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.5
Virus Dengue dapat ditularkan oleh Nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk
Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk yang paling sering
ditemukan. Nyamuk Aedes aegypti hidup di daerah tropis, terutama hidup dan
berkembang biak di dalam rumah, yaitu tempat penampungan air jernih atau
tempat penampungan air sekitar rumah. Nyamuk ini sepintas lalu tampak berlurik,
berbintik – bintik putih, biasanya menggigit pada siang hari, terutama pada pagi

dan sore hari. Jarak terbang nyamuk ini 100 meter. Sedangkan nyamuk Aedes
albopictus memiliki tempat habitat di tempat air jernih. Biasanya nyamuk ini
berada di sekitar rumah dan pohon – pohon, tempat menampung air hujan yang
bersih, seperti pohon pisang, pandan, kaleng bekas. Nyamuk ini menggigit pada
siang hari dan memiliki jarak terbang 50 meter.
Gambar 1.4 Distribusi nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus
(WHO, 2011)
D. Patogenesis
Virus merupakan mikrooganisme yang hanya dapat hidup di dalam sel
hidup. Maka demi kelangsungan hidupnya, virus harus bersaing dengan sel
manusia sebagai pejamu (host) terutama dalam mencukupi kebutuhan akan
protein. Persaingan tersebut sangat tergantung pada daya tahan pejamu, bila daya
tahan baik maka akan terjadi penyembuhan dan timbul antibodi, namun bila daya
tahan rendah maka perjalanan penyakit menjadi makin berat dan bahkan dapat
menimbulkan kematian.2
Patogenesis DBD dan SSD (Sindrom Syok Dengue) masih merupakan
masalah yang kontroversial. Dua teori yang banyak dianut pada DBD dan SSD
adalah hipotesis infeksi sekunder (teori secondary heterologous infection) atau
hipotesis immune enhancement. Hipotesis ini menyatakan secara tidak langsung
bahwa pasien yang mengalami infeksi yang kedua kalinya dengan serotipe virus
dengue yang heterolog mempunyai risiko berat yang lebih besar untuk menderita
DBD/Berat. Antibodi heterolog yang telah ada sebelumnya akan mengenai virus
lain yang akan menginfeksi dan kemudian membentuk kompleks antigen antibodi
yang kemudian berikatan dengan Fc reseptor dari membran sel leukosit terutama

makrofag. Oleh karena antibodi heterolog maka virus tidak dinetralisasikan oleh
tubuh sehingga akan bebas melakukan replikasi dalam sel makrofag.
Dihipotesiskan juga mengenai antibody dependent enhancement (ADE), suatu
proses yang akan meningkatkan infeksi dan replikasi virus dengue di dalam sel
mononuklear. Sebagai tanggapan terhadap infeksi tersebut, terjadi sekresi
mediator vasoaktif yang kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas
pembuluh darah, sehingga mengakibatkan keadaan hipovolemia dan syok.2
Patogenesis terjadinya syok berdasarkan hipotesis the secondary
heterologous infection dapat dilihat pada Gambar 1 yang dirumuskan oleh
Suvatte, tahun 1977. Sebagai akibat infeksi sekunder oleh tipe virus dengue yang
berlainan pada seorang pasien, respons antibodi anamnestik yang akan terjadi
dalam waktu beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan transformasi limfosit
dengan menghasilkan titer tinggi antibodi IgG anti dengue. Disamping itu,
replikasi virus dengue terjadi juga dalam limfosit yang bertransformasi dengan
akibat terdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini akan mengakibatkan
terbentuknya virus kompleks antigen-antibodi (virus antibody complex) yang
selanjutnya akan mengakibatkan aktivasi sistem komplemen. Pelepasan C3a dan
C5a akibat aktivasi C3 dan C5 menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding
pembuluh darah dan merembesnya plasma dari ruang intravaskular ke ruang
ekstravaskular.Pada pasien dengan syok berat, volume plasma dapat berkurang
sampai lebih dari 30 % dan berlangsung selama 24-48 jam. Perembesan plasma
ini terbukti dengan adanya, peningkatan kadar hematokrit, penurunan kadar
natrium, dan terdapatnya cairan di dalam rongga serosa (efusi pleura, asites). Syok
yang tidak ditanggulangi secara adekuat, akan menyebabkan asidosis dan anoksia,
yang dapat berakhir fatal; oleh karena itu, pengobatan syok sangat penting guna
mencegah kematian.2
Hipotesis kedua, menyatakan bahwa virus dengue seperti juga virus
binatang lain dapat mengalami perubahan genetik akibat tekanan sewaktu virus
mengadakan replikasi baik pada tubuh manusia maupun pada tubuh nyamuk.
Ekspresi fenotipik dari perubahan genetik dalam genom virus dapat menyebabkan
peningkatan replikasi virus dan viremia, peningkatan virulensi dan mempunyai

potensi untuk menimbulkan wabah. Selain itu beberapa strain virus mempunyai
kemampuan untuk menimbulkan wabah yang besar. Kedua hipotesis tersebut
didukung oleh data epidemiologis dan laboratoris.2
Gambar 1. Patogenesis terjadinya syok pada DBD2
Sebagai tanggapan terhadap infeksi virus dengue, kompleks antigen-
antibodi selain mengaktivasi sistem komplemen, juga menyebabkan agregasi
trombosit dan mengaktivitasi sistem koagulasi melalui kerusakan sel endotel
pembuluh darah (gambar 2). Kedua faktor tersebut akan menyebabkan perdarahan
pada DBD. Agregasi trombosit terjadi sebagai akibat dari perlekatan kompleks
antigen-antibodi pada membran trombosit mengakibatkan pengeluaran ADP
(adenosin di phosphat), sehingga trombosit melekat satu sama iain. Hal ini akan
menyebabkan trombosit dihancurkan oleh RES (reticulo endothelial system)
sehingga terjadi trombositopenia. Agregasi trombosit ini akan menyebabkan
pengeluaran platelet faktor III mengakibatkan terjadinya koagulopati konsumtif
(KID = koagulasi intravaskular deseminata), ditandai dengan peningkatan FDP
(fibrinogen degredation product) sehingga terjadi penurunan faktor pembekuan.2

Gambar 2. Patogenesis Perdarahan pada DBD2
Agregasi trombosit ini juga mengakibatkan gangguan fungsi trombosit,
sehingga walaupun jumlah trombosit masih cukup banyak, tidak berfungsi baik.
Di sisi lain, aktivasi koagulasi akan menyebabkan aktivasi faktor Hageman
sehingga terjadi aktivasi sistem kinin sehingga memacu peningkatan permeabilitas
kapiler yang dapat mempercepat terjadinya syok. Jadi, perdarahan masif pada
DBD diakibatkan oleh trombositpenia, penurunan faktor pembekuan (akibat
KID), kelainan fungsi trombosit, dankerusakan dinding endotel kapiler. Akhirnya,
perdarahan akan memperberat syok yang terjadi.1
E. Diagnosis
Perubahan patofisiologis pada DBD adalah kelainan hemostasis dan
perembesan plasma. Kedua kelainan tersebut dapat diketahui dengan adanya
trombositopenia dan peningkatan hematokrit.2

Bentuk klasik dari DBD ditandai dengan demam tinggi, mendadak 2-7
hari, disertai dengan muka kemerahan. Keluhan seperti anoreksia, sakit kepala,
nyeri otot, tulang, sendi, mual, dan muntah sering ditemukan. Beberapa penderita
mengeluh nyeri menelan dengan faring hiperemis ditemukan pada pemeriksaan,
namun jarang ditemukan batuk pilek. Biasanya ditemukan juga nyeri perut
dirasakan di epigastrium dan dibawah tulang iga. Demam tinggi dapat
menimbulkan kejang demam terutama pada bayi.2
Bentuk perdarahan yang paling sering adalah uji tourniquet (Rumple
Leede) positif, kulit mudah memar dan perdarahan pada bekas suntikan intravena
atau pada bekas pengambilan darah. Kebanyakan kasus, petekia halus ditemukan
tersebar di daerah ekstremitas, aksila, wajah, dan palatum mole, yang biasanya
ditemukan pada fase awal dari demam. Epistaksis dan perdarahan gusi lebih
jarang ditemukan, perdarahan saluran cerna ringan dapat ditemukan pada fase
demam. Hati biasanya membesar dengan variasi dari just palpable sampai 2-4 cm
di bawah arcus costae kanan. Sekalipun pembesaran hati tidak berhubungan
dengan berat ringannya penyakit namun pembesaran hati lebih sering ditemukan
pada penderita dengan syok.2
Masa kritis dari penyakit terjadi pada akhir fase demam, pada saat ini
terjadi penurunan suhu yang tiba-tiba yang sering disertai dengan gangguan
sirkulasi yang bervariasi dalam berat-ringannya. Pada kasus dengan gangguan
sirkulasi ringan perubahan yang terjadi minimal dan sementara, pada kasus berat
penderita dapat mengalami syok.2
Berdasarkan kriteria WHO 1997 diagnosis DBD ditegakkan bila semua
hal dibawah ini dipenuhi:2
Demam atau riwayat demam akut, antara 2 – 7 hari, biasanya bifasik
Terdapat minimal satu dari manifestasi perdarahan berikut:
o Uji bendung positif

o Petekie, ekimosis, atau purpura
o Perdarahan mukosa (tersering epistaksis atau perdarahan gusi)
o Hematemesis atau melena
Trombositopenia (jumlah trombosit <100.000/ul)
Terdapat minimal satu tanda-tanda plasma leakage (kebocoran plasma)
sebagai berikut:
o Peningkatan hematokrit >20% dibandingkan standar sesuai dengan
umur dan jenis kelamin
o Penurunan hematokrit >20% setelah mendapat terapi cairan,
dibandingkan dengan nilai hematokrit sebelumnya
o Tanda kebocoran plasma seperti efusi pleura, asites atau
hipoproteinemi.
WHO (1997) membagi DBD menjadi 4 (Vasanwala dkk, 2011):
a. Derajat 1
Demam tinggi mendadak (terus menerus 2-7 hari) disertai tanda dan gejala
klinis (nyeri ulu hati, mual, muntah, hepatomegali), tanpa perdarahan
spontan, trombositopenia dan hemokonsentrasi, uji tourniquet positif.
b. Derajat 2
Derajat 1 dan disertai perdarahan spontan pada kulit atau tempat lain seperti
mimisan, muntah darah dan berak darah.
c. Derajat 3
Ditemukan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan darah
rendah (hipotensi), kulit dingin, lembab dan gelisah, sianosis disekitar
mulut, hidung dan jari (tanda-tand adini renjatan).
d. Renjatan berat (DSS) / Derajat 4
Syok berat dengan nadi tak teraba dan tekanan darah tak dapat diukur
F. Manifestasi Klinis
a. Demam5
Demam berdarah dengue biasanya ditandai dengan demam yang
mendadak tanpa sebab yang jelas, continue, bifasik. Biasanya berlangsung
2-7 hari (Bagian Patologi Klinik, 2009). Naik turun dan tidak berhasil

dengan pengobatan antipiretik. Demam biasanya menurun pada hari ke-3
dan ke-7 dengan tanda-tanda anak menjadi lemah, ujung jari, telinga dan
hidung teraba dingin dan lembab. Masa kritis pda hari ke 3-5. Demam akut
(38°-40° C) dengan gejala yang tidak spesifik atau terdapat gejala penyerta
seperti , anoreksi, lemah, nyeri punggung, nyeri tulang sendi dan kepala.
Gambar: Kurva suhu pada DHF
b. Perdarahan
Manifestasi perdarahan pada umumnya muncul pada hari ke 2-3 demam.
Bentuk perdarahan dapat berupa: uji tourniquet positif yang menandakan
fraglita kapiler meingkat (Bagian Patologi Klinik, 2009). Kondisi seperti
ini juga dapat dijumpai pada campak, demam chikungunya, tifoid, dll.
Perdarahan tanda lainnya ptekie, purpura, ekomosis, epitaksis dan
perdarahan gusi, hematemesisi melena. Uji tourniquet positif jika terdapat
lebih dari 20 ptekie dalam diameter 2,8 cm di lengan bawah bagian volar
termasuk fossa cubiti.
c. Hepatomegali
Ditemukan pada permulaan demam, sifatnya nyeri tekan dan tanpa disertai
ikterus. Umumnya bervariasi, dimulai dengan hanya dapat diraba hingga
2-4 cm di bawah lengkungan iga kanan (Bagian Patologi Klinik, 2009).

Derajat pembesaran hati tidak sejajar dengan beratnya penyakit namun
nyeri tekan pada daerah tepi hati berhubungan dengan adanya perdarahan.
d. Renjatan (Syok)
Syok biasanya terjadi pada saat demam mulai menurun pada hari ke-3 dan
ke-7 sakit. Syok yang terjadi lebih awal atau periode demam biasanya
mempunyai prognosa buruk (Bagian Patologi Klinik, 2009). Kegagalan
sirkulasi ini ditandai dengan denyut nadi terasa cepat dan lemah disertai
penurunan tekanan nadi kurang dari 20 mmHg. Terjadi hipotensi dengan
tekanan darah kurang dari 80 mmHg, akral dingin, kulit lembab, dan
pasien terlihat gelisah.
G. Pemeriksaan Penunjang
a. Darah5
1) Kadar trombosit darah menurun (trombositopenia) (≤ 100000/µI)
2) Hematokrit meningkat ≥ 20%, merupakan indikator akan timbulnya
renjatan. Kadar trombosit dan hematokrit dapat menjadi diagnosis
pasti pada DBD dengan dua kriteria tersebut ditambah terjadinya
trombositopenia, hemokonsentrasi serta dikonfirmasi secara uji
serologi hemaglutnasi (Brasier, Ju, Garcia, Spratt, Forshey, Helsey,
2012).
3) Hemoglobin meningkat lebih dari 20%.
4) Lekosit menurun (lekopenia) pada hari kedua atau ketiga
5) Masa perdarahan memanjang
6) Protein rendah (hipoproteinemia)
7) Natrium rendah (hiponatremia)
8) SGOT/SGPT beisa meningkat
9) Asidosis metabolic
10) Eritrosit dalam tinja hampir sering ditemukan
b. Urine
Kadar albumine urine positif (albuminuria) (Vasanwala, Puvanendran,
Chong, Ng, Suhail, Lee, 2011).
c. Foto thorax

Pada pemeriksaan foto thorax dapat ditemukan efusi pleura. Umumnya
posisi lateral dekubitus kanan (pasien tidur di sisi kanan) lebih baik dalam
mendeteksi cairan dibandingkan dengan posisi berdiri apalagi berbaring.
d. USG
Pemeriksaan USG biasanya lebih disukai pada anak dan dijadikan sebagai
pertimbangan karena tidak menggunakan system pengion (Sinar X) dan
dapat diperiksa sekaligus berbagai organ pada abdomen. Adanya acites
dan cairan pleura pada pemeriksaan USG dapat digunakan sebagai alat
menentukan diagnose penyakit yang mungkin muncul lebh berat misalnya
dengan melihat ketebalan dinding kandung empedu dan penebalan
pancreas.
e. Diagnosis Serologis
1) Uji hemaglutinasi inhibisi (Uji HI)
Tes ini adalah gold standard pada pemeriksaan serologis, sifatnya
sensitive namun tidak spesifik artinya tidak dapat menunjukkan tipe
virus yang menginfeksi. Antibody HI bertahan dalam tubuh lama
sekali (>48 tahun) sehingga uji ini baik digunakan pada studi serologi-
epidemioligi. Untuk diagnosis pasien, Kenaikan titer konvalesen 4x
lipat dari titer serum akut atau titer tinggi (> 1280) baik pada serum
akut atau konvalesen daianggap sebagai presumtif (+) atau di dugan
keras positif infeksu dengue yang baru terjadi (Vasanwala dkk, 2011).
2) Uji komplemen fiksasi (uji CF)
Jarang digunakan secara rutin karena prosedur pemeriksaannya rumit
dan butuh tenaga berpengalaman. Antibodi komplemen fiksasi
bertahan beberapa tahun saja (sekitar 2-3 tahun).
3) Uji neutralisasi
Uji ini paling sensitif dan spesifik untuk virus dengue. Biasanya
memamkai cara Plaque Reduction Neutralization Test (PNRT) yaitu
berdasarkan adanya reduksi dari plaque yang terjadi. Anti body

neutralisasi dapat dideteksi dalam serum bersamaan dengan antibody
HI tetapi lebih cepat dari antibody komplemen fiksasi dan bertahan
lama (>4-8 tahun). Prosedur uji ini rumit dan butuh waktu lama
sehingga tidak rutin digunakan (Vasanwala dkk, 2011).
4) IgM Elisa (Mac Elisa, IgM captured ELISA)
Banyak sekali dipakai. Uji ini dilakukan pada hari ke-4-5 infeksi virus
dengue karena IgM sudah timbul kamudian akan diikuti IgG. Bila IgM
negative uji ini perlu diulang. Apabila hari sakit ke-6 IgM msih
negative maka dilaporkan sebagai negative. IgM dapat bertahan dalam
darah samapi 2-3 bulan setelah adanya infeksi. Sensitivitas uji Mac
Elisa sedikit di bawah uji HI dengan kelebihan uji Mac Elisa hanya
memerlukan satu serum akut saja dengan spesifitas yang sama dengan
uji HI (Vasanwala dkk, 2011).
5) Identifikasi Virus
Cara diagnostic baru dengan reverse transcriptase polymerase chain
reaction (RTPCR) sifatnya sangat sensitive dan spesifik terhadap
serotype tertentu, hasil cepat didapat dan dapat diulang dengan mudah.
Cara ini dapat mendeteksi virus RNA dari specimen yang berasal dari
darah, jaringan tubuh manusia, dan nyamuk. Sensitifitas PCR sama
dengan isolasi virus namun PCR tidak begitu dipengaruhi oleh
penanganan specimen yang kurang baik bahkan adanya antibody
dalam darah juga tidak mempengaruhi hasil dari PCR (Vasanwala dkk,
2011).
H. Diagnosis Banding
a. Pada awal perjalanan penyakit, diagnosis banding mencakup infeksi
bakteri virus, atau infeksi parasit seperti demam tifoid,campak, influenza
hepatitis, demam, chikungunya, leptospirosis, dan malaria. Adanya

trombositopenia yang jelas disertai hemokonsentrasi dapat membedakan
antara DBD dengan penyakit lain.6
b. Demam berdarah dengue harus dibedakan dengan demam chikungunya
(DC). Pada DC biasanya seluruh anggota keluarga dapat terserang dan
penularannya mirip dengan influenza. Bila dibandingkan dengan DBD,
DC memperlihatkan serangan demam mendadak, masa demam lebih
pendek, suhu lebih tinggi, hamper selalu disertai ruam
makulopapular,injeksi konjungtiva, dan lebih sering dijumpai nyeri sendi.
Proporsi uji tourniquet positif, petekie epistaksis hampir sama dengan
DBD. Pada DC tidak ditemukan perdarahan gastrointestinal dan syok.
c. Perdarahan seperti petekie dan ekimosis ditemukan pada beberapa
penyakit infeksi, misalnya sepsis, meningitis meningokokus. Pada sepsis,
sejak semula pasien tampak sakit berat, demam naik turun, dan ditemukan
tanda-tanda infeksi. Disamping itu jelas terdapat leukositosis disertai
dominasi sel polimorfonuklear (pergeseran kekiri pada hitung jenis)
pemeriksaan LED dapat dipergunakan untuk membedakan infeksi bakteri
dengan virus. Pada meningitis meningokokus, jelas terdapat gejala
rangsangan meningeal dan kelainan pada pemeriksaan cairan serebrospinal
d. Idiophatic Thrombocytopenic Purpura (ITP) sulit dibedakan dengan DBD
derajat II, oleh karena didapatkan demamdisertai perdarahan dibawah
kulit. Pada hari-hari pertama, diagnosis ITP sulit dibedakan dengan
penyakit DBD, tetapi pada ITP demam cepat menghilang, tidak dijumpai
leukopeni, tidak dijumpai hemokonsentrasi, tidak dijumpai pergeseran
kekanan pada hitung jenis. Pada fase penyembuhan DBD jumlah
trombositlebih cepat kembali normal daripada ITP
e. Perdarahan dapat juga terjadi pada leukemia atau anemia aplastik. Pada
leukemia demam tidak teratur, kelenjar limfe dapat teraba dan anak sangat
anemis. Pemeriksaan darah tepi dan sumsum tulang akan memperjelas
diagnosis leukemia. Pada anemia aplastik akan sangat anemic, demam
timbul karena infeksi sekunder. Pada pemeriksaan darah ditemukan
pansitopenia (leukosit, hemoglobin, trombosit menurun). Pada pasien

dengan perdarahan hebat pemeriksaan foto toraks dan atau kadar protein
dapat membantu menegakkan diagnosis. Pada DBD ditemukan efusi
pleura dan hipoproteinemia sebagai tanda perembesan plasma
I. Penatalaksanaan
a. Pre Hospital7
Penatalaksanaan prehospital DBD bisa dilakukan melalui 2 cara
yaitu pencegahan dan penanganan pertama pada penderita demam
berdarah. DinasKesehatan Kota Denpasar menjelaskan pencegahan
yang dilakukan meliputi kegiatan pemberantasan sarang nyamuk
(PSN), yaitu kegiatan memberantas jentik ditempat perkembangbiakan
dengan cara 3M Plus:
1) Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, seperti
bak mandi / WC, drum, dan lain-lain seminggu sekali (M1).
2) Menutup rapat-rapat tempat penampungan air, seperti gentong
air/tempayan, dan lain-lain (M2).
3) Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat
menampung air hujan (M3).
Plusnya adalah tindakan memberantas jentik dan menghindari
gigitan nyamuk dengan cara:
1) Membunuh jentik nyamuk Demam Berdarah di tempat air yang
sulit dikuras atau sulit air dengan menaburkan bubuk Temephos
(abate) atau Altosid. Temephos atau Altosid ditaburkan 2-3 bulan
sekali dengan takaran 10 gram Abate ( ± 1 sendok makan peres
untuk 100 liter air atau dengan takaran 2,5 gram Altosid ( ± 1/4
sendok makan peres) untuk 100 liter air. Abate dan Altosid dapat
diperoleh di puskesmas atau di apotik.
2) Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk.
3) Mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk
4) Mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat nyamuk gosok

5) Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi
6) Tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar
7) Melakukan fogging atau pengasapan bila dilokasi ditemukan 3
kasus positif DBD dengan radius 100 m (20 rumah) dan bila di
daerah tersebut ditemukan banyak jentik nyamuk.
IDAI (2009) menjelaskan tanda-tanda syok harus dikenali dengan
baik karena sangat berbahaya. Apabila syok tidak tertangani dengan
baik maka akan menyusul gejala berikutnya yaitu perdarahan. Pada
saat terjadi perdarahan hebat penderita akan tampak sangat kesakitan,
tapi bila syok terjadi dalam waktu yang lama, penderita sudah tidak
sadar lagi. Dampak syok dapat menyebabkan semua organ tubuh akan
kekurangan oksigen dan akhirnya menyebabkan kematian dalam
waktu singkat. Oleh karena itu penderita harus segera dibawa kerumah
sakit bila terdapat tanda gejala dibawah ini:
1) Demam tinggi (lebih 39oc ataulebih)
2) Muntah terus menerus
3) Tidak dapat atau tidak mauminum sesuai anjuran
4) Kejang
5) Perdarahan hebat, muntah atau berak darah
6) Nyeri perut hebat
7) Timbul gejala syok, gelisah atau tidak sadarkan diri, nafas cepat,
seluruh badan teraba lembab, bibir dan kuku kebiruan, merasa
haus, kencing berkurang atau tidak ada sama sekali
8) Hasil laboratorium menunjukkan peningkatan kekentalan darah
atau penurunan jumlah trombosit
b.Intra Hospital di Unit Gawat Darurat 7
Pada dasarnya pengobatan DBD bersifat suportif, yaitu mengatasi
kehilangan cairan plasma sebagai akibat peningkatan permeabilitas
kapiler dansebagai akibat perdarahan. Pasien DD dapat berobat jalan

sedangkan pasien DBD dirawat di ruang perawatan biasa. Tetapi pada
kasus DBD dengan komplikasi diperlukan perawatan intensif.
Perbedaan patofisilogik utama antara DD/DBD/SSD dan penyakit
lain adalah adanya peningkatan permeabilitas kapiler yang
menyebabkan perembesan plasma dan gangguan hemostasis.
Gambaran klinis DBD/SSD sangat khas yaitu demam tinggi
mendadak, diastesis hemoragik, hepatomegali, dan kegagalan sirkulasi.
Maka keberhasilan tatalaksana DBD terletak pada bagian mendeteksi
secara dini fase kritis yaitu saat suhu turun (the time of defervescence)
yang merupakan ease awal terjadinya kegagalan sirkulasi, dengan
melakukan observasi klinis disertai pemantauan perembesan plasma
dan gangguan hemostasis. Prognosis DBD terletak pada pengenalan
awal terjadinya perembesan plasma, yang dapat diketahui dari
peningkatan kadar hematokrit
Fase kritis pada umumnya mulai terjadi pada hari ketiga sakit.
Penurunanjumlah trombosit sampai <100.000/pl atau kurang dari 1-2
trombosit/ Ipb (rata-rata dihitung pada 10 Ipb) terjadi sebelum
peningkatan hematokrit dansebelum terjadi penurunan suhu.
Peningkatan hematokrit 20% atau lebih mencermikan perembesan
plasma dan merupakan indikasi untuk pemberian caiaran. Larutan
garam isotonik atau ringer laktat sebagai cairan awal pengganti volume
plasma dapat diberikan sesuai dengan berat ringan penyakit. Perhatian
khusus pada kasus dengan peningkatan hematokrit yang terus menerus
dan penurunan jumlah trombosit < 50.000/41. Secara umum pasien
DBD derajat I danII dapat dirawat di Puskesmas, rumah sakit kelas D,
C dan pada ruang rawat sehari di rumah sakit kelas B dan A
1) Fase Demam
Tatalaksana DBD fase demam tidak berbeda dengan
tatalaksana DD, bersifat simtomatik dan suportif yaitu pemberian
cairan oral untuk mencegah dehidrasi. Apabila cairan oral tidak
dapat diberikan oleh karena tidak mau minum, muntah atau nyeri

perut yang berlebihan, maka cairan intravena rumatan perlu
diberikan. Antipiretik kadang-kadang diperlukan, tetapi perlu
diperhatikan bahwa antipiretik tidak dapat mengurangi lama
demam pada DBD. Parasetamol direkomendasikan untuk
pemberian atau dapat di sederhanakan seperti tertera pada Tabel 1.
Rasa haus dan keadaan dehidrasi dapat timbul sebagai akibat
demam tinggi, anoreksia danmuntah. Jenis minuman yang
dianjurkan adalah jus buah, air teh manis, sirup, susu, serta larutan
oralit. Pasien perlu diberikan minum 50 ml/kg BB dalam 4-6 jam
pertama. Setelah keadaan dehidrasi dapat diatasi anak diberikan
cairan rumatan 80-100 ml/kg BB dalam 24 jam berikutnya. Bayi
yang masih minum asi, tetap harus diberikan disamping larutan
oiarit. Bila terjadi kejang demam, disamping antipiretik diberikan
antikonvulsif selama demam 8
Tabel 1
Dosisi Parasetamol Menurut umur
Umur (Tahun) Parasetaol (tiap kali pemberian)
Dosis (mg) Tablet (1 tab = 500
mg)
< 1 60 1/8
1-3 60-125 1/8-1/4
4-6 125-250 1/4-1/2
7-12 250-500 1/2-1
Pasien harus diawasi ketat terhadap kejadian syok yang
mungkin terjadi. Periode kritis adalah waktu transisi, yaitu saat
suhu turun pada umumnya hari ke 3-5 fase demam. Pemeriksaan
kadar hematokrit berkala merupakan pemeriksaan laboratorium
yang terbaik untuk pengawasan hasil pemberian cairan yaitu
menggambarkan derajat kebocoran plasma danpedoman kebutuhan
cairan intravena. Hemokonsentrasi pada umumnya terjadi sebelum

dijumpai perubahan tekanan darah dantekanan nadi. Hematokrit
harus diperiksa minimal satu kali sejak hari sakit ketiga sampai
suhu normal kembali. Bila sarana pemeriksaan hematokrit tidak
tersedia, pemeriksaan hemoglobin dapat dipergunakan sebagai
alternatif walaupun tidak terlalu sensitif. Untuk Puskesmas yang
tidak ada alat pemeriksaan Ht, dapat dipertimbangkan dengan
menggunakan Hb. Sahli dengan estimasi nilai Ht = 3 x kadar Hb
a) Penggantian Volume Plasma
Dasar patogenesis DBD adalah perembesan plasma, yang
terjadi pada fase penurunan suhu (fase a-febris, fase krisis, fase
syok) maka dasar pengobatannya adalah penggantian volume
plasma yang hilang. Walaupun demikian, penggantian cairan
harus diberikan dengan bijaksana dan berhati-hati. Kebutuhan
cairan awal dihitung untuk 2-3 jam pertama, sedangkan pada
kasus syok mungkin lebih sering (setiap 30-60 menit). Tetesan
dalam 24-28 jam berikutnya harus selalu disesuaikan dengan
tanda vital, kadar hematokrit, dan jumlah volume urin.
Penggantian volume cairan harus adekuat, seminimal
mungkin mencukupi kebocoran plasma. Secara umum volume
yang dibutuhkan adalah jumlah cairan rumatan ditambah 5-8%.
Cairan intravena diperlukan, apabila (1) Anak terus menerus
smuntah, tidak mau minum, demam tinggi sehingga tidak
rnungkin diberikan minum per oral, ditakutkan terjadinya
dehidrasi sehingga mempercepat terjadinya syok. (2) Nilai
hematokrit cenderung meningkat pada pemeriksaan berkala.
Jumlah cairan yang diberikan tergantung dari derajat dehidrasi
dankehilangan elektrolit, dianjurkan cairan glukosa 5% di
dalam larutan NaCl 0,45%. Bila terdapat asidosis, diberikan

natrium bikarbonat 7,46% 1-2 ml/kgBB intravena bolus
perlahan-lahan8
Apabila terdapat hemokonsentrasi 20% atau lebih maka
komposisi jenis cairan yang diberikan harus sama dengan
plasma. Volume dankomposisi cairan yang diperlukan sesuai
cairan untuk dehidrasi pada diare ringan sampai sedang, yaitu
cairan rumatan + defisit 6% (5 sampai 8%), seperti tertera pada
tabel 2 dibawah ini
Tabel 2
Kebutuhan Cairan pada Dehidrasi Sedang
(defisit cairan 5 – 8 %)
Berat Badan waktu masuk
RS ( kg )
Jumlah cairan Ml/kg berat
badan per hari
< 7 220
7-11 165
12-18 132
>18 88
Pemilihan jenis dan volume cairan yang diperlukan
tergantung dari umur dan berat badan pasien serta derajat
kehilangan plasma, yang sesuai dengan derajat
hemokonsentrasi. Pada anak gemuk, kebutuhan cairan
disesuaikan dengan berat badan ideal untuk anak umur
yang sama8.
Mengingat pada saat awal pasien datang, kita belum selalu dapat
menentukan diagnosis DD/DBD dengan tepat, maka sebagai pedoman tatalaksana
awal dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:2
1. Tatalaksana kasus tersangka DBD, termasuk kasus DD, DBD derajat I dan
DBD derajat II tanpa peningkatan kadar hematokrit. (Bagan 1 dan 2)

2. Tatalaksana kasus DBD, termasuk kasus DBD derajat II dengan peningkatan
kadar hematokrit. (Bagan 3)
3. Tatalaksana kasus sindrom syok dengue, termasuk DBD derajat III dan IV.
(Bagan 4)
Bagan 1. Tatalaksana kasus tersangka DBD[2]
Tersangka DBD
Demam tinggi, mendadakterus menerus <7 hari
Tersangka DBD

tidak disertai infeksi saluran nafas bagian atas, badan lemah/lesu
Ada kedaruratan Tidak ada kedaruratan
Tanda syok Periksa uji torniquetMuntah terus menerusKejang Uji torniquet (+) Uji torniquet (-)Kesadaran menurun (Rumple Leede) (Rumple Leede)Muntah darahBerak darah
Jumlah trombosit Jumlah trombosit Rawat Jalan<100.000/µl >100.000/µl Parasetamol
Kontrol tiap hariTatalaksana sampai demam hilangdisesuaikan,(Lihat bagan 3,4,5)
Rawat Inap (lihat bagan 3)
Rawat Jalan Nilai tanda klinis &Minum banyak 1,5 liter/hari jumlah trombosit, Ht
Parasetamol bila masih demam Kontrol tiap hari hari sakit ke-3sampai demam turun periksa Hb, Ht, trombosit tiap kali Perhatian untuk orang tua Pesan bila timbul tanda syok: gelisah, lemah, kaki/tangan dingin, sakit perut, BAB hitam,
BAK kurang
Lab : Hb & Ht naik Trombosit turun
Segera bawa ke rumah sakit
Bagan 2. Tatalaksana kasus DBD derajat I dan II
tanpa peningkatan hematokrit[2]
DBD derajat I atau II tanpa peningkatan hematokrit
Gejala klinis:Demam 2-7 hari

Uji torniquet (+) atauperdarahan spontanLaboratorium: Hematokrit tidak meningkatTrombositopenia (ringan)
Pasien masih dapat minum Pasien tidak dapat minumBeri minum banyak 1-2 liter/hari Pasien muntah terus menerusAtau 1 sendok makan tiap 5 menitJenis minuman; air putih, teh manis,Sirup, jus buah, susu, oralitBila suhu >39oC beri parasetamol Pasang infus NaCl 0,9%:Bila kejang beri obat antikonvulsi dekstrosa 5% (1:3)Sesuai berat badan tetesan rumatan sesuai berat badan
Periksa Ht, Hb tiap 6 jam,trombosit
Tiap 6-12 jamMonitor gejala klinis dan laboratoriumPerhatikan tanda syokPalpasi hati setiap hariUkur diuresis setiap hari Ht naik dan atau trombosit turunAwasi perdarahanPeriksa Ht, Hb tiap 6-12 jam
Infus ganti RLPerbaikan klinis dan laboratoris (tetesan disesuaikan, lihat Bagan 4)
Pulang (Kriteria memulangkan pasien)• Tidak demam selama 24 jam tanpa antipiretik• Nafsu makan membaik• Secara klinis tampak perbaikan• Hematokrit stabil• Tiga hari setelah syok teratasi• Jumlah trombosit >50.000/µl• Tidak dijumpai distress pernafasan (disebabkan oleh efusi pleura atau asidosis)
Bagan 3. Tatalaksana kasus DBD derajat II dengan peningkatan
hematokrit >20%[2]
DBD derajat I atau II dengan peningkatan hematokrit >20%DBD derajat I atau II dengan peningkatan hematokrit >20%

Cairan awalRL/RA/NaCl 0,9% atau RLD5/NaCl 0,9%
+D5 6-7 ml/kgBB/jam
Monitor tanda vital/Nilai Ht & Trombosit tiap 6 jam
Perbaikan Tidak ada perbaikan
Tidak gelisah GelisahNadi kuat Distress
pernafasanTek.darah stabil
Frek.nadi naikDiuresis cukup Tanda vital memburuk Ht
tetap tinggi/naik(12 ml/kgBB/jam) Ht meningkat Tek.nadi <20
mmHgHt turun Diuresis
</tidak ada(2x pemeriksaan)
Tetesan dikurangi Tetesan dinaikkan10-15 ml/kgBB/jam
Perbaikan Evaluasi 12-
24 jam
Tanda vital tidak stabil
PerbaikanSesuaikan tetesan
Distress pernafasan Ht turun 3 ml/kgBB/jam Ht naik
Tek.nadi < 20 mmHgIVFD stop setelah 24-48 jamApabila tanda vital/Ht stabil dan Koloid Transfusi darah segardiuresis cukup 20-30 ml/kgBB 10 ml/kgBB
Indikasi Transfusi pd
Anak - Syok yang belum
teratasi
5 ml/kgBB/jam

Perbaikan - Perdarahan masif
Bagan 4. Tatalaksana kasus DBD derajat III dan IV
(Sindrom Syok Dengue/SSD)[6,2]
DBD derajat III & IVDBD derajat III & IV

1. Oksigenasi (berikan O2 2-4 liter/menit2. Penggantian volume plasma segera (cairan kristaloid isotonis)
Ringer laktat/NaCl 0,9%20ml/kgBB secepatnya (bolus dalam 15 menit)
Evaluasi 30 menit, apakah syok teratasi ?Pantau tanda vital tiap 10 menitCatat balance cairan selama pemberian cairan intravena
Syok teratasi Syok tidak teratasiKesadaran membaik Kesadaran menurunNadi teraba kuat Nadi lembut/tidak terabaTekanan nadi >20 mmHg Tekanan nadi <20 mmHgTidak sesak nafas/sianosis Distress pernafasan/sianosisEkstrimitas hangat Kulit dingin dan lembabDiuresis cukup 1 ml/kgBB/jam Ekstrimitas dingin
Periksa kadar gula darah
Cairan dan tetesan disesuaikan 1. Lanjutkan cairan
10 ml/kgBB/jam 15-20 ml/kgBB/jamEvaluasi ketat
Tanda vital 2.Tambahkan koloid/plasma
Tanda perdarahan Dekstran/FFPDiuresisPantau Hb, Ht, Trombosit 3. Koreksi asidosis
Evaluasi 1 jam
Stabil dalam 24 jamTetesan 5 ml/kgBB/jam Syok
belum teratasiHt stabil dalam 2x Syok teratasiPemeriksaan Ht turun Ht tetap
tinggi/naik
Tetesan 3 ml/kgBB/jam Transfusi darah segar10 ml/kgBB Koloid 20
ml/kgBBdapat diulang sesuai
Infus stop tidak melebihi 48 jam kebutuhansetelah syok teratasi

J. Pemberantasan Demam Berdarah Dengue
Kegiatan pemberantasan DBD terdiri atas kegiatan pokok dan kegiatan
penunjang. Kegiatan pokok meliputi pengamatan dan penatalaksaan penderita,
pemberantasan vektor, penyuluhan kepada masyarakat dan evaluasi.3
Kegiatan pokok
1. Pengamatan dan penatalaksanaan penderita
Setiap penderita/tersangka DBD yang dirawat di rumah sakit/puskesmas
dilaporkan secepatnya ke Dinas Kesehatan Dati II. Penatalaksanaan penderita
dilakukan dengan cara rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan prosedur
diagnosis, pengobatan dan sistem rujukan yang berlaku.3
2. Pemberantasan vektor
Pemberantasan sebelum musim penularan meliputi perlindungan
perorangan, pemberantasan sarang nyamuk, dan pengasapan. Perlindungan
perorangan untuk mencegah gigitan nyamuk bisa dilakukan dengan
meniadakan sarang nyamuk di dalam rumah dan memakai kelambu pada
waktu tidur siang, memasang kasa di lubang ventilasi dan memakai penolak
nyamuk. Juga bisa dilakukan penyemperotan dengan obat yang dibeli di toko
seperti mortein, baygon, raid, hit dll.3
Pergerakan pemberantasan sarang nyamuk adalah kunjungan ke
rumah/tempat umum secara teratur sekurang-kurangnya setiap 3 bulan untuk
melakukan penyuluhan dan pemeriksaan jentik. Kegiatan ini bertujuan untuk
menyuluh dan memotivasi keluarga dan pengelola tempat umum untuk
melakukan PSN secara terus menerus sehingga rumah dan tempat umum
bebas dari jentik nyamuk Ae. aegypti. Kegiatan PSN meliputi menguras bak
mandi/wc dan tempat penampungan air lainnya secara teratur sekurang-
kurangnya seminggu sekali, menutup rapat TPA, membersihkan halaman dari
kaleng, botol, ban bekas, tempurung, dll sehingga tidak menjadi sarang

nyamuk, mengganti air pada vas bunga dan tempat minum burung,
mencegah/mengeringkan air tergenang di atap atau talang, menutup lubang
pohon atau bambu dengan tanah, membubuhi garam dapur pada perangkap
semut, dan pendidikan kesehatan masyarakat.3
Pengasapan masal dilaksanakan 2 siklus di semua rumah terutama di
kelurahan endemis tinggi, dan tempat umum di seluruh wilayah kota.
Pengasapan dilakukan di dalam dan di sekitar rumah dengan menggunakan
larutan malathion 4% (atau fenitrotion) dalam solar dengan dosis 438 ml/Ha.3
3. Penyuluhan kepada masyarakat dan evaluasi
Penyuluhan perorangan dilakukan di rumah pada waktu pemeriksaan
jentik berkala oleh petugas kesehatan atau petugas pemeriksa jentik dan di
rumah sakit/puskesmas/praktik dokter oleh dokter/perawat. Media yang
digunakan adalah leaflet, flip chart, slides, dll.3
Penyuluhan kelompok dilakukan kepada warga di lokasi sekitar rumah
penderita, pengunjung rumah sakit/puskesmas/ posyandu, guru, pengelola
tempat umum, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.3
Evaluasi operasional dilaksanakan dengan membandingkan pencapaian
target masing-masing kegiatan dengan direncanakan berdasarkan pelaporan
untuk kegiatan pemberantasan sebelum musim penularan. Peninjauan di
lapangan dilakukan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kegiatan
program.3
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan

Demam dengue dan demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang
disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot
dan/atau nyeri sendi yang disertai lekopeni, ruam, limfadenopati,
trombositopenia dan diatesis hemoragik. Pada DBD terjadi perembesan
plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit) atau
penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom renjatan dengue adalah demam
berdarah dengue yang ditandai oleh renjatan/syok.
Untuk mengurangi kecenderungan penyebarluasan wilayah terjangkit
DBD, mengurangi kecenderungan peningkatan jumlah penderita dan
mengusahakan agar angka kematian tidak melebihi 3% maka pemerintah terus
menyempurnakan program pemberantasan DBD. Strategi pemberantasan
DBD lebih ditekankan pada upaya preventif.
Peran dokter dalam program pemberantasan DBD adalah penemuan,
diagnosis, pengobatan dan perawatan penderita, pelaporan kasus dan
penyuluhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengetahuan
patofisiologi, patogenesis, manifestasi klinis/laboratoris DBD, pengenalan
vektor dan pemberantasannya adalah sangat penting.
DAFTAR PUSTAKA

1) Hadinegoro S.R.H, Soegijanto S, dkk. Tatalaksana Demam Berdarah
Dengue di Indonesia Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan
Lingkungan.. Edisi 3. Jakarta. 2004.
2) Suhendro dkk. Demam Berdarah Dengue. Buku Ajar Ilmu Penyakit
Dalam. Jilid III. Edisi VI. Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit
Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta, Juni 2016.
Hal. 1731-5.
3) Sungkar S. Demam Berdarah Dengue. Pendidikan Kedokteran
Berkelanjutan Ikatan Dokter Indonesia. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter
Indonesia. Jakarta, Agustus 2008.
4) Asih Y. S.Kp. Demam Berdarah Dengue, Diagnosis, Pengobatan,
Pencegahan, dan Pengendalian. World Health Organization. Edisi 2.
Jakarta. 1998.
5) Gubler D.J. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. PubMed Central
Journal List. Terdapat di:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1508601.
Diakses pada: 2009, Desember 29.
6) Gubler DJ, Clark GG. Dengue/Dengue Hemorrhagic Fever: The
Emergence of a Global Health Problem. National Center for Infectious
Diseases
Centers for Disease Control and Prevention
Fort Collins, Colorado, and San Juan, Puerto Rico, USA. 2006. Terdapat
di: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8903160. Diakses pada: 2016,
Februari, 7.
7) Fernandes MDF. Dengue/Dengue Hemorrhagic Fever. Infectious disease.
Terdapat di: http://www.medstudents.com.br/dip/dip1.htm. Diakses pada:
2009, Desember 29.

8) World Health Organization. Dengue and dengue haemorrhagic fever.
Terdapat di: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/htm.
Diakses pada: 2016, februari 7.