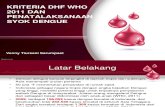Nuzul-dhf Last Referat
description
Transcript of Nuzul-dhf Last Referat

BAB I
PENDAHULUAN
Istilah Dengue mengacu pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus
dengue, mencakup: Dengue Fever (DF), Dengue Haemorrhagic Fever (DHF),
serta Dengue Shock Syndrome (DSS). DF merupakan infeksi virus dengue yang
paling ringan dan biasanya ditandai dengan gejala sakit kepala, nyeri tulang atau
persendian maupun otot, ruam dan leukopenia. Sedangkan DHF ditandai dengan
empat manifestasi klinis yang utama, meliputi: (i) demam tinggi, (ii) fenomena
perdarahan, (iii) seringkali disertai hepatomegali, dan (iv) pada kasus yang parah
akan dijumpai tanda-tanda kegagalan sirkulasi. Keadaan ini dapat berlanjut
menjadi DSS jika terjadi hypovolaemic shock akibat kebocoran plasma.1
DF, DHF, DSS tersebar di wilayah Asia tenggara, Pasifik barat, karibia
dan negara-negara beriklim tropis lainnya. Tercatat ± 75 juta kasus DF terjadi
setiap tahunnya di seluruh dunia, ± 250 ribu kasus DHF dan ± 25 ribu kasus
kematian karena DHF dan DSS. Kasus DHF di Indonesia, pertama kali dijumpai
di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1968. Berdasarkan laporan World Health
Organization (WHO), terdapat empat kejadian luar biasa (KLB) DHF di
Indonesia yang signifikan selama periode 1968-1998, yaitu pada tahun 1973,
1983, 1988 dan 1998. Pada tahun 1998, tercatat 16.005 kasus DHF dengan jumlah
kematian 250 orang (Case Fatality Rate/CFR: 1,5%). Selanjutnya, area sebaran
maupun jumlah kasus DHF cenderung meningkat.1
Sampai saat ini, infeksi virus Dengue tetap menjadi masalah kesehatan di
Indonesia. Indonesia dimasukkan dalam kategori “A” dalam stratifikasi DHF oleh
World Health Organization (WHO) 2001 yang mengindikasikan tingginya angka
perawatan rumah sakit dan kematian akibat DHF, khususnya pada anak. Data
Departemen Kesehatan RI menunjukkan pada tahun 2006 (dibandingkan tahun
2005) terdapat peningkatan jumlah penduduk, provinsi dan kecamatan yang
terjangkit penyakit ini, dengan case fatality rate sebesar 1,01% (2007).2
1

Upaya pengendalian terhadap faktor kependudukan tersebut (terutama
kontrol vektor nyamuk) harus terus diupayakan, di samping pemberian terapi
yang optimal pada penderita DHF, dengan tujuan menurunkan jumlah kasus dan
kematian akibat penyakit ini. Sampai saat ini, belum ada terapi yang spesifik
untuk DHF, prinsip utama dalam terapi DHF adalah terapi suportif, yakni
pemberian cairan pengganti. Dengan memahami patogenesis, perjalanan penyakit,
gambaran klinis dan pemeriksaan laboratorium, diharapkan penatalaksanaan dapat
dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya pada refrat ini akan dibahas
terapi cairan pada demam dengue dan demam berdarah dengue sebagai
penatalaksaan definitif pada kasus ini yang akan sangat berguna dan mampu
menambah wawasan mengenai DF, DHF dan DSS.1
2

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. EPIDEMIOLOGI
Di Indonesia, penyakit demam berdarah dengue cenderung semakin
meningkat jumlah penderitanya dan semakin menyebar luas. Pada tahun 1968
terjadi wabah demam berdarah dengue di Surabaya dengan jumlah penderita 58
orang dan kematian 24 orang (41,3% ). Selanjutnya penyakit DHF ini kemudian
menyebar keseluruhan tanah air Indonesia dan mencapai puncak klimaksnya pada
tahun 1988, yaitu 20 tahun sejak keberadaannya di Indonesia penyakit ini
mengukir puncak tertinggi serangannya. Angka insiden pada waktu itu mencapai
27,09 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 3,2 %.3
Berdasarkan laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pada
tahun 1999 terjadi 21.134 kasus, tahun 2000 terjadi 33.443 kasus, tahun 2001
terjadi 45.904 kasus, tahun 2002 terjadi 40.377 kasus dan tahun 2003 terjadi
50.131 kasus dengan jumlah kematian 743 orang.3
Gambar 2.1. Distribusi Virus Dengue di Dunia Tahun 20004
3

2.2. ETIOLOGI5
Dengue dan DHF disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue adalah
suatu arbovirus yang termasuk ke dalam genus Flavivirus. Virus dengue terdiri
dari 4 serotipe yaitu:
1. Dengue 1 (DEN-1), diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944.
2. Dengue 2 (DEN-2), diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944.
3. Dengue 3 (DEN-3), diisolasi oleh Sather.
4. Dengue 4 (DEN-4), diisolasi oleh Sather.
Keempat serotipe ini bisa menyebabkan penyakit yang berat dan fatal.
Infeksi oleh salah satu dari keempat serotipe tersebut tidak menimbulkan
kekebalan protektif silang, artinya jika seseorang pernah terinfeksi oleh DEN 1,
maka di kemudian hari mungkin saja orang tersebut akan terinfeksi oleh serotipe
lainnya, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah endemis dengue, bisa
menderita keempat jenis infeksi dengue. Keempat serotype ditemukan di
Indonesia dengan DEN-3 merupakan serotype terbanyak. Terdapat reaksi silang
antara serotype dengue dengan flavivirus lain seperti yellow fever, japanese
enchepalitis dan West Nile virus. Dalam laboratorium virus dengue dapat
bereplikasi pada hewan mamalia seperti tikus, kelinci, anjing, kelelawar dan
primata. Survei epidemiologi pada hewan ternak didapatkan antibody terhadap
virus dengue pada hewan kuda, sapi dan babi. Penelitian pada artropoda
menunjukkan virus dengue dapat bereplikasi pada nyamuk Aedes (Stegomya) dan
Toxorhynchites.
2.2.1. Virus Dengue5
Dengue merupakan penyakit tropis dan virus penyebabnya bertahan dalam
suatu siklus yang melibatkan manusia dan Aedes aegypti. Aedes aegypti adalah
sejenis nyamuk rumah yang lebih senang menggigit manusia di siang hari.
Dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina, yang lebih menyukai untuk
menyimpan telurnya di dalam wadah yang berisi air bersih dan terletak di sekitar
habitat manusia.
4

Gambar 2.2. Morfologi Virus Dengue5
Siklus transmisi virus di dalam tubuh manusia:
1. Virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui liur nyamuk
2. Virus berkembangbiak di dalam organ target, misalnya kelenjar getah
bening dan hati
3. Virus dilepaskan dari organ tersebut dan melalui darah menyebar
untuk menginfeksi sel darah putih dan jaringan getah bening lainnya
4. Virus dilepaskan dari sel darah putih dan jaringan getah bening
lainnya dan beredar di dalam darah.
Siklus transmisi virus di dalam tubuh nyamuk:
1. Nyamuk menelan darah yang mengandung virus
2. Virus berkembangbiak di dalam usus, indung telur, jaringan saraf dan
lemak tubuh nyamuk; kemudian virus masuk ke dalam rongga tubuh
dan menginfeksi kelenjar liur nyamuk
3. Virus berkembangbiak di dalam kelenjar liur dan jika nyamuk
menggigit manusia lainnya, maka siklus transmisi akan berlanjut.
Pada kebanyakan kasus, demam dengue akan sembuh dengan sendirinya
dan tidak pernah berkembang menjadi DHF. Beberapa faktor resiko yang
berperan dalam berkembangnya demam dengue menjadi DHF adalah:
5

Jenis dan serotipe virus (DHF bisa terjadi pada infeksi primer oleh virus
serotipe tertentu)
Adanya antibodi anti-dengue akibat infeksi sebelumnya atau akibat
berpindahnya antibodi dari ibu ke janin yang dikandungnya
Faktor genetik (misalnya faktor ras tampaknya berperan karena
berdasarkan data, di Kuba DHF lebih banyak ditemukan pada orang kulit
putih)
Usia (di Asia Tenggara, DHF lebih banyak menyerang anak-anak,
sedangkan di Amerika DHF bisa menyerang semua kelompok umur)
Resiko yang lebih tinggi pada infeksi sekunder
Resiko yang lebih tinggi dari lokasi dimana lebih dari 2 serotipe virus
beredar secara bersamaan pada kadar yang tinggi (transmisi hiperendemik)
2.3. PATOGENESIS2
Dua teori yang banyak dianut dalam menjelaskan patogenesis infeksi
dengue adalah hipotesis infeksi sekunder (secondary heterologous infection
theory) dan hipotesis immune enhancement.
Pertama, menurut hipotesis infeksi sekunder yang diajukan oleh Suvatte,
1977, sebagai akibat infeksi sekunder oleh tipe virus dengue yang berbeda, respon
antibodi anamnestik pasien akan terpicu, menyebabkan proliferasi dan
transformasi limfosit dan menghasilkan titer tinggi IgG antidengue. Karena
bertempat di limfosit, proliferasi limfosit juga menyebabkan tingginya angka
replikasi virus dengue. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kompleks virus-
antibodi yang selanjutnya mengaktivasi sistem komplemen. Pelepasan C3a dan
C5a menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan
merembesnya cairan ke ekstravaskular. Hal ini terbukti dengan peningkatan kadar
hematokrit, penurunan natrium dan terdapatnya cairan dalam rongga serosa
Patogenesis terjadinya syok berdasarkan hipotesis the secondary heterologous
infection dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang dirumuskan oleh Suvatte,
tahun 1977.
6

Gambar 2.3. Patogenesis Terjadinya Syok pada DBD2
Sebagai akibat infeksi sekunder oleh tipe virus dengue yang berlainan
pada seorang pasien, respons antibodi anamnestik yang akan terjadi dalam waktu
beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan transformasi limfosit dengan
menghasilkan titer tinggi antibodi Ig G anti dengue. Disamping itu, replikasi virus
dengue terjadi juga dalam limfosit yang bertransformasi dengan akibat
terdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya
virus kompleks antigen-antibodi (virus antibody complex) yang selanjutnya akan
mengakibatkan aktivasi sistem komplemen. Pelepasan C3a dan C5a akibat
aktivasi C3 dan C5 menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh
darah dan merembesnya plasma dari ruang intravaskular ke ruang ekstravaskular.
Pada pasien dengan syok berat, volume plasma dapat berkurang sampai lebih dari
30 % dan berlangsung selama 24-48 jam. Perembesan plasma ini terbukti dengan
adanya, peningkatan kadar hematokrit, penurunan kadar natrium, dan terdapatnya
cairan di dalam rongga serosa (efusi pleura, asites). Syok yang tidak ditanggulangi
7

secara adekuat, akan menyebabkan asidosis dan anoksia, yang dapat berakhir
fatal; oleh karena itu, pengobatan syok sangat penting guna mencegah kematian.
Gambar 2.4. Patogenesis Perdarahan pada DBD2
Sebagai tanggapan terhadap infeksi virus dengue, kompleks
antigenantibodi selain mengaktivasi sistem komplemen, juga menyebabkan
agregasi trombosit dan mengaktivitasi sistem koagulasi melalui kerusakan sel
endotel pembuluh darah (gambar 2). Kedua faktor tersebut akan menyebabkan
perdarahan pada DHF. Agregasi trombosit terjadi sebagai akibat dari perlekatan
kompleks antigen-antibodi pada membran trombosit mengakibatkan pengeluaran
ADP (adenosin di phosphat), sehingga trombosit melekat satu sama iain. Hal ini
akan menyebabkan trombosit dihancurkan oleh RES (reticulo endothelial system)
sehingga terjadi trombositopenia. Agregasi trombosit ini akan menyebabkan
pengeluaran platelet faktor III mengakibatkan terjadinya koagulopati konsumtif
(KID = koagulasi intravaskular deseminata), ditandai dengan peningkatan FDP
(fibrinogen degredation product) sehingga terjadi penurunan faktor pembekuan.
8

Kedua, hipotesis immune enhancement menjelaskan secara tidak langsung
bahwa mereka yang terkena infeksi kedua oleh virus heterolog mempunyai risiko
berat yang lebih besar untuk menderita DHF berat. Antibodi herterolog yang telah
ada akan mengenali virus lain kemudian membentuk kompleks antigen-antibodi
yang berikatan dengan Fc reseptor dari membran leukosit terutama makrofag.
Sebagai tanggapan dari proses ini, akan terjadi sekresi mediator vasoaktif yang
kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga
mengakibatkan keadaan hipovolemia dan syok.
Gambar 2.5. Teori Infection Enhancing Antibody2
2.4. MANIFESTASI KLINIS
Terdapat 4 sindroma klinis dengue:6
• Demam biasa
• Demam dengue klasik
• Demam berdarah dengue (DHF)
• Sindroma syok dengue (DSS, Dengue Shock Syndrome).
9

Gambar 2.6. Spektrum Klinis Infeksi Virus Dengue6
Demam biasa merupakan manifestasi yang paling sering ditemukan pada
dengue. Suatu penelitian prospektif di Bangkok melaporkan bahwa 90 dari 103
(87%) siswa yang terinfeksi oleh virus dengue menunjukkan gejala yang minimal
atau bahkan tanpa gejala, dan hanya absen sekolah selama 1 hari.7
Gambar 2.7. Kurva Suhu DBD7
10

Demam dengue adalah suatu penyakit virus akut yang ditandai oleh:6
demam (seringkali muncul secara tiba-tiba)
sakit kepala hebat (seringkali digambarkan sebagai sakit di
belakangmata)
mialgia (nyeri otot) dan atralgia (nyeri persendian) - mual dan muntah
ruam kulit yang mungkin muncul pada stadium penyakit
yangberlainan dan bisa berupa makulopapuler, peteki maupun eritema
manifestasi perdarahan.
Penderita juga mungkin mengeluhkan gejala lainnya, seperti gatal-gatal
dan gangguan pengecapan (terutama lidah terasa seperti logam). Beberapa kasus
infeksi dengue akut mungkin disertai dengan tanda dan gejala ensefalitik atau
ensefalopatik, seperti:6
penurunan kesadaran (berupa letargi, linglung dan koma)
kejang
kaku kuduk
kelumpuhan
Beberapa dari kasus tersebut kemudian diikuti dengan timbulnya DHF.
Manifestasi perdarahan pada dengue
Sebanyak sepertiga penderita mungkin akan mengalami manifestasi
perdarahan, yang biasanya bersifat ringan. Pada beberapa kasus, perdarahan
tampak jelas dan cukup berat sehingga menyebabkan syok akibat kekurangan
darah. Manifestasi perdarahan tersebut antara lain: perdarahan kulit (peteki,
purpura, ekimosis), perdarahan gusi, hidung, perdarahan saluran pencernaan
(hematemesis, melena, hematokezia), hematuria, dan bertambahnya perdarahan
menstruasi.7
11

2.5. DIAGNOSIS
2.5.1. Dasar diagnosis
Berdasarkan kriteria WHO 1997, diagnosis DHF ditegakkan bila semua
hal ini terpenuhi:2
1. Demam atau riwayat demam akut, antara 2-7 hari biasanya bifasik.
2. Terdapat minimal 1 manifestasi perdarahan berikut: uji bendung
positif; petekie, ekimosis, atau purpura; perdarahan mukosa;
hematemesis dan melena.
3. Trombositopenia (jumlah trombosit <100.000/ ml).
4. Terdapat minimal 1 tanda kebocoran plasma sbb:
Peningkatan hematokrit >20% dibandingkan standar sesuai
umur dan jenis kelamin.
Penurunan hematokrit >20% setelah mendapat terapicairan,
dibandingkan dengan nilai hematokrit sebelumnya.
Tanda kebocoran plasma seperti: efusi pleura, asites,
hipoproteinemia, hiponatremia.
Terdapat 4 derajat spektrum klinis DHF (WHO, 1997), yaitu:2
Derajat 1: Demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya
manifestasi perdarahan adalah uji torniquet.
Derajat 2: Seperti derajat 1, disertai perdarahan spontan di kulit
dan perdarahan lain.
Derajat 3: Didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan
lemah, tekanan nadi menurun (20 mmHg atau kurang) atau
hipotensi, sianosis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab,
tampak gelisah.
Derajat 4: Syok berat, nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah
tidak terukur.
DSS: Kalau memenuhi kriteria diatas ditambah dengan bukti
kegagalan sirkulasi berupa tekanan nadi sempit < 20 mmHg atau
12

hipotensi untuk usia itu, kulit yang dingin dan lembab serta anak
gelisah. (Derajat III dan IV)
Gambar 2.8. Spektrum Klinis DBD6
2.5.2. Langkah diagnosis7
o Pemeriksaan klinis: panas, manifestasi perdarahan, tanda efusi,
hepatomegali, tanda kegagalan sirkulasi.
o Pemeriksaan laboratorium: uji torniquet, hematokrit dan hitung
trombosit secara berkala serta pemeriksaan serologi, pemeriksaan
LPB, albumin darah, CT, BT, PT, PTT, gambaran darah tepi pada
kecurigaan DIC.
o Pemeriksaan penunjang: foto thorak pada dispneu untuk
menelusuri penyebab lain disamping efusi pleura, USG bila ada,
dapat dipakai untuk memeriksa efusi pleura minimal.
2.5.3. Indikasi rawat
13

o Penderita tersangka demam berdarah derajat I dengan panas 3 hari
atau lebih sangat dianjurkan untuk dirawat.
o Tersangka demam berdarah derajat I disertai hiperpireksia atau
tidak mau makan atau muntah-muntah atau kejang-kejang atau Ht
cenderung meningkat dan trombosit cenderung turun harus dirawat.
o Penderita demam berdarah derajat I pada follow up berikutnya
ditemukan status mental berubah, nadi menjadi cepat dan kecil,
kaki tangan dingin, tekanan darah menurun , oligouria harus
dirawat.
o Seluruh derajat II, III, IV.
Gambar 2.9. Keluhan DBD7
2.5.4. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan laboratorium meliputi kadar hemoglobin, kadar
hematokrit,jumlah trombosit, dan hapusan darah tepi untuk melihat adanya
limfositosis relatif disertai gambaran limfosit plasma biru (sejak hari ke 3).
Trombositopenia umumnya dijumpai pada hari ke 3-8 sejak timbulnya demam.
Hemokonsentrasi dapat mulai dijumpai mulai hari ke 3 demam. Pada DBD yang
disertai manifestasi perdarahan atau kecurigaan terjadinya gangguan koagulasi,
dapat dilakukan pemeriksaan hemostasis (PT, APTT, Fibrinogen, D-Dimer, atau
14

FDP). Pemeriksaan lain yang dapat dikerjakan adalah albumin, SGOT/SGPT,
ureum/ kreatinin.
Untuk membuktikan etiologi DHF, dapat dilakukan uji diagnostik melalui
pemeriksaan isolasi virus, pemeriksaan serologi atau biologi molekular. Di antara
tiga jenis uji etiologi, yang dianggap sebagai baku emas adalah metode isolasi
virus. Namun, metode ini membutuhkan tenaga laboratorium yang ahli, waktu
yang lama (lebih dari 1–2 minggu), serta biaya yang relatif mahal. Oleh karena
keterbatasan ini, seringkali yang dipilih adalah metode diagnosis molekuler
dengan deteksi materi genetik virus melalui pemeriksaan reverse transcription
polymerase chain reaction (RT-PCR). Pemeriksaan RT-PCR memberikan hasil
yang lebih sensitif dan lebih cepat bila dibandingkan dengan isolasi virus, tapi
pemeriksaan ini juga relatif mahal serta mudah mengalami kontaminasi yang
dapat menyebabkan timbulnya hasil positif semu. Pemeriksaan yang saat ini
banyak digunakan adalah pemeriksaan serologi, yaitu dengan mendeteksi IgM dan
IgG-anti dengue. Imunoserologi berupa IgM terdeteksi mulai hari ke 3-5,
meningkat sampai minggu ke 3 dan menghilang setelah 60-90 hari. Pada infeksi
primer, IgG mulai terdeteksi pada hari ke 14, sedangkan pada infeksi sekunder
dapat terdeteksi mulai hari ke 2.
Gambar 2.10. Viremia, IgM, dan IgG pada Infeksi Primer dan Sekunder Virus Dengue
15

Salah satu metode pemeriksaan terbaru yang sedang berkembang adalah
pemeriksaan antigen spesifik virus Dengue, yaitu antigen nonstructural protein 1
(NS1). Antigen NS1 diekspresikan di permukaan sel yang terinfeksi virus
Dengue. Masih terdapat perbedaan dalam berbagai literatur mengenai berapa lama
antigen NS1 dapat terdeteksi dalam darah. Sebuah kepustakaan mencatat dengan
metode ELISA, antigen NS1 dapat terdeteksi dalam kadar tinggi sejak hari
pertama sampai hari ke 12 demam pada infeksi primer Dengue atau sampai hari
ke 5 pada infeksi sekunder Dengue. Pemeriksaan antigen NS1 dengan metode
ELISA juga dikatakan memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi (88,7%
dan 100%). Oleh karena berbagai keunggulan tersebut, WHO menyebutkan
pemeriksaan deteksi antigen NS1 sebagai uji dini terbaik untuk pelayanan primer.
Pemeriksaan radiologis (foto toraks PA tegak dan lateral dekubitus kanan) dapat
dilakukan untuk melihat ada tidaknya efusi pleura, terutama pada hemitoraks
kanan dan pada keadaan perembesan plasma hebat, efusi dapat ditemukan pada
kedua hemitoraks. Asites dan efusi pleura dapat pula dideteksi dengan USG.
2.6. PENATALAKSANAAN
Pada dasarnya terapi DHF adalah bersifat suportif dan simtomatis.
Penatalaksanaan ditujukan untuk mengganti kehilangan cairan akibat kebocoran
plasma dan memberikan terapi substitusi komponen darah bilamana diperlukan.
Dalam pemberian terapi cairan, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah
pemantauan baik secara klinis maupun laboratoris.
Proses kebocoran plasma dan terjadinya trombositopenia pada umumnya
terjadi antara hari ke 4 hingga 6 sejak demam berlangsung. Pada hari ke-7 proses
kebocoran plasma akan berkurang dan cairan akan kembali dari ruang interstitial
ke intravaskular. Terapi cairan pada kondisi tersebut secara bertahap dikurangi.
Selain pemantauan untuk menilai apakah pemberian cairan sudah cukup atau
kurang, pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kelebihan cairan serta
terjadinya efusi pleura ataupun asites yang masif perlu selalu diwaspadai.
Terapi nonfarmakologis yang diberikan meliputi tirah baring (pada
trombositopenia yang berat) dan pemberian makanan dengan kandungan gizi yang
16

cukup, lunak dan tidak mengandung zat atau bumbu yang mengiritasi saluran
cerna. Sebagai terapi simptomatis, dapat diberikan antipiretik berupa parasetamol,
serta obat simptomatis untuk mengatasi keluhan dispepsia. Pemberian aspirin
ataupun obat antiinflamasi nonsteroid sebaiknya dihindari karena berisiko
terjadinya perdarahan pada saluran cerna bagaian atas (lambung/duodenum).
Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam terapi cairan
khususnya pada penatalaksanaan demam berdarah dengue:
1. jenis cairan
2. jumlah serta kecepatan cairan yang akan diberikan
Karena tujuan terapi cairan adalah untuk mengganti kehilangan cairan di
ruang intravaskular, pada dasarnya baik kristaloid (ringer laktat, ringer asetat,
cairan salin) maupun koloid dapat diberikan. WHO menganjurkan terapi kristaloid
sebagai cairan standar pada terapi DHF karena dibandingkan dengan koloid,
kristaloid lebih mudah didapat dan lebih murah. Jenis cairan yang ideal yang
sebenarnya dibutuhkan dalam penatalaksanaan antara lain memiliki sifat bertahan
lama di intravaskular, aman dan relatif mudah diekskresi, tidak mengganggu
sistem koagulasi tubuh, dan memiliki efek alergi yang minimal. Secara umum,
penggunaan kristaloid dalam tatalaksana DHF aman dan efektif. Beberapa efek
samping yang dilaporkan terkait dengan penggunaan kristaloid adalah edema,
asidosis laktat, instabilitas hemodinamik dan hemokonsentrasi. Kristaloid
memiliki waktu bertahan yang singkat di dalam pembuluh darah. Pemberian
larutan RL secara bolus (20 ml/kg BB) akan menyebabkan efek penambahan
volume vaskular hanya dalam waktu yang singkat sebelum didistribusikan ke
seluruh kompartemen interstisial (ekstravaskular) dengan perbandingan 1:3,
sehingga dari 20 ml bolus tersebut dalam waktu satu jam hanya 5 ml yang tetap
berada dalam ruang intravaskular dan 15 ml masuk ke dalam ruang interstisial.
Namun demikian, dalam aplikasinya terdapat beberapa keuntungan penggunaan
kristaloid antara lain mudah tersedia dengan harga terjangkau, komposisi yang
menyerupai komposisi plasma, mudah disimpan dalam temperatur ruang, dan
bebas dari kemungkinan reaksi anafilaktik.
17

Dibandingkan cairan kristaloid, cairan koloid memiliki beberapa
keunggulan yaitu: pada jumlah volume yang sama akan didapatkan ekspansi
volume plasma (intravaskular) yang lebih besar dan bertahan untuk waktu lebih
lama di ruang intravaskular. Dengan kelebihan ini, diharapkan koloid memberikan
oksigenasi jaringan lebih baik dan hemodinamik terjaga lebih stabil. Beberapa
kekurangan yang mungkin didapatkan dengan penggunaan koloid yakni risiko
anafilaksis, koagulopati, dan biaya yang lebih besar.
Namun beberapa jenis koloid terbukti memiliki efek samping koagulopati
dan alergi yang rendah (contoh: hetastarch). Penelitian cairan koloid dibandingkan
kristaloid pada sindrom renjatan dengue (DSS) pada pasien dengan parameter
stabilisasi hemodinamik pada 1 jam pertama renjatan, memberikan hasil
sebanding pada kedua jenis cairan.
2.6.1. Protokol 1. Penanganan Tersangka (Probable) DHF Dewasa Tanpa Syok
Protokol 1 ini digunakan sebagai petunjuk dalam memberikan pertolongan
pertama pada penderita DHF atau diduga DHF di Instalasi Gawat Darurat dan juga bisa
dipakai sebagai petunjuk dalam memutuskan indikasi rawat. Seseorang yang tersangka
menderita DHF di ruang Gawat Darurat dilakukan pemeriksaan hemoglobin (Hb),
hematokrit (Ht) dan trombosit bila:
Hb, Ht dan trombosit normal atau trombosit antara 100.000-150.000, pasien dapat
dipulangkan dengan anjuran kontrol atau berobat jalan ke Poliklinik dalam waktu 24
jam berikutnya (dilakukan pemeriksaan Hb, Ht, leukosit dan trombosit tiap 24 jam)
atau bila keadaan penderita memburuk segera kembali ke IGD.
Hb, Ht normal tetapi trombosit < 100.000 dianjurkan untuk dirawat.
Hb, Ht meningkat dan trombosit normal atau turun juga dianjurkan untuk dirawat.
2.6.2. Protokol 2. Pemberian Cairan pada Tersangka DHF Dewasa di Ruang
Rawat
Pasien yang tersangka DHF tanpa perdarahan spontan dan masif fan tanpa
syok maka di ruang rawat diberikan cairan infus kristaloid dengan jumlah rumus
berikut ini:
Volume cairan kristaloid per hari yang diperlukan, sesuai rumus berikut;
18

1500 + {20 x (BB dalam kg – 20)}
Setelah pemberian cairan dilakukan pemeriksaan Hb, Ht tiap 24 jam:
Bila Hb, Ht meningkat 10-20% dan trombosit < 100.000 jumlah
pemberian cairan tetap seperti rumus diatas tetapi pemantauan Hb,
Ht dan trombosit dilakukan tiap 12 jam.
Bila Hb, Ht meningkat > 20% dan trombosit < 100.000 maka
pemberian cairan sesuai cairan sesuai dengan protokol penatalaksaan
DHF dengan Ht > 20%
Gambar 2.11. Pemberian Cairan pada Suspek DBD Dewasa
2.6.3. Protokol 3. Penatalaksaan DHF dengan Peningkatan Ht > 20%
Meningkatknya Ht > 20% menunjukkan bahwa tubuh mengalami defisit
cairan sebanyak 5%. Pada keadaan ini terapi awal pemberian cairan adalah
dengan memberikan infus cairan kristaloid sebanyak 6-7 ml/kgBB/jam. Pasien
kemudian dipantau setelah 3-4 jam pemberian cairan. Bila terjadi perbaikan yang
ditandai dengan tanda-tanda hematokrit turun, frekuensi nadi turun, tekanan darah
stabil, produksi urine meningkat maka jumlah cairan infus dikurangi menjadi 5
ml/kgBB/jam. 2 jam kemudian dilakukan pemantauan kembali dan bila keadaan
19

tetap menunjukkan perbaikan maka jumlah cairan infus dikurangi menjadi 3
ml/kgBB/jam. Bila dalam pemantuan keadaan tetap membaik maka pemberian
cairan dapat dihentikan 24-48 jam kemudian.
Apabila setelah pemberian terapi cairan awal 6-7 ml/kgBB/jam tadi
keadaan tetap tidak membaik, yang ditandai dengan hematokrit dan nadi
meningkat, tekanan nadi menurun < 20 mmHg, produksi urin menurun, maka kita
harus menaikkan jumlah cairan infus mejadi 10 ml/kgBB/jam. Dua jam kemudian
dilakukan pemantauan kembali dan bila keadaan menunjukkan perbaikan maka
jumlah pemberian cairan dikurangi menjadi 5 ml/kgBB/jam tetapi bila keadaan
tidak menunjukkan perbaikan maka jumlah pemberian cairan infus dinaikkan
menjadi 15 ml/kgBB/jam dan bila dalam perkembangannya kondisi menjadi
memburuk dan didapatkan tanda-tanda syok maka pasien ditangani sesuai dengan
protokol tatalaksana DSS pada dewasa. Bila syok telah teratasi maka pemberian
cairan dimulai lagi seperti terapi pemberian cairan awal.
20

Gambar 2.12. Peningkatan DBD dengan Peningkatan Ht > 20%2.6.4. Protokol 4. Penatalaksaan Perdarahan Spontan pada DHF Dewasa
Perdarahan spontan masif pada penderita DHF dewasa adalah: perdarahan
hidung/epistaksis yang tidak terkendali walaupun talah diberikan tampon hidung,
perdarahan saluran cerna (hematemesis dan melena atau hematoskesia),
perdarahan saluran kemih (hematuria), perdarahan otak atau perdarahan
tersembunyi dengan jumlah perdarahan 4-5 ml/kgBB/jam. Pada keadaan seperti
ini jumlah dan kecepatan pemberian cairan tetap seperti keadaan DHF tanpa syok
lainnya. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan jumlah urin dilakukan
sesering mungkin dengan kewaspadaan Hb, Ht dan trombosis serta hemostase
harus segera dilakukan dan pemeriksaan Hb, Ht dan trombosit sebaiknya diulang
setiap 4-6 jam.
Pemberian heparin diberikan apabila secara klinis dan laboratoris
didapatkan tanda-tanda koagulasi intravaskular diseminata (KID). Transfusi
komponen darah diberikan sesuai indikasi. FFP diberikan bila didapatkan
defisiensi faktor-faktor pembekuan (PT dan aPTT yang memanjang), PRC
diberikan bila nilai Hb kurang dari 10 g/dl. Transfusi trombosit hanya diberikan
pada pasien DHF dengan perdarahan spontan dan masif dengan jumlah trombosit
<100.000/mm3 disertai atau tanpa KID.
21

Gambar 2.13. Penatalaksanaan Perdarahan Spontan pada DBD Dewasa
2.6.5. Protokol 5. Penatalaksaan Sindrom Syok Dengue pada DHF Dewasa
Bila kita berhadapan dengan dengue shock syndrome (DSS) maka hal
pertama yang harus diingat adalah bahwa rejatan harus segera diatasi dan oleh
karena itu penggantian cairan intravaskular yang hilang harus segera dilakukan.
Angka kemtian DSS sepuluh kali lipat dibandingkan dengan penderita DHF tanpa
rejatan, dan rejatan dapat terjadi karena keterlambatan penderita DHF
mendapatkan pertolongan/pengobatan, penatalaksaan yang tidak tepat termasuk
kurangnya kewaspadaan terhadap tanda-tanda rejatan dini, dan penatalaksanaan
rejatan yang tidak adekuat.
Pada kasus DSS cairan kristaloid adalah pilihan utama yang diberikan.
Selain resusitasi cairan, penderita juga diberi oksigen 2-4 liter/menit.
Pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan darah perifer
lengkap, hemostasis, analisis gas darah, kadar natrium, kalium dan klorida, serta
ureum dan kreatinin.
22

Pada fase awal, cairan kristaloid diguyur sebanyak 10-20 ml/kgBB dan
dievaluasi setelah 15-30 menit. Bila rejatan telah teratasi jumlah cairan dikurangi
menjadi 7 ml/kgBB/jam. Bila dalam 60-120 menit keadaan tetap stabil pemberian
cairan sebanyak 5 ml/kgBB/jam. Bila dalam 60-120 menit keadaan tetap stabil
pemberian cairan menjadi 3 ml/kgBB/jam. Bila 24-48 jam setelah rejatan teratasi
tanda-tanda vital dan hematokrit tetap stabil serta diuresis cukup maka pemberian
cairan perinfus harus dihentikan (karena jika reabsorbsi cairan plasma yang
mengalami ekstravasasi telah terjadim ditandai dengan turunnya hematokrit,
cairan infus terus diberikan maka keadaan hipervolemi, edema paru atau gagal
jantung dapat terjadi).
Pengawasan dini kemungkinan terjadinya rejatan berulang harus dilakukan
terutama dalam waktu 48 jam pertama sejak terjadi rejatan (karena selain proses
patogenesis penyakit masih berlangsungm ternyata cairan kristaloid hanya sekitar
20% saja yang menetap dalam pembuluh darah setelah 1 jam saat pemberian).
Oleh karena untuk mengetahui apakah rejatan telah teratasi dengan baik,
diperlukan pemantauan tanda vital secara ketat. Diuresis diusahakan 2
ml/kgBB/jam. Pemantauan kadar Hb, Htm dan jumlah trombosit dapat
dipergunakan untuk pemantauan perjalanan penyakit.
Bila setelah fase awal pemberian cairan ternyata rejatan belum teratasi,
maka pemberian cairan kristaloid dapat ditingkatkan menjadi 10-30 ml/KgBB,
dan kemudian dievaluasi setelah 20-30 menit. Bila keadaan tetap belum teratasi,
maka perhatikan nilai hematokrit. Bila nilai Ht meningkat, berarti perembesan
plasma masih berlangsung maka pemberian cairan koloid merupakan pilihan,
tetapi bila nilai Ht menurun, berarti terjadi perdarahan (internal bleeding) maka
penderita diberikan transfusi darah segar 10 ml/kgBB dan dapat diulang sesuai
kebutuhan.
Sebelum cairan koloid diberikan maka sebaiknya kita harus mengetahui
sifat-sifat cairan tersebut. Pemberian koloid sendiri mula-mula diberikan dengan
tetesan cepat 10-20 ml/kgBB dan dievaluasi setelah 10-30 menit. Bila keadaan
tetap belum teratasi maka untuk memantau kecukupan cairan dilakukan
pemasangan kateter vena sentral, dan pemberian koloid dapat ditambah hingga
23

jumlah maksimum 30 ml/kgBB (maksimal 1-1,5 liter/hari) dengan sasaran
tekanan vena sentral 15-18 cmH2O. Bila keadaan tetap belum teratasi harus
diperhatikan dan dilakukan koreksi terhadap gangguan asam basa, elektrolit,
hipoglikemi, anemia, KID, infeksi sekunder. Bila tekanan vena sentral penderita
sudah sesuai dengan target tetapi rejatan tetap belum teratasi maka dapat diberikan
obat inotropik/vasopresor.
Gambar 2.14. Penatalaksanaan DSS
24

2.7. TINDAK LANJUT
2.7.1. Pengamatan rutin7
DSS : tensi/nadi diperiksa setiap 15-20 menit sampai keadaan stabil,
Ht, trombosit setiap 3-6 jam sampai keadaan menetap.
Derajat I dan II : pemeriksaan Ht dan trombosit minimal 2 kali sehari.
Pada semua DSS pada saat masuk rumah sakit harus diperiksa juga
CT dan BT. Bila CT cenderung memanjang lakukan juga pemeriksaan
gambaran darah tepi.
Pemeriksaan khusus: EKG bila gagal jantung, foto thorax bila pleural
efusi dan edema paru. USG bila curiga efusi pleura minimal. BT, CT,
PT, PTT, dan gambaran darah tepi bila curiga DIC.
Penderita yang berobat jalan diperiksa trombosit setiap hari. Penderita
yang dirawat, tampung urine 24 jam, bila kurang dari 2 ml/kgBB/jam
periksa ureum dan kretinin.
Elektrolit darah astrup bila keadaan umum tidak membaik.
Pelaporan pada dinas kesehatan Tk II setempat melalui kurir, telepon
atau surat secara mingguan.
2.7.2. Indikasi pulang6
Keadaan umum baik dan masa krisis telah berlalu atau >7 hari sejak panas.
Keadaan umum baik ditandai dengan:
nafsu makan membaik,
keadaan klinis penderita membaik,
tidak demam paling sedikit 24 jam tanpa antipiretik,
tidak dijumpai distress pernafasan minimal 3 hari setelah syok teratasi,
hematokrit stabil
trombosit >50.000 mm3
2.8. KOMPLIKASI
25

Beberapa komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh DHF adalah sebagai
berikut: perdarahan gastrointestinal masif, ensepalopati, edema paru, DIC, dan
efusi pleura.6
2.9. PROGNOSIS
Angka kematian kasus di Indonesia secara keseluruhan < 3%. Angka
kematian DSS di RS 5-10%. Kematian meningkat bila disertai komplikasi. DHF
yang akan berlanjut menjadi syok atau penderita dengan komplikasi sulit
diramalkan, sehingga harus hati-hati dalam melakukan penyuluhan.5
BAB III
26

PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
Sampai saat ini, infeksi virus Dengue tetap menjadi masalah kesehatan di
Indonesia. Indonesia dimasukkan dalam kategori “A” dalam stratifikasi DHF oleh
World Health Organization (WHO) 2001 yang mengindikasikan tingginya angka
perawatan rumah sakit dan kematian akibat DHF, khususnya pada anak. Data
Departemen Kesehatan RI menunjukkan pada tahun 2006 (dibandingkan tahun
2005) terdapat peningkatan jumlah penduduk, provinsi dan kecamatan yang
terjangkit penyakit ini, dengan case fatality rate sebesar 1,01% (2007).
Penyakit demam dengue atau demam berdarah dengue disebabkan oleh
virus dengue. Virus dengue adalah suatu arbovirus yang termasuk ke dalam genus
Flavivirus. Virus dengue terdiri dari 4 serotipe yaitu:
1. Dengue 1 (DEN-1), diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944.
2. Dengue 2 (DEN-2), diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944.
3. Dengue 3 (DEN-3), diisolasi oleh Sather.
4. Dengue 4 (DEN-4), diisolasi oleh Sather.
Keempat serotipe ini bisa menyebabkan penyakit yang berat dan fatal.
Infeksi oleh salah satu dari keempat serotipe tersebut tidak menimbulkan
kekebalan protektif silang, artinya jika seseorang pernah terinfeksi oleh DEN 1,
maka di kemudian hari mungkin saja orang tersebut akan terinfeksi oleh serotipe
lainnya, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah endemis dengue, bisa
menderita keempat jenis infeksi dengue. Keempat serotype ditemukan di
Indonesia dengan DEN-3 merupakan serotype terbanyak. Terdapat reaksi silang
antara serotype dengue dengan flavivirus lain seperti yellow fever, japanese
enchepalitis dan West Nile virus.
Dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina, yang lebih
menyukai untuk menyimpan telurnya di dalam wadah yang berisi air bersih dan
terletak di sekitar habitat manusia. Virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui
liur nyamuk, berkembangbiak di dalam organ target, misalnya kelenjar getah
bening dan hati. Kemudian virus dilepaskan dari organ tersebut dan melalui darah
27

menyebar untuk menginfeksi sel darah putih dan jaringan getah bening lainnya
Perdarahan gastrointestinal masif, ensepalopati, edema paru, DIC, efusi pleura,
syok hipovolemik bahkan kematian merupakan komplikasi dari demam berdarah
dengue.
Pencegahan terhadap perkembangan hidup nyamuk Aedes aegepty
merupakan langkah terpenting dalam upaya menekan angka kejadian demam
dengue dan demam berdarah dengue. Tidak ada terapi spesifik untuk demam
dengue, prinsip utama adalah terapi suportif. Dengan terapi suportif yang adekuat,
angka kematian dapat diturunkan hingga kurang dari 1%. Pemeliharaan volume
cairan sirkulasi merupakan tindakan yang paling penting dalam penanganan kasus
DHF, asupan cairan pasien harus tetap dijaga, terutama cairan oral. Jika asupan
cairan oral pasien tidak mampu dipertahankan, maka dibutuhkan suplemen cairan
melalui intravena untuk mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi secara
bermakna.
3.2. SARAN
Demam dengue dan demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi
yang cukup serius dan banyak menyebabkan kematian individu tanpa
membedakan umur dan jenis kelamin. Oleh karena itu informasi tentang penyakit
ini di seluruh kalangan masyarakat harus terus diperluas. Informasi tersebut dapat
melalui diskusi, penyuluhan, seminar dan sejenisnya untuk memperdalam
pengetahuan masyarakat mengenai demam dengue dan demam berdarah dengue,
terutama mengenai proses terjadinya, pencegahan serta pengobatan yang benar.
Pada kasus yang telat terdeteksi dimana pasien dalam kondisi syok lebih
sering dijumpai dengan berbagai komplikasi sebagai akibatnya dan angka
kematiannya pun cukup tinggi. Sehingga kontrol terhadap kurva suhu, pemberian
cairan oral, pencegahan maupun pengobatannya perlu perhatian khusus.
Pencegahan dan pengobatan perlu dilakukan sedini mungkin guna menghentikan
penyebaran parasit lebih luas dan mencegah komplikasi yang lebih berat. Dengan
keputusan dan pemberian terapi yang tepat maka diharapkan angka kejadian
28

demam dengue dan demam berdarah dengue bisa diturunkan dan komplikasi serta
akibat lainnya yang lebih berat pun bisa dihentikan.
29

DAFTAR PUSTAKA
1. Anonim. Media informasi peresepan rasional bagi tenaga kesehatan
Indonesia, Vol.2, No.4, Maret-April 2002.
2. Pohan, Herdiman. dan Khie Chen. Diagnosis dan Terapi Cairan pada
Demam Berdarah Dengue. 2009. Medicinus: Medical Journal of
Pharmaceutical Development and Medical Application; Vol.22 No.1; hlm
3-7.
3. http://library.usu.a c.id/download/fkm/fkm-hiswani9.pdf .
4. Anonim. Dengue Fever. From Wikipedia, the Free Encyclopedia.
5. http://www.geocities.com/trisaktigeology84/
Demam_Berdarah_Dengue.pdf.
6. Staf pengajar FK UI. Infeksi Virus: Dengue. 2005. Buku Kuliah Ilmu
Penyakit Dalam Jilid 3. Jakarta: Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK UI;
hlm1709-1713.
7. Staf pengajar Fk UI. Infeksi Tropik: Demam Dengue. Edisi Ketiga. 2005.
Kapita Selekta Kedokteran Jilid II. Jakarta: Bagian Ilmu Penyakit Dalam
FK UI; hlm 428-433
30