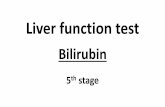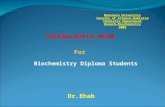General Bilirubin
-
Upload
deprotunisba -
Category
Documents
-
view
124 -
download
4
Transcript of General Bilirubin
General The Advanced Model BR2 Bilirubin Stat-Analyzer photometer is a dual-arm, dual-wavelength, narrowband-pass photometer that measures Bilirubin (TBR) and Azobilirubin (DBR) absorbance quantitatively. The digital readout is calibrated to read bilirubin in milligrams per deciliter (mg/dL).
Total Bilirubin The maximum light absorption of bilirubin occurs at a wavelength of 454 nm. Oxyhemoglobin (HbO2) has nearly equal absorbance at 454 and 540 nm. In the BR2, the absorbance at 540 nm (HbO2) is subtracted from the absorbance at 454 nm (TBR + HbO2). The remainder corresponds to TBR concentration corrected for oxyhemoglobin up to 600 mg/dL. Light from an incandescent source is collimated and directed through a cuvette containing the diluted sample. A fiber optic beam splitter with 454-nm and 540-nm channels splits the transmitted light, each made monochromatic by a narrowbandpass interference filter. Matched solid-state photo-detectors and signal processing electronics measure the transmittances at 454 and 540 nm and display the TBR concentration digitally.
Direct Bilirubin Direct Bilirubin is measured as the change in absorbance at 540 nm due to the formation of azobilirubin, using a two-minute, timed-endpoint modification to the Malloy and Evelyn method. After TBR has been measured on a sample, that same sample is acidified with HCl, establishing an absorbance baseline. Next, diazotized sulfanilic acid is added. Under these conditions, the conjugated (Direct) bilirubin fraction will react to form azobilirubin, which has maximum light absorption at 540 nm. At the end of the two-minute reaction period, the digital display locks in to hold the DBR readout until the next test is initiated.
umum Advanced Model Br2 Bilirubin Lembaran Analyzer fotometer adalah dual-lengan, dual-panjang gelombang, sempit-band-pass fotometer yang mengukur Bilirubin (TBR) dan Azobilirubin (DBR) absorbansi kuantitatif. Pembacaan digital dikalibrasi untuk membaca bilirubin dalam miligram per desiliter (mg / dL).
Jumlah Bilirubin - Penyerapan cahaya maksimum bilirubin terjadi pada panjang gelombang 454 nm. Oksihemoglobin (HbO2) memiliki absorbansi hampir sama di 454 dan 540 nm. Dalam Br2 ini, absorbansi pada 540 nm (HbO2) dikurangi dari absorbansi 454 nm di (TBR + HbO2). Sisanya sesuai dengan konsentrasi TBR dikoreksi untuk oksihemoglobin hingga 600 mg / dL. Cahaya dari sumber pijar adalah collimated dan diarahkan melalui kuvet yang berisi sampel yang diencerkan. Sebuah beam splitter serat optik dengan 454-nm dan 540 nm saluran membelah cahaya yang ditransmisikan, masing-masing dibuat monokromatik dengan filter bandpass sempit gangguan. Cocok solid-state foto-detektor dan elektronik pemrosesan sinyal mengukur transmittances di 454 dan 540 nm dan menampilkan konsentrasi TBR digital. Langsung Bilirubin - Bilirubin langsung diukur sebagai perubahan absorbansi pada 540 nm karena pembentukan azobilirubin, menggunakan dua menit, timed-titik akhir modifikasi ke Malloy dan metode Evelyn. Setelah TBR telah diukur pada sampel, sampel yang sama yang diasamkan dengan HCl, mendirikan dasar absorbansi. Selanjutnya, asam sulfanilic diazotized ditambahkan. Dengan kondisi tersebut, fraksi (langsung) bilirubin terkonjugasi akan bereaksi untuk membentuk azobilirubin, yang memiliki penyerapan cahaya maksimum pada 540 nm. Pada akhir periode reaksi dua menit, tampilan digital untuk memegang kunci dalam pembacaan DBR sampai tes berikutnya dimulai.
Bilirubin, di hadapan senyawa diazonium tertentu, memotong pada kelompok metilen pusat untuk membentuk dua molekul pigmen yang dikenal sebagai azobilirubin. Molekul-molekul ini terlihat biru pada pH asam dan ungu di dasar dan merah pada pH netral. Reaksi struktural dapat divisualisasikan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN A. Judul Praktikum Penentuan kadar bilirubin darah C. Tujuan 1. Mengukur kadar bilirubin total, bilirubin direct dan bilirubin indirect. 2. Menjelaskan nilai normal enzim amilase dalam darah serta nilai patologis dari hasil praktikum. 3. Melakukan diagnosa dini penyakit apa saja yang ditandai oleh hasil aktivitas abnormal (patologis) melalui bantuan hasil praktikum yang dilakukan. D. Dasar Teori Pada manusia dewasa, 1-2 x 108 eritrosit dihancurkan tiap jamnya. Ketika hemoglobin dihancurkan dalam tubuh, globin diuraikan menjadi asan amino pembentuknya yang kemudin akan digunakan kembali, sedangkan zat besi dari heme akan memasuki depot yang juga akan dipakai kembali. Bagian porfirin dalam heme juga diuraikan, terutama di dalam sel sel retikuloendotel hati, limpa dan sumsum tulang. Katabolisme heme dari semua protein heme terjadi di dalam fraksi mikrosom sel retikuloendotel oleh sebuah sistem enzim yang dinamakan heme oksigenase. Adanya bantuan NADPH mengakibatkan penambahan oksigen pda jembatan -metenil antara pirol I dan pirol II porfirin, sehingga besi fero teroksidasi menjaid bentuk feri. Ion feri ini akan dilepaskan, dan bliverdin terbentuk akibat pemecahan cincin tetrapirol. Pada mamalia, enzim biliverdin reduktase akan mereduki jembatan metenil antara pirol III dan pirol IV menjadi gugus metilen untuk menghasilkan bilirubin, yaitu suatu pigmen berwarna kuning. Bilirubin hanya sedikit larut dalam plasma dan air, tetapi kelarutan bilirubin dapat ditingkatkan oleh pengikatan non-kovalen dengan albumin. Dalam 100 ml plasma kurang lebih 25 mg bilirubin dapat diikat erat oleh albumin. Bilirubin selanjutnya diangkut ke hati. Hepatosit kemudian akan mengubah bilirubin bentuk polar dengan penambahan satu molekul asam glukoronat (konjugasi) sehingga terbentuk bilirubin terkonjugasi. Apabila bilirubin mencapai ileum termialis dan usus besar, bilirubin akan direduksi oleh bakteri menjadi urobilinogen,. Urobilinogen yang sebagian besar tidak berwarna, selanjutnya akan teroksidasi menjadi zat berwarna (sterkobilin) dan disekresikan ke dalam feses. Satu gram hemoglobin diperkirakan menghasilkan 35 mg biliruin. Pembentukan bilirubin setiap hari pada manusia dewasa kurang lebih berjumlah 250 35- mg yang terutama berasal dari hemoglobin. Namun demikian, bilirubin dapat juga berasal dari proses eritropoesis yang tidak efektif dan dari berbagai protein heme lainnya seperti sotokrom P-450.
E. Alat dan Bahan 1. Alat a. Spuit 3 cc b. Torniquet 1 buah c. Eppendorf 1 buah d. Rak tabung reaksi 1 buah l 1 buahe. Mikropipet 10-100 l 1 buahf. Mikropipet 100-1000 g. Blue tip 1 buah h. Yellow tip 1 buah i. Kuvet 4 buah j. Spektrofotometer k. Sentrifugator 2. Bahan a. Reagen T-Bil 2 cc b. Reagen T-Nit 40 l c. Reagen D-Bil 2cc d. Reagen D-Nit 40 l le. Serum darah 200 f. Alkohol 70% F. Metode Pemeriksaan Metode Jendrassik-Grof G. Cara Kerja 1. Persiapan sampel: a. Darah diambil menggunakan spuit kira-kira sebanyak 3 cc. b. Darah dimasukkan ke dalam tabung eppendorf dan disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit, kemudian diambil serumnya untuk sampel. 2. Pemeriksaan bilirubin total: a. 2 kuvet disiapkan untuk wadah blanko dan sampel yang akan diukur pada spektrofotometer b. Reagen T-Bil sebanyak 1cc dimasukkan kedalam kuvet blanko c. Reagen T-Bil 1 cc dan T-Nit 40 l dimasukkan kedalam kuvet sampel d. Kedua kuvet tersebut diinkubasi selama 5 menit e. 100 l serum darah dimasukkan kedalam masing-masing kuvet tersebut f. Kedua kuvet diinkubasi selama 10 menit g. nilai kadar bilirubin dibaca total dengan spektofotometer 3. Pemeriksaan bilirubin direct: a. 2 kuvet disiapkan untuk wadah blanko dan sampel yang akan diukur pada spektrofotometer b. Reagen D-Bil sebanyak 1cc dimasukkan kedalam kuvet blanko c. Reagen D-Bil 1 cc dan D-Nit 40 l dimasukkan kedalam kuvet sampel d. Kedua kuvet tersebut diinkubasi selama 2 menit e. 100 l serum darah dimasukkan kedalam masing-masing kuvet tersebut
f. Kedua kuvet diinkubasi selama 5 menit g. nilai kadar bilirubin dibaca total dengan spektofotometer H. Nilai Normal Pengukuran Nilai normal Bilirubin total 0-1 mg/dl Bilirubin direct 0-1,2 mg/dl Bilirubin indirect 0,2-0,7 mg/dl BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Pengamatan Probandus : Ester Moryaan Umur : 19 tahun Jenis kelamin : Perempuan 1. Bilirbin Total Blanko Sample T- Bil 1 cc T-Bil 1 cc, T Nit 40L Diinkubasi selama 5 menit Blanko dan sample ditambah serum 100L Inkubasi lagi 10 menit Di baca pada spektofotometer 2. Biliribin Direct Blanko Sample D Bil 1cc D Bil 1 cc, D Nitrat 40L Diinkubasi selama 2 menit Blanko dan sample ditambah serum 100L Inkubasi lagi 5 menit Di baca pada spektofotometer B. Hasil Pengukuran Pengukuran Hasil Nilai normal Bilirubin total 0 mg/dl 0-1 mg/dl Bilirubin direct 1 mg/dl 0-1,2 mg/dl Bilirubin indirect
-1 mg/dl 0,2-0,7 mg/dl C. Pembahasan Kadar bilirubin indirect probandus pada praktikum kali ini memberikan nilai yang tidak normal, yaitu -1 mg/dl, namun ini belum dapat dikatakan bahwa terdapat ketidaknormalan pada serum probandus. Hal ini bisa saja terjadi karena ada kemungkinan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh praktikan ketika melakukan praktikum atau kesalahan alat spektrofotometer dalam proses pembacaan hasil. Hemoglobin dihancurkan di dalam tubuh menjadi heme dan globin. Globin diuraikan diuraikan menjadi asam amino pembentuknya yang kemudian akan digunakan kembali dan zat besi dari heme akan memasuki depot zat besi yang juga untuk pemakaian kembali. Bagian porfirin tanpa besi pada heme juga diuraikan, terutama di dalm sel-sel retikuloendotelial hati, limpa, dan sumsum tulang. Katabolisme heme dari semua protein heme dilaksanakan di dalam fraksi mikrosom sel retikuloendotelial oleh sebuah sistem enzim yang kompleks yang dinamakan heme oksigenase. Pada saat heme pada protein heme mencapai sistem heme oksigenase, zat besi biasanya sudah teroksidasi menjadi bentuk feri yang merupakan hemin. Sistem heme oksigenase dapat diinduksi oleh substrat. Sistem ini terletak sangat dekat dengan system pengangkutan electron mikrosom. Hemin direduksi dengan NADPH, dan dengan bantuan lebih banyak NADPH, oksigen ditambahkan pada jembatan metenil antara pirol I dan II porfirin. Besi fero sekali lagi teroksidasi menjadi bentuk feri. Dengan penambahan lebih lanjut oksigen, ion feri dilepaskan, kemudian karbon monoksida dihasilkan, dan biliverdin IX- dengan jumlah ekuimolar terbentuk dari pemecahan cincin tetrapirol. Kemudian enzim biliverdin reduktase mereduksi jembatan metenil antara pirol III dan pirol IV menjadi gugus metilen untuk menghasilkan bilirubin IX-. Bilirubin yang terbentuk dijaringan perifer akan diangkut ke hati oleh albumin plasma. Metabolisme bilirubin lebih lanjut terutama di hati. Peristiwa metabolisme ini dapat dibagi menjadi tiga proses, yaitu : a. Ambilan bilirubin oleh sel parenkim hati b. Konjugasi bilirubin dalam reticulum endoplasma halus c. Sekresi bilirubin terkonjugasi ke dalam empedu Bilirubin hanya sedikit larut dalam plasma dan air, tetapi kelarutan bilirubin dalam plasma ditingkatkan oleh pengikatan nonkovalen dengan albumin. Setiap molekul albumin mempunyai satu tapak dengan afinitas tinggi dan satu tapak dengan afinitas rendah untuk pengikatan bilirubin. Di hati, bilirubin dilepaskan dari albumindan diambil pada permukaan sinusoid hepatosit oleh sistem saturable yang diperantarai oleh zat pembawa. Sistem pengangkutan yang difasilitasi ini mempunai kapasitas yang sangat besar sehingga sekalipun pada keadaan patologik, sistem tersebut tidak membatasi kecepatannya dalam metabolisme bilirubin. Bilirubin bersifat nonpolar dan akan bertahan didalam sel. Hepatosit akan merubah bilirubin menjadi bentuk polar yang dapat dieksresikan dengan mudah ke dalam empedu dengan penambahan molekul asam glukoronat pada bilirubin tersebut. Proses ini dinamakan konjugasi dan dapat memakai molekul polar yang bukan asam glukoronat (misal, sulfat).hati mengandung sedikitnya dua buah isoform enzim glukoronosiltransferase yang keduanya bekerja pada bilirubin. Enzim ini terutama terdapat dalam reticulum endoplasma halus dan menggunakn UDP-asam glukoronat sebagai donor glukoronosil. Bilirubin monoglukoronida merupakan intermediate dan selanjutnya akan dikonversikan menjadi bentuk diglukoronida. Sebagian besar bilirubin yang diekskresikan ke dalam empedu dalam bentuk bilirubin
diglukoronida. Sekresi bilirubin terkonjugasi kedalam empedu terjadi melalui mekanisme pengangkutan yang aktif, yang mungkin bersifat membatasi kecepatan bagi keseluruhan proses metabolisme bilirubin hepatik. Dalam keadaan fisiologis, pada hakekatnya seluruh bilirubin yang diekskresikan ke dalam empedu berada dalam bentuk terkonjugasi. Setelah bilirubin-terkonjugasi mencapai ileum terminalis dan usus besar, glukuronida dilepaskan oleh enzim bakteri yang spesifik (enzim -glukuronidase), dan pigmen tersebut selanjutnya direduksi oleh flora feses menjadi sekelompok senyawa tetrapirol tidak berwarna yang dinamakan urobilinogen. Di ileum terminalis dan usus besar, sebagian kecil urobilinogen diserap kembali dan diekskresikan kembali lewaat hati untuk menjalani siklus urobilinogen enterohepatik. Pada keadaan abnormal, khususnya jika terbentuk pigmen empedu yang berlebihan atau jika ada penyakit hati yang mengganggu siklus entero hepatik ini, urobilinogen dapat pula diekskresikan ke dalam urine. Normalnya, sebagian besar urobilinogen tidak berwarna yang terbentuk di dalam kolon akan teroksidasi oleh flora feses menjadi urobilin (senyawa berwarna) dan diekskresikan ke dalam feses. Bilirubin indirect merupakan bilurubin bebas (tak terkonjugasi) yang sedang dalam perjalanan menuju hati dari jaringan, tempat bilirubin tersebut dihasilkan melalui pemecahan porfirin heme. Bilirubin jenis ini tidak larut dalam air. Di hati, bilirubin bebas akan berkonjugasi dengan asam glukoronat dan kemudian konjugatnya (bilirubin glukoronida), bisa diekskresikan ke dalam empedu. Bilirubin tersebut dapat larut dalam air dan selanjutnya disebut dengan bilirubin terkonjugasi (bilirubin direct). (Murray, 2003) Bila darah mengandung bilirubin dalam jumlah besar, sklera (bagian yang putih dari bola mata) dan kulit akan berwarna kekuningan karena bilirubin diikat oleh protein jaringan. Keadaan ini sangat penting untuk dikenali, dan disebut ikterus atau sakit kuning. Meskipun ikterus ini sendiri bukan penyakit akan tetapi merupakan suatu gejala dari suatu penyakit yang mendasarinya. Pengukuran kadar bilirubin total di dalam serum, begitu pula unsur-unsurnya (bilirubin bebas dan bilirubin diglukoronida) akan mempunyai nilai diagnostik yang sangat penting. Berbagai penyakit ataupun keracunan yang menyebabkan pemecahan sel-sel darah merah dalam jumlah yang melebihi normal akan memyebabkan pembebasan hemoglobin dalam jumlah besar. Hem yang dilepaskan dari hemoglobin tapi dengan cepat akan diubah menjadi bilirubin tidak terkonjugasi dan dibawa ke hati. Meskipun hati berada dalam keadaan yang sehat, peningkatan aliran bilirubin ini tidaklah dapat diatasi dengan mengolahnya lebih cepat, akibatnya konsentrasi bilirubin ini dalam plasma tidak dapat dipertahankan dalam batas-batas yang lazim. Peningkatan ini terutama ialah pada bilirubin tidak terkonjugasi. Keadaan ini sering terjadi pada bayi baru lahir yang tidak mempunyai kecocokan golongan darah Rhesus (Rh) dengan ibunya. Kadar bilirubin total dapat mencapi 10 atau bahkan 20 kali kadar normal, yang sebagian besar berada dalam bentuk bilirubin bebas. Biasanya bayi ini lahir prematur dan disamping mempunyai masalah hemolisis ini, kerap kali pula kekurangan enzim-enzim yang diperlukan untuk proses pembentukan konjugat diglukoronida tadi. Hal ini terjadi pada keadaan ikterus prehepatik. Pada kerusakan hati yang tersebar rata, seperti pada hepatitis atau sirosis, sel-sel hati tadi kehilangan sebagian dari kemampuannya menarik bilirubin dari peredaran darah dan mungkin pula kehilangan kemampuan untuk membentuk derivat diglukoronida. Karena itu dalam keadaan seperti ini kadar bilirubin total sering kali naik, disertai kenaikan kadar bilirubin tidak terjonjugasi. Oleh karena sel-sel yang rusak tadi menyebabkan terlepasnya sejumlah bilirubin diglukoronida ke dalam aliran darah, maka
kadar senyawa yang terakhir ini pun mungkin pula bertambah. Keadaan ini terdapat pada ikterus hepatik. Ikterus pascahepatik disebabkan oleh penyakit yang mengganggu perlepasan empedu ke dalam saluran cerna. Akibatnya yang pertama ialah sangat berkurangnya pembentukan urobilinogen sehingga sedikit sekali dari senyawa ini terdapat di dalam urin. Oleh karena pembentukan sterkobilin juga sangat berkurang, tinja penderita akan berwarna putih keabu-abuan. Oleh karena bilirubin terus terbentuk, maka konsentrasi bilirubin total di dalam serum meningkat, terutama disebabkan oleh meningkatnya kadar bilirubin terkonjugasi yang terjadi pada tahap awal dari penyakit. Bilirubin terkonjugasi yang meningkat kadarnya ini akan keluar bersama urin, sehingga cairan ini akan berwarna coklat gelap. Ekskresi bilirubin larut kedalam saluran dan kandung empedu berlangsung dengan mekanisme transport aktif yang melawan gradien konsentrasi. Dalam keadaan fisiologis, seluruh bilirubin yang diekskresikan ke kandung empedu berada dalam bentuk terkonjugasi. Bilirubin terkonjugasi yang mencapai ileum terminal dan kolon dihidrolisa oleh enzym bakteri glukoronidase dan pigmen yang bebas dari glukoronida direduksi oleh bakteri usus menjadi urobilinogen, suatu senyawa tetrapirol tak berwarna. Sejumlah urobilinogen diabsorbsi kembali dari usus ke perdarahan portal dan dibawa keginjal kemudian dioksidasi menjadi urobilin yang memberi warna kuning pada urine. Sebagian besar urobilinogen berada pada feces akan dioksidasi oleh bakteri usus membentuk sterkobilin yang berwarna kuning kecoklatan (Montgomery, 1993) D. Aplikasi Klinis 1. Sirosis hepatik Sirosis adalah suatu keadaan patologis yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepatik yang berlangsung progresif dengan distorsi dari arsitektur hepar dan pembentukan nodulus degeneratif. Gambaran ini terjadi akibat nekrosis hepatoseluler. Etiologi dari sirosis hepatis dapat berupa penyakit infeksi, penyakit keturunan dan metabolik, obat, dan toksin. (Nurdjanah, 2007) Pada keadaan sirosis, fungsi hepar dalam metabolisme, sintesis, sekresi, dan ekskresi terganggu. Sebagai contohnya, sintesis albumin terjadi di jaringan hati. Maka pada sirosis akan terjadi gangguan sintesis dan sekresi albumin yang menyebabkan hipoalbuminemia. Keadaan hipoalbuminemia dapat menyebabkan acites, edema perifer dan hiperbilirubinemia. Hiperbilirubeinemia diakibatkan kadar albumin, yang berfungsi membawa bilirubin tak-terkonjugasi dari jaringan perifer ke hepar, tidak mencukupi sehingga bilirubin bebas tersebut berdifusi ke dalam jaringan. Manifestasi klinis dari proses difusi tersebut adalah timbulnya ikterik (Sri Maryani Sutadi, 2004). 2. Anemia Hemolitik Anemia Hemolitik adalah anemia yang terjadi karena meningkatnya penghancuran sel darah merah. Dalam keadaan normal, sel darah merah mempunyai waktu hidup 120 hari. Jika menjadi tua, sel pemakan dalam sumsum tulang, limpa dan hati dapat mengetahuinya dan merusaknya. Jika suatu penyakit menghancurkan sel darah merah sebelum waktunya (hemolisis), sumsum tulang berusaha menggantinya dengan mempercepat pembentukan sel darah merah yang baru, sampai 10 kali kecepatan normal. Jika penghancuran sel darah merah melebihi pembentukannya, maka akan terjadi anemia hemolitik. Sejumlah faktor dapat meningkatkan penghancuran sel darah merah: 1. Pembesaran limpa (splenomegali). 2. Sumbatan dalam pembuluh darah. 3. Antibodi bisa terikat pada sel darah merah dan menyebabkan sistem kekebalan menghancurkannya
dalam suatu reaksi autoimun. 4. Kadang sel darah merah hancur karena adanya kelainan dalam sel itu sendiri (misalnya kelainan bentuk dan permukaan, kelainan fungsi atau kelainan kandungan hemoglobin). 5. Penyakit tertentu (misalnya lupus eritematosus sistemik dan kanker tertentu, terutama limfoma) 6. Obat-obatan (misalnya metildopa, dapson dan golongan sulfa). (Sylvia, 2006). BAB III KESIMPULAN 1. Kadar bilirubin total probandus normal karena kadar bilirubin total sebesar 0 mg/dl. 2. Kadar bilirubin indirek probandus menunjukkan nilai yang tidak normal, yaitu sebesar -1 mg/dl. 3. Aplikasi klinis untuk kadar bilirubin serum adalah : a. Sirosis hepatik b. Anemia Hemolitik