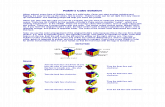14104922
-
Upload
lilik-iik-husada -
Category
Documents
-
view
39 -
download
5
Transcript of 14104922

PARADIGMA POSITIVISME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESLA
Oleh : Yusrivadi Dosen Fakultas Huk8um UNDIP Semarang
Abstract.
In the reL:nt practice of high education of law, dogmatic jurisdiction paradigm, which means positivistic, is dominant. Consequently, there is a tendentious perspective that law is only about malting rules. Law is something to implement but does not necessarily talte equality and advantages to the society into account. Law and reinforcement discussion just evolve about what is right and what is not, what is wrong and what is not, and other prescriptive forms. Thus, the normutiwe approach of positivists who occupy either jurisprudence field or legal studies tends to claim that positivists' research techniques are the only ways studying law.
Kata kunci : I ' a r a d i p , Positivisme, Impliltasi, Hulum.
, A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Tulisan ini untuk mei~gungkap sesuatu yang diyakini dari hasil
perenungan dan pemikiran yang cukup panjang. Awalnya antara lain dimulai pada waktu diselenggarakan sebuah diskusi Panel "Membangun Sinergi Pendidikan Tinggi Dengan Mitra Kerja" (2003) .' Diskusi panel ini diselenggarakan karena ada "kerisauan" dwia pendidikan tinggi kita yang bermula karena rendahnya relevansi pendidikan tinggi, sehingga out put yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Rendahnya relevansi pendidikan tinggi tersebut, ditemui juga pada pendidikan tinggi hukum kita, sehingga diasutnsikan berimplikasi pada penegakan hukumnya. Penegakan hukum di Indonesia, sering disebut sebagai penegakan hukum yang tak pernah nenghasilkan sesuatu yang maksimal, sehingga muncul berbagai kritik yang dialarnatkan kepada para penegak hukum.
- -
' Diskusi panel tersebut diseletlggarakan atas kerjasama Asean Fundation dan Undip dalam rangka Peringatan D;es Natalis yang ke 46.
. l u m l Hukztm, Vol. XIV, No. 1, April 2004 9

Sebagai 'seorang yang terlibat dalam pendidikan tinggi hukum, diskusi panel tersebut telah melahirkan kerisauan baru. Terlebih apabila dikaitkan dengan model pendidikan hukum yang telah "mentradisi" di Indonesia. Model pendidikan hukum yarlg dijalankan, selalu berlangsung lebih berat menuruti dalil-dalil logika deduksi (formal). Kaidah-kaidah hukum positif (menggantikan asas-asas moral yang itnplisist) dipraktikkan dala~n fungsinya sebagai pren7is-pren~is mayor in abstracto yang kebenaran dan keabsahannya tak lagi boleh dicabar. Kemudian melalui penyimpulan deduksi, melahirkan premis-premis conclusio. Dalam penegakan hukum, cara ini kemudian dipakai sebagai dasar pembenar keputusan peradilan in concrete. Keniscayaannya pun bukan keniscayaan objektif yang bekerja di slam etnpiris melainkan kepastian
I hukum yang hendak diupayakan realisasinya melalui sanksi-sanksi kekuasaan. Dalam model ini, tidak mengenal silogisme induksi dalam
1 prosedur-prosedur penerapannya, sehingga apa yang disebut ilmu I hukum sampai pada taraf ini bukanlah ilmu hukum yang berkualifikasi
sebagai sains.'
B. RUANG LINGKUP DAN PERMASALAHAN POKOK Permasalahan pokok tulisan ini yakni, kaitan antara paradigm
positivisme dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Secara lebih spesifik, pennasalahan pokok tersebut dirumuskan
sebagai berikut : a. Apakah yang dumaksud dengan paradigma positivisnle tersebut? b. Bagaimanakah implika-i paradigma positivisme tersebut terhadap
penegakan hukum di Indonesia ?
C. PEMBAHASAN a. Paradigma Positivisme.
Sebelurn membahas tentang apa yang dimaksud dengan paradigma positivisme, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian paradigma. Untuk ini komunitas ilnluum pa& umumnya mengacu pada pokok-pokok pikiran Thomas S. Kuhn3 Fecara etimologis, paradigma berasal dari kata-kata dalam bahasa Yunani para ( "di sanlpiug", atau
Soetandyo Wignyosocbroto, Hukum : Paradigma, Mclodc dan Dinamika Masalahnya, Len~baga SLudi dm Advokasi Masyar;ik;~t (ELSAM) d;ln Pcrkumpulan w ~ t u k Penibal~an~an Hukum Bcrbasis Mnsy;lrnkal dan Ekologi (HUMA), Jakarla, 2002, hal. 19.
Kuhn, Tho~uas. S. 9 2 The Slrucll~re uJ Scier~liJic Re~~olulio,rs. Chicago University of Chicago Prcss.

"berdampingan") dan deigpma ('contoh"). Oleh Thomas S. Kuhn, paradigma juga disebut contoh (exemplar) atau " matriks disipliner" (disciplinary matrix). Sesuai dengan makna deigma atau exeml~lar, paradigm memang merupakan semacam model yang dijadikan contoh oleh para ilmuwan yang melakukan kegiatan keilrnuwannya di dalam paradigtna itu. Selaras dengan arti "matriks" dan " disiplin", paradigma merupakan kerangka keyakinan ( belief framework) atau komihnen intelektual yaug metnberi batasan tentang niasalah dan prosedur serta 1 metode penyelesaiannya. Jadi paradigma ialah model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuwannya untuk menentukan jenis-jenis I
persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang baga:mana penggarapan itu harus dilakukan, Model ini
!
tersirat dalam asumsi-asumsi dasar yang menjadi tumpuan karya I,
monumental- seminal dari (sejumlah) jenius di bidang ilmu tertentu. !,
"Monumental" berarti " raksasa", "agung", atau "sangat hebat" luas dan dalamnya cakupannya. "Seminal" berarti bersifat mengilhami arau , n~emicu lahirnya karya-karya lain yang diturunkan dari, atau mengacu ke, karya yang paradigniatik it^.^
Paradigm dapat lahir bersama (sejumlah) teori dan tersirat dari, serta dirnengerti nlelalui, pemahaman atas teori itu, tetapi ia sendiri berada pada aras metateoritik, dan pada dasarnya tak terartikulasikan. Ia diterima oleh para ilmuwau dan dijadikan pegangan di dalam mereka berkiprah di bidang ilmunya, karena mampu menghadirkan ketertiban di dalam dunia ilmu -yang sedang kacau dilanda krisis besar. Krisis ini , .
muncul dari akumulasi anol~~ali, dari kian menyeruaknya banyak gejala/peristiwa yanj: tak dapat dijelaskan secara memuaskan dalam terang paradigma lama yang nmih berlaku. Ini terjadi dipenghujung periode ilmu n o m d , ketika sudah terlalu banyak " teka-teki" yang terpecahkan dengan ancangan ( approach ), metode, teknik, dan prosedur yang berturiipu pada paradigma yank masih bertahan.'
Manakala d;runut ke belakang, mqdel pendidikan hukum di Indonesia dewasa i n , sebenarnya berikhwal dari paradigma positivisme. Paradigma ini kemulian mendominasi ajaran hukum ya:~g bersikukuh menuruti ' konfigura: i ajarannya yang libertarian dan individuaiistis. Paradigma positivisme ini, dijadikan sebagai pegangan berkiprah para
-. 4 LiekWilardjo, Perarr Paradig~~ro Dolonr Perkenrbonp Ihru. Makalall,
Siillposiu~~i Nasional tentang Paradignu 11111u Huku~n Indonesia, ITNDIP, Selllarang, 1998.
Ibid.
Jzi?nnl Hz~kunz, Vol. XrV, No. I April 2304 , 11

I
ilmuwan hukun~' dan yang kemudian beri?plikasi pula pada penegakan hukumnya.
Diakui atau tidak, masyarakAt sekarang bolehlah disebut sebagai tnasyarakat yang penuh penyimpangan, kalau tidak boleh disebut sebagai a n o n i Sementara itu kajian-kajian hukum di lingkungan akademis, hanya tnenyoroti hal-ha1 konvensional, seperti institusi, sistem dan perilaku sehingga tidak ada yang menyoalkan kontribusi pendidikan hukutn terhadap kejadian serta praktik-praktik negatif dan destruktif terhadap hukum di Indonesia kini. Apakah pendidikan hukum harus ada di luar carut-rnarut hukum dewasa ini dan tidak ada hubungan sama sekali atau kita perlu membawa pendidikan hukum ke tengah masalah bangsaa6 Model pendidikan hukum yang diselenggarakan, menjadi tak aneh lagi ~nanakala dianggap tidaii metnpunyai kemampuan n~emberikan penjelasan (terlebih penyelesaian) persoalan yang timbul di masyarakat. Di sinilah mulai tinbul suatu kerisauan yakni berupa "kesangsian validitas" tentang apa yang selarna ini dijalankan. Untuk itulah maka melalui pemahaman paradigma yang dipaparkan sebelumnya, maka sudah saatnya untuk n~en~ikirkan kembali paradigma iltnu hukun~ Indonesia yang kita kukuhi selama ini. Dari pemahaman yang didapat, dapat dipakai untuk menemukan paradigma baru yang seharusnya dijadikan pegangan berkiprah para ilrnuan hukum sehingga berdampak positif terhadap penegakan hukumnya.
b. Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam ilmu hukum dijutnpai
adanya berbagai aliran. Oleh karena itu tidak boleh ada tempat untuk mengklaim aliran yang dipillh dan dianut sebagai satu-satunya aliran yang paling benar. Diakui atau tidak, di antara komunitas hukum baik yang akademisi maupun yang praktisi terdapat perbedaan paradigmatik dalam meniandang hakikat hlkum. Implikasinya, bahwa cara,cara yang dijalankan, dikembangkan d m tujuan-tujuan yang ingin dicapai pun juga menjadi berbeda. Di sadari sejak awal bahwa dalam ilmu hukum, terdapat berbagai aliran pernikiran ( schools of thought ) yang secara tradisional-konvensicnal disebut dengan istilah n~azhab-mazhab hukum (schools of jurisprudence).
Satjipto Rahardjo, Di ntanakah Pendidikan Hukum ?, Kolrlpas 8 April 2004, hal. 5.
12 Paradigma Positivisrne Thd Hk. Di Indonesia - Yusriadi

Dalarn iltnu hulium, biasanya dipcrgunakan beberapa metode pendekatan yaitu sebagai berikutl : 1. Yuridis - dogmatis, yaitu suatu cars pendekatan di mana diolah
peraturan-peraturan hukum dengan logika aka1 saja dan selanjutnya pengertian-pcngertial~ hukum terscbut diberlakukan hanya dengan aka1 logika tanpa lnemperhitungkan kenyataan dan keadilan (dogma adalah ajaran atau pendapat yallg diterima begitu saja tanpa menyelidiki benar tidaknya);
2. Kausal-empiris/sosiologis, ialah suatu cara pendekatan yang menggarap peraturan-peraturan hukum dengan cara menipelajari sebab akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataa11-kenyataan sosial dalam masyarakat;
3. Filosofis/idealis/ideologis, yaitu metode pendekatan yang menggarap peraturan,peraturan hukum dengan lnempelajari hubungannya dengan hal-ha1 yang timbul dari ide-ide atau cita-cita atau hasil pen~ikiran manusia.
Dalam perkembangannya, ditemui bahwa masing-masing metode tersebut cenderung untuk menempati dominasinya sendiri-sendiri baik dalam lnenentukan batas-batas ilmu pengetahuan huku~nnya maupun metode yang digunakan. Masing-masing mazhab tersebut mempunyai paradigma, konsepsi, teori dan metodologinya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Para penstudi hukum, secara sadar tnauvun tidak, sesungguhnya telah memilih paradigma, konsep, hingga teori yang akan dikukuhi dan dikembangkan. Tak mengherankan kalau ha1 ini senlpat menlancing pendapat orang, khususnya di luar komunitas ilmuwan hukutn unruk nxngatakan bahwa seolah-olah dalam iltnu dan profesi hukum di Indonesia terdapat berbagai paradigma yang paralel dan sama-sama berfungsi. Bahkan secara ekstrem ada yang ~nengatakan bal~wa dalam ilmu hukum di Indonesia sampai sekarang ini' belum terbentuk konsensus mengenai konsep-konsep fundamental, sehingga dalam ilmu hukum tak ditemukan paradigma seperti dalam fisika misalnya,
Telah . dikemukakan ' bahwa paradigma ialah kon~itmen intelektual yang dipegang teguh oleh ilmuwan di bidang tertentu dalam kegiatan keilmuannya. Dalap bahasa yang tidak "keren" , "komitmen intelektual" ialah keyakinan (belief). Dan keyakinan artinya penerimaan
' ROZUIY Hmitijo Soemitro, Pengantar Ilnm Hukunr, Scniarang, UNDIP Tanpa talml, hal. 5.
Jurnal Hukunz, L bl. XIV; No. I , April 2004 13

keberadaan "obyek-obyek" (n~isalnya hal-ha1 di luar kita, pikiran atau aka1 budi lain, Tuhan da11 sebagain~a) atau persetujuan terhadap kebenaran dalil-dalil (misalnya yangberupa pernyataan keilmuan, moral, aesthetik, atau metafisik). Ke~akinan terhadap objek sering seketika dan tidak ~nelalui/muncul dari proses penyimpulan; sebaliknya, keyakinan terhadap dalil biasan~a berlandaskan perenungan dan penyimpulan.s Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam ilmu hukum belum ada kerangka ke~akinan yang berperan nle;lgatur dan menerbitkan penelaahan dan pemecahan masalah. Belum 'ada ordering belief frameworlc yang oleh Thomas S. Kuhn disebut paradigma. Sinonim dari pendapat itu mungkin dapat dikatakan bahwa ilmu 1;Lukurn Indonesia dewasa ini berparadigma ganda? Masing-masing paradigma itu adalah paradigma yuridis-normatif, paradigma sosiologis, dan paradigma ideologis/fil~sofis.~~ Selanjutnya manakala masing-maiiing paradigma tersebut dikukuhi secara sendiri- sendiri, memisahkan diri satu sanm lain atau bahkan yang satu mengkesampingkan yang lain, maka akan mempunyai implikasinya tersendiri terhadap penegakan hukum idi Indonesia, ' bahkan implikasinya lebih bersifat negatif dari pada positifnya.
Munculnya dominasi masing-masing paradigma tersebut, sebenarnya dapat "dirunut" dari adanya perbedaan paradigmatik sebagai pandangan filsafati yang mendasari pemikiran ilmuwan hukum tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh ilmu hukum. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa teori-teori yang dibangun dan dikembangkannya pun berbeda satu sama lain, bahkan mungkin dipandang sebagai ha1 yang bertentangan. Sebagai kelanjutan dari adanya perbedaan paradigma tersebut, maka metode yang digunakan untuk memahami dan rnenerangkan substansi disiplin ilmu hukumpun juga berbeda.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa n~etode-metode itu adalah, pertama metade yuridis-normatif yang memandang hukum sebagai sistem peraturan-peraturan yang abstrak, tersusun secara logis, sistematis dalam suatu undang-undang, sehingga siap untuk diterapkan.
' Liek Wilardjo, -Peran Paradigma Dalanr Perkenrbangan Iltnu. Makalah, Siinposiuin Nasional tentang Paradigma Ilnlu H~ki~m Indonesia, UNDIP, Seinarang, 1998, hal. 5.
Lihat dan bandingkan G Ritzer, Sosiologi Ilnlu Pengetahua17 Berparadignra Ganda, terjemallan Aliinandan, Rajawali, Jakarta, 1985
lo Satjipto Rahardjo, Il~nn Hukuln, Citra Aditya Bakti, ~andund, hal. 5
14 Parndignin Positivisnle Thd. Hk. Di Indonesia - Yusrindi

Fokus perhatiannya adalah, bahwa hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang dapat dibicarakan sebagai obyek tersendiri dan terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-ha1 di luar peraturan- peraturan tersebut. Studi yang dilakukan n~enjadi tekstuaI, bukan kontekstual. Dalanx metode ini, tidak menghiraukan apakah hukum mewujudkan n i k a i d a i tertentu atau apakah hukum itu dituntut untuk nxencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang utama bagi metode ini adalah lebih menitik beratkan pada seni menemukan dan menerapkan aturan- aturan dalam suatu kasus (in concrete) dan yang kemudian sering dikenal sebagai mazhab positivisme. Kedua, bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihanqa akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dengan yang pertama, maka metode ini mengkaitkan hukum pada persoalar, persoalan riil masyarakatnya, keparla usaha untuk mencapai tujuan. tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Untuk kepentingan yang denxikian ini, maka dibutuhkan pendekat-an ilmu-ilmu sosial (sosiologi) dalam mempelajari dan memahami hukum. Hukum selalu berurusan dengan pertanyaan law as whdt it is Cfunctioning) in sockty. Kalau toh ketertiban sosial harus dianggap berkaitan erat dencan kaidah-kaidah sosial (baca kaidah hukum), maka bukan kaidah-kaidah itu sendiri yang dikukuhi sebagai prioritas studi melainkan jug;[ aktualisasinya berikut variabel-variabel kondisional danlatau penyebahya. Ketiga, metode idealis/filosofis yang senantiasa berusaha untuk menguji hukum yaitu bahwa hukum harus nxewujudkan nilai keadilan. I'
~ e n ~ u n ~ ~ u l k d n salah satu metode dan terlebih mengkesampingkan nxetode yang lain, tidak niembantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan benar mengenai hukum. Idealnya adalah bahwa masing-masing paradigma tersebut, entah normatif, sosiologis maupun yang filosofis, bukan untuk mengabaikan bahkan menggantikan nxetode pendekatan-pendekatan yang lain. Paradigma normatif, juga yang sosiologis dan filosofis, masing-masing seharusnya tidak berkehendak mengklaim diri sebagai satu-satunya paradigma yang sah dan dikukuhi dalam kajian-kajian ilmu hukum.
Dalam praktik pendidikan tinggi hukum dewasa ini, terkesan kuat bahwa paradigma yuridis dogmatis yang berarti positivistik, lebih
I I Satjipto Rshardjo, 1999, Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 : 12, Achtnad Ali, 1998
Jlirnnl Hz~kunl, Vol, XIK No. I , April 2004 15

didominankan. Konsekuensinya, cenderung berat untuk memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang- undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi mhsyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskripstif. Yang terjadi adalah bahwa pendekatan nortnatif kaum positivistis (paradigm positivistis/positivisme) baik yang berkhidmat di lingkungan jurisprudence maupun di ~ingkungan legal studies, terkesan mengklaim bahwa paradigma dan metode serta teknik-teknik penelitiannya adalah satu-satunya yang sah untuk mempelajari hukum. Bahkan ha1 yang demikian ini dan yang selanjutnya boleh disebut model pendidikan hukum, leb~h cenderung ke upaya pengajaran ayilikasi teknis semata, sehingga dimungkinkan ~nenjadi studi tentang bagai~nana hukum harus ditelusur dan diterapkan serta ditafsirkan menuruti doktrin positivisme. Mengikuti tradisi reine rechtskhre atau rechts-geleerdheid atau jurisprudence, ilmu hukum yang diajarkan di fakultas-fakulras hukum di Indonesia sesungguhnya tidaklah terbilang ke dalam kerabat sains, ilnlu hukum tidaklah ditradisikan dalam alur sains sebagai kgal science. Sekalipun ilmu ini memang benar-bendr bekerja dengan berpangkal dari,- serta herseluk beluk dengan proposisi-proposisi hukum yang positif, akan tetapi apa yang dimaksud dengan p o s h c legal di sini bukanlah ha i l observasi-observasi danlatau pengukurnn-pengukuran atas gejala- gejala dunia en~piris, melainkan hasil positive judgement- baik in abstracto maupun in concreto- oleh otoritas-otoritas te:tentu yang berkewenangan. Kata "positif .di sini nyata kalau lebih dekat ke m k n a "non-n~oral" atau "netral" daripaaa ke makna "empiris" atau "sesuatu yang observable". '"tudi yang demikian ini juga membawa implikasi pada praktik penegakan hukunmya yang di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman bewuste rechtspolitiek penguasa-penguasa kolonial sampai era Chde Baru. Bahkan jauh sebelu~nnya dalam sejarah ajaran hukum, secara klasik contoh dominasi yang demikian ini dapat ditunjukkan n~elalui apa yang disebut begriffjurisprudew, yaitu suatu ajaran yang hanya memperhatikan pengertian (begriff) dari undang- undang saja. Akibatnya rasa keadilan dan realitas dalam masyarakat tak
12 Soetandyo Wigiijosoebroto, Hukuiii : Paradigma, Mctode dm Di~iamika Masalahnya, Lenibaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkunlpulen untuk Pe~nbalian~an Hukuru Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta, 2002. 108-109.
16 Paradigma Positivisnze Thd Hk. Di Indonesia - Yzrsriadi

pernah tersentuh, bahkan terabaikan demi pengertian-pengertian hukum itu sendiri.13 Paradigma yang selanjutnya dijadikan senlacam model para ilmuwan hukum di Iqdonesia dalam n~elakukan kegiatan keilmuwannya di dalam paradigma tersebut, tidak hanya akan melahirkan konsep-konsep epistemologis yang berbeda, akan tetapi juga metode-metode berpikir dan metode-metode penelitian yang berbeda pula. Dalam konteks penegakan hukum, ha1 ini tentu saja membawa imnplikasinya tersendiri dan lebih bersifat negatif dari pada positifnya. Ini sudah sering terjadi dan mudah-mudahan bukan karena kecemburuan atau koinpetisi status , melainkan bersebab pada tiadanya pengenalan terhadap sistem konseptual masing-masing, sehingga tidak ada kemanlpuan di antara mereka untuk "saling menyapa " secara konstrulitif. I
i IMam penegakan hukum meskipun sama-sama mengaku dirinya
I sebagai r egara hukurn (rechtsstaat), sebenarnya di manapun di dunia ini, tidak ads standar yang absolut. Konsekuensinya, meskipun sama-sama sebagai ncgara hukurn yang nlodern, dapat juga terdapat berbagai tipe penegakar hukum. Dianalogkan dalam permainan sepak bola misalnya, meskipun &lam setiap kesebehsan telah digunakan suatu standar ynng baku dengan tujuan agar keselrelasannya menang, akan tetapi toh dapat juga munc~ll gayalstile yang oerbeda-beda. Ada gaya totaal voetbal di Belanda, cattenacio di Itali dan Samba di Brasilia.I4
Tidak adanya keharusan absolut bagi tersedianya standar yang baku dalam design penegakan hukum, mengantarkan saya untuk - merenung dan berpkir sehingga sampai pa& suatu keinginan melonearkan gagasan yang boleh disebut baru yakni perlunya ada t~pefstile petygakan hukum yang salna sekali berbeda dengan design penegakan huku~n yang selalna ini dikukuhi, menstradisi dan seolah- olah sebagai :satu-satunya yang terbaik, schingga mau tidak luau harus dijalankan. Gagasan yaug saya ajukan, sebenarnya bukanlah satu- satunya, sebah sebelunmya oleh Satjipto Rahardjo misalnya, pernah dimunculkan suatu gagasan yang tentunya di samping baru juga istimewa, ialah digunakannya istilah tipe Pencgakan Hukum Progresif. l5
Mengenai g a p a n ini, melalui tulisan ini ini ingin saya tambahkan
'' Ronny Mnnitijo Soemitro, Perrganlar Ilnru Hukunr, Semarang, UNDP Tanpa taliun. ha1.45.
14 Satjipto Raliardjo, 2003. I S Satjipta Raliardjo, Di Manakah Pendidikan Hulkurn ?, Kompas 8 April 2004,
hal. 5.
Jurnnl Hukunz, Vol. XIK No. I , April 2004 . 17

1\1'11 ~~~ ~~ i~:'! '
1, " menjadi ripe Penegz'kan Hukum Progresif Yang Revolusioner. Kata revolusioner sengaja ditambahkan untuk gagasan tipe penegakan hukum yang saya ajukan, sebab tanpa tambahan kata revolusioner diyakini bahwa agenda reformasi yang sekarang sedzng digulirkan tidak akan sampai menuju pada aras perubahan secard revolusioner dala~n semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tatanan kehidupan hukunmya. Manakala ha1 ini tidak dilakukan, dikuatirkan bahwa hasil yang dicapai dalam penegakan huku~n tetap diyakini menjadi tidak maksimal. Untuk n~erealisisr gagasan tentang tipe penegakan hukum progresif yang revolusioner tersebut, maka harus ada suatu lon~vatan baru tentang paradigma ilmu hukum Indonesia. - - Lompatan paradigma ini tentunya dimulai oleh ketiadaan dominasi paradign~a ilmu hukum yang selama ini kita kukuhi sebagai suatu yang benar. Inilah yang oleh Thomas S. Kuhn disebut sebagai revolusi keilmuwan.
Dengan adanya suatu lompatan baru dari adanya dominasi paradigma positivist,~e yang yuridis dogmatis/yuridis normatif ke paradign~a yang baru dalaln penegakan hukum mendatang, diharapkan bahwa para penegak hukum (advokat, polisi, jaksa dan hakinl) tidak lagi terjebak pada absolutisn~e yang sangat yuridis dogmatis. Apabila ha1 ini tetap dikukuhi sebagai satu-satunya paradigma dalam model penegakan hukum , kita tak perlu heran kalau penegakan hukum di Indonesia selama ini tak pernah tnenghasilkan sesuatu yang memuaskan. Para penegak hukum telah terjerat pada formalitas atau prosedur hukumnya semata, sehingga mengabaikan substansinya yaitu keadilan dan ke~nanfaatan bagi masyarakatnya. Apabila ha1 ini yang terjadi, maka tak mengherankan apabila dalam realitasnya, para pelangga~ hukum tetap dapat hidup bebas di masyarakat seolah-olah tanpa terbebani rasa salah atau melanggar hukum. Para pelanggar hukum dapat berlindung di bawah panji-panji dogmatis : Setiap orang dianggap tidak bersalah selama kesalahannya itu belurn dibuktikan di depan pengadilan. Akibatnya yang lebih jauh adalah, terjadi demoralisasi hukum, yaitu pernisahan secara tajam antara hukum dan moral. Untuk itulah nmka paradigma baru ini senantiasa harus melihat hukum dalam kebenarannya secara substansial, ialah n~eletakkan inti ;huklim dalam kaitan moral atau n~oralitas, n~isalnya keadilan. Contoh yang baik mengenai ha1 ini adalah apa yang telah dilakukan Amerika Serikat yang sekalipun amat liberal, toh tetap perlunya inen~bicarakan the conscience of the a u ~ t (nurani pengadilan) .
~ i , ~ , , ! 18 Parndignm Positivisnw Thd. Hk. Di Indonesia - Yusriadr

Dalam kaitannya deng,~n model pendidikan tinggi hukum, maka ~nulai diperlukan adanya pcrubahan paradigma. Ditemukan bahwa paradigma pendidikan tinggi, hukum yang selama ini digunakan dan dikukuhi, telah menjadi faktor penyebab doniinan dalam inemberikan kontribusinya terhadap praktik penegakan hukunmya. Paradigma baru yang dapat ditaws.rkan/diajukan untuk dijadikan sebagai pegangan berkiprah para ilmuwan dan praktisi hukum adalah paradigma terpadu yang memandang bahwa masing-masing paradigma yang ada p k n i normatif, sosiologis dan filosofis hendaknya rligunakan.secara terpadu, tidak ada dominasi paradigma yang satu t:rhadap yang lain. Dengan paradigma terpadu ini, berarti para penstudi hukum dan para penegak hukum akan memandang hukum dalam demensinya yang lengkap yakni demensi normatif (nilai dasar kepastian) , sosiologis (nilai dasar kegunaan) maupun dalam demensinya yang Alsafati (nilai dasar keadilan). Dengan paradigma terpadu inilah dimungkinkan tak ada lagi kecemburuan dan terlebih kompetisi status di antara para profesi hukum '
baik yang akademisi maupun yang praktis. Di sinilah dimungkinkan bagi mereka untuk bersama W i n g menyapa" secara kontruktif, bukan destruktif dan inilah yang dalam tulisan ini saya sebut sebagai progresif revolusioner, sehingga harus ada unsur perubahan secara radikal dan mendasar. Para penegak hukum harus melihat masing-masing nilai dasar tersebut sebagai satu kesatuan nilai dasar yang utuh dan terpadu, bukan sebagai nilai yang berditi sendiri-sendiri terlepas/terpisah satu sama lain. Dengan demikian, didapat pemahaman bahwa keabsahan berlakunya hukum harus dipandang baik secara yutidis, sosiologis maupun secara filosofis. Sah berlakunya hukum dari segi kepastian saja hanyalah merupakan salah satu as$ek sahnya berlakunya hukum. Bahkan keabsahan yang demikian semata, tidak begitu saja akan memenuhi rasa keadilan apalagi rasa kebutuhan masyarakat. Kebutuhan niasyarakat, tampaknya m tampaknya merupak~nasional, dan ha1 ini merupakan kebutuhan bangsa termasuk kebutuhan untuk memerangi kejahatan entah itu dalam bentuk korupsi, kolusi maupun nepotisme. Meniang diakui, bahwa dalam meramu ketiga nilai dasar hukum tersebut sebagai satu kesatuan adalah sulit, lebih-lebih mengimple~nentasikann~a dalam penegakan hukum. Akan tetapi ha1 ini adalah suatu keharusan, bukankah belajar hukum terlebih menegakkannya adalah merupakan pergulatan kemauusiaau ?.
JIII; April 2004 19

D. KESIMPULAN
Diakui atau tidak, terdapat kerisauan dalam pendidikan tinggi hukun~, terlebih dalam lnasalah penegakan hukumnya. Anehnya, kerisauan ini tak begitu saja dengan mudah dicarikan jawabnya oleh ilmu hukum atau oleh hukum itu sendiri. Dalam pendidikan tinggi hukum maupun praktik hukum, diperlukan ilmu dan perspektif lain, bukan untuk mendominasi melsinkan untuk melengkapi, misalnya sosiologi dan filsafat, yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu baru yakni sosiologi hukum dan filsafat hukum. Kecenderungan ini, tak perlu nxnggelisahkan para ilmuwan hukum yang mapan alias positivistis serta penganut pahatn legisme dan formalisme,
Diakui bahwa apa yang dikemukakan melalui tulisan ini, mungkin dapat menimnbulkan pen~ikiran baru, bahkan mungkin berbeda. Akan tetapi haruslah dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Suasara akademis adalah suasana yang memberi ruang terhadap perbedaan pemikiran bahkan keragaman cara pandang terhadap objek yang digelutinya. Cara pandang inilah yang sebenarnya tidak statis, melainkan
1 1
I dinamis dan akan memperkaya pemahaman kita terhadap hukum. Cara
I ' ! I pandang inilah yang dapat menxbantu melnandang fakta, terlebih fakta
I : ! bukanlah sekedar yang hanya terlihat. Di sinilah pada akhirnya harus l l disadari bahwa hukum dalarnpraktiknya tidaklah senetral seperti yang l I i '
1 , ' dipersangkakan oleh paradigm positivisme.
20 Pcrrndign7a Positivistne Thd. Hk. Di Indonesia - Yusriadi

DAFTAR PUSTAICA.
Anonim, Wajah H u l u m di Era Reformasi (Kumpulan Karya Iltniah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SHO, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. I
Ali, Achmad, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yarsif Watan~pone, Jakarta.
Kuhn, Thomas. S., T h e Structure of Scientific Revolutions. Chicago Uiiversity of Chicago Press, 1962.
Soenutro, Ronny Hanitijo. Pengantar Ilmu H:nkum, Semarang, UNDIP Tanpa tahun.
Rahardjo, Satjipto,l989, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
--.,.--,-~,--~-~-..~~- , Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan 'Sosiclo&, Bandung, Sinar Baru, 1992.
-.-,---.-.,--.+~~,~-~~- , Hukum, Masyarakat dun Pembungunan, Bandung, Alumni, 1976.
-.--------.-------------, Hukum dun Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Bandung, Alumni, 1979.
---...---.--,.-*...--. , Indonesia In$nkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas, 15 Juli 2002.
Ritzer, G. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terjemahan Alimandan, Rajawali, Jakarta, 1985
Suriasumantri, Jujun. S. Fikafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Pustaka, Sinar Harapan. Jakarta. 1998.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukun~ : Paradigma, Metode dun Dinarnika Masalahnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jak: rta, 2002.
J~rrnnl Hukunz, Vol. XIY, No. I , April 2004 ' 2 1
, I ! _ -. .--:--a

I Wilardjo, L. Realita dun Desiderata. Duta Wacana University Press.
Yogyakarta, 1990.
--------Peran Paradigm Dalam Perkembangan Ilmu. Makalah, Si~nposium Nasional tentang Paradigm Illnu Hukum Indonesia, UNDIP, Semarang, 1998.
Yudho, Winarno dkk (Ed) , Sosok Guru dun Ilmuwan Yang K~itis dun
1 Konsisten, Kurnpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
I (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta, 2002,