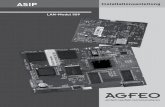Modul 1
-
Upload
teuku-fadli-sani -
Category
Documents
-
view
69 -
download
0
Transcript of Modul 1
Blok IV Modu l 1 PERLENGKAPAN
KEHIDUPAN SELULARSel Sebagai Unit Kehidupan TubuhThe basic unit of life in our body is the cell. Each organ is a collection of many different cells that are united by a variety of support structure between cells. This paper will discuss many things about the characteristics of cells, organelles within cell, and about tools to view the cell.
T. Fadli Nazwan Sani110610032Blok IV Modul 1
BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Jauh sebelum Robert Hooke mempopulerkan istilah sel, beberapa ahli filsafat Yunani telah mengemukakan pandangannya berkenaan dengan penyusun tubuh makhluk hidup. Aristotles dan Paracelcius telah mengemukakan bahwa tubuh semua hewan dan tumbuhan tersusun atas elemen-elemen sederhana. Elemen-elemen sederhana tersebut secara bersama-sama membentuk struktur makroskopis makhluk hidup (De Robertis et al., 1979). Belakangan, elemen-elemen sederhana tersebut dikenal dengan istilah sel (dari bahasa Yunani, yaitu Cella atau Cellula yang berarti ruang atau kamar kecil). Sebuah sel dapat berperan sebagai suatu organisme yang dikenal sebagai organisme uniseluler atau organisme bersel satu, misalnya berbagai jenis protozoa. Sel dapat tersusun berkelompok dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis jaringan dan membentuk organ. Selanjutnya, beberapa organ membentuk sistem organ dan pada akhirnya beberapa sistem organ, secara bersama-sama membentuk suatu organisme. Organisme yang dibentuk dinamakan organisme multiseluler. Pemahaman mengenai sel baik dari aspek ultrastruktur maupun dari aspek fungsionalnya tidak terlepas dari hasil kerja keras sejumlah pakar ilmu pengetahuan. Penelitian-penelitian terus dikembangkan, bahkan dari berbagai sudut pandang dan melibatkan disiplin ilmu-ilmu lain. Penemuan mikroskop sederhana hingga mikroskop elektron telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam perkembangan biologi sel. Kemajuan yang dicapai di bidang kimia organik dan biokimia telah mengantar umat manusia pada pemahaman sel yang lebih mendalam hingga pada tingkatan yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Perkembangan pengetahuan di bidang genetika molekuler dan disiplin ilmu yang lain telah mengantar umat manusia pada pemahaman hingga tingkatan rekayasa genetika yang sangat menakjubkan. Melalui pendekatan yang lebih holistik dan integratif, kini biologi sel tampil sebagai sebuah ilmu yang mampu menjadi dasar bagi pengembangan ilmu-ilmu hayati lainnya. Sebagai pemahaman awal dapat dikatakan bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan pada tubuh manusia. Setiap organ merupakan kumpulan dari berbagai sel berbeda yang disatukan oleh berbagai struktur penunjang antar sel. Setiap jenis sel beradaptasi secara khusus untuk melakukan satu atau beberapa fungsi tertentu. Dalam menjalankan fungsinya sel disokong dengan organela- organela yang mempunya fungsi masing-masing dalam sebuah sel. System kerja dari setiap organela berkaitan satu
sama lain, sebagai contoh ribosom yang bertugas sebagai tempat sintesis protein dalam sel akan dibantu oleh badan golgi yang berfungsi sebagai alat pengeluaran protein dan lendir dan apabila badan golgi rusak atau sudah tua nantinya akan dicerna oleh lisosom agar tidak mengganggu system kerja organela sel. Rumit dan kompleksnya pembahasan tentang sel serta keterkaitannya dalam proses metabolisme tubuh ini menuntut mahasiswa untuk mampu memahami hal- hal yang berkaitan dengan sel, jenis- jenis sel yang berpengaruh dalam kehidupan, organela- organela yang terdapat dalam sel, serta penggunaan mikroskop sebagai alat untuk dapat melihat keberadaan sel. Pelajaran sel ini merupakan materi dasar yang harus dapat dikuasai mahasiswa kedokteran agar mampu menjalani proses pendekatan klinis sebagai inti materi perkuliahan jurusan kedokteran.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sejarah dan Perkembangan Sel Sel merupakan massa protoplasma berbatas membran dengan sistem organisasi yang sangat kompleks. Sel bukan merupakan suatu bangunan statis, melainkan sebuah struktur yang sangat dinamis. Berbagai jenis aktivitas hidup yang berlangsung di dalam tubuh organisme pada dasarnya berlangsung di dalam sel dengan mekanisme sistem yang sangat harmonis. Aktivitas satu sel menunjang aktivitas sel yang lain membentuk suatu sistem yang sangat harmonis untuk menunjang sebuah kehidupan yang fungsional. Anthony van Leeuwenhoek (1632-1723), seorang yang berkebangsaan Belanda merupakan orang pertama yang menemukan mikroskop dan meneliti organisme mikroskopis seperti berbagai Protozoa dan Rotifera yang oleh Beliau diberi nama animanculus, berbagai jenis bakteri, meliputi bakteri basil dan bakteri spiral;. mengamati sperma pada manusia, katak, anjing, kelinci, dan ikan. Beliau juga mengamati pergerakan sel-sel darah di dalam kapiler kaki katak dan daun telinga pada kelinci.
Sumber : http://www.royalsociety.org/downloaddoc.asp dan http://www.tulane.edu/~wiser/cells/ Gambar 1. Anthony van Leeuwenhoek (1632-1723), dan mikroskop sederhana serta jenis protozoa hasil temuannya Marcello Malphigi (1628-1694), seorang berkebangsaan Italia merupakan orang pertama yang menggunakan mikroskop dalam mengamati sayatan jaringan pada organ-organ tertentu, seperti otak, hati, ginjal, limfa, dan paru-paru. Selain itu, dia juga
mengamati perkembangan embrio ayam. Dari hasil pengamatannya, dia menyimpulkan bahwa jaringan tersusun atas unit-unit struktural yang ia sebut utricles (De Robertis, 1988).
Sumber : http://www.crimezzz.net/forensichistory/images/MALPIGHI_marcello
Gambar 2. Marcello Malphigi (1628-1694) Robert Hooke (1663) merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah sel berdasarkan hasil pengamatannya pada sayatan sumbat gabus. Ia melaporkan bahwa sumbat gabus terdiri atas ruang-ruang kecil yang diberi nama sel (bahasa Yunani: Cellula yang bermakna ruang-ruang kecil).
Sumber : http://www.tulane.edu/~wiser/cells/ dan http://www.nndb.com/people Gambar 3. Ruang-ruang kecil pada sayatan sumbat gabus, R. Hooke (1663) dan mikroskop sederhana Rene Dutrochet (1776-1847), seorang yang berkebangsaan Perancis, melaporkan bahwa semua hewan dan tumbuhan terdiri atas kumpulan sel-sel globular. Pada tahun 1831, Robert Brown (1773-1858), seorang yang berkebangsaan Inggris, melaporkan bahwa sel-sel epidermis tumbuhan, serbuk sari, dan kepala putik mengandung suatu struktur yang konstan yang disebut inti. Pada tahun 1840, Johannes E. Purkinye (17871869), seorang yang berkebangsaan Cekoslovakia, memperkenalkan istilah protoplasma. Pada tahun 1861, W. Schultze menyatakan bahwa protoplasma
merupakan dasar fisik dari kehidupan. Protoplasma adalah substansi hidup yang berbatas membran dimana di dalamnya terdapat inti atau nukleus (Karp, 1984).
Sumber : http://clendening.kumc.edu/dc/pc/hitzig.jpg Gambar 4. Johannes E. Purkinye (1787-1869)
Sumber : http:// home.tiscalinet.ch/biografien/images/schleiden dan http://home.tiscalinet.ch/biografien/images/ Gambar 5. Mathias J. Schleiden(1804-1882), T(1810-1882). Schwann dan R. Virchow(1821-1902)
Pada tahun 1938, Mathias J. Schleiden (1804-1882), seorang ahli pengetahuan berkebangsaan Jerman, melaporkan bahwa tubuh tumbuhan tersusun atas sel. Secara terpisah, pada tahun 1839 Theodore Schwann (1810-1882) yang juga seorang ahli pengetahuan berkebangsaan Jerman, melaporkan bahwa tubuh hewan tersusun atas sel. Schwann kemudian mengusulkan dua azas yang dikenal dengan teori sel, yaitu: Semua organisme terdiri atas sel, dan sel merupakan unit dasar organisasi kehidupan. Sepuluh tahun kemudian R. Virchow (1821-1902) mengusulakn azas ketiga teori sel yang berbunyi: Semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya (Omnis cellula e cellulaI) (Sheeler & Bianchi, 1983). Kemudian Louis Pasteur (1908-1895) mengemukakan teori biogenesis yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari
makhluk hidup sebelumnya (Omne vivum e vivo). (Thorpe, 1984; Sheeler and Bianchii, 1983; dan Albert et al., 1984)
Sumber : http://art-random.main.jp/samescale/
Gambar 6. L. Pasteur (1808-1895)
Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan para ilmuwan tersebut diambil suatu kesimpulan, yaitu: sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup, sel merupakan kesatuan fungsional dari makhluk hidup, dan sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Namun, dalam lingkup yang lebih kompleks, teori sel mengandung makna (Villee et al., 1985), yaitu: 1. Semua makhluk hidup terdiri atas sel; 2. Sel yang baru dibentuk, berasal dari pembelahan sel sebelumnya; 3. Semua sel memiliki kemiripan yang mendasar dalam hal komposisi kimia dan aktivitas metabo-lismenya; 4. Aktivitas dari suatu organisme dapat dimengerti sebagai aktivitas kolektif, dan interaksi-interaksi dari unit-unit seluler bergantung satu dengan yang lainnya. 2.2 Jenis- Jenis Sel Berdasarkan keberadaan membran inti, sel dapat dibedakan menjadi: Sel Prokariotik Prokariotik dibangun dari kata pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi prokariotik berarti sebelum inti. Ini mengandung arti bahwa prokariotik bukan tidak memiliki inti sel namun materi inti tersebar dalam sitoplasmanya.
Sel Eukariotik Eu mengandung arti benar sedangkan karyon berarti inti. Jadi sel eukarioti adalah sel yang sudah memiliki inti sel dan sudah terlindungi oleh selaput yang disebut dengan membran inti. Tabel 1.1 Perbandingan antara sel Prokariotik dengan sel eukariotik No Pembanding 1 Contoh Organisme 2 Ukuran Sel 3 Metabolisme 4 Organela Prokariotik Bakteri dan ganggang hijau biru Umumnya 1- 10 m Anaerobik dan aerobik Sedikit atau tidak ada Eukariotik Protista, fungi, tumbuhan, dan hewan Umumnya 5- 100 m Aerobik Nukleus, mitokondria, kloroplas. Reticulum endoplasma, dll. Sangat panjang terdapat dalam inti sel Sintesis RNA terjadi dalam nucleus, protein disintesis dalam sitoplasma. Sitoskeleton tersusun dari filament protein Kromosom memisah melalui gelondong pembelahan
5 6
DNA RNA dan Protein Sitoplasma Pembelahan Sel
Sirkular dalam sitoplasma Disintesis pada beberapa kompartemen Tidak ada sitoskeleton Kromosom memisahkan diri oleh adanya pemisahan membrane plasma Umumnya uniselular
7 8
9
Organisasi Selular
Umumnya multiselular
Berdasarkan letak kromosom dan fungsinya, sel dapat dibedakan menjadi: Sel Somatis Sel somatis merupakan sel yang menyusun tubuh dan bersifat diploid. Sel Germinal Sel Germinal merupakan sel kelamin yang berfungsi untuk reproduksi dan bersifat haploid.
Berdasarkan makhluk hidupnya, sel dapat dibedakan menjadi: Sel Hewan Sel Tumbuhan Gambar 7. Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
2.3
KOMPONEN KIMIAWI PENYUSUN SEL Sel merupakan struktur yang dibangun oleh komponen kimiawi berupa bahan organik dan anorganik. Bahan kimia anorganik misalnya H2O, O2, C, dll. Sedangkan bahan organik yang menyusun sel diantaranya adalah Karbohidrat, Lipid dan Protein. Karbohidrat, lipid dan protein merupakan bahan-bahan penyusun sel yang berukuran besar, disebut juga makromolekul.
a. Karbohidrat Fungsi : a. sebagai sumber energi (contoh :glukosa, fruktosa) b. sebagai cadangan energi (contoh : glikogen)
c. sebagai sumber kerangka karbon penyusun tubuh (contoh : pati,selulosa,kitin) Ada 3 golongan Karbohidrat, yaitu : a. Monosakarida6 CH2OH
H4C
5C
O H C 1 H C2 O H H O H
CH2OH O H O H H H O H O HSimbol monosakarida
H O O H H 3C H
H
O
O Rumus Hbangun
Contoh monosakarida : glukosa, fruktosa, dan galaktosa b. Disakarida merupakan gabungan dari 2 monosakarida. Penggabungan ini terjadi melalui reaksi kondensasi / dehidrasi.CH2O H O H H H O H O H H H O H O Glukosa H CH2O HO H O H H H O H CH2O HO H O H H H O H Contoh disakarida : a. Maltosa (gabungan H O H 2 glukosa), b. sukrosa (gabungan glukosa + fruktosa), dan c. Laktosa (gabungan glukosa + galaktosa)
H HO
Glukosa
H H O
H O
H
H2 O CH2O HO H O H H H O H
H O H
Maltosa
c. Polisakarida Merupakan gabungan dari banyak monosakarida. Contohnya pati/ amilum, selulosa (serat), kitin, dll.
b. Lipid Merupakan molekul hidrokarbon yang memiliki sifat hidrofob (sukar larut dalam air). Ada 3 kelompok lipid, yaitu : a. Lemak (Trigliseraldehid) Merupakan lipid yang disusun oleh gabungan 1 gliserol dengan 3 asam lemak.
H H C O C CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3
H C O O C
H C O O C CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 O H
Di alam, lemak terdapat dalam bentuk 2 macam, yaitu: 1. Lemak jenuh : ditemukan pada hewan, memiliki ciri berbentuk padat pada suhu kamar (250 C). 2. Lemak tak jenuh : Ditemukan pada tumbuhan (disebut juga minyak). Memiliki cirri berbentuk cair pada suhu kamar ( 250C)
CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3
b. Fosfolipid Merupakan lipid penyusun membran sel. Fosfolipid disusun oleh gugus fosfat dan 2 asam lemak. c. Steroid Merupakan lipid yang disusun oleh rantai hidrokarbon berbentuk cincin berjumlah 4 buah. Fungsinya sebagai bahan baku pembentukkan hormone seks, vitamin D, komponen membrane sel, dll.CH3 H3
CCH3
CH3
CH3
6C 6C
5C
6CH
c. Protein Merupakan molekul yang disusun oleh 20 jenis asam amino. Protein memiliki fungsi diantaranya : a. sebagai penyusun membrane sel b. sebagai katalis reaksi kimiawi sel/ dalam tubuh ( oleh enzim) c. pembentuk struktural sel, dllIkatanPeptidaH H N H C R C O H O + H R H N C C O H H O
O
Reaksi DehidrasiH2 O
H N H
H C R
O C N H
H C R C
O O H
Asam Amino
Asam Amino
Dipeptida
Beberapa dipeptida melalui penambahan asam amino lain akan membentuk polipeptida. Polipeptida ini nantinya dapat dibuat menjadi protein pada sel/ tubuh.
2.4 Bagian- Bagian Sel Secara umum sel terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Membran Plasma Sitoplasma Inti sel 2.4.1Membran Plasma
Gambar 8. Membran Sel Membran plasma membungkus sebuah sel selain membatasi keberadaan sebuah sel, juga memelihara perbedaan- perbedaan pokok antara isi sel dengan lingkungannya. Membaran plasma terdiri dari lapisan rangkap lipid yang diapit oleh lapisan protein pada kedua sisinya (lipoprotein). Membran sel berupa selaput tipis, disebut juga plasmalema. Tebal membran antara 5-10 nm. Apabila diamati dengan mikroskop cahaya tidak terlihat jelas, tetapi keberadaannya dapat dibuktikan pada waktu sel mengalami plasmolisis S. Singer dan E.Nicolson (1972) menyampaikan teori tentang membran sel. Teori ini disebut teori membran mozaik cair, yang menjelaskan bahwa membran sel terdiri atas protein yang tersusun seperti mozaik (tersebar) dan masing-masing tersisip di antara dua lapis fosfolipid. Membran sel merupakan bagian terluar sel dan tersusun secara berlapislapis. Bahan penyusun membran sel yaitu lipoprotein yang merupakan gabungan antara lemak dan protein. Membran sel mengandung kira-kira 50% lipid dan 50% protein. Lipid yang menyusun membran sel terdiri atas fosfolipid dan sterol. Fosfolipid memiliki bentuk tidak simetris dan berukuran panjang. Salah satu ujung fosfolipid bersifat mudah larut dalam air (hidrofilik), yang disebut dengan ujung polar. Bagian sterol bersifat tidak larut dalam air (hidrofobik) yang disebut dengan ujung nonpolar. Fosfolipid tersusun atas dua lapis. Dalam hal ini protein dibedakan menjadi 2 sebagai berikut.
a. Protein Ekstrinsik (Perifer) Protein ini letaknya tersembul di antara dua lapis fosfolipid. Protein ekstrinsik bergabung dengan permukaan luar membran dan bersifat hidrofilik yaitu mudah larut dalam air. b. Protein Intrinsik (Integral) Protein ini letaknya tenggelam di antara dua lapis fosfolipid. Protein intrinsik bergabung dengan membran dalam dan bersifat hidrofobik yaitu tidak mudah larut dalam air. Penyusun membran sel yang berupa karbohidrat berikatan dengan molekul protein yang bersifat hidrofilik sehingga disebut dengan glikoprotein. Adapun karbohidrat yang berikatan dengan lipid yang bersifat hirofilik disebut dengan glikopolid. Sifat dari membran sel ini adalah selektif permiabel artinya adalah dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya. Membran sel memiliki fungsi antara lain: a. sebagai pelindung sel, b. mengendalikan pertukaran zat, dan c. tempat terjadinya reaksi kimia. Untuk menunjang fungsinya ini, membran sel memiliki kemampuan untuk mengenali zat. Zat yang dibutuhkan akan diizinkan masuk (Selektif Permeabel), sedangkan zat yang sudah tidak digunakan berupa sampah akan dibuang. Ada juga zat tertentu yang dikeluarkan untuk diekspor ke sel lain. Masuknya zat dari luar melalui membran sel yaitu melalui peristiwa transpor pasif dan transpor aktif. Agar lebih jelas memahami struktur membran sel, coba Anda
2.4.2 Sitoplasma Sitoplasma terdiri dari matriks atau sitosol tempat terbenamnya organela, sitoskeleton dan timbunan karbohidrat, lipid dan pigmen, protoplasma dari sel hewan dan tumbuhan mengandung 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipid, dan 1% karbohidrat, dan 1% bahan organik. Organela dalam sitoplasma antara lain:
Mitokondria
Gambar 9. Mitokondria
Mitokondria merupakan organela penghasil energi dalam suatu sel. Mitokondria memiliki bentuk bulat tongkat dan berukuran panjang antara 0,2-5 mikrometer dengan diameter 0,5 mikrometer. Dengan bantuan mikroskop cahaya, keberadaan mitokondria dapat terlihat, tetapi untuk dapat melihat struktur dasarnya harus menggunakan mikroskop elektron. Mitokondria disusun oleh bahan-bahan antara lain fosfolipid dan protein. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Permukaan pada membran luar halus, sedangkan pada membran dalam banyak terdapat lekukan-lekukan ke dalam yang disebut krista. Adanya lekukanlekukan ini akan dapat memperluas bidang permukaannya. Krista berperan dalam penyerapan oksigen untuk respirasi. Dari proses respirasi inilah dapat dihasilkan energi. Jadi, mitokondria berfungsi untuk tempat respirasi sel atau sebagai pembangkit energi. Mitokondria mempunyai enzim yang dapat mengubah energi potensial dari makanan kemudian disimpan dalam bentuk ATP. ATP inilah yang merupakan sumber energi sebagai bahan bakar untuk melakukan proses kegiatan untuk hidup. Sel-sel mana saja yang banyak terdapat mitokondria pada tubuh manusia? Tentu saja sel-sel yang banyak melakukan aktivitas kerja. Pada bagian organ mana dalam tubuh Anda yang paling aktif dan giat bekerja? Misalnya jika seorang olahragawan melakukan aktivitas berolahraga, maka bagian tubuh yang paling aktif bekerja adalah otot. Otot akan selalu berkontraksi ketika seseorang bergerak. Bahkan, ketika Anda tidur pun sel selalu melakukan pemecahan ATP. Coba analisalah kegunaan ATP ketika kita dalam keadaan tidur. Kegunaan ATP yaitu sebagai energi yang digunakan untuk mengganti sel-sel yang rusak, untuk memompa jantung, dan lain-lain. Mitokondria banyak terdapat pada bagian tubuh antara lain otot, hati, jantung, ginjal, karena bagian tubuh tersebut paling aktif melakukan kerja dan menghasilkan energi.
Retikulum Endoplasma
Retikulum endoplasma merupakan sistem yang sangat luas, membran di dalam sel berupa saluran-saluran dan tabung pipih. Membran ini lebih tipis dari membran plasma. Komposisi kimia tersusun atas lipoprotein. Retikulum endoplasma ada dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. 1) Retikulum Endoplasma Kasar (REK) Retikulum endoplasma kasar ditempeli dengan ribosom yang tersebar merata pada permukaannya. Ribosom merupakan tempat sintesis protein. Protein yang sudah terbentuk kemudian akan diangkut ke bagian dalam retikulum endoplasma, dan kemudian disimpan di dalam membran yang berkantong yang disebut vesikula. 2) Retikulum Endoplasma Halus (REH) Retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Permukaan REH ini menghasilkan enzim yang dapat mensintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Jadi, secara umum fungsi retikulum endoplasma antara lain: 1) penghubung selaput luar inti dengan sitoplasma, sehingga menjadi penghubung materi genetik antara inti sel dengan sitoplasma; 2) transpor protein yang disintesis dalam ribosom; dan 3) biosintesis fosfolipid, glikolipid, dan sterol.
Ribosom
Gambar 10. Ribosom Ribosom merupakan struktur terkecil yang bergaris tengah 17-20 mikron, letaknya di dalam sitoplasma sehingga hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Semua sel hidup memiliki ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein, yang selanjutnya digunakan untuk pertumbuhan, perkembangbiakan atau perbaikan sel yang rusak. Pada sel-sel yang aktif dalam sintesis protein, ribosom dapat berjumlah
25% dari bobot kering sel. Coba sebutkan pada bagian organ mana saja pada tubuh manusia yang paling banyak terdapat ribosom? Keberadaan ribosom secara acak tersebar di dalam sitoplasma, tetapi ada beberapa yang terikat pada membran retikulum endoplasma kasar (REK). Sel hati merupakan sel yang banyak mengandung ribosom, karena sel hati terlibat aktif dalam melakukan sintesis protein. Badan Golgi
Gambar 11. Badan Golgi
Organela ini ditemukan pertama kali oleh Camilio Golgi, seorang ilmuwan dari Italia. Badan golgi biasa dijumpai pada sel tumbuhan maupun hewan. Pada sel hewan terdapat 10-20 badan golgi. Lain halnya dengan tumbuhan yang memiliki ratusan badan golgi pada setiap sel. Badan golgi terdiri atas sekelompok kantong pipih yang dibatasi membran yang dinamakan saccula. Di dekat saccula terdapat vesikel sekretori yang berupa gelembung bulat. Badan golgi pada tumbuhan disebut dengan diktiosom. Pada diktiosom terjadi pembuatan polisakarida dalam bentuk selulosa yang digunakan sebagai bahan penyusun dinding sel. Secara umum fungsi dari badan golgi antara lain: 1) secara aktif terlibat dalam proses sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. 2) membentuk dinding sel pada tumbuhan. 3) menghasilkan lisosom. 4) membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur.
Lisosom Lisosom bekerja sebagai organel pencerna. Lisosom mengandung berbagai macam enzim hidrolitik yang dihasilkan oleh reticulum endoplasma. Lisosom dapat mencerna semua mokromolekul menjadi molekul yang lebih kecil dan dikeluarkan ke sitoplasma. Enzim lisosom sangat penting. Enzim merupakan asam hidrolase sehingga dapat bekerja secara optimum pada pH asam. Lisosom
secara mikroskopis merupakan suatu partikel yang secara struktur dibatasi oleh suatu membran, mengandung hidrolase yang berupa asam fosfatase.
Gambar 12. Lisosom
Berdasarkan keadaan fisiologisnya lisosom dapat dibedakan atas 2 yaitu; Lisosom primer yang merupakan lisosom yang baru terbentuk dan terlibat dalam kegiatan degradasi. - Lisosom sekunder yang berasal dari vakuola fagositosis (heterofagosom) atau bagian dari sitoplasma yang dibatasi oleh suatu membran (autofagosome) di mana tertuang enzim lisosom primer. Lisosom primer dan sekunder selanjutnya menjadi Telolysosome yang berdegenerasi menjadi residu di dalam sel dan disebut Badan residu pascalisosom. Lisosom primer mengandung enzim hidrolase dan dapat bergabung (fusi) dengan vesikula endositosis (heterofagi) atau dengan vakuola autofagi. Hasil dari lisosom sekunder adalah merupakan tempat digesti. a. Struktur 1. Lisosom primer Lisosom primer adalah organel sel yang tetap, dibatasi oleh satu membran, mengandung enzim hidrolisa yang belum terlibat dalam proses katabolisme. Strukturnya berupa suatu badan yang bulat atau oval berdiameter antar 0,3 dan 1,5 micrometer. Dibatasi oleh hanya satu membran yang memungkinkan penyimpanan enzim. Lisosom primer dapat ditemukan pada hepatocyte yang jumlahnya tergantung pada aktivitas sel. Lisosom primer diketahui mengandung lebih dari 60 jenis enzim. Enzim lisosom menghidrolisa substrat dari 4 kelompok utama makromolekul yaitu: Protein Asam nukleat Karbohidrat
- Lemak Semuanya merupakan enzim degradasi atau enzim katabolisme yang aktivitas optimalnya berada di sekitar pH 5. Sintesa enzim lisosomal dilakukan oleh ribosom dari Retikulum endoplasma granular, selanjutnya menuju ke apparatus golgi yang selanjutnya berkecambah menjadi lisosom primer.
Gambar 13. Perbandingan ukuran antara lisosom dan peroksisom 2. Lisosom sekunder Lisosom sekunder terlibat dalam fenomena digesti seluler dan merupakan hasil fusi dari lisosom primer dengan fagosom atau autofagosome. Lisasom sekunder dari jenis heterolysosome (vakuola heterofagi atau heterofagolisosom) dihasilkan dari vesikula tertentu. Sedangkan autolysosome (vakuola autofagi atau eytolisasom) adalah dibentuk dari fusi satu autofagosome dengan lisosom primer)
Gambar 14. keterkaitan antara RE, apparatus Golgi dan lisosom 3. Badan residu Suatu badan residu adalah suatu vakuola yang berasal dari suatu heterolysome atau heterolysome atau suatu autolysome yang berupa residu non digesti oleh enzim lisosomal. Residu memiliki sifat dan bentuk yang sangat bervariasi karena aspeknya tergantung pada asalnya. Badan residu mengandung: Myelinis: merupakan produk dari degradasi fosfolipoprotein atau merupakan senyawa yang menyusun membran dari berbagai organel. - Pigmen biliair - Ferritin - Lipuscin: merupakan pigmen coklat termasuk grup chromolipoid. Merupakan hasil oksidasi non enzimatik lemak. - Suatu substansi asing yang dibuang. b. Fungsi 1. Lisosom primer Peranan utama dari lisosom primer adalah berisi hydrolase yang memungkinkan transport intrasitoplasma menuju fagosome atau autofagosome dan menuangkan produk enzimatiknya balk di dalam vakuola intraseluler dari system digestif seluler maupun dalam miliu ekstraseluler. 2. Lisosom sekunder Vakuola heterofagi memiliki fungsi sebagai digesti intraseluler dan pertahanan. Fungsi sebagai digesti intraseluler yaitu bahwa alimentasi yang dalam bentuk solid atau
liquid ditangkap oleh sel dan didegradasi dan komponennya menembus membran lisosom untuk dapat digunakan sebagai bahan sintesa. Sedangkan fungsi sebagai pertahanan yaitu bahwa lisosom melindungi sel melawan agresi patogen. Bakteri, dan virus difagosit serta dihancurkan oleh enzim lisis. Senyawa toksik atau obat-obatan yang didegradasi oleh lisosom dikenal sebagai detoksikasi. Autofagi adalah suatu mekanisme di rnana sel membersihkan diri dari partikel atau fragmen sitoplasma yang tidak digunakan lagi, tanpa kehilangan bahan kimia penyusunnya yang digunakan lagi oleh sel. Vakuola autofagi terlibat dalam beberapa aktivitas sel yaitu: - "cell turnover" clan penyusun sel - Differensiasi sel atau metamorfosis - Autofagi senyawa toksik 3. Badan residu Bahan yang diindigesti dan terdapat dalam vakuola dieliminasi secara exocytosis (defekasi seluler). Kadang-kadang herada dalam kondisi ketidakmampuan mengeliminasi residu tersebut {konstipasi seluler), sehingga tetap berada hingga sel mati.
Peroksisom
Peroksisom dibentuk oleh penonjolan dari retikulum endoplasma halus, sedangkan membrannya disintesa oleh retikulum endoplasma kasar. Peroksisom bilamana tidak mengandung nukleid dan plak marginal sukar untuk diindentifikasi atau diamati. a. Struktur Peroksisom diidentifikasi sebagai suatu partikel yang berdiameter antara 0,151,7 mikrometer. Memiliki elemen dan struktur (membran dan matriks) yang tetap dan yang tidak tetap (nukleid dan lapisan marginal).
Gambar 15. Peroksisom Membran yang membatasi peroksisom pada bagian periferiknya memiliki struktur yang mirip pada membran plasma dengan ketebalan 6 - 8 nm. Berhubungan dengan retikulum endoplasma halus dengan perantaraan tubuli yang memanjang. Matriksnya dapat homogen atau bergranula halus, kadang-kadang mengandung filamen yang bercabang dengan diameter 4 - 4,5 nm. Pada bagian pusat peroksisom dari hewan tertentu ditemukan adanya satu struktur yang berdensitas yang disebut nukleid dan ini tidak ditemukan pada Primata. Nukleid ini berupa suatu struktur yang poly atau multi tubular. Organel ini tidak mengandung DNA atau molekul untuk sintesa protein. Bagaimana mekanisme pembelahan dari peroksisom sama sekali belum diketahui. Lapisan marginal adalah suatu struktur yang berbentuk datar tebal dan linear, terletak pada bagian periferik dari peroksisom dan dipisahkan dari permukaan internal membran oleh suatu ruang. Lapisan marginal memiliki ketebalan 8,5 nm. Enzim yang terkandung dalam peroksisom adalah: Katalase yang memungkinkan destruksi transformasi menj adi H20. L - Hidroksi-oksidase (glycolat oksidase) D-Amino-oksidase Urikase dari peroksida-hidrogen dan
b. Fungsi Peroksisom berfungsi dalam: Katabolisme purin Nuklease spesifik mendegradasi nukleotida yang berasal dari hidrolisa asam nukleat menjadi nukleosida, kemudian purin dan pirimidin. Basa ini dapat digunakan, kembali (biosintesa asam nukleat) atau didegradasi. Degradasi tersebut tergantung pada kelengkapan enzimatik dari peroksisom. Regulasi katabolisme Glukosa Peroksisom menghasilkan sejumlah kecii energi (dalam bentuk panas). Bertindak sebagai pengoksidasi NADH menjadi NAD oleh suatu transfer elektron. DI samping itu berfungsi dalam mengontrol degradasi glukosa menjadi piruvat. Metabolisme lemak Peroksisom berpartisipasi pada B-oksidasi asam lemak. Menghasilkan asetil radikal (CH3CO) yang herkombinasi pada enzim A (asetilkoenzim A). Koenzim A ini ditranpsfer ke mitokondria melalui berbagai jaiur metabolisme. Sitoskeleton
-
-
Merupakan benang- benang sel yang fungsinya seperti kerangka bagi sel. a. Struktur: kumpulan benang-benang (ada 3 tipe) yang berada di sitoplasma. i. Mikrotubulus ii. Mikrofilamen iii. Filamen Intermediet b. Fungsi : Penyokong struktural sel, pergerakan sel dan regulasi sel.
Mikrofilamen
Gambar 16. Sitoskeleton
Filamen intermediet
Mikrotubulus
Jenis Sitoskeleton
Mikrotubulus
Mikrofilamen
Filamen Intermediet
Hal
1. Struktur
Disusun oleh polimer protein tubulin a. Menjaga bentuk sel. b. Mendukung pergerakan organel. c. Mendukung pergerakan sel (contoh cilia dan flagel). d. Terlibat dalam pembelahan sel.
Disusun oleh polimer protein aktin a. Menjaga bentuk sel. b. Mendukung pergerakan di dalam sel.
Disusun oleh serat protein keratin a. Menjaga bentuk sel. b. Menjaga letak organel di dalam sel.
2. Fungsi
3. Dite mukan pada :
a. cilia dan flagella b. sentriol dan sentromer
a. sel-sel otot b. mikrofili c. pseudopodia amoeba
a. lapisan membrane inti b. lapisan membrane beberapa organel
4. Gambar :
Sentriol
Gambar 17. Sentriol Sentriol merupakan organel tak bermembran yang hanya ditemukan pada sel hewan. Organel ini berukuran kecil , jumlahnya sepasang dan letaknya dekat membrane inti dalam posisi tegak lurus antar keduanya. Organel ini berfungsi saat terjadi pembelahan sel, yaitu pada saat pergerakan kromosom. Organel ini akan memisah satu sama lain untuk membentuk gelendong pembelahan pada saat terjadi pembelahan sel. Vakuola
Merupakan organel yang ditemukan hanya pada sel tumbuhan, sel jamur dan beberapa sel hewan. Struktur vakuola adalah berupa kantung bermembran. Ada 3 tipe vakuola, yaitu : a. vakuola makanan, terbentuk melalui fagositosis pada sel protozoa, dll b. vakuola kontraktil, yaitu vakuola yang berfungsi memompa kelebihan air pada sel protista c. vakuola sentral, ditemukan pada sel tumbuhan / sel jamur. Memiliki ukuran yang sangat besar. Vakuola sentral memiliki fungsi - menyimpan cadangan makanan. - Menyimpan senyawa sisa metabolisme - Menyimpan air - Menyimpan pigmen warna tumbuhan
Gambar 18. Vakuola Sentral
2.4.3 Inti Sel Nukleus merupakan organ terbesar sel, dengan ukuran diameter antara 10-20 nm. Nukleus memiliki bentuk bulat atau lonjong. Hampir semua sel memiliki nukleus, karena nukleus ini berperan penting dalam aktivitas sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Namun ada beberapa sel yang tidak memiliki nukleus antara lain sel eritrosit dan sel trombosit. Pada kedua sel ini aktivitas metabolisme terbatas dan tidak dapat melakukan pembelahan. Biasanya sebuah sel hanya memiliki satu nukleus saja, yang terletak di tengah. Namun ada sel-sel yang memiliki inti lebih dari satu yaitu pada sel parenkim hati dan sel otot jantung, yang memiliki dua buah nukleus. Adapun pada sel otot rangka terdapat banyak nukleus. Komposisi nukleus terdiri atas membran nukleus, matriks, dan anak inti.
a. Membran Nukleus (Karioteka) Susunan molekul membran ini sama dengan susunan molekul membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Membran inti juga dilengkapi dengan poripori yang dapat memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Pori-pori ini berperan dalam memindahkan materi antara inti sel dan sitoplasmanya. Membran inti hanya bisa dilihat dengan jelas dengan menggunakan mikroskop elektron. Membran inti terdiri atas dua selaput yaitu selaput luar dan selaput dalam. Selaput luar mengandung ribosom pada sisi yang menghadap sitoplasma dan sering kali berhubungan dengan membran retikulum endoplasma.
Gambar 19. Inti Sel b. Matriks (Nukleoplasma) Nukleoplasma terdiri atas cairan inti yang tersusun dari zat protein inti yang disebut dengan nukleoprotein. c. Anak Inti (Nukleolus)
Di dalam nukleolus banyak terkandung kromosom, yaitu benang-benang halus DNA. Kromosom tersebut berfungsi untuk: 1) menentukan ciri-ciri yang dimiliki sel; 2) mengatur bentuk sel; 3) menentukan generasi selanjutnya. DNA tersusun dalam kromosom yang terdapat pada nukleoplasma, sedangkan tempat sintesis RNA terjadi pada nukleolus.
2.5 Mikroskop Sebagai Alat Bantu untuk Melihat Sel Mikroskop adalah alat optik untuk mengamati benda- benda yang sangat kecil, misalnya rambut, bakteri dan sel sehingga tampak jelas. Mikroskop sederhana terdiri dari dua buah lensa positif (cembung). Lensa positif yang berdekatan dengan mata disebut lensa okuler. Lensa ini berfungsi sebagai lup. Lensa positif yang berdekatan dengan benda disebut lensa objektif. Jarak titik api lensa objektif lebih kecil dari pada jarak titik api lensa okuler. Resolusi dan Magnifikasi Resolusi adalah kemampuan sistem optikal untuk membedakan detil sangat kecil pada suatu spesimen (sebagai jarak terkecil antara 2 poin yang berdekatan dimana mereka dapat dibedakan dalam 2 bagian yang berbeda. Resolusi ditentukan oleh: a. Kemampuan mengumpulkan cahaya (numerical aperture atau N.A) lensa
NA = n x sin b. Panjang gelombang () cahaya yang digunakan
Resolusi = 0.61 x / NA Komponen Suatu Mikroskop 1. Sistem iluminasi sumber cahaya dan kondensor 2. Pegangan dan tempat spesimen 3. Sistem lensa obyektif dan okuler (eye piece lens, biasanya memiliki kekuatan perbesaran 10x atau 15x) 4. Sitem fotografi (dipasang pada lensa okuler)
Perkembangan Mikroskop Antony Van Leuwenhoek orang yang pertama kali menggunakan mikroskop walaupun dalam bentuk sederhana pada bidang mikrobiologi. Kemudian pada tahun 1600 Hans dan Z Jansen telah menemukan mikroskop yang lebih maju dengan nama mikroskop ganda. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan scopium (penglihatan). Mikroskop adalah suatu benda yang berguna untuk memberikan bayangan yang diperbesar dari benda-benda yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Mikroskop pada prinsipnya terdiri dari dua lensa cembung yaitu sebagai lensa objektif (dekat dengan mata) dan lensa okuler (dekat dengan benda). Baik objektif maupun okuler dirancang untuk perbesaran yang berbeda. Lensa objektif biasanya dipasang pada roda berputar, yang disebut gagang putar. Setiap lensa objektif dapat diputar ke tempat yang sesuai dengan perbesaran yang diinginkan. Sistem lensa objektif memberikan perbesaran mula-mula dan menghasilkan bayangan nyata yang kemudian diproyeksikan ke atas lensa okuler. Bayangan nyata tadi diperbesar oleh okuler untuk menghasilkan bayangan maya yang kita lihat. Kebanyakkan mikroskop laboratorium dilengkapi dengan tiga lensa objektif : lensa 16 mm, berkekuatan rendah (10 X); lensa 4 mm, berkekuatan kering tinggi (4045X); dan lensa celup minyak 1,8 mm (97-100X). Objektif celup minyak memberikan perbesaran tertinggi dari ketiganya. Lensa okuler terletak pada ujung atas mikroskop, terdekat dengan mata. Lensa okuler biasanya mempunyai perbesaran: 5X, 10X, 12,5X dan 15X. Lensa okuler terdiri dari lensa plankonveks yaitu lensa kolektif dan lensa mata. MACAM-MACAM MIKROSKOP 1. Mikroskop Cahaya
Gambar 20. Mikroskop Cahaya
Mikroskop cahaya memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop memeiliki kaki yang berat dan kokoh agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki tiga dimensi lensa yaitu lensa objektif, lensa okuler dan lensa kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop.Lensa okuler pada mikroskop bias membentuk bayangan tunggal (monokuler) atau ganda (binikuler). Paada ujung bawah mikroskop terdapat dudukan lensa obektif yang bias dipasangi tiga lensa atau lebih. Di bawah tabung mikroskop terdapat meja mikroskop yang merupakan tempat preparat. Sistem lensa yang ketiga adalah kondensor. Kondensor berperan untuk menerangi objek dan lensa mikroskop yang lain. Pada mikroskop konvensional, sumber cahaya masih barasal dari sinar matahari yang dipantulkan oleh suatu cermin dataar ataupun cukung yang terdapat dibawah kondensor. Cermin in akan mengarahkan cahaya dari luar kedalam kondensor. Pada mikroskop modern sudah dilengkapai lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Lensa objektif bekerja dalam pembentukan bayangan pertama. Lensa ini menentukan struktur dan bagian renik yang akan menentukan daya pisah specimen, sehingga mampu menunjukkan struktur renik yang berdekatan sebagai dua benda yang terpisah.Lensa okuler, merupakan lensa likrskop yang terdpat dibagian ujung atas tabung, berdekatan dengan mata pengamat. Lensa ini berfugsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Perbesran bayangan yang terbentuk berkisar antara 4-25 kali.Lensa kondensor berfungsi untukk mendukung terciptanya pencahayaan padda objek yang akan difokus, sehinga pengaturrnnya tepat akan diperoleh daya pisah maksimal, dua benda menjadi satu. Perbesaran akan kurang bermanfatjika daya pisah mikroskop kurang baik. 2. Mikroskop Stereo Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relative besar. Mikroskop stereo memiliki perbesasran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Komponen utama mikroskop stereo hamper sama dengan mikroskop cahaya. Lensa terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif. Beberapa perbedaan dengan mikroskop cahaya adalah: (1) ruang ketajaman lensa mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandinhkan denan mikroskop cahaya ssehingga kita dapat melihat bentuk tiga dimensi benda yang diamati, (2) sumber cahaya berasal dari atas sehingga objek yang tebbbbbbbal dapat diamati. Perbesaran lensa okuler
biasannya 3 kali, sehingga prbesaran objek total minimal 30 kali. Pada bagian bawah mikroskop terdapat meja preparat. Pada daerah dekat lenda objektif terdapat lampu yang dihubungkan dengan transformator. Pengaturan focus objek terletak disamping tangkai mikroskop, sedangkan pengaturan perbesaran terletak diatas pengatur fokos. 3. Mikroskop Elektron Mikroskop Elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakuakan peambesaran obyek sampai duajuta kali, yang menggunakan elektro statik dan elektro maknetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan p[embesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus dari pada mikroskop cahaya. Mikroskop electron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektro maknetikmyang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Macam macam mikroskop elektron: 1) Mikroskop transmisi elektron (TEM) 2) Mikroskop pemindai transmisi elektron (STEM) 3) Mikroskop pemindai elektron 4) Mikroskop pemindai lingkungan electron (ESEM) 5) Mikroskop refleksi elektron (REM) 4. Mikroskop Ultraviolet Suatu variasi dari mikroskop cahaya biasa adalah mikroskop ultraviolet. Karena cahaaya ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari pada cahaya yang dapat dilihat, penggunaan cahaya ultra violet untuk pecahayaan dapat meningkatkan daya pisah menjadi 2 kali lipat daripada mikroskop biasa. Batas daya pisah lalu menjadium. Karena cahaya ultra violet tak dapat di;lihat oleh nata manusia, bayangan benda harus direkam pada piringan peka cahaya9photografi Plate). Mikroskop ini menggunakan lensa kuasa, dan mikroskop ini terlalu rumit serta mahal untuk dalam pekerjaan sehari-hari. 5. Mikroskop Pender (Flourenscence Microscope) Mikroskop pender ini dapat digunakan untuk mendeteksi benda asing atau Antigen (seperti bakteri, ricketsia, atau virus) dalam jaringan. Dalam teknk ini protein anttibodi yang khas mula-mula dipisahkan dari serum tempat terjadinya rangkaian atau dikonjungsi dengan pewarna pendar. Karena reaksi AntibodiAntigen itu besifat khas, maka peristiwa pendar akanan terjadi apabila antigen yang dimaksut ada dan dilihat oleh antibody yang ditandai dengan pewarna pendar.
6. Mikroskop medan-gelap Mikroskop medan gelapdigunakan untuk mengamati bakteri hidup khususnya bakteri yang begitu tipis yang hamper mendekai batas daya mikrskop majemuk. Mikroskop medan-Gelap berbeda dengan mikroskop cahaya majemuk biasa hanya dalam hal adanya kondensor khusus yang dapat membentuk kerucut hampa berkas cahaya yang dapat dilihat. Berkas cahaya dari kerucut hampa ini dipantulkan dengan sudut yang lebih kecil dari bagian atas gelas preparat. 7. Mikroskop Fase kontras Cara ideal untuk mengamati benda hidup adalah dalam kadaan alamiahnya : tidak diberi warna dalam keadan hidup, namun pada galibnya fragma bend hidup yang mikroskopik (jaringan hewan atau bakteri) ttembus chaya sehingga pada masingmasing tincram tak akan teramati, kesulitan ini dapat diatasi dengan menggunakan mikroskop fasekontras. Prinsip alat ini sangat rumit.. apabila mikroskop biasa digunakan nuklus sel hidup yang tidak diwwarnai dan tidak dapat dilihat, walaupun begitu karena nucleus dalam sel, nucleus ini mengubah sedikit hubungan cahaya yang melalui meteri sekitar inti. Hubungan ini tidak dapaat ditangkap oleh mata manusia disebut fase. Namun suatu susunan filter dan diafragma pada mikroskop fase kontras akan mengubah perbedaan fase ini menjadi perbedaan dalam terang yaitu daerah-daerah terang dan bayangan yang dapat ditangkap oleh mata.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Sel dalam menjalankan aktivitasnya tidak lepas dari andil setiap organelaorganela yang mempunyai fungsi masing- masing dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Jika salah satu organela fungsinya terganggu barang tentu juga mempengaruhi kerja organela yang lain. Sehingga untuk menjaga agar setiap sel dapat tumbuh dengan baik dan dapat berdegenerasi maka kita harus menjaga asupan gizi yang tepat baik karbohidrat, protein, lemak dan unsur zat lainnya. Mikroskop sangat dibutuhkan dalam mengamati dan mempelajari sel, penemuan mikroskop juga bertepatan dengan berkembangnya ilmu dibidang sel yang disebut sitologi dan ilmu mikrobiologi lainnya seperti biologi molekoler dan sebagainya.
Kata Pengantar Dengan selesainya penulisan makalah ini, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT , karena dengan izinNya-lah makalah ini dapat diselesaikan. Makalah ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sel. Namun, dalam penulisan makalah mungkin masih ada yang perlu diperbaiki sebagai bahan pertimbangan dalam tutorial 1 modul 1 blok empat yang terlewatkan oleh penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dr. Riska Sofia sebagai tutor pada kelompok tempat penulis berdiskusi dan kepada seluruh partner yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaian makalah ini.
Lhokseumawe, 16 Februari 2012 Penulis
Daftar Pustaka Guyton, Hall. 2008. Fisiologi Kedokteran. Misisippi: Elsevier Marianti, Aditya, Sumadi. 2007. Biologi Sel. Semarang: Graha Ilmu Subowo. 2007. Biologi Sel. Bandung: Angkasa Yuwono, Triwibowo. 2005. Biologi Molekular. Yogyakarta: Erlangga