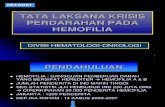LAPORAN HEMOFILIA
-
Upload
wahyu-tiara-dewiyanti -
Category
Documents
-
view
167 -
download
5
Transcript of LAPORAN HEMOFILIA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Meski belum memiliki nama, hemofilia telah ditemukan sejak lama. Talmud, yaitu sekumpulan tulisan para rabi Yahudi, 2 abad setelah masehi menyatakan bahwa seorang bayi laki-laki tidak harus dikhitan jika dua kakak laki-lakinya mengalami kematian akibat dikhitan. Selain itu, seorang dokter asal Arab, Albucasis, yang hidup pada abad ke-12 menulis tentang sebuah keluarga yang setiap anak laki-lakinya meninggal setelah terjadi perdarahan akibat luka kecil. Pada tahun 1803, Dr. John Conrad Otto, seorang dokter asal Philadelphia menulis sebuah laporan mengenai perdarahan yang terjadi pada suatu keluarga tertentu saja. Ia menyimpulkan bahwa kondisi tersebut diturunkan hanya pada pria. Ia menelusuri penyakit tersebut pada seorang wanita dengan tiga generasi sebelumnya yang tinggal dekat Plymouth, New Hampshire pada tahun 1780. Kata hemofilia pertama kali muncul pada sebuah tulisan yang ditulis oleh Hopff di Universitas Zurich, tahun 1828. Dan menurut ensiklopedia Britanica, istilah hemofilia (haemophilia) pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Jerman, Johann Lukas Schonlein (1793 - 1864), pada tahun 1928. Hemofilia juga disebut dengan "The Royal Diseases" atau penyakit kerajaan. Ini di sebabkan Ratu Inggris, Ratu Victoria (1837 - 1901) adalah seorang pembawa sifat/carrier hemofilia. Anaknya yang ke delapan, Leopold adalah seorang hemofilia dan sering mengalami perdarahan. Leopold meninggal dunia akibat perdarahan otak pada saat ia berumur 31 tahun. Salah seorang anak perempuan Victoria yaitu Alice, ternyata adalah carrier hemofilia dan anak laki-laki dari Alice, Viscount Trematon, juga meninggal akibat perdarahan otak
1
pada tahun 1928. Alice dan Beatrice, adalah carrier dan merekalah yang menyebarkan penyakit hemofilia ke Spanyol, Jerman dan Keluarga Kerajaan Rusia. Pada abad ke 20, pada dokter terus mencari penyebab timbulnya hemofilia. Hingga mereka percaya bahwa pembuluh darah dari penderita hemofilia mudah pecah. Kemudian pada tahun 1937, dua orang dokter dari Havard, Patek dan Taylor, menemukan pemecahan masalah pada pembekuan darah, yaitu dengan menambahkan suatu zat yang diambil dari plasma dalam darah. Zat tersebut disebut dengan "anti - hemophilic globulin". Di tahun 1944, Pavlosky, seorang dokter dari Buenos Aires, Argentina, mengerjakan suatu uji coba laboratorium yang hasilnya memperlihatkan bahwa darah dari seorang penderita hemofilia dapat mengatasi masalah pembekuan darah pada penderita hemofilia lainnya dan sebaliknya. Secara kebetulan, ia menemukan dua jenis penderita hemofilia dengan masing - masing kekurangan zat protein yang berbeda - Faktor VIII dan Faktor IX. Dan hal ini di tahun 1952, menjadikan hemofilia A dan hemofilia B sebagai dua jenis penyakit yang berbeda. Kemudian di tahun 1960-an, cryoprecipitate ditemukan oleh Dr. Judith Pool.Dr. Pool menemukan bahwa pada endapan di atas plasma yang mencair mengandung banyak Faktor VIII. Untuk pertama kalinya Faktor VIII dapat dimasukkan pada penderita yang kekurangan, untuk menanggulangi perdarahan yang serius. Bahkan memungkinkan melakukan operasi pada penderita hemofilia. Walaupun Hemofilia telah dikenal lama di ilmu dunia kedokteran, namun baru pada tahun 1965, diagnosis melalui laboratorium baru diperkenalkan oleh Kho Lien Kheng. Diagnosis laboratorium yang diperkenalkannya menggunakan Thromboplastin
Generation Test (TGT), selain pemeriksaan waktu perdarahan dan masa waktu pembekuan darah. Pada saat itu pemberian darah lengkap segar merupakan satu-satunya cara pengobatan yang tersedia di rumah sakit (http://www.wikipedia.com)
2
B. Rumusan Masalah 1. Apa itu hemophilia ? 2. Bagaimana dengan epidemiologi hemophilia ? 3. Klasifikasi apa saja untuk membedakan hemophilia ? 4. Apa saja tanda dan gejala dari hemophilia ? 5. Jelaskan patofisiologi hemophilia ! 6. Diagnosis apa saja yang dapat ditegakka pada penyakit hemophilia ? 7. Penatalaksanaan apa saja yang dapat diberikan pada penderita hemophilia ? 8. Komplikasi apa saja yang dapat di temukan pada penderita hemophilia ? C. Tujuan 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi hemofilia 2. Mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi hemofilia 3. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi hemofilia 4. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisologis hemofilia 5. Mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis hemofilia 6. Mahasiswa mampu menjelaskan penatalaksanaan hemofilia 7. Mahasiswa mampu menjelaskan komplikasi hemofilia D. Manfaat 1. Mahasiswa mengetahui definisi hemofilia 2. Mahasiswa mengetahui epidemiologo hemofilia 3. Mahasiswa mengetahui klasifikasi hemofilia 4. Mahasiswa mengetahui patofisiologis hemofilia 5. Mahasiswa mengetahui diagnosis hemofilia 6. Mahasiswa mengetahui penatalaksanaan hemofilia 7. Mahasiswa mengetahui komplikasi hemofilia
3
BAB II STUDI PUSTAKA A. Definisi Hemofilia Hemofilia adalah penyakit perdarahan akibat kekurangan faktor pembekuan darah yang diturunkan (herediter) secara sex-linked recessive p k omo om Sudoyo,
2007). Hemofilia merupakan penyakit pembekuan darah kongenital yang disebabkan karena kekurangan faktor pembekuan darah, yaitu faktor VIII dan faktor IX yang bersifat herediter secara sex-linked recessive pada kromosom X (Xh). Factor tersebut merupakan protein plasma yang merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh pembekuan darah khususnya dalam pembentukan bekuan fibrin pada daerah trauma (Dorland, 2006). B. Epidemiologi Penyakit ini bermanifestasi klinik pada laki laki. Angka kejadian hemophilia A sekita 1:10.000 orang dan hemophilia B sekita 1:25.000-30.000 orang. Belum data mengenai angka kekerapan di Indonesia, namun diperkirakan sekitar 20.000 dari 200 juta penduduk Indonesia saat ini. Kasus hemophilia A lebih sering di jumpai dibanding kan hemophilia B, yaitu berturut turut mencapai 80%-85% dan 10%-15% tanpa memandang ras,geografis dan keadaan social ekonomi. Mutasi gen secara spontan diperkirakan mencapai 20-30% yang terjadi pada pasien tanpa riwayat keluarga (Sudoyo, 2007). C. Klasifikasi Sampai saat ini dikenal 2 macam hemophilia yang diturunkan secara sex-linked recessive yaitu : 1. Hemofilia A (hemofila klasik), akibat defisiensi atau disfungsi factor pembekuan VII (F VIIIc). 2. Hemofilia B (Chistmas disease) akibat defisiensi atau disfungsi F IX ( Faktor Christmas).4
3. Hemofilia C merupakan penyakit perdarahan akibat kekurangan factor XI yang diturunkan secara utosomal ressecive pada kromsom 4q32q35. Klasifikasi hemophilia menurut berat ringannya penyakit : 1. Berat 2. Sedang 3. Ringan 4. Normal : : : : 1% 2 5% 6 10% 50 150%
( Sudoyo, 2007). D. Tanda dan Gejala Perdarahan adalah gejala dan tanda klinis yang khas yang sering di jumpai pada kasus hemophilia. Perdarahan dapat timbul secara spontan atau akibat trauma ringan sampai sedang serta dapat timbul saat bayi mulai belajar merangkak. Tanda perdarahan yang sering dijumpai yaitu : 1. hemartrosis 2. hematom subkutan/intramuscular 3. perdarahan mukosa mulut 4. perdarahan intracranial 5. epistaksis 6. hematuria E. Patofisiologi Hemofilia adalah penyakit gangguan pembekuan darah yang diturunkan melalui kromosom X. Karena itu, penyakit ini lebih banyak terjadi pada pria karena mereka hanya mempunyai kromosom X, sedangkan wanita umumnya menjadi pembawa sifat saja (carrier). Namun, wanita juga bisa menderita hemofilia jika mendapatkan kromosom X dari ayah hemofilia dan ibu pembawa carrier.Penyakit hemofilia ditandai oleh5
perdarahan spontan maupun perdarahan yang sukar berhenti. Selain perdarahan yang tidak berhenti karena luka, penderita hemophilia juga bisa mengalami perdarahan spontan di bagian otot maupun sendi siku. Pada orang normal, ketika perdarahan terjadi maka pembuluh darah akan mengecil dan keping-keping darah (trombosit) akan menutupi luka pada pembuluh. Pada saat yang sama, trombosit tersebut bekerja membuat anyaman (benang-benang fibrin) untuk menutup luka agar darah berhenti mengalir keluar dari pembuluh. Pada penderita hemofilia, proses tersebut tidak berlangsung dengan sempurna. Kurangnya jumlah faktor pembeku darah menyebabkan anyaman penutup luka tidak terbentuk sempurna sehingga darah terus mengalir keluar dari pembuluh yang dapat berakibat berbahaya. Perdarahan di bagian dalam dapat mengganggu fungsi sendi yakni mengakibatkan otot sendi menjadi kaku dan lumpuh, bahkan kalau perdarahan berlanjut dapat mengakibatkan kematian pada usia dini (Sylvia, 2006). F. Diagnosis Walaupun terdapat 20-30% kasus hemophilia terjadi akibat mutasi spontan kromosom X pada gen peyandi VIII dan F IX. Seorang anak lelaki diduga menderita hemophilia jika terdapat riwayat pendarahan berulang ( hematrosis, hematom ) atau riwayat perdarahan yang memanjang setelah trauma atau tindakan tertentu dengan atau riwayat keluarga. Kelainan laboratorium ditemukan pada gangguan uji hemeostatis, seperti pemanjangan masa pembekuan (CT) dan masa tromboplastin partial terativasi (aPTT), abnormalital uji tromboplastin generation, dengan masa perdarahan dan masa protombin (PT) dalam batas normal. Diagnosis definitive ditegakka dengan berkurangnya aktivitas F VIII/ F IX, dan jika sarana pemeriksaan sitogenik tersedia dapat dilakukan pemeriksaan petanda gen F VIII/ F XI. Aktivitas F VIII / F IX dinyatakan dalam U/ml denhgan arti aktivitas factor pembekuan darah 1 ml plasma normal adalah 100%. Nilai normal aktivitas F VIII/ F IX adalahn0,5 1,5 U/ ml atau 50 150%. Harus diinga adalah membedakan hemophilia A
6
dengan penyakit von Willebrand, dengan melihat rasio F VIIIc: F VIIIag dan aktivitas F vW (uji risositin) rendah. Diagnosis Banding 1. Hemofilia A dan B dengan defisiensi faktor XI dan XII. 2. Hemofilia A dengan penyakit von Willerbrand (khususnya varian Normandy) inhibitor F VIII yang didapat dan dikombinasi defisiensi F VIII dan kongeital. 3. Hemofilia B dengan penyakit hari, pemakaian warfarin, defisiensi vitamin K, sangat jarang inhibitor F IX yang didapat. G. Penatalaksanaan 1. Terapi Suportif 1.1.1.1. 1.1.1.2. Melakukan pencegahan baik menghindari luka / benturan Merencanakan suatu tindakkan operasi serta mempertahankan
kadar aktivitas faktor pembekuan sekita 30 50%. 1.1.1.3. Untuk mengatasi perdarahan akut yang terjadi maka dilakukan
tindakkan pertama seperti rest, ice, compression, elevation (RICE) pada lokasi perdarahan 1.1.1.4. Kortikosteroid sangat membentu untuk menghilangkan proses
inflamasi pada sinovitis akut yang terjadi setelah serangan akut hemartroisis 1.1.1.5. Analgetika diindikasi pada pasien hemartroisis dengan nyeri hebat
dan sebaiknya dipilih analgetik yang tidak mengganggu agregasi trombosit (harus dihindari penggunaan aspirin dan antikoagulan). 1.1.1.6. Rehabilitas medic dilakukan sedini mungkin secara komprehensif
dan holistik dalam sebuah tim karena keterlambatan dalam pengelolaan akan kecacatan atau ketidakmampuan baik fisik, okupasi maupun psikososial dan edukasi. 2. Terapi Pengganti Faktor Pembekuan7
Terapi pengganti faktor pembekuan pada kasus hemophilia dilakukan dengan pemmberian F VIII dan F IX, baik rekombinan, konsentrat maupun komponen darah yang mengandung cukup banyak faktor faktor pembekuan tersebut. Pemberian biasanya dilakuakan dalam beberapa hari sampai luka atau pembengkakan membaik serta khususnya selama fisioterapi. 3. Konsentrat F VIII/ F IX Hemofila A berat maupun hemophilia ringan dan sedang dengan episode perdarahan yang serius membutuhkan koreksi faktor pembekuan dengan kadar yang tinggi yang harus diterapi dengan konsentrat F VIII yang telah dilemahkan virusnya. Faktor IX tersedia dalam 2 bentuk yaitu prothrombin complex concentrates (PCC) yang berisi F II, VIII, IX, dan X dan purified F IX concentrates yang berisis berjumlah F IX tanpa faktor yang lain. PCC dapat menyebabkan thrombosis paradoksial dan koagulasi interavena tersebar yang disebabkan oleh sejumlah konsentrat faktor pembekuan lain. Resiko ini meningkatkan pada pemberian F IX berulang, sehingga purifefied kosentrat F IX lebih diinginkan. 4. Kriopesipitat AHF Kriopesipitat AHF adalah salah satu komponen darah non selular yang merupakan konsentrat plasma tertentu yang mengandung F VIII, fibrinogen, faktor von Willebrand. Dapat diberikan apabila konsentrat F VIII tidak ditemukan. Efek samoing dapat menimbulkan alergi dan demam. 5. 1-deamino 8-D Arginin Vasopresin (DDAVP) atau Desmopresin Hormon sintetik anti diuretic (DDAVP) merangsang peningkatan kadar aktivitas F VIII di dalam plasma sampai 4 kali, namun bersifat sementara. Pemberian dapat dengan intravena dengan dosis 0,3mg/kg BB dalam 30-50 NaCl 0,9% selama 15 menit atau 20 menit dengan lama kerja 8 jam. Efek samping yang dapat terjadi berupa takikardia, flushing, thrombosis (sangat jarang) dan hiponatremia.
8
6. Antifibrinolitik Digunakan pada pasien hemophilia B untuk menstabilisasikan bekuan / fibrin dengan cara menghambat proses fibrinolisis. Epsilon aminocaproic acid (EACA) dapat diberikan secara oral maupun intravena dengan dosis awal 200mg/ kg BB ( maksimum 5 g setiap pemberian ). Asam traneksamat diberikan dengan dosis 25mg/kg BB ( maksimum 1,5g ) secara oral, atau 10 mg/kg BB (maksimum 1 g) secara intravena setiap 8 jam. Asam traneksamat juga dapat dilarutkan 10 % bagian dengan perenteral, terutama salin normal. 7. Terapi Gen Saat ini sedang intensif dilakukan penelitian invivo denga memindahkan vector adenovirus yang membawa gen antihemofilia ke dalam sel hati. Gen F VIII relatif lebih sulit dibandingkan gen F IX, karena ukurannya (9 kb) lebih besar,namun akhir tahun 1998 para ahli berhasil melakukan pemindahan plasmid-based faktor VIII secara ex vivo ke fibroblas. H. Komplikasi Komplikasi yang sering ditemukan adalah artropati hemophilia, yaitu penimbunan darah intra artikuler yang menetap dengan akibat degenerasi kartilago dan tulang sendi secara progesif. Hal ini menyebabkan penurunan sampai rusaknya fungsi sendi. Hemartrosis yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menyebabkan sinovitis kronik akibat proses peradangan jaringan synovial yang tidak kunjung henti. Sendi yang sering mengalami komplikasi adalah sendi lutut, pergelangan kaki dan lutut.
BAB III PEMBAHASAN9
Anton 3 tahun datang ke dokter diantar ibunya dengan keluhan memar memar ( kebirubiruan ) setelah jatuh dari tangga 2 minggu yang lalu dan terjadi hemathrosis. Ibunya mengeluh sendi anaknya bertambah bengkak dan memarnya bertambah luas. Pernah menjadi memar seperti ini hilangnya 2 minggu, riwayat mimisan tidak ada. Kakak kandung laki lakinya meninggal pada usia 5 tahun dan sebelumnya mengalami keluhan yang serupa, sedangkan pamanya (adik Ibu Anton) juga mengalami hal yang sama, meninggal pada usia yang masih muda. Hasil laboratorium menunjukkan Hb 10 mg/ dL, AL 6000/ L, AT 257.000/ L, PT normal/ APTT memanjang. Rumple Leede (-). Ibunya men y k n : ken p ke u Hasil Pembahasan : 1. Anton memar-memar (kebiru-biruan) setelah jatuh dari tangga 2 minggu yang lalu dan terjadi hemarthrosis. Memar-memar terjadi karena adanya perdarahan di dalam jaringan akibat trauma (jatuh) sehingga eritrosit ke luar vascular kemudian terkumpul dalam jaringan dan kemudian difagosit oleh jaringan. Hb dimetabolisme menjadi hemosiderin (besi) berwarna coklat hitam dan hematoidin yang berwarna kuning muda yang kemudian keduanya saling berinteraksi sehingga terciptalah warna memar yang kebiru-biruan. Memar ini lama-kelamaan akan berwarna kuning sebagai pertanda memar akan segera hilang dan sirkulasi jaringan kembali normal (Anonim, 2008). 2. Ibunya mengeluh sendi anaknya bertambah bengkak dan memarnya bertambah luas. Sendi bertambah bengkak dikarenakan adanya perdarahan yang tidak berhenti dan semakin menumpuk sehingga mengakibatkan sendi tampak semakin bengkak. Memar bertambah luas dikarenakan adanya gangguan yakni defek pada faktor koagulasi (faktor VIII atau IX) sehingga terjadi gangguan pada proses pembekuan darah yang mengakibatkan perdarahan terjadi semakin lama dan bertambah luas ke daerah sekitar sehingga memar juga bertambah luas. 3. Sebelumnya pernah terjadi memar seperti ini dan hilangnya 2 minggu. 2 minggu bukanlah waktu yang pasti mengenai pembekuan darahnya karna lama perdarahan ditentukan oleh derajat hemofilia yang dipengaruhi oleh tingkat aktivitas faktor pembekuan (faktor VIII atau IX). 2 minggu ini menunjukkan jika waktu10
n k lel ki
y meng l mi peny kit y ng e up , Dok?.
pembekuan darah yang abnormal karena dalam keadaan normal waktu pembekuan terjadi dalam 5-7 menit namun dalam hemofilia waktu pembekuan memanjang menjadi 50 menit-2 jam. Memar hilang setelah semua jaringan atau daerah sudah mengalami pembekuan darah. Karena walaupun ada gangguan pada salah satu faktor pembekuan namun masih ada faktor-faktor pembekuan yang lain yang masih bisa menutupi sehingga proses pembekuan masih tetap bisa berjalan. 4. Kakak kandung laki-lakinya meninggal pada usia 5 th dan sebelumnya mengalami keluhan yang serupa, sedangkan pamannya (adik ibu Anton) juga mengalami hal yang sama, meninggal pada usia yang masih muda. Hal itu menunjukkan adanya hubungan genetik dalam penyakit ini. 5. Hasil laboratorium menunjukkan Hb 10 mg/dl, AL 6000/uL, AT 257.000/uL, PT normal/APTT memanjang. Dari hasil pemeriksaan laboratorium dan dari gejala serta riwayat keluarga tersebut maka hipotesis penyakit Anton yakni hemofilia. Hb, AL, dan AT menunjukkan nilai normal. PT normal menunjukkan jika faktor pembekuan pada jalur ekstrinsik dan aPTT menunjukkan hasil pemeriksaan pada jalur intrinsik. PT normal/aPTT memanjang menunjukkan adanya gangguan pada jalur intrinsik yang memanjang. Sehingga didapat hasil bahwa adanya defek atau gangguan pada jalur ekstrinsik pembekuan darah yakni gangguan pada faktor pembekuannya (faktor VIII atau IX) (Graber, 2006). 6. Ibuny men ny k n: Ken p ke u n k lel ki y meng l mi peny kit y ng l h peny kit y ng e up , ok? Kej i n te ebut menunjukk n jik hemofili
dapat diturunkan atau herediter dari orang tua ke anaknya, namun bisa juga kongenital akibat mutasi spontan gen (Sudoyo, 2007).
11
BAB IV Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan 1. Hemofilia adalah penyakit perdarahan akibat kekurangan faktor pembekuan darah yang diturunkan (herediter) secara sex-linked recessive pada kromosom. 2. Sampai saat ini dikenal 2 macam hemophilia yang diturunkan secara sexlinked recessive yaitu : Hemofilia A (hemofila klasik), Hemofilia B (Chistmas disease), dan Hemofilia C. 3. Klasifikasi hemophilia menurut berat ringannya penyakit :Berat 1%, Sedang 2 5%, Ringan 6 10%, dan Normal 50 150%.
12
4. Tanda perdarahan yang sering dijumpai yaitu : hemartrosis, hematom, subkutan/intramuscular, perdarahan mukosa mulut, perdarahan intracranial, epistaksis, dan hematuria. 5. Walaupun terdapat 20-30% kasus hemophilia terjadi akibat mutasi spontan kromosom X pada gen peyandi VIII dan F IX. 6. Diagnosis definitive ditegakka dengan berkurangnya aktivitas F VIII/ F IX, dan jika sarana pemeriksaan sitogenik tersedia dapat dilakukan pemeriksaan petanda gen F VIII/ F XI. 7. Diagnosis Banding: Hemofilia A dan B dengan defisiensi faktor XI dan XII. 8. Penatalaksanaan yang dapat diberikan pada penderita hemophilia yaitu : Terapi Suportif, Terapi Pengganti Faktor Pembekuan, Konsentrat F VIII/ F IX, Kriopesipitat AHF, 1-deamino 8-D Arginin Vasopresin (DDAVP) atau Desmopresin, Antifibrinolitik dan Terapi Gen. 9. Komplikasi yang sering ditemukan adalah artropati hemophilia, yaitu penimbunan darah intra artikuler yang menetap dengan akibat degenerasi kartilago dan tulang sendi secara progesif.
B. Saran 1. Yang paling penting, penderita hemofilia tidak boleh mendapat suntikan kedalam otot karena bisa menimbulkan luka atau pendarahan. 2. Penderita hemofilia juga harus rajin melakukan perawatan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan gusi secara rutin. Untuk pemeriksaan gigi dan khusus, minimal setengah tahun sekali, karena kalau giginya bermasalah semisalnya harus dicabut, tentunya dapat menimbulkan perdarahan. 3. Mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat dan menjaga berat tubuh agar tidak berlebihan. Karena berat badan berlebih dapat mengakibatkan
13
perdarahan pada sendi-sendi di bagian kaki (terutama pada kasus hemofilia berat). 4. Penderita hemofilia harus menghindari penggunaan aspirin karena dapat meningkatkan perdarahan dan jangan sembarang mengonsumsi obat-obatan. 5. Olahraga secara teratur untuk menjaga otot dan sendi tetap kuat dan untuk kesehatan tubuh. Kondisi fisik yang baik dapat mengurangi jumlah masa perdarahan..
DAFTAR PUSTAKA Dorland. 2002. Kamus Kedokteran, edisi 26, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, Pp 523,638,1119. http://www.hemofilia.or.id ( diakses tanggal 02 Desember 2009 ) http://www.fk-ui.ac.id ( diakses tanggal 02 Desember 2009 ) http://www.wikipedia.com ( diakses tanggal 02 Desember 2009 )
14
Price, Sylvia Anderson.2006. Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. (Edisi VI). Jakarta: EGC.Pp. 340-84 Robbins.2002. Buku Ajar Patologi Anatomi.Jakarta : EGC. Pp. 862-89 Sedoyo, dkk.Nyeri. 2007. In BukuAjar Ilmu Penyakit Dalam.Edisi II Jilid II.Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedoteran Universitas Indonesia,; 759-69 Sulistia,dkk.2007.Farmakologi dan Terapi. Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK-UI,Pp.210-99 Sutejo, AY.2007.Buku Saku Mengenal Penyakit Melalui Hasil Pemeriksaan
Laboratorium.Yogyakarta:Amara Books Setyabudi, Rahajuningsih D. et al.2007.Hemostasis dan Trombosis.Jakarta:Balai Penerbit FK UI
15