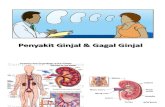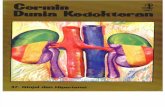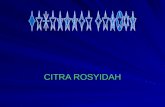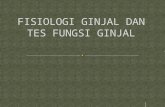TINJAUAN PUSTAKA - eprints.ung.ac.ideprints.ung.ac.id/6200/3/2012-1-48401-821309015-bab2... ·...
Transcript of TINJAUAN PUSTAKA - eprints.ung.ac.ideprints.ung.ac.id/6200/3/2012-1-48401-821309015-bab2... ·...

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sejarah Farmasi Klinik
Sejak masa Hipocrates (460-370 SM) yang dikenal sebagai “Bapak Ilmu
Kedokteran”, belum dikenal adanya profesi Farmasi. Seorang dokter yang
mendignosis penyakit, juga sekaligus merupakan seorang “Apoteker” yang
menyiapkan obat. Semakin lama masalah penyediaan obat semakin rumit, baik
formula maupun pembuatannya, sehingga dibutuhkan adanya suatu keahlian
tersendiri. Pada tahun 1240 M, Raja Jerman Frederick II memerintahkan
pemisahan secara resmi antara Farmasi dan Kedokteran dalam dekritnya yang
terkenal “Two Silices”. Dari sejarah ini, satu hal yang perlu direnungkan adalah
bahwa akar ilmu farmasi dan ilmu kedokteran adalah sama.
Dampak revolusi industri merambah dunia farmasi dengan timbulnya
industri-industri obat, sehingga terpisahlah kegiatan farmasi di bidang industri obat
dan di bidang “penyedia/peracik” obat ( apotek ). Dalam hal ini keahlian
kefarmasian jauh lebih dibutuhkan di sebuah industri farmasi dari pada apotek.
Dapat dikatakan bahwa farmasi identik dengan teknologi pembuatan obat.
Buku Pharmaceutical handbook menyatakan bahwa farmasi merupakan
bidang yang menyangkut semua aspek obat, meliputi : isolasi/sintesis, pembuatan,
pengendalian, distribusi dan penggunaan.

Sedangkan Herfindal dalam bukunya “Clinical Pharmacy and
Therapeutics” (1992) menyatakan bahwa Pharmacist harus memberikan
“Therapeutic Judgement” dari pada hanya sebagai sumber informasi obat.
Silverman dan Lee (1974) dalam bukunya, “Pills, Profits and Politics”,
menyatakan bahwa :
1) Pharmacist lah yang memegang peranan penting dalam membantu dokter
menuliskan resep rasional. Membantu melihat bahwa obat yang tepat, pada
waktu yang tepat, dalam jumlah yang benar, membuat pasien tahu mengenai
“bagaimana, kapan, mengapa” penggunaan obat baik dengan atau tanpa resep
dokter.
2) Pharmacist lah yang sangat handal dan terlatih serta pakar dalam hal
produk/produksi obat yang memiliki kesempatan yang paling besar untuk
mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang obat, yang dapat melayani
baik dokter maupun pasien, sebagai “penasehat” yang berpengalaman.
3) Pharmacist lah yang meupakan posisi kunci dalam mencegah penggunaan obat
yang salah, penyalahgunaan obat dan penulisan resep yang irrasional
Istilah farmasi klinik mulai muncul pada tahun 1960an di Amerika,
dengan penekanan pada fungsi farmasis yang bekerja langsung bersentuhan
dengan pasien. Saat itu farmasi klinik merupakan suatu disiplin ilmu dan profesi
yang relatif baru, di mana munculnya disiplin ini berawal dari ketidakpuasan atas
norma praktek pelayanan kesehatan pada saat itu dan adanya kebutuhan yang
meningkat terhadap tenaga kesehatan profesional yang memiliki pengetahuan
komprehensif mengenai pengobatan. Gerakan munculnya farmasi klinik dimulai

dari University of Michigan dan University of Kentucky pada tahun 1960-an
(Miller,1981).
Pada era itu, praktek kefarmasian di Amerika bersifat stagnan. Pelayanan
kesehatan sangat terpusat pada dokter, di mana kontak apoteker dengan pasien
sangat minimal. Konsep farmasi klinik muncul dari sebuah konferensi tentang
informasi obat pada tahun 1965 yang diselenggarakan di Carnahan House, dan
didukung oleh American Society of Hospital Pharmacy (ASHP). Pada saat itu
disajikan proyek percontohan yang disebut “9th floor project” yang
diselenggarakan di University of California. “Perkawinan” antara pemberian
informasi obat dengan pemantauan terapi pasien oleh farmasis di RS mengawali
kelahiran suatu konsep baru dalam pelayanan farmasi yang oleh para anggota
delegasi konferensi disebut sebagai farmasi klinik. Hal ini membawa implikasi
terhadap perubahan kurikulum pendidikan farmasi di Amerika saat itu,
menyesuaikan dengan kebutuhan akan adanya farmasis yang memiliki keahlian
klinik.
Perubahan visi pada pelayanan farmasi ini mendapat dukungan signifikan
ketika Hepler dan Strand (Hepler dan Strands, 1990) pada tahun 1990
memperkenalkan istilah pharmaceutical care. Pada dekade berikutnya, kata itu
menjadi semacam kata “sakti” yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi
farmasi di dunia. Istilah pharmaceutical care, yang di-Indonesia-kan menjadi
“asuhan kefarmasian”, adalah suatu pelayanan yang berpusat pada pasien dan
berorientasi terhadap outcome pasien. Pada model praktek pelayanan semacam ini,

farmasis menjadi salah satu anggota kunci pada tim pelayanan kesehatan, dengan
tanggung jawab pada outcome pengobatan.
Perkembangan peran farmasi yang berorientasi pada pasien semakin
diperkuat pada tahun 2000, ketika organisasi profesi farmasis klinik Amerika
American College of Clinical Pharmacy (ACCP) mempublikasikan sebuah
makalah berjudul, “A vision of pharmacy’s future roles, responsibilities, and
manpower needs in the United States.” Untuk 10-15 tahun ke depan, ACCP
menetapkan suatu visi bahwa farmasis akan menjadi penyedia pelayanan
kesehatan yang akuntabel dalam terapi obat yang optimal untuk pencegahan dan
penyembuhan penyakit (ACCP, 2008). Untuk mencapai visi tersebut, harus
dipastikan adanya farmasis klinik yang terlatih dan mendapat pendidikan
memadai.
Dalam sistem pelayanan kesehatan, farmasis klinik adalah ahli pengobatan
dalam terapi. Mereka bertugas melakukan evaluasi pengobatan dan memberikan
rekomendasi pengobatan, baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain.
Farmasis klinik merupakan sumber utama informasi ilmiah yang dapat dipercaya
tentang obat dan penggunaannya, memberikan informasi terkait dengan
penggunaan obat yang aman, tepat, dan cost-effective.
Konsep farmasi klinik pun kemudian berkembang di berbagai negara di
dunia, termasuk Indonesia, dengan penerapan yang bervariasi pada tiap negara
berdasarkan kondisi masing-masing.
2.2 DRUG RELATED PROBLEM

Drug Related Problems (DRPs) dapat juga dikatakan sebagai suatu
pengalaman atau kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami oleh pasien
yang melibatkan atau diduga berkaitan dengan terapi obat dan secara actual
maupun potensial mempengaruhi outcome terapi pasien (Cipolle et al., 1998).
DRPs ada dua yaitu DRPs aktual dan potensial. Keduanya memiliki perbedaan,
tetapi pada kenyataannya problem yang muncul tidak selalu terjadi dengan segera
dalam prakteknya. DRPs aktual adalah suatu masalah yang telah terjadi dan
farmasis wajib mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Sedangkan potensial,
karena resiko yang sedang berkembang jika farmasis tidak turun tangan (Rovers,
et al., 2003).
Tabel 1. Kategori DRPs dan penyebabnya
Kategori DRP Penyebab DRPIndikasi yang tidak diterapi a. Pasien membutuhkan terapi obat
barub. Pasien menderita penyakit kronis
sehingga membutuhkan terapi obatlanjutan.
c. Pasien membutuhkan kombinasiobat untuk memperoleh efeksinergis.
d. Pasien beresiko mengalami kejadianyang tidak diharapkan akibat terapiobat yang dapat dicegah denganterapi profilaksis.
Pemilihan obat tidak tepat a. Pasien mempunyai riwayat alergiterhadap obat yang diterima.
b. Obat yang diterima pasien bukanmerupakan obat yang paling efektif.
c. Pasien mempunyai kontra indikasiterhadap obat yang diterima.
d. Pasien menerima obat efektif tetapibukan yang paling murah.
e. Obat yang diterima pasien tidakefektif terhadap bakteri penyebabinfeksi (bakteri bersifat resisten

terhadap obat).f. Pasien menerime kombinasi obat
yang sebenernya tidakperlu.
Penggunaan obat tanpaIndikasi
a. Pasien menerima obat tanpa indikasimedis yang jelas.
b. Adanya duplikasi terapi.c. Pasien menerima obat untuk
mengatasi efek samping obat lainyang sebenarnya dapat dicegah.
d. Terapi non obat (misalnyaperubahan pola hidup) lebihbaik untuk pasien.
Dosis kurang a. Dosis obat yang diberikan terlalurendah untuk menghasilkan responyang diharapkan.
b. Kadar obat dalam darah pasiendibawah kisaran terapi.
c. Frekuensi pemberian, durasi terapi,dan cara pemberian obat pada pasientidak tepat.
d. Waktu pemberian profilaksis tidaktepat (misalnyaprofilaksis pembedahan diberikan
terlalu awal)
Dosis Lebih a. Dosis obat yang diberikan terlalutinggi.
b. Kadar obat dalam darah pasienmelebihi kisaran terapi.
c. Dosis obat dinaikkan terlalu cepat.d. Frekuensi pemberian, durasi terapi
dan cara pemberian obat pada pasientidak tepat
Adverse Drug Reaction (ADR) a. Pasien mengalami reaksi alergiterhadap obat.
b. Pasien mempunyai resikomengalami efek samping obat.
c. Pasien mengalami reaksiidiosinkrasi terhadap obat.
d. Biavailabilitas obat berubah akibatinteraksi obat dengan obat lain ataudengan makanan.

e. Efek obat berubah akibat inhibisiatau induksi enzim oleh obat lain.
f. Efek obat berubah akibatpenggantian ikatan antara obatdengan protein aleh obat lain.
Kegagalan dalam menerimaObat
a. Pasien gagal menerima obat yangtepat karena adanya medicationerrors.
b. Pasien tidak mampu membeli obat(obat terlalu mahal untuk pasien).
c. Pasien tidak memahami petunjukpenggunaan obat.
d. Pasien tidak mau minum obat(misalnya karena rasaobat tidak enak).
(Cipolle, et al., 1998)
2.3 Ginjal
Ginjal merupakan sepasang organ berbentuk kacang buncis yang terletak
dekat punggung bagian tengah, persis di bawah sangkar tulang rusuk sebelah
kanan dan kiri tulang punggung. Masing-masing ginjal berukuran 10-15 cm
panjangnya dan berat sekitar 160 gram. Setiap hari kedua ginjal tersebut
mengeluarkan sekitar 1,5 sampai 2,5 liter urine.
Fungsi utama ginjal yaitu :
1. Mempertahankan keseimbangan air dan kadar unsur kimia ( elektrolit,
hormone, gula darah, dll) dalam cairan tubuh.
Fungsi dasar ginjal (terutama nefron) adalah untuk membersihkan atau
menjernihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak diperlukan dicegah agar
tidak diserap ulang. Sementara zat-zat yang diperlukan, terutama air dan
banyak elektrolit, diserap kembali ke darah. Ketika kadar zat-zat dalam darah
dipertahankan, jumlah zat-zat dalam cairan tubuh lain juga dipertahankan.

2. Mengatur Tekanan Darah
Laju cairan yang disaring dalam ginjal dipengaruhi besarnya tekanan darah
dalam arteri. Jika tekanan meningkat berlipat ganda, pengeluaran urine dapat
meningkat delapan kali lipat. Ini akan mengakibatkan hilangnya cairan tubuh
lebih banyak sampai volume darah menjadi kurang cukup mengembalikan ke
keadaan normal. Di sisi lain, jika tekanan darah sangat rendah, aliran darah
dalam ginjal menurun. Diikuti dengan penurunan kecepatan penyaringan
cairan. Sebagai akibatnya, ginjal cenderung menahan garam dan air untuk
meningkatkan tekanan pada tingkat normal.
3. Membantu Mengendalikan Keseimbangan Asam-Basa Darah
Jika berbicara mengenai pengaturan keseimbangan asam basa, biasanya berarti
pengaturan konsentrasi ion hydrogen dalam cairan tubuh. Jika ion hydrogen
menyimpang dari nilai normal, ginjal akan membentuk urine asam maupun
alkaline. Dengan begitu ginjal akan membantu menyesuaikan kembali
konsentrasi ion hydrogen untuk mempertahan keseimbangannya pada tingkat
normal,. Jika keseimbangan asam basa tidak diatur seperti pada beberapa
kondisi di mana pasien mengalami asidosis, ini bisa menuntun pada keadaan
koma dan akhirnya mati. Disisi lain, jika pasien mengalami alkalosis,
kematian bisa jadi merupakan akibat dari tetanus atau kejang.
4. Membuang Sisa Bahan Kimia Dari Dalam Tubuh
Dari waktu ke waktu darah kita mengumpulkan zat-zat yang harus dibuang.
Ini termasuk produksi akhir dari metabolisme seperti urea, keratin, asam urat
dan urates. Selain itu, banyak zat lain seperti ion sodium, potassium, klorida

dan hydrogen cenderung menumpuk dalam darah dengan jumlah yang
berlebihan. Oleh sebab itu fungsi ginjal adalah membersihakan kelebihan itu.
5. Bertindak sebagai kelenjar- menghasilkan hormone dan enzim , yang
memilki fungsi penting dalam tubuh.
Zat-zat berikut dihasilkan oleh ginjal:
Rennin : sebuah enzim yang mengatur tekanan darah.
Bentuk aktif vitamin D: membantu mempertahankan penyerapan kalsium
untuk pembentukan tulang. Pada saat yang sama mempertahankan
keseimbangan kalsium dalam tubuh.
Erythtropoletin : sebuah hormone yang merangsang sumsum tulang untuk
membuat sel darah merah.
2.3.1 Anatomi dan fisiologi ginjal dan saluran kemih
Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan komposisi
kimia darah (dan linkungan dalam tubuh) dengan mengeksresikan zat terlarut dan
air secara selektif. Apabila kedua ginjal karena sesuatu hal gagal menjalankan
fungsinya, akan terjadi kematian dalam waktu 3-4 minggu. Fungsi vital ginjal
dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus, diikuti dengan reabsorbsi
sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai disepanjang tubulus ginjal.
Kelebihan zat terlarut dan air dieksresikan keluar tubuh dalam urin melalui system
pengumpul urin.
1. Saluran kemih
Saluran kemih terdiri dari ginjal yang terus-menerus menghasilkan urine, dan
berbagai saluran dan resevoar yang dibutuhklan untuk membawa urine keluar

tubuh . Ginjal merupakan oragan berbentuk kacang terletak di kedua sisi kolumna
vertebralis. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kirin karena
tertekan kebawah hati . kutub atasnya terletak lebih tinggi setinggi iga kedua
belas. Sedangkan kutub atas ginjal kiri terletak setinggi iga kesebelas.
Kedua ureter merupakan saluran yang panjangnya sekitar 10 – 12 inci (25-30 cm),
terbentang dari ginjal sampai vesika urinaria. Fungsi satu-satunya adalah
menyalurkan urine ke vesika urinaria.
Vesika urinaria adalah suatu kantong berotot yang dapat mengempis, terletak
dibelakang simfisis pubis. Vesika urinaria mempunyai tiga muara : dua dari ureter
dan satu menuju uretra. Dua fungsi urinaria adalah : (a) sebagai tempat
pemyimpanan urine sebelum meninggalkan tubuh dan (b) berfungsi mendorong
urine keluar dari tubuh (dibantu uretra).
Uretra dalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari vesika urinaria
sampai keluar tubuh. Panjang pada perempuan sekitar 11/2 inci (4 cm) dan pda
laki-laki 8 inci (20 cm). Muara urerta keluar tubuh disebut meatus urinarius.
2. Nefron
Unit kerja fungsional ginjal disebut sebagai nefron. Dalam setiap ginjal
terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai strukur dan fungsi
yang sama. Dengan demikian, kerja ginjal dapat dianggap sebagai jumlah total
dari fungsi semua nefron tersebut . Setiap nefron terdiri dari kapsula bowman
yang mengitari rumbai kapiler glomerulus, tubulus kontortus proksimal,
Lengkung henle, dan tubulus kontortus distal, yang mengosongkan diri ke duktus

pengumpul. Orang yang normal masih dapat bertahan (walaupun dengan susah
payah) dengan jumlah nefron kurang dari 20.000 atau 1% dari massa nefron total.
Dengan demikian, masih mungkin untuk transplantasi tanpa ,membahayakan
kehidupan.
3. Korpuskulus Ginjal
Korpuskulus ginjal terdiri dari kapsul bowman dan rumbai kapiler glomerulus.
Istilah glomerulus seringkali digunakan untuk menyatakan korpuskulus ginjal
walaupun glomurulus lebih sesuia untuk meyatakan rumbai kapiler. Kapsula
bowman merupakan suatu invaginasi dari tubulus proksimal. Terdapat ruang yang
mengandung urine antara rumbai kapiler dan kapsula bowman dan ruang yang
mengandung urine ini diikenal dengan nama ruang bowman atau ruang kapsular.
Kapsula bowman dilapisi oleh sel-sel epitel. Sel epitel parietalis berbentuk gepeng
dan membentuk bagian terluar dari kapsula, sel epitel viseralis jauh lebih besar
dan membentuk bagian dalam kapsula dan juga melapisi bagian luar dari rumbai
kapiler. Sel viseralis membentuk tonjolan-tonjolan atau kaki-kaki yang dikenal
sebagai podosit yang bersinggungan dengan membrane basalis pada jarak-jarak
tertentu sehingga terdapat daerah-daerah yang bebas dari kontak antar sel epitel.
2.3.2 Penyebab penyakit ginjal
1. Infeksi
Infeksi dapat terjadi dibeberapa bagian ginjal yang berbeda. Ini termasuk
unit penyaringan atau glomerulus pada kasus glomerulonefritis atau renal
pelvis dan sel tubulointerstitial pada pielonefritis. Infeksi juga bisa naik dari
kandung kemih melewati ureter menuju ginjal dimana terdapat sumbatan

disaluran kencing bawah. Beberapa infeksi dapat menunjukkan gejala
sementara yangt lain tanpa gejala. Jika tidak diperhatikan, semakin banyak
jaringan fungsional ginjal yang perlahan-lahan hilang. Selama proses
peradangan tubuh kita secara normal berusaha menyembuhkan diri. Hasil
akhir penyembuhan adalah adanya bekas luka jaringan dan atrofi sel (sel yang
menyusut jadi kecil) yang mengubah fungsi penyaringan ginjal. Ini merupakan
kondisi yang tidak dapat dipulihkan. Jika presentase jaringan yang rusak besar
akan berakhir pada kegagalan ginjal.
2. Obat-obatan
Sebagian besar obat dieksresikan lewat ginjal. Padahal, banyak dari obat-
obatan ini bersifat racun, oleh sebab itu istilahnya disebut nefrotoksik. Ini
termasuk:
a. Antibiotik
Aminoglikosid, sulfonamid, amphotericin B, polymyxin, neomycin,
bacitracin, rifampicin, aminosalicylic acid, oxy- dan chlortetracyclines.
b. Analgesic ( pereda sakit)
Salisilat, acetaminofhen, phenacetin, dan NSAID, phenylbutazone, semua
penghambat prostaglandin synthetase.
c. Antiepilektik ( untuk epilepsy dan kejang)
Trimethadione, paramethadione, succinamide, carbamezapine.
d. Obat-obat anti kanker

Cyclosporine, cisplatin, cyclophospamide, streptozocin, methotrexate,
nitrosoureas, (CCNU, BCNU, methyl,CCNU), doxorubicin, daunorobicin.
e. Immune –complex inducers ( obat-obat untuk kekebalan tubuh)
Penicillamine, captopril levamisole, gold salt.
3. Bahan nefrotoksik umum lainnya.
a. Logam berat : klorida merkuri anorganik, garam merkuri anorganik,
timah anorganik, cadmium, uranium, emas, tembaga, arsenic, besi,
kromium. Talium, selenium, vanadium, bismuth.
b. Pelarut : methanol , alcohol, amylglikol etilen, dietilen glikol, cellosolves,
karbontetra klorida, trikloroetilen, aneka hidrokarbon.
c. Bahan pembentuk oxalosis: asam oksalat, methoxyflurane, glikol etilen,
asam askorbat, bahan anti karat.
d. Herbisida dan peptisida : paraquat, sianida, dioksin, dipenil,
cycloheximide, dan organoklorin insektisida.
e. Bahan diagnostic : sodium iodide, semua bahan kontras organic iodide.
f. Bahan botanical dan biological : mushroom (misalnya Amanita
phallodes- racun muscarine berat)
g. Methemoglobin forms ( pembentuk methehoglobin) : bahan- bahan
medis, industry dan makanan yang memabukkan.
4. Makanan protein hewani
Terlalu banyak protein dalam makanan menuntun pada kerusakan ginjal dan
gagal ginjal dini. Anjuran asupan tiap hati (RDA) dari protein sekitar 0,8 gr
untuk setiap kilogram berat badan.banyak penelitian menunjukkan adanya

hubungan antara makanan tinggi protein dan kerusakan ginjal. Asupan
protein hewani yang berlebih bertanggung jawab pada eksresi kalsium yang
lebih banyak melalui ginjal dan juga berkaitan dengan meningkatnya resiko
berkembangnya batu ginjal terutama batu kalsium.
2.3.3 Uji Fungsi Ginjal
Uji fungsi ginjal hanya menggambarkan penyakit ginjal secara kasar atau
garis besar saja dan lebih dari setengah bagian ginjal harus mengalami kerusakan
sebelum terlihat nyata adanya gangguan ginjal. Ada beberapa metode yang dapat
digunakan untuk memperkirakan fungsi ginjal dan menunjukkan apakah ada
penyakit ginjal jenis apapun. Ini meliputi :
1. Kreatinin serum
Kreatinin serum merupakan produk sampingan dari metabolisme otot rangka
normal. Laju produksinya bersifat tetap dan sebanding dengan jumlah massa otot
tubuh. Kreatinin dieksresikan terutama oleh filtrasi glomeruler dengan sejumlah
kecil yang disekresikan atau direabsorsi oleh tubulus. Bila massa otot tetap, maka
adanya perubahan pada kreatinin mencerminkan perubahan pada klirens melalui
filtrasi, sehingga dapat dijadikan indicator fungsi ginjal. Nilai kreatinin serum
yang normal berbeda menurut jenis kelamin, usia dan ukuran. Kreatinin serum
meningkat pada gagal ginjal. Namun ada beberapa factor yang mempengaruhi
kadar kreatinin serum. Diet, saat pengukuran, usia penderita, jenis kelamin, berat
badan, latihan fisik, keadaan pasien dan obat.
2. Klirens kreatinin ( Klkr)

Dalam keadaan normal, kreatinin tidak disekresi atau direabsopsi oleh tubuluh
ginjal dalma jumlah yang bermakna. Oleh karena itu eksresi terutama ditentukan
oleh filtrasi glomeruler, sehinnga laju filtrasi glomeruler (LFG) dapat diperkirakan
melalui penentuan laju klirens kreatinin endogen. Bila massa obat tetap, maka
perubahan apapun pada klirens kreatinin akan mencerminkan perubahan pada laju
klirensnya melalui filtrasi. Nilai klirens kreatinin berbeda menurut usia, jenis
kelamin dan ukuran tubuh . LFG misalnya, berkurang sesuai peningkatan usia
(terutama pada pria dibanding wanita).
3. Urea
Urea disintesa dalam hati seagai produk metabolisme makanan dan protein
endogen. Eliminasinya dalam urin menggambarkan eksresikan utama nitrogen.
Laju produksi lebih beragam dibandingkan kreatinin. Urea disaring oleh
glomerulus dan sebagian reabsorbsi oleh tubulus. Kadar diatas 10 mmol/liter
mungkin mencerminkan gangguan ginjal walaupun kecendrungan dalam individu
lebih penting dibandingkan dengan satu hasil pengukuran semata. Urea adalah
penguuran yang kurang tepat menggambarkan fungsi ginjal tetapi sering
digunakan sebagai perkiraan kasar, karena dapat memberikan informasi mengenai
keadaan umum penderita beserta tingkat hidrasinya.
2.4 Jenis – Jenis Gangguan Fungsi Ginjal
2.4.1 Gagal Ginjal Akut
Ini adalah kondisi di mana ginjal berhenti bekerja seluruhnya atau hamper
seluruhnya. Penyebab palng umum adalah:

Glomerulonefritis akut, ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh
reaksi kekebalan yang tidak normal. Sekitar 95 % pasien akan menderita
glomerulonefritis akut satu sampai tiga minggu seseudah terjadi infeksi ditempat
lain dalam tubuh. Ini karena beberapa tipe tertentu bakteri yang disebut
betastreptococci kelompok A. Infeksi itu baik berupa sakit tenggorokan,
tonsillitis, atau bahkan infeksi kulit. Infeksi ini memicu berkembangnya kompleks
antigen-antibodi yang tersimpan dalam saringan dan dapat menyebabkan
sumbatan secara keseluruhan. Secara tidak normal, protein dan darah bocr ke
saringan glomerular yang mengakibatkan adanya darah dalam urin.
Tubular nekrosis, ini merupakan kerusakan sel epitel dalam tubulus,
penyebabnya termasuk racun-racun ginjal. Contoh racun ginjal adalah karbon
tetraklorida dan logam berat seperti ion merkuri. Zat-zat ini begitu beracun
terhadap sel epitel tubular, sehingga menyebabkan banyak kematian. Ketika sel-
sel ini terlepas dari tempatnya, sel-sel tersebut tersangkut ditubulus. Perbaikan
bisa terjadi 10-20 hari dengan pertumbuhan sel tubular yang baru.
Iskemia ginjal akut berat, kehilangan suplai darah yang berat dalam
ginjal biasanya akibat syok sirkulasi berat. Pada syok, jantung gagal
memompakan cukup darah yang benutrisi pada berbagai bagian yang berbeda dari
tubuh. Pembuluh darah dalam ginjal cenderung mengecil dalam usaha
mempertahankan tekanan darah. Akibatnya, kurangnya nurtisi yang adekuat
(memadai) sering menghancurkan banyak sel epitel tubular yang menyebabkan
sel-sel mati ini menyumbat banyak nefron.

Reaksi transfusi, reaksi transfuse yang berat biasanya berakibat pada
rusaknya sel darah merah yang jumlah besar (hemolisis) yang melepaskan
hemoglobin lebih kecil daripada pori-pori saringan, hemoglobin dengan mudah
melalui saringan glomerular. Karena konsentrasi hemoglobin meningkat
cenderung mengakibatkan penumpukan nefron sehingga timbul sumbatan. Selain
itu, kerusakan darah merah menyebabkan pelepasan bahan konstruksi dalam
aliran darah, menyebabkan suplai darah yang buruk pada ginjal dan tubular yang
rusak.
2.4.2 Penyakit ginjal Hipertensi
Hipertensi renal hipertensif dalam pembulu darah dan unit penyaringan
atau glomeruli dapat menyebabkan darah tinggi, tetapi belum tentu menyebabkan
gagal ginjal. Jika terdapat aliran darah yang rendah atau kecepatan saringan
glomerular rendah, akan terjadi retensi garam dan air. Ketika tekanan darah
meningkat untuk kompensasi, kecepatan filtrasi glomerular seluruhnya kembali
normal. Selama nefron tidak dihancurkan, tidak akan terjadi kegagalan.
Peningkatan tekanan darah adalah respon mekanisme rennin-angiostensin seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya.
2.4.3 Sindroma Nefrotik
Keadaan ini ditandai dengan hilangnya banyak plasma protein atau karena
albumin yang masuk ke dalam urin. Penyebab kebocoran ini adalah peningkatan
permeabilitas membran glomerular. Penyakit-penyakit yang menyebabkan
peningkatan permeabilitas tersebut adalah : glomerulonefritis akut, zat-zat protein

abnormal dalam dinding pembuluh darah (amyloidosis), dan perubahan minimal
sindroma nefrotik.
2.4.4 Gagal Ginjal Kronik
Gagal ginjal kronik atau penyakit renal tahap akhir (ESRD) merupakan
gangguan fungsi yang progresif dan irreversibel dimana kemampuan tubuh gagal
untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit,
menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lainnya dalam darah.
(Brunner & Suddart edisi 8 vol 2, 2001)
Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi
yang beragam , mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan pada
umumnya berakhir dengan gagal ginjal kronik. Selanjutnya gagal ginjal adalah
suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang
irreversible, pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang
tetap berupa dialysis atau transplantasi ginjal.( Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam
jilid 1 Edisi IV 2006)
2.5 Patofisiologi
a. Fungsi renal menurun, produk akhir metabolisme protein ( yang normal
dieksresikan ke dalam urine) tertimbun dalam darah. Terjadi uremia dan
mempengaruhi setiap system tubuh, semakin banyak timbunan produk sampah
maka gejala akan semakin berat.
b. Gangguan klirens renal. Banyak masalah muncul pada gagal ginjal sebagai
akibat dari penurunan jumlah glumeruli yang berfungsi, yang menyebabkan

penurunan klirens substansi darah yang seharusnya dibersihakan oleh ginjal.
Dengan menurunnya fungsi glumeruli maka klirens keratin akan menurun dan
kadar keratin darah meningkat. Selain itu kadar nitrogen urea darah (BUN)
biasanya meningkat. Keratin merupakan indicator yang paling sensitive dari
fungsi renal subsans ini diproduksi secara konstan oleh tubuh.
c. Retensi cairan dan natrium. Ginjal juga tidak mampu umtuk
mengkonsentrasikan atau mengencerkan urine secra normal pada penyakit
ginjal tahap akhir, respon ginjal yang sesuai terhadap masukan cairan dan
ekektrolit sehari-hari tidak terjadi. Natrium dan cairan yang tertimbun akan
meningkatkan resiko terjadinya edema, gagal jantung kongesti dan hipertensi.
Hipertensi dapat terjadi akibat aktivasi aksis rennin angiostensin dan
kerjasama keduanya meningkatkan sekresi hormonal aldosteron.
Kecenderungan yang lain adalah hilangnya garam yang mengakibatkan resiko
hipotensi dan hipovolemia. Episode muntah dan diare menyebabkan
menipiskan air dan natrium yang semakin memperburuk status uremik.
d. Asidosis metabolic terjadi karena ketidakmampuan ginjal dalam
mengekskersikan muatan asam (H+) yang berlebihan. Penurunan sekresi asam
terutama akibat ketidakmampuan tubulus ginjal untuk sekresi ammonia (NH3-
) dan mengabsorpsi natrium bikarbonat. Penurunan eksresi fosfat dan asam
organic lain juga terganggu.
e. Anemia, terjadi karena produksi eritropoetin oleh ginjal yang tidak adekuat,
memendeknya usia sel darah merah, defesiensi nutrisi dan kecenderungan
mengalami pendarahan akibat status uremik pasien terutama dari saluran

gastrointerstinal. Fungsi eritropoetin adalah untuk menstimulsi sumsum tulang
dalam pembentukan sel darah merah.
f. Ketidak seimbangan kalsium dan fosfat, kadar serum kalsium dan fosfat
mempunyai hubungan timbal balik, jika salah satu meningkat yang lain turun.
Dengan menurunnya filtrasi melalui glumerulus ginjal, terdapat peningkatan
kadar fosfat serum menyebabkan sekresi parathormon dari kelenjar paratiroid.
Namun pada gagal ginjal tubuh tidak merespon secara normal terhadap
peningkatan sekresi parathormon, akibatnya kalsium ditulang menurun
menyebabkan perubahan pada tulang penyakit ginjal.
2.6 Etiologi
a. Amerika serikat( 1995-1999)
Diabetes mellitus : DM tipe 1 adalah 7%, DM tipe 2 adalah 37% (total) 47%.
Hipertensi dan penyakit pembuluh darah besar 27 %
Glumerulonefritis 10 %
b. Indonesia (tahun 2000) menurut Pernefri
Glumerulonefritis : 46, 39 %
Diabetes mellitus : 18, 65 %
Obstruksi dan infeksi : 12, 85 %
Hipertensi : 8, 46%
Sebab lain : 13, 65%
2.7 Hemodialisis

Dialysis merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan
cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ginjal tidak mampu melaksanakan
proses tersebut. (Brunner & Suddart, 2001).
Hemodialisis berasal dari kata haemo yang berarti darah dan dialysis yang
berarti dipisahkan. Hemodialisis merupakansalah satu dari terapi pengganti
Ginjal, yang digunakan pada penderita dengan penurunan fungsi ginjal, baik itu
akut maupun kronik. Prinsip dasar dari Hemodialisis adalah dengan menerapkan
proses osmotik dan ultrafiltrasi pada ginjal buatan, dalam membuang sisa-sisa
metabolisme tubuh. Hemodialisis dapat dikerjakan untuk sementara waktu
(misalnya pada gagal ginjal akut) atau dapat pula untuk seumur hidup (misalnya
pada gagal ginjal kronik).
1. Tujuan Hemodialisis
a. Untuk mengambil zat-zat nitrogen yang toksik dari dalam darah dan
mengeluarkan air yang berlebihan.
b. Untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan pasien sampai fungsi
ginjal pulih kembali.
2. Indikasi
a. LFG < 5 ml/ menit
b. Keadaan umum buruk dan gejala klinis nyata
c. Nilai kalium darah > 6 mEq/ L
d. Nilai ureum darah > 200 mg/dl
e. PH darah < 7,1
f. Cairan overload.

3. Prinsip- prinsip Dasar Hemodialisis
Berdasarkan prinsip yang mendasar hemodialisis
a. Difusi : Proses pemindahan toksin dan zat limbah dari konsentrasi yang
lebih tinggi ke cairan dialisat dengan konsentrasi yang lebih rendah.
Cairan dialisat tersusun dari semua elektolit yang penting dengan
konsentrasi ekstrasel yang ideal. Kadar elektrolit darah dapat dikendalikan
dengan mengatur rendaman dialisat (dialysate bath) secara tepat. Pori-pori
kecil dalam membrane semipermeabel tidak memungkinkan lolosnya sel
darah merah dan protein.
b. Osmosis : air yang berlebihan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses
osmosis. Pengeluaran air dapat dikendalikan dengan menciptakan tekanan
gradient, dengan kata lain air bergerak dari daerah tekanan yang lebih
tinggi(tubuh pasien) ke tekanan yang lebih rendah (cairan dialisat)
c. Ultafiltrasi : tekanan negative diterapkan pada alat (mesin dialysis) sebagai
kekuatan pengisap pada membrane dan memfasilitasi peneluaran air.
Karena pasien tidak dapat mengeksresikan air, kekuatan ini diperlukan
untuk mengeluarkan cairan hingga tercapai isovolemia (keseimbangan
cairan)
d. System buffer tubuh dipertahankan dengan penambahan asetat yang akan
berdifusi dari cairan dialisat ke dalam darah pasien dan mengalami
metabolisme untuk membentuk bikarbonat. Darah yang sudah
dibersihakan kemudian dikembalikan ke dalam tubuh melalui pembuluh
darah vena pasien. Pada akhir terapi hemodialisis banyak zat limbah telah

dikeluarkan, keseimbangan elektrolit sudah dipulihkan dan sitem buffer
juga telah diperbaharui.(Price. 2006)
2.8 Dosis
2.8.1 Pengertian Dosis
Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dosis adalah dosis maksimum
dwwasa untuk pemakaian melalui mulut, injeksi subkutan dan rectal.
Selain dosis maksimum dikenal juga dosis lazim. Dalam FI ed III tercantum
dosis lazim untuk dewasa dan bayi atau anak yang merupakan takaran petunjuk
yang tidak mengikat.
Dosis atau takaran suatu obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat
dipergunakan atau diberikan untuk obat dalam maupun obat luar.
2.8.2 Macam- Macam Dosis
1. Dosis terapi , suatu takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dapat
dan dapat menyembuhkan penderita.
2. Dosis minimum, suatu takaran obat terkecil yang diberikan yang masih dapat
menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi pada penderita.
3. Dosis maksimum, suatu takaran obat terbesar yang diberikan yang masih
dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita.
4. Dosis letal, takaran suatu obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan
kematian pada penderita
a. L.D 50 : takaran yang menyebabkan kematian pada 50% hewan
percobaan.

b. L.D 100: takaran yang menyebabkan kematian pada 100% pada hewan
percobaan
5. Dosis toksis : suatu takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat
menyebabkan keracunan pada penderita. (Syamsuni. 2007)
2.9 Prinsip penyesuaian dosis pada gangguan ginjal
Peresepan untuk penderita dengan gagal ginjal memerlukan pengetahuan
mengenai fungsi hati dan ginjal penderita, riwayat pengobatan, metabolisme, dan
aktivitas obat, lama kerja obat serta cara eksresinya. Tingkatan fungsi ginjal yang
memerlukan penurunan dosis tergantung beberapa obat yang secara noral
dikeluaran melalui ginjal dan beberapa bagian yang melalui rute metabolisme lain
serta seberapa toksik obat tersebut.
1. Rute eliminasi, eliminasi obat merupakan parameter yang paling penting
untuk dipertimbangkan pada saat penentuan dosis karena eliminasi obat atau
metabolitnya mungkin menurun sehngga menyebabkan peningkatan efek
farmakologis atau toksisitas.
2. Indeks terapi, indeks terapi suatu obat merupakan pengukuran secara garis
besar mengenai keamanan obat jika digunakan, dengan cara memperlihatkan
hubungan antara dosis efektis dan toksiknya.
3. Penyesuaian dosis, pengobatan yang benar-benar bermanfaat diperlukan oleh
pasien dengan gangguan ginjal dan penyesuain dosis berupa penurunan
terhadap total dosis penjagaan hatian sering kali diperlukan. Perubahan dosis
obat yang hanya memiliki efek samping ringan atau tidak tergantung dosis,

perubahan pemberian obat yang sangat rinci tidak penting dan cukup
menggunakan skema penurunan secara sederhana.
4. Obat yang bersifat nefrotoksik, obat yang bersifat nefrotoksik sedapat
mungkin harus dihindari pada pasien penyakit ginjal karena efek yang
diakibatkan oleh nefrotoksisitasmya akan lebih berbahaya, jika cadangan
ginjal menurun. Idealnya obat yang digunakan untuk mengobati penderita
ginjal memiliki karakteristik berikut:
a. Tidak menghasilkan metabolit aktif
b. Disposisi obat tidak dipengaruhi oleh perubahan keseimbangan cairan
c. Disposisi obat tidak dipengaruhi oleh perubahan ikatan protein
d. Respon obat tidak dipengaruhi oleh perubahan kepekatan jaringan
e. Mempunyai/ rentang terapi yang lebar
f. Tidak bersifat nefrotoksik
5. Perhitungan dosis, anjuran dosis didasarkan pada tingkatan keparahan
gangguan ginjal, yang biasanya dinyatakan dengan istilah laju filtrasi
glomeruler (LFG), umumnya diperkirankan dengan mengukur klirens
kreatinin. Jika dianggap klirens kreatinin normal adalah 120 ml/menit, maka
untuk tujuan peresepan gangguan ginjal dapat dibagi menjadi :
Tabel 2. Perbandingan nilai klirens kreatinin, LFG dengan gangguan
ginjal
Tingkat LFG Kreatinin serum
Ringan 20-50 ml/ menit 150 – 300 mikromol/L
Sedang 10-20 ml / menit 300-700 mikromol / L

Berat < 10 ml/ menit > 700 mikromol/L
Istilah gangguan ginjal sering digunakan jika LFG turun sampai dibawah 60
ml/menit tetapi tetap diatas 30 ml/menit, pada tahap ini,penderita mungkin masih
belum menunjukkan gejala apapun. Gagal ginjal dapat dijabarkan sebagai nilai
LFG dibawah 30 ml/menit, dimana gejala muncul secara jelas. Apabila LFG turun
sampai dibawah 10 ml/menit, maka keadaan ini disebut sebagai gagal ginjal
terminal atau “end stage”.
Gagal ginjal memperlihatkan adanya granul-granul pada permukaan ginjal,
fungsi ginjal menurun, ukurannya mengecil, dan pada protein urine sangat tinggi.
Obat yang telah diketahui dapat merusak ginjal melalui berbagai mekanisme.
Bentuk kerusakan yang paling sering dijumpai adalah interstitial nefritis dan
glomeruloneprihis. Obat dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal melalui dua
cara : kerusakan atau perubahan fungsi ginjal secara langsung atau kerusakan
secara tidak langsung melalui efek pada pasokan darah. Obat dapat menyebabkan
kerusakan ginjal secara langsung meliputi aminoglikosida, amfoterisin B,
cisplatin, bentuk garam dari emas, logam brat, penisilamin, metotreksat dan
radiocontrast media.
2.10 Pemerikasaan Penunjang
Untuk mementukan diagnosa pada gagal ginjal kronik dapat dilakukan cara
sebagai berikut :
1. Pemerikasaan urin, urin merupakan hasil akhir proses filtrasi, reabsorbsi dan
eksresi ginjal, dan merupakan jendela untuk mulai melihat apakah ada

kelainan pada saluran kemih. Karena pada malam hari penderita istirahat dan
tidak minum, pada umumnya kemih pertama paling kental dan terbanyak
dapat menunjukkan kelainan, sehingga pemerikasaan urin hendaknya pada
urin yang pertama keluar pagi hari.
2. Pemeriksaan laboratorium. Menentukan derajat keparahan GGK, menentukan
gangguan system dan membantu menetapkan etiologi. Seperti pemeriksaan
darah untuk fungsi, meliputi pemeriksaan ureum dan kreatinin darah.
Pemeriksaan kreatinin lebih konstan daripada oleh diet, pendarahan usus dan
gangguan fungsi hati.
3. Pemeriksaan USG. Untuk mencari apakah ada bantuan, atau massa tumor,
juga untuk mengetahui beberapa pembesaran ginjal.
4. Pemeriksaan EKG. Untuk melihat kemungkinan hipertropi ventrikel kiri,
tanda-tanda perikarditis, aritmia dan gangguan elektrolit.