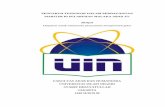Teori Ketergantungan Dan Keterbelakangan
-
Upload
luthfi-ghifariz-walther -
Category
Documents
-
view
76 -
download
3
description
Transcript of Teori Ketergantungan Dan Keterbelakangan

Teori ketergantungan dan keterbelakangan (DIPEDENSIA) menurut Samir amin
Secara historis :
Secara historis, teori Dependensia lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.1
Salah satu pandangan Samir Amin dalam menerangkan ketergantungan dan keterbelakangan dari negara-negara miskin adalah masalah konsep pertukaran yang tidak adil (unequal exchange). 2Konsep pertukaran yang tidak adil ini, menurut Samir Amin menunjukkan bagaimana terjadinya pengalihan surplus dari negara-negara miskin (periphery/negara pinggiran) ke negara-negara maju (centre/negara sentral) sebagai akibat proses perdagangan internasional diantara kedua kelompok negara tersebut.
Konsep pertukaran yang tidak adil tersebut oleh Samir Amin dijelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa akibat oleh adanya rintangan-rintangan dalam proses pertukaran yang tidak adil diantara negara-negara terbelakang dengan negara-negara maju;
2. Bahwa akibat masuknya modal asing dengan mendirikan industri-industri baru, maka mereka sangat berorientasi keluar negeri (Extravert Orientation). Sehingga negera-negara terbelakang, khususnya yang menyangkut ekonomi rakyat, kerajinan rakyat dan industri-industri kecil rakyat lainnya menjadi gulung tikar dan hancur;
3. Walaupun ada pengembangan industri-industri pengganti import dan timbulnya spesialisasi baru di negara-negara terbelakang sebagai akibat beroperasinya perusahaan-perusahaan asing (mancanegara) di negara-negara terbelakang, namun negara terbelakang ini pada hakekatnya berada di atas landasan yang sama seperti yang sudah dan masih dialaminya sebagai produsen dan pengekspor bahan-bahan mentah primer dalam keadaan ketergantungan dan mengekspor barang-barang industripun juga dalam keadaan ketergantungan;
4. Distorsi keadaan tersebut, menimbulkan peningkatan yang menyolok dalam jumlah yang bukan merupakan hasil evolusi dan struktur permintaan efektif didalam negeri maupun hasil evolusi dan kenaikan produktivitas;
5. Proses spesialisasi internasional yang tidak adil, juga menimbulkan distorsi di negara-negara terbelakang dalam bentuk penggunaan teknik-teknik produksi modern yang padat modal untuk kegiatan-kegiatan yang ringan. Hal demikian disebabkan oleh karena adanya penentuan yang
1 Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.2 Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga

datang dari pihak luar yaitu pemilik-pemilik modal asing yang datang menginvestasikan modal mereka dalam membina industri-industi ringan ini. Umumnya pemilik-pemilik modal ini datang membawa mesin-mesin sebagai penyertaan mereka dalam perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan di negara-negara terbelakang. Disamping adanya pemikiran bahwa penggunaan tenaga kerja yang relatif lebih banyak dalam proses produksi akan tidak menjurus kepada pemupukan surplus yang tinggi dalam waktu singkat untuk digunakan dalam proses reinvestasi;
6. Dalam konteks hubungan ekonomi dengan negara-negara maju dan dengan modal asing yang banyak beroperasi di negara-negara terbelakang, maka kebocoran (leakage) yang berbentuk import dan hoarding (simpanan yang tidak produktif) bukanlah merupakan faktor-faktor yang menentukan kecilnya pengganda (multiplier) di negara-negara terbelakang ini;
7. Manifestasi dan keterbelakangan negara-negara terbelakang tidaklah diukur dari rendahnya produksi per kepala, melainkan dicerminkan oleh adanya ciri-ciri struktural di negara-negara ini. Ciri-ciri struktural tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Adanya ketidakmerataan yang parah dalam distribusi industri dan produksi serta adanya suatu sistem harga yang dipaksakan dari luar yang menimbulkan distorsi dan kepincangan distribusi pendapatan dalam negeri;
b. Adanya situasi yang tidak saling terkait antar sektor sebagai akibat penyesuaian produksi terhadap kebutuhan negara-negara maju sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak menyebar keseluruh sistem ekonomi. sehingga pertumbuhan ekonomi mengarah pada autocentric growth dan autodynamic growth;
8. Bahwa perkembangan sistem kapitalis di negara-negara terbelakang (kapitalisme pinggiran/peripheral capitalism) sama sekali berbeda dengan perkembangan sistem kapitalis di negara maju. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan sistem kapitalis di negara-negara terbelakang ditentukan oleh sistem prakapitalis yang ada sebelum sistem kapitalis (baru) masuk dalam jaringan sistem kapitalis dunia yang kemudian menimbulkan sistem kapitalis yang terbatas dan penuh ketergantungan keluar, dimana sangat ditentukan oleh hubungan-hubungan politik dengan pihak luar atau hubungan antar kelas di dalam negeri.

DEPENDENSIA DAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA
Pada pertengahan 1960-an di dunia ketiga sedang menggejala mengundang masuknya modal asing dalam bentuk Multinational Corporations (MNC) dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonominya, menciptakan lapangan kerja dan meraih teknologi. Kehadiran modal asing dalam bentuk Multinational Corporations diharapkan menumbuhkan/melahirkan usaha-usaha lain (forward linkage and backward linkage), yang juga akan meningkatkan daya beli masyarakat (trickle down effect). Model pembangunan dengan teori modernisasi yang pernah berhasil diterapkan misalnya di Jepang setelah perang dunia kedua, hendak diulangi di dunia ketiga. Nilai yang kontekstual diangkat menjadi universal. Sejarah ditransformasi menjadi ideologi atau menjadi hukum ahistoris.3
Termasuk di Indonesia, hal ini ditandai dengan adanya penetrasi finansial, teknologi dan penetrasi poltik serta budaya. Melalui penetrasi finansial, teori dependesi masuk dengan liberalisasi sektor ekonomi yang ditandai dengan masuknya FDI dan MNC yang mulai beroperasi di Indonesia dan penetrasi politik serta budaya juga telah dimasuki oleh budaya asing khususnya budaya barat, baik itu melalui film, gaya hidup, bahan bacaan dan lain-lain.
Pada bulan Januari 1967 Pemerintah Orde Baru mengambil keputusan penting dengan mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (the Foreign Capital Investment Law No. 1 of January 1967), maka investor dari berbagai negara mulai masuk ke Indonesia. Apa yang mendasari masuknya MNC ke Indonesia? Pada umumnya keputusan sebuah MNC menanam modalnya di negara sedang berkembang didorong oleh keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan kemungkinan investasi di negaranya sendiri atau di negara maju yang lain. Keuntungan relatif dari investasi seperti itu tergantung dari faktor-faktor ekonomi maupun politik. Karena itu baik faktor ekonomi maupun politik dipertimbangkan bersama-sama. Sehubungan dengan ini, kiranya tepat pendapat Robert Gilpin:
“Direct investments are intended to establish a permanent source of income or supply in the foreign economy; consequently, they create economic and political relationships of a lasting andsignificant character”
Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sesungguhnya dihadapkan pada dua pilihan: apakah mereka memilih ketergantungan kepada modal dan bantuan asing atau menempuh jalan mereka sendiri dalam proses menuju swadaya nasional berdasarkan keikutsertaan rakyat secara aktif dan sadar dalam proses pembangunan. Apabila jalan pertama yang ditempuh, yakni pembangunan yang bergantung kepada asing, seperti yang ditempuh Indonesia pasca 1966, maka
3 Heryanto, J, 2003. “Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru”. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 5, No. 1, Maret 2003: 17 – 24.

akibat yang terjadi sudah jelas, yakni polarisasi yang makin tajam antara si kaya dan si miskin, serta kesediaan untuk memobilisasi sumber-sumber nasional guna kebutuhan asing. Dalam situasi seperti itu menurut Adi Sasono “stabilitas hanya bisa ditegakkan melalui pengetatan politik, karena keresahan sosial dan kemiskinan massal akan merupakan biaya sosial yang harus dibayar bagi pertumbuhan ekonomi di sektor modern dalam rangka integrasi dengan dunia kapitalisme internasional”.
Sedangkan pembahasan mengenai industri-industri di Indonesia, terlihat jelas bahwa walaupun terjadi perkembangan, namun tetap ada ketergantungan dan nampaknya sejalan dengan teori Associated-Dependent Development-nya Fernando Hendrique Cardoso. Dalam teori ini, “pemilikan” industri nampaknya tidak penting, apakah dimiliki pihak asing, berbentuk perusahaan patungan atau perusahaan domestik yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan asing, tetapi penekanan justru pada siapa yang mengambil keputusan, umumnya berada di luar negeri.
Dalam kasus Indonesia, ketergantungan utang yang terlalu besar dinilai mengakibatkan tergadaikannya kedaulatan negara, menyengsarakan rakyat, dan menghancurkan ekosistem hutan. Benarkah demikian? Argumen pemerintah berutang selama ini adalah adanya kebutuhan investasi yang besar untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan dan memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat yang terus meningkat.
Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber dana untuk melaksanakan agenda pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, utang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada antara kebutuhan investasi dan kemampuan mobilitas dana di dalam negeri (saving investment gap). Mereka yang mendukung utang cenderung hanya melihat manfaat, tanpa melihat biaya politik dan dampak utang terhadap sosial ekonomi serta ekosistem. Bagi mereka, sah-sah saja kita berutang selama utang dipakai untuk tujuan produktif, sebagaimana tecermin dari meningkatnya kapasitas perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, dan juga kapasitas membayar utang.
Sementara mereka yang menentang utang melihat adanya kesenjangan antara janji manfaat dan konsekuensi mahal yang harus ditanggung bangsa akibat utang. Mereka melihat tak kunjung berubahnya paradigma kebijakan berutang pemerintah dan tak adanya komitmen untuk menciptakan kemandirian ekonomi, seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers).
Padahal, banyak contoh negara yang mampu berdiri sendiri menjadi negara maju dan bermartabat tanpa terus-menerus bergantung pada utang kendati mereka tak memiliki sumber daya melimpah seperti Indonesia. Juga banyak contoh negara yang selama ini menjadi langganan krisis utang berhasil bangkit dan tumbuh menjadi perekonomian yang jauh lebih sehat setelah memperoleh penghapusan utang. Jika dicermati, kekhawatiran berbagai pihak menyangkut utang dilandasi sejumlah hal antara lain: ketergantungan pembiayaan pembangunan

pada utang yang tinggi serta konsekuensinya bagi kemandirian Indonesia dalam menetapkan kebijakan yang tepat buat mereka sendiri tanpa didikte kepentingan kreditor.
Stok utang yang terus membengkak secara nominal kendati secara rasio terhadap PDB angkanya menurun. Utang Rp 1.700 triliun lebih tahun ini memang bukan yang terbesar dalam sejarah. Total utang Indonesia pernah mencapai Rp 2.100 triliun pasca krisis 1997/1998 antara lain karena adanya beban biaya restrukturisasi perbankan yang mencapai Rp 650 triliun lebih, tetapi situasi waktu itu bisa dikatakan tak normal.
Semakin membengkaknya kewajiban utang ini menjadi beban bagi APBN dan generasi mendatang karena menyedot anggaran pembangunan dan mengakibatkan kontraksi belanja sosial. Praktis sepertiga penerimaan pajak tersedot untuk membayar bunga utang. Sementara untuk memenuhi kewajiban cicilan pokok, termasuk utang luar negeri, pemerintah terus dipaksa menerbitkan utang baru (gali lubang tutup lubang). Pada masa Orde Baru, seperti diungkapkan Alm Prof Soemitro Djojohadikusumo, 30 persen utang dikorupsi sehingga kemudian muncul istilah utang najis (odiuos debt) dan desakan untuk meminta penghapusan utang. Pasca-Orde Baru, banyak utang yang sudah dibuat dan dikenai commitment fee mahal ternyata tak dicairkan sehingga jadi beban ekonomi. Hanya sekitar 44 persen utang yang akhirnya terserap.
Kini, meskipun rezim utang sudah lebih terbuka (utang tak lagi dianggap sebagai sumber penerimaan negara seperti pada era Orde Baru) dan sudah ada apa yang disebut ”manajemen risiko utang”, kita masih melihat begitu gampang pemerintah membuat utang baru tanpa memikirkan bebannya bagi generasi mendatang. Padahal, tanpa tambahan utang baru pun, utang sekarang ini baru akan lunas 40 tahun lagi.