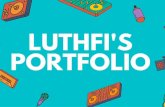Muhammad Ais Luthfi Fisip
-
Upload
muhammad-aiz-luthfi-kariem -
Category
Documents
-
view
43 -
download
0
description
Transcript of Muhammad Ais Luthfi Fisip
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk yang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik,
karena manusia - sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles - adalah zoon
politicon, yakni makhluk yang berpolitik, ini terlihat ketika manusia menjalani
kehidupannya selalu membutuhkan orang lain, dan dalam interaksi dengan orang
lain tersebut terjadi sebuah proses atau perilaku politik dalam skala pengertian
perilaku politik yang bersifat makro.
Sementara perilaku politik dalam skala mikro, dalam hal ini dilihat dari
sudut pandang ilmu politik, menurut Ramlan Surbakti pada dasarnya merupakan
interaksi antara pemerintah dan masyarakat baik individu maupun kelompok
dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik,1
dengan demikian, perilaku politik erat kaitannya dengan interaksi individu-
individu maupun kelompok atau organisasi dengan pemerintah.
Salah satu kelompok atau organisasi di Indonesia yang sejak kelahirannya
selalu berinteraksi dengan pemerintah adalah kumpulan para ulama yang
tergabung dalam wadah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi ini didirikan di Jawa
Timur pada tanggal 31 Januari 1926 M yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab
1344 H.
1 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo: 1999), cet. IV, h. 15
-
2
Dalam perjalanannya yang sangat panjang, NU memiliki dinamika
multidimensi, terutama jika dikaitkan dengan negara yang terpersonifikasi
dalam pemerintah, sehingga NU membutuhkan sebuah improvisasi dalam
menjalani perilaku politiknya.
Salah satu improvisasi perilaku politik NU yang sangat terkenal terjadi
pada tahun 1980-an, pada saat itu dalam tubuh NU terjadi dinamika politik
sebagai ekses dari perilaku politik J. Naro2 yang menekan dan meminimalisir
peranan NU dalam tubuh PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Andree Feillard
menyebut keadaan ini dengan istilah de-NU-isasi,3 para tokoh NU kemudian
mengambil sikap tegas dalam muktamar ke 27 di Situbondo dengan menyatakan
bahwa NU kembali ke Khittah 1926,4 keluar dari Partai Persatuan Pembangunan
2 Pada saat itu J. Naro adalah ketua umum PPP yang mempunyai kedekatan khusus
dengan Presiden Soeharto, dan Soeharto melakukan resistensi terhadap kelompok-kelompok Islam termasuk NU. Menurut A. M Fatwa, pada tahun 1986-1985 merupakan fase marjinalisasi Islam, dalam fase ini keberadaan umat Islam sungguh sengsara. Islam dianggap sebagai kelompok pembangkang dan segala aspirasi politiknya selalu dicurigai. Bahasa yang sering digunakan oleh rezim orde baru saat itu adalah Koji (komando Jihad), golongan anti pancasila dan kelompok ekstrem kanan yang mempunyai cita-cita ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan semua istilah tersebut dimaksudkan untuk mendeskriditkan Islam dan dengan demikian Islam berada di tempat yang marjinal. semua terjadi dikarenakan pertama, pemerintah orde baru yang bersifat militeristik masih dibayangi oleh trauma sejarah terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam dan masih dianggap sebagai kelompok pengganggu stabilitas dan kesatuan bangsa. Kedua rezim orde baru didominasi oleh kelompok figur atau kelompok yang anti-Islam dan Islam fobia. Lihat A. M. Fatwa Satu Islam Multipartai, (Bandung: Mizan), 2000, cet. I, h. 37-38
3 Andree Feillard, NU vis a vis Negara, penj. Lesmana, (Jogjakarta: LKiS, 1999), cet. I, h.223-224
4 Keputusan Kembali Khittah 1926 berarti NU menyatakan kembali kepada jati dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang lebih beorientasi dan berkonsentrasi pada pembinaan ummat dari pada berkicimpung dalam dunia politik praktis. Walaupun secara kelembagaan NU tidak berpolitik praktis, namun secara individual membolehkan para kadernya untuk terlibat dalam politik praktis. Dalam proses perumusan kembali ke khittah 1926 Menurut Mitsuo Nakamura, ada dua dokumen penting yang harus dikaji secara teliti, kedua dokumen tersebut ditulis oleh KH Ahmad Siddik, yakni Khittah Nahdliyin yang diterbitkan beberapa bulan sebelum Mutamar Semarang dan kertas kerja yang berjudul pemulihan Khittah NU 1926 yang
-
3
(PPP) serta menerima Pancasila sebagai asas Organisasi.5 Bukan hanya itu saja,
dalam muktamar tersebut Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus
Dur terpilih menjadi ketua umum tanfidziyah PBNU.
Mengenai konteks naiknya Gus Dur sebagai ketua umum PBNU
nampaknya bisa dilihat melalui pendekatan teori kepemimpinan klasik, yakni
teori sifat (trait theori) atau disebut juga dengan teori the great man, menurut
teori ini seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin
tanpa memperhatikan apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat
sebagai pemimpin, atau dengan kata lain pemimpin itu bukan dibuat, melainkan
diciptakan.6
Begitu pun dengan Gus Dur, seolah ia dilahirkan untuk memimpin NU,
karena dalam diri Gus Dur mengalir darah kepemimpinan dua founding father
NU, yakni KH. Hasyim Asy`ari dan KH. Bisri Syansuri, dan ditambah lagi
dikemukakannya dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo bulan Desember 1983, setahun sebelum Muktamar diadakan. Pemahaman terhadap arah dan tujuan kedua dokumen tersebut sangatlah penting jika ingin menyibak apa yang terjadi sepanjang periode ini. Semua terfokus pada ide-ide prospektif dari gerakan reformasi yang dimotori oleh Ahmad Siddik dan Abdurrahman Wahid. Sumber-sumber penting yang dicatat Nakamura adalah artikel Abdurrahman Wahid yang diangkat dari wawancara panjang dengannya berjudul Menerapkan pangkalan-pangkalan pendaratan menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Dalam artikel tersebut Abdurrahman Wahid menyiratkan adanya keinginan yang lebih kuat untuk lebih intensif mengurusi persoalan-persoalan sosial, dan bukan persoalan-persoalan politik. Lihat Greg Barton & Greg Fealy, Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama - Negara, Penj. Ahmad Suaedy, dkk, (Yogyakarta: LKiS; 2010), cet. III, h. 122-123
5 Dalam proses penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi, internal NU mengalami kontroversi, dan persoalan utama yang ditimbulkan pancasila adalah bukanlah masalah tidak dicantumkannya syariat, tapi soal penganut kepercayaan dan animisme yang dituduh syirik oleh Islam. Namun kemudian KH Ahmad Shidik yang ditunjuk oleh para ulama besar untuk mengemukakan argumen-argumen fikih menyatakan bahwa Islam dan pancasila memang berbeda, namun memiliki persamaan. Lihat Andree Feillard, NU vis a vis Negara, h 219-222
6 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2006), cet. I, h. 32
-
4
melihat potensi yang dimilikinya serta dengan dukungan beberapa tokoh senior
NU pada saat itu sehingga Gus Dur pun menjadi seorang pemimpin Tanfidziyah
PBNU.
Pada saat Gus Dur menjabat sebagai ketua umum, perilaku politik Gus
Dur di satu sisi bersikap akomodatif dengan pemerintah, sehingga hubungan NU
dengan pemerintah yang sebelumnya saling berhadapan menjadi membaik,
namun di sisi lain perilaku politik Gus Dur cenderung menjadi oposan
pemerintah karena Gus Dur sering mengkritisi pemerintah dengan lantang dan
alasan inilah yang membuat pemerintah sering melakukan intervensi terhadap
NU.
Pada tahun 1998 rezim Soeharto tumbang oleh gerakan mahasiswa dan
Gerakan Rakyat yang menuntut agar Soeharto melepaskan jabatan Presiden dan
diadakannya reformasi di Indonesia, setelah Soeharto turun dari jabatan Presiden
Republik Indonesia ia mengangkat Wakil Presiden B.J Habibie sebagai
penggantinya.
Dengan runtuhnya rezim Soeharto membawa implikasi euforia politik
pada rakyat Indonesia, dengan ditandai munculnya puluhan bahkan ratusan partai
politik termasuk partai politik milik warga NU, pada waktu itu sebagian besar
warga NU menginginkan agar NU memiliki partai politik, dikarenakan desakan
dari warga NU semakin meningkat pada akhirnya usulan ini diterima oleh
PBNU dan kemudian dideklarasikanlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh
-
5
Gus Dur, partai tersebut dideklarasikan di kediamannya Gus Dur yang ada di
daerah Ciganjur Jakarta Selatan.
Namun setelah dilakukannya verifikasi terhadap partai politik hanya 42
partai politik yang diperbolehkan menjadi peserta pemilu, dan PKB termasuk
salah satu dari 42 partai politik tersebut. Setelah diadakannya pemilihan umum,
perolehan kursi di DPR dari PKB adalah sebanyak 41 kursi.
Pada saat pemilihan legislatif telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam proses pemilihan Presiden ini,
partai-partai Islam yang mendapatkan kursi di parlemen membentuk kaukus
Islam dengan nama poros tengah yang menjadikan Gus Dur sebagai Calon
Presidennya,7 melalui Poros Tengah inilah kemudian Gus Dur menjadi Presiden
keempat Republik Indonesia, dan pada saat yang bersamaan Gus Dur masih
menjabat sebagai ketua umum PBNU. Gus Dur menjabat ketua Umum PBNU
selama tiga periode, yakni dari tahun 1984 sampai 1999.
Setelah Gus Dur tidak lagi memimpin NU, dalam muktamar ke-30 NU
pada tahun 1999 yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Hasyim
Muzadi terpilih menjadi ketua umum PBNU, dan jika memakai pendekatan teori
the great man, naiknya Hasyim menjadi ketua umum lebih karena faktor
7 Koalisi Islam ini dipelopori oleh Amien Rais, lihat Bahtiar Effendy, ISLAM DAN
NEGARA: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, LSI dan Prenida Media Group), 2009, Cet. II, h. 389
-
6
pendidikan dan pengalaman,8 karena sebelumnya Hasyim pernah menjadi ketua
umum NU pada tingkat ranting, cabang dan wilayah.
Ketika Hasyim memimpin NU Gus Dur adalah Presiden keempat RI,
kedekatan secara kultural dan emosional antara pemerintah dan NU ini kemudian
membuat perilaku politik Hasyim Muzadi dan NU menjadi cenderung
menenggelamkan daya kritisisme terhadap pemerintah.
Misalnya Hasyim sering memberikan pernyataan-pernyataan yang seolah
memberikan legitimasi pada pernyataan dan kebijakan Gus Dur yang
kontroversial, seperti pada kontroversi pencabutan Tap MPRS No. 25 tahun 1966
tentang PKI dan kehalalan Ajinomoto, dalam setiap kesempatan Hasyim selalu
menyatakan hal yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh Gus Dur.9
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004 perilaku politik
Hasyim bisa dikatakan sama dengan perilaku politik Gus Dur persamaan perilaku
politik ini dapat dilihat ketika menjabat ketua umum PBNU (terlepas dari
menang atau kalah) Hasyim mencalonkan diri menjadi wakil Presiden Republik
Indonesia yang bergandengan dengan Megawati dan kemudian dalam pemilihan
Presiden putaran kedua, pasangan Mega Hasyim ini kalah suara oleh pasangan
8 Setelah mendapat pengaruh dari aliran perilaku dan pemikir psikologi, teori the great
man mendapat pengembangan dengan menyatakan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, tapi dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman, lihat Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen, h. 32-34
9 Bahrul Ulum, BODOHNYA NU APA NU DIBODOHI?: Jejak langkah NU Era reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik, (Yogyakarta; Arruzz Press; 2002), cet. I, h. 49
-
7
SBY-JK. Hasyim Muzadi menjabat ketua umum PBNU selama dua Periode
yakni dari tahun 1999 sampai 2010.
Berangkat dari uraian di atas, antara Gus Dur dan Hasyim memiliki
persamaan berikut perbedaan perilaku politik ketika keduanya memimpin
organisasi besar yang bernama NU, Persamaan berikut perbedaan ini kemudian
sedikit banyaknya turut mempengaruhi pula perilaku politik NU sehingga perlu
adanya kajian mendalam untuk bisa dijadikan sebagai indikator dalam menilai
perilaku politik kedua tokoh tersebut ketika memimpin NU yang dirumuskan
dalam format judul skripsi Perilaku politik Nahdlatul Ulama (Studi Komparatif
perilaku politik Abdurrahman Wahid Dan Hasyim Muzadi)
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terlihat sebuah perbedaan
berikut persamaan antara perilaku politik Abdurrahman Wahid dan Hasyim
Muzadi, maka pembahasan skripsi ini akan dirumuskan pada beberapa persoalan
yang mencakup:
1. Bagaimana perilaku politik Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi ketika
memimpin NU.
2. Apa saja persamaan dan perbedaan perilaku politik dari dua tokoh tersebut.
3. Apa implikasi perilaku politik kedua tokoh tersebut terhadap politik NU.
Kemudian, agar penelitian ini dapat lebih fokus, maka penulis membatasi
permasalahan-permasalahan di atas pada persoalan perilaku politik Abdurrahman
Wahid dan Hasyim Muzadi.
-
8
C. Tujuan Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki tujuan di antaranya:
1. Mengetahui perilaku politik Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi saat
memimpin NU
2. Membandingkan perilaku politik Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi,
3. Mengetahui pengaruh kedua tokoh tersebut dalam NU
D. Metodologi Penelitian
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian
pustaka dan dibarengi dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis
lakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, majalah, media
massa dan internet yang erat kaitanya dengan masalah yang akan dikaji serta
melakukan wawancara untuk pendalaman.
Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman
Karya Tulis Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh CeQDA
(Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta tahun 2006.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan dibagi
dalam 5 bab yang terinci sebagai berikut:
BAB I: Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan
Penulisan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan,
-
9
BAB II : Kerangka teori tentang perilaku politik, model perilaku politik dan
faktor yang mempengaruhi perilaku politik,
BAB III : Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi dalam Nahdlatul Ulama,
yang mencakup Kondisi Sosio-Politik dan Menjadi Kader dan Ketua Umum.
BAB IV : Perilaku Politik Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi yang
menyangkut Gaya Kepemimpinan, Pengaruh dan Wibawa, Faktor yang
mempengaruhi Perilaku politik, serta Gerakan Politik
BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
-
10
BAB II
PANDANGAN UMUM TENTANG PERILAKU POLITIK
A. Kerangka Teori Tentang Perilaku Politik
Secara etimologis perilaku politik merupakan terjemahan dari bahasa asing,
yakni political behaviour, kata tersebut terdiri dari suku kata political dan
behaviour, di dalam kamus Oxford, arti kata political kurang lebih adalah hal-hal
yang menyangkut negara, warga negara, pemerintahan dan kebijakan.8 Adapun
arti dari kata behaviour adalah cara seseorang dalam melakukan hubungan
dengan pihak luar.9
Jika ditelusuri dari pengertian bahasa Indonesia, di dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, perilaku adalah adalah tanggapan atau reaksi individu yang
terwujud dalam gerakan atau sikap tidak saja badan dan ucapan,10 dan politik
adalah segala urusan dan tindakan - seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya -
mengenai pemerintahan negara atau negara lain.11
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara etimologis perilaku politik
adalah tindakan, gerakan atau sikap seseorang terhadap pemerintahan atau
negara, maupun sebaliknya, yakni tindakan, gerakan atau sikap pemerintahan
atau negara terhadap individu.
8 The Oxford English Dictionary, (London: Oxford University Press; 1993), Volume I,
cet. I, h. 772 9 The Oxford English Dictionary, Volume VII, h. 1074 10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka; 1988), cet. I, h. 671 11 Kamus Besar Bahasa Indonesia..., h. 694
-
11
Pada tataran terminologis, perilaku politik adalah kegiatan antara
pemerintah dengan masyarakat atau pun sebaliknya yang memiliki unsur
pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.
Pengertian secara terminologis ini sesuai dengan pengertian yang
dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yang mengatakan bahwa interaksi antara
pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di
antara kelompok individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan,
pelaksanaan dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan
perilaku politik.12
Perilaku politik merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang
dikembangkan oleh kaum behavioralis dengan melihat dan menekankan pada
aspek individual sebagai insan politik daripada melihat sistem-sistem ataupun
lembaga politik, pendekatan ini digunakan untuk mengamati perilaku-
perilaku individual dengan melihat pada hubungan antara pengetahuan politik
dan tindakannya, termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan pendapat
politik dan memperoleh kecakapan politik serta menyadari peristiwa-peristiwa
politik yang berlangsung.13
Secara historis, perilaku politik merupakan gerakan protes kaum
behavioralis terhadap aliran tradisional dalam ilmu politik, dan secara garis
besar protes mereka adalah pertama kelompok tradisional telah mengembangkan
12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 15 13 David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, penj. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES;
1987), cet. II, h. 209
-
12
ilmu politik yang tidak memiliki sifat-sifat sebagai penghasil pengetahuan politik
yang reliabel, dan kedua, banyak pengetahuan politik yang reliabel dapat
diterima dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metode-metode
alternatif, namun demikian kaum behavioralis tidak sepenuhnya membuang
pendekatan yang digunakan oleh kaum tradisionalis, seperti sistem politik dan
lembaga-lembaga yang ada dalam sistem politik tersebut.14
Menurut Trubus Rahardiansyah, mengenai perilaku itu sendiri, baik
individu maupun kelompok pada dasarnya semuanya adalah aksi dan reaksi,
dan dalam hal ini ada ada dua cara pandang mengenai signifikansi tingkatan
perilaku.
Pertama, individualisme, yakni pandangan bahwa kelompok tidak lain
hanya terdiri atas anggota-anggota kelompoknya, misalnya perilaku lembaga
peradilan merupakan perilaku sejumlah individu yang kebetulan menjadi anggota
lembaga tersebut. Tidak ada sifat-sifat kelompok yang diturunkan dari sifat-sifat
individu, dan begitu pun sebaliknya, tidak ada sifat-sifat individu yang
diturunkan dari sifat-sifat kelompok, dan cara pandang ini digunakan oleh kaum
behavioralis.
Kedua, holisme, yakni pandangan tentang timbulnya sifat kelompok yang
diturunkan, dalam hubungan ini diakui bahwa kelompok pada dasarnya
merupakan serangkaian bagian-bagiannya, dan cara pandang ini digunakan oleh
14 Trubus Rahardiansah, Pengantar Ilmu Politik: Konsep Dasar, Paradigma dan
Pendekatannya. (Jakarta: Universitas Trisakti: 2006), cet. I, h. 39-40
-
13
kaum tradisional.15
Pendekatan perilaku politik dipakai untuk melihat kegiatan dan dinamika
yang terjadi dalam lingkup kelembagaan negara. Selain itu, perilaku politik juga
dirancang sebagai suatu pendekatan ilmu politik yang menekankan pada perilaku
individual sebagai objek utama analisis, dan juga lebih memusatkan perhatian
pada perilaku kelompok, tetapi dengan asumsi bahwa kelompok tersebut adalah
interaksi kolektif yang terjadi antar individu. Dan yang termasuk ke dalam
kategori perilaku politik adalah respon-respon internal seperti pikiran, persepsi,
sikap dan keyakinan dan juga respon-respon eksternal seperti pemungutan suara,
gerak protes, lobbying, kaukus dan kampanye.16
Menurut Prof. Miriam Budiardjo, salah satu pemikiran pokok dari
pendekatan perilaku adalah tidak memberikan apresiasi terhadap pembahasan
lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi
informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, pendekatan ini
lebih berkonsentrasi untuk mempelajari perilaku individu yang ada dalam
lembaga tersebut karena dengan melihat perilaku individu merupakan sebuah
gejala yang benar-benar dapat diamati.
Pendekatan ini pun menganggap bahwa lembaga-lembaga formal bukan
sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya
merupakan akumulasi dari kegiatan manusia. Misalnya, jika pendekatan ini
15 Ibid, h. 41 16 Jack C. Plano, dkk, Kamus Analisis Politik, penj. Drs. Edi S. Siregar, (Jakarta: CV.
Rajawali; 1985), cet. I, h. 161
-
14
digunakan untuk mempelajari parlemen, maka yang akan dibahas adalah
perilaku anggota yang ada dalam parlemen tersebut seperti pola pemberian
suaranya (voting behavior) terhadap sebuah rancangan undang-undang tertentu,
pidato-pidatonya, cara berinteraksi dengan kerabatnya, kegiatan lobbying dan
latar belakang sosialnya.17
Pemerintah dan masyarakat, baik individu maupun kelompok merupakan
objek yang dijadikan pusat perhatian dari pendekatan perilaku politik, dalam hal
ini pemerintah dan masyarakat yang dilihat sebagai subjek maupun
karakteristiknya, bukan dilihat dari fungsi-fungsi pemerintahan maupun fungsi-
fungsi politik, karena jika fungsi-fungsi tersebut dijadikan sebagai pusat
perhatian maka pendekatannya adalah bukan pendekatan perilaku politik
melainkan pendekatan perilaku lembaga.18
Menurut Gabriel Almond, seorang ilmuwan politik struktural-fungsional,
fungsi-fungsi tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni fungsi infrastruktur
politik, fungsi ini dipegang oleh masyarakat, baik oleh individu maupun
kelompok dan fungsi suprastruktur politik, fungsi ini dipegang oleh lembaga-
lembaga pemerintahan.
Fungsi infrastruktur politik terdiri dari sosialisasi dan rekrutmen politik,
agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan dan komunikasi politik, dan fungsi
17 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama;2008), Cet. I h. 74-75 18 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 15
-
15
suprastruktur adalah pembuatan peraturan (Rule making), pelaksanaan peraturan
(rule application), dan peradilan peraturan (rule adjudication).19
Dalam suatu sistem politik, selalu ada aliran terus menerus mengalir dari
input yang muncul dari infrastruktur politik kemudian terjadi proses dan
dinamika tertentu dan akhirnya menjadi output yang dilakukan oleh kelompok
suprastruktural politik dan setelah itu akan terbentuk kembali menjadi sebuah
input,20 dan begitu seterusnya, sehingga terbentuk sebuah siklus dalam kehidupan
bernegara.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku politik merupakan
sebuah kaca mata politik yang digunakan untuk melihat (dengan lebih
mengkonsentrasikan pada) perilaku seseorang dari pada perilaku lembaga politik.
B. Model Perilaku Politik
Unit analisis dalam melakukan kajian politik dengan menggunakan
pendekatan perilaku politik, menurut Ramlan Surbakti dapat ditinjau dari
tiga kemungkinan, yakni ;
Pertama individu sebagai aktor politik, dan yang masuk dalam kategori ini adalah aktor politik yakni pemimpin, aktivis politik dan individu warga negara biasa, kedua, Agregasi Politik yakni individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, dan lembaga-lembaga pemerintahan atau bangsa, ketiga, adalah tipologi kepribadian politik yakni tipe - tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist dan demokrat.21
19 Lihat Ng. Philipus & Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada; 2006), h. 106 20 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 78 21 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 132
-
16
Pemimpin dalam model pertama adalah lebih cenderung kepada sosok
subjeknya dan pemimpin dalam model yang ketiga lebih menekankan pada
tipologi atau sifat seorang pemimpin.
Seperti yang telah dikemukakan, salah satu aktor politik adalah pemimpin,
dan salah satu tipe aktor politik yang mempunyai pengaruh dalam proses politik
adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Mengenai konsep memiliki
kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, perbedaan ini
terletak pada sumber pengaruh dan tujuan penggunaan pengaruh.
Sebutan politik pada kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan
tersebut berlangsung dalam suprastruktur politik, yakni lembaga-lembaga
pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan yang berlangsung dalam
infrastruktur politik yakni masyarakat, individu maupun kelompok, seperti partai
politik dan organisasi kemasyarakatan.
Pemimpin politik pun di satu sisi dapat berbeda dengan pemimpin dalam
suatu instansi pemerintahan, perbedaan ini terlihat dalam cara, proses serta
komunikasi yang dibangun dengan jajaran dan pengikutnya, dalam mencapai
tujuan tertentu pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan
informal dan personal untuk menggerakkan pengikutnya.
Pemimpin suatu instansi cenderung menggunakan kewenangannya dengan
cara melakukan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam
menggerakkan pengikutnya. Akan tetapi orang yang secara formal menjadi elit
politik atau pemimpin suatu instansi dapat memainkan peranan sebagai
-
17
pemimpin politik dengan catatan dapat memenuhi karakteristik kepemimpinan
politik.22
Dengan demikian, kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai bagian dari
perilaku politik, dan secara definitif kepemimpinan kurang lebih adalah
sebuah aktifitas mempengaruhi orang lain untuk berusaha mencapai tujuan
bersama,23 sehingga ketika terjadi sebuah aktifitas yang memiliki motivasi untuk
mempengaruhi orang lain, pada saat yang sama terjadi sebuah kepemimpinan.
Kepemimpinan merupakan bentuk mashdar, sementara pemimpin adalah bentuk
fa`il (subjek).
Dalam perjalanannya, teori kepemimpinan mengalami perkembangan dari
waktu ke waktu, dan teori kepemimpinan yang paling awal muncul adalah teori
sifat atau the great man yang menganggap bahwa kepemimpinan merupakan
sifat bawaan yang ada sejak lahir. Pada perkembangan selanjutnya teori ini
kemudian mendapat masukan dari kalangan psikologi yang menilai bahwa tidak
semuanya kepemimpinan dibawa sejak lahir, kepemimpinan pun bisa lahir dari
sebuah pengalaman dan pendidikan.24
22 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 133-134 23 Paul Harsey dan Kenneth H. Blanchard, Manajemen Perilaku Organisasi:
Pendayagunaan sumber Daya Manusia, Edisi keempat, penj. Agus Dharma (Jakarta: Erlangga; 1982), h. 98
24 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam manajemen, h. 32
-
18
Mengenai kategorisasi kepemimpinan, Ramlan Surbakti membaginya
menjadi tiga kriteria, yakni proses kepemimpinan berikut karakter pemimpin,
hasil kepemimpinan dan sumber kekuasaan.25
Kategori proses kepemimpinan di antaranya autokratis dan demokratis.
Autokratis adalah sebuah tipologi pemimpin yang identik dengan pemusatan
otoritas pada pemimpin dan dalam pengambilan keputusan lembaga sangat
bergantung padanya. Demokratis adalah tipologi pemimpin yang berdasarkan
pada desentralisasi kekuasaan dan dalam pengambilan keputusan sering
melibatkan anggota yang lain,26
Selanjutnya masih berkaitan dengan proses kepemimpinan yakni karakter
pemimpin. Karakter yang dimaksud berupa keaktifan pemimpin dalam
melakukan tugasnya serta penilaiannya terhadap tugas tersebut, dan berdasarkan
karakter pemimpin ini terbagi menjadi empat.
Pertama adalah pemimpin pasif-positif yang berarti pemimpin yang tidak
aktif dalam melaksanakan pekerjaan tetapi ia sangat menilai tinggi terhadap
pekerjaannya. Kedua, aktif-negatif yakni pemimpin yang aktif melaksanakan
pekerjaan tetapi kurang begitu tinggi dalam menilai pekerjaannya. Ketiga, pasif-
negatif yaitu pemimpin yang tidak aktif dalam melaksanakan pekerjaan dan juga
kurang menilai tinggi pekerjaannya. Dan terakhir adalah aktif-positif yaitu
25 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 138 26 S.G. Hunneryager & I. L. Heckman, ed. Kepemimpinan, (Semarang: Dahara Prize:
1992), cet. I, h. 10
-
19
pemimpin yang aktif dalam melaksanakan pekerjaan dan juga menilai tinggi
pekerjaannya.
Mengenai kepemimpinan yang dilihat dari hasil proses kepemimpinan
biasanya muncul ketika rezim lama telah berakhir dan digantikan oleh rezim
baru. Dalam konteks kepemimpinan ini dibagi menjadi dua, yaitu ekstrimis
dan moderat. Kepemimpinan model ini muncul ketika rezim lama berakhir.
Pemimpin moderat adalah seorang pemimpin yang lebih banyak
menggunakan dialog daripada tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya,
sedangkan pemimpin yang ekstrim adalah pemimpin yang berusaha
menghancurkan seluruh sistem rezim lama dan menggantinya dengan sistem
yang benar-benar baru serta lebih banyak menggunakan kekerasan dalam
mencapai tujuannya.
Tipe kepemimpinan selanjutnya adalah dilihat dari hubungan antara
pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin model ini dibagi menjadi dua, yakni
pemimpin transformatif dan pemimpin transaksional, pemimpin transformatif
adalah pemimpin yang melakukan sesuatu untuk meningkatkan moral, motivasi
dan kegiatan yang lebih tinggi, sementara pemimpin transaksional adalah
pemimpin yang melakukan sesuatu dengan tujuan pertukaran nilai yang dianggap
penting.
Kategorisasi kepemimpinan yang terakhir adalah ketegorisasi yang
berdasarkan sumber kekuasaan, dan kepemimpinan model ini dibagi menjadi
-
20
tiga, yakni kepemimpinan rasional, kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan
kharismatik.
Kepemimpinan rasional memiliki kekuasaan yang bersumber pada legalitas
kewenangan yang berasal dari pola-pola peraturan normatif, kepemimpinan
tradisional memiliki kekuasaan yang bersumber dari kewenangan tradisional
yang lahir dari kepercayaan mapan terhadap tradisi dan legitimasi orang yang
memiliki kewenangan berdasarkan tradisi yang dianggap keramat tersebut. Dan
terakhir adalah sumber kekuasaan yang dimiliki oleh kepemimpinan kharismatik,
sumber kepemimpinan karismatik adalah berpegang pada kekaguman
masyarakat terhadap seorang pemimpin yang memiliki kelebihan luar biasa. 27
Menurut penulis konsep kepemimpinan tersebut tidak selamanya melekat
pada seseorang, hal ini disebabkan oleh faktor pengaruh dari situasi dan kondisi
di sekelilingnya, misalnya ketika seorang pemimpin berada dalam kondisi yang
sangat mendesak, kemungkinan besar ia akan menjadi seorang yang autokratis,
sebaliknya jika seorang pemimpin tersebut mengalami persoalan yang sangat
pelik, kemungkinan besar ia akan menjadi seorang yang demokratis.
Hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kepemimpinan adalah
pengaruh dan wibawa dari seorang pemimpin, karena (seperti yang telah
dikemukakan dalam definisi kepemimpinan) pengaruh merupakan bagian dari
proses sebuah kepemimpinan.
27 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 138-139
-
21
Di sisi lain, wibawa pun merupakan bagian dari kepemimpinan karena
peran wibawa dapat dikatakan lebih luas dari pada pengaruh, peran pengaruh ada
dalam otoritas formal, sementara wibawa dapat berperan di luar otoritas formal.28
Misalnya ketika seseorang memiliki kepemimpinan kharismatik, di dalam
maupun di luar lembaga ia akan memiliki sebuah pengaruh yang cukup dominan,
sementara kepemimpinan rasional belum tentu mendapatkan hal itu, karena ia
dibatasi oleh ruang dan waktu.
Kepemimpinan memang bagian dari perilaku politik, namun jika melihat
definisi perilaku politik yang telah dikemukakan pada bagian awal bab ini,
kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang memiliki korelasi dan
interaksi antara dua subjek, baik di dalam masyarakat maupun pemerintahan dan
interaksi tersebut memiliki muatan-muatan atau unsur-unsur dalam bentuk proses
pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.
C. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik
Dalam melakukan perilaku politik, seseorang atau kelompok tidak bisa
dilepaskan dari konteks maupun variabel-variabel lain yang ada di sekitarnya,
karena konteks dan variabel-variabel tersebut mempunyai peran dan fungsi
yang saling berkaitan satu sama lain.
Hal ini senada dengan pandangan kelompok struktural-fungsional, yang
menganggap bahwa kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti halnya tubuh
28 DR. Thariq Muhammad as-Suwaidan & Faish. Umar Basyarahil, Penj. Samson Rahman,
Sukses Menjadi Pemimpin Islami, (Jakarta: Maghfirah Pustaka; 2005), cet. I, h. 188
-
22
beserta organ-organnya, masing-masing organ dalam tubuh tersebut mempunyai
fungsi dan peran yang berbeda-beda namun memiliki saling keberkaitan satu
sama lain.29
Begitu pun dalam kehidupan ini, masing-masing orang, lembaga dan lain
sebagainya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda serta saling memiliki
keberkaitan satu sama lain dan tetap dalam sebuah sirkulasi kehidupan. Dengan
demikian faktor eksternal sedikit banyaknya berperan serta dalam
mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku politiknya, dan mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik tersebut adalah:
Pertama, lingkungan sosial politik tidak langsung, yang termasuk dalam
kategori ini adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media
massa. Dan lingkungan tak langsung ini, selain mempengaruhi aktor politik juga
dapat mempengaruhi faktor-faktor selanjutnya, yakni;
Kedua, lingkungan sosial politik langsung, berupa keluarga, agama,
sekolah dan lembaga-lembaga lain yang yang menjadi media dalam pergaulan.
Dari lingkungan sosial politik langsung ini seseorang mengalami sosialisasi,
transformasi dan internalisasi nilai, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai
kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.
Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, untuk
memahami struktur kepribadian ini, terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu
29 Peter Westey, Pengantar Sosiologi; Sebuah Pembanding Jilid 2, Penj. Hartono
Hadikusumo, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya; 1992), cet. I, h. 244-245
-
23
kepentingan, penyesuaian dan eksternalisasi dan pertahanan diri. Struktur
kepribadian dalam konteks kepentingan melihat bahwa penilaian seseorang
terhadap sebuah objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan terhadap objek
tersebut. Adapun struktur kepribadian dalam konteks penyesuaian diri, melihat
bahwa penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh sebuah
keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objek tersebut, dan mengenai struktur
kepribadian eksternalisasi dan pertahanan diri melihat bahwa penilaian
seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginannya untuk mengatasi
atau paling tidak meminimalisir konflik batin atau tekanan psikis yang terjadi di
dalam dirinya.
Keempat lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan
yang mempengaruhi seseorang dengan langsung ketika seseorang tersebut
hendak melakukan sebuah kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan
ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan lain sebagainya.30
Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan
perilaku politiknya, sehingga ketika ada beberapa orang dengan perbedaan
faktor-faktor yang telah disebutkan diatas maka perilaku politik dari masing-
masing orang tersebut akan berbeda pula. Begitu pun dengan perubahan faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku politik tersebut, dengan berubahnya faktor-
faktor tersebut, maka akan terjadi pula perubahan pada perilaku politik
seseorang.
30 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 132-133
-
24
BAB III
ABDURRAHMAN WAHID DAN HASYIM MUZADI
DALAM NAHDLATUL ULAMA
A. ABDURRAHMAN WAHID
Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipangil Gus Dur dilahirkan di
Jombang, Jawa Timur pada tahun 1940,31 nama Abdurahman Wahid kecil
adalah Abdurrahman al-dakhil, nama tersebut merupakan bentuk tafaul 32
sang ayah kepada sosok Abdurrahman al-dakhil,33 seorang pendiri Daulah
Umayyah di Spanyol.34
Gus Dur sempat mengenyam pendidikan formal di Perguruan Tinggi
Timur Tengah, yakni di Universitas Al-Azhar Mesir dan karena sistem
pendidikan di Al-Azhar dinilai tidak cocok karena mengandalkan sistem
hafalan kemudian Gus Dur memutuskan untuk pindah ke Universitas Bahdad
31 Mengenai tanggal kelahirannya adalah tanggal empat bulan kedelapan tahun 1940, yang berarti tanggal 4 bulan Agustus 1940, namun menurut Greg Barton tanggal dan bulan tersebut dihitung menurut kalender Hijriyyah, yang berarti tanggal 4 bulan Sya`ban, dan tanggal 4 Sya`ban pada tahun 1940 bertepatan dengan tanggal 7 September, dengan demikian menurut Greg Barton, Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940. Lihat Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid, Penj. Lie Hua, (Yogyakarta: LKiS: 2010), cet. II, h. 25
32 Secara bahasa, tafaul ( ) adalah pengharapan nasib baik, lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif; 1997), cet. XXV, hal 1029, begitupun dengan Wahid Hasyim yang mengharapkan anaknya kelak mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Abdurrahman al-Dakhil.
33Abdurrahman al-dakhil adalah negarawan Muslim yang berhasil mendirikan kekhalifahan Bani Umayah di Andalusia (Spanyol). Ketika gerakan oposisi Abbasiyah pada tahun 750 M berhasil menggulingkan dan melakukan pembunuhan terhadap seluruh Bani Umayah di Damaskus, Abdurrahman yang pada waktu itu masih berusia 22 tahun berhasil lolos untuk menyelamatkan diri dan pada tahun 756 M, Dinasti Umayyah berdiri di Cordova, Abdurrahman kemudian digelari al-dakhil, yang berarti orang yang memasuki Andalusia. Abdurrahman al-dakhil memerintah dari tahun 756-788. Ia berhasil membangun peradaban di Andalusia, sehingga dibawah pemerintahannya Andalusia mengalami dan menikmati masa-masa kemajuan. Lihat Faisal Ismail, Dilema NU di Tengah Pragmatisme Politik, (Jakarta: DEPAG: 2004), Cet. I, h. 140-141
34 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 35
-
25
di Irak, namun intelektualitas yang dimiliki Gus Dur lebih banyak didapat
dari belajar secara otodidak, melalui membaca dan diskusi bersama kawan-
kawannya.
Setelah Pulang dari Baghdad, Gus Dur mengabdi di Pondok
Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan kemudian menjadi dosen sekaligus
Dekan pada Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy`ari (Unhasy),
sekitar tahun 1970-an, Dawam Rahardjo mengajak Gus Dur bergabung di
Lembaga Penelitian Pengabdian dan Pengembangan Ekonomi Sosial (LP3ES)
Jakarta, sejak saat itu ia rajin menulis dan namanya mulai muncul pada
kolom-kolom media cetak seperti Tempo dan Kompas serta majalah Prisma.35
1. Kondisi Sosio-Politik
Menjelang Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU, ada
beberapa kondisi sosio-politik yang sedikit banyaknya turut
mempengaruhi karir Gus Dur dalam kepemimpinan nasional NU. Kondisi
sosio-politik tersebut di antaranya adalah de-NU-isasi dalam tubuh PPP,
Istilah de-NU-isasi ini mengacu pada pendapat Andree Feillard yang
memandang bahwa sejak J. Naro terpilih sebagai ketua umum PPP pada
tahun 1978, terjadi minimalisasi dan marjinalisasi peran dan porsi warga
NU dalam tubuh PPP, hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah
yang ingin mengondisikan NU, karena pada waktu itu NU bisa dikatakan
cukup vokal dalam mengkritisi pemerintah.36
35 Elyasa KH. Darwis, ed., Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, (Yogyakarta: LKiS,
2010), cet. III, h. 69 36 Andree Feillard, NU vis a vis Negara ,h.223-224
-
26
Adapun bentuk marjinalisasinya adalah pertama berkurangnya
jumlah warga NU dalam kepengurusan PPP, hal ini disebabkan oleh
adanya dominasi dari kelompok modernis, yakni Muslimin Indonesia (MI)
yang mempunyai pemikiran dan gerakan berseberangan dengan NU yang
tradisionalis, kedua berkurangnya jumlah calon anggota legislatif (caleg)
NU yang diajukan oleh PPP kepada pemerintah, sebab J. Naro
menginginkan agar pembagian kursi di DPR pada pemilu 1982 dihitung
menurut hasil pemilu 1955, ini berarti merugikan pihak NU dan
sebaliknya menguntungkan pihak MI, karena MI adalah pewaris sah
Masyumi, dan yang ketiga adalah berkurangnya peran majelis syura dalam
kepengurusan PPP yang didominasi oleh NU, ini terlihat ketika kebijakan-
kebijakan syura dalam PPP sering diabaikan oleh kalangan politisi dari
PPP.37
Kondisi sosio-politik lain yang mempengaruhi terpilihnya Gus Dur
sebagai ketua umum PBNU adalah konflik dalam tubuh NU yang terjadi
pada tahun 1982, konflik ini terjadi antara KH. As`ad Syamsul Arifin dan
tiga kiai senior NU lainnya dengan Idham Chalid, ketua umum
tanfidziyah PBNU yang memimpin sejak tahun 1956.
Konflik bermula ketika Kiai As`ad Syamsul Arifin dari Situbondo,
KH. Ali Ma`sum dari Krapyak, KH. Mahrus Aly dari Lirboyo dan KH.
Masykur dari Jakarta mendatangi kediaman Idham Chalid di Jakarta dan
meminta agar Idham Chalid mengundurkan diri dari jabatan ketua umum
37 Andree Feillard, NU vis a vis Negar, , h. 201-203
-
27
PBNU karena ia dinilai lebih fokus pada PPP dari pada NU, ditambah lagi
pada saat itu Idham Chalid sering sakit-sakitan, sehingga tugasnya di NU
ikut terganggu.
Idham Chalid bersedia mengundurkan diri dengan menandatangani
surat pengunduran diri yang telah disiapkan oleh Kiai As`ad, dan
pengunduran diri ini kemudian mencuat di berbagai media massa sehingga
mengundang kontroversi dan polemik dalam tubuh NU, sebagian
menganggap pengunduran diri Idham Chalid adalah inkonstitusional
karena media untuk naik dan turunnya seorang ketua umum tanfidziyah
adalah muktamar, sebagian lagi menganggap bahwa hal itu sesuai dengan
konstitusi, karena dalam AD/ART NU pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa
syuriah mempunyai wewenang untuk menegur, menyarankan dan
membimbing perangkat organisasi termasuk ketua umum tanfidziyah.38
Akibat konflik tersebut muncul dua kelompok yang saling
bertentangan, yakni kelompok Situbondo yang didominasi oleh kelompok
ulama, dan kelompok Cipete yang didominasi oleh kelompok politisi,39
dalam keadaan seperti ini Gus Dur menjadi aktif menjadi mediator di
antara kedua kubu tersebut.40
Pada tahun 1983, Gus Dur pun sering melakukan perjalanan untuk
38 Untuk mengetahui lebih detail mengenai kronologisnya lihat Slamet Effendy Yusuf,
dkk, DIMANIKA KAUM SANTRI; Menelusuri Jejak dan Pergolakan Kaum Santri, (Jakarta: CV. Rajawali; 1983), cet. I, h. 86-117
39 Nama Situbondo diambil dari tempat Pondok Pesantren yang dipimpin oleh KH. As`ad Syamsul Arifin, dan Cipete mengacu pada tempat kediaman Idham Chalid di Jakarta. Lihat Greg Fealy & Greg Barton, TRADISIONALISME RADIKAL: Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara, Penj. Ahmad Suaedy, dkk (Yogyakarta: LKiS; 2010), cet. III, h. 125-126
40 Greg Fealy & Greg Barton, TRADISIONALISME RADIKAL, h. 132
-
28
mengunjungi satu Pesantren ke Pesantren lainnnya dan menemui
pemimpin-pemimpin Cabang NU yang ada di beberapa kota basis massa
NU seperti di Jawa, Sumatra dan Kalimantan untuk memberikan pejelasan
mengenai perlunya mengadakan pembaruan dan mendesak mereka untuk
mengakui adanya keperluan tersebut,41 keadaan ini dengan sendirinya
membuat Gus Dur cukup dikenal oleh para kyai dan pengurus-pengurus
NU di daerah.
Kondisi sosio-politik selanjutnya yang turut mempengaruhi
terpilihnya Gus Dur menjadi ketua umum PBNU adalah menguatnya
wacana kembali ke Khittah NU 1926. Secara etimologis khittah adalah
garis lurus, sementara jika dilihat dari terminologis dalam wacana ke-NU-
an khittah adalah garis pendirian, perjuangan dan kepribadian NU yang
harus dicerminkan dalam perorangan maupun organisasi, serta dalam
setiap proses pengambilan keputusan.42
KH. Ahmad Shiddiq adalah penggagas ide khittah, dalam
mengartikan khittah KH. Ahmad Shiddiq mengungkapkannya dengan
istilah sederhana, NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana,
kalimat tersebut mengindikasikan bahwa warga NU memiliki kebebasan
dalam menyalurkan hak politiknya dalam partai politik mana pun yang
sesuai dengan pilihannya.43 tidak seperti sebelumnya yang menjadikan
PPP sebagai satu-satunya wadah politik bagi warga NU.
41 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 159 42 Bahrul Ulum, BODOHNYA NU APA NU DIBODOHI" ?..., h. 86 43 H. Sulaiman Fadeli & Muhammad Subhan, ANTOLOGI NU: Sejarah-Istilah-
Amaliah-Uswah, (Surabaya : Khalista : 2007), cet. I, h. 60-61
-
29
Inti dari rumusan Kembali ke Khittah 1926 adalah sikap NU yang
tidak lagi memiliki afiliasi pada salah satu partai politik. Wacana kembali
ke khittah 1926 sebenarnya sudah muncul dalam Muktamar ke-22 NU di
Jakarta pada tahun 1959 yang diungkapkan oleh KH Achyat Chalimi dari
pengurus cabang NU Mojokerto, ia mengatakan: Peranan politik partai
NU telah hilang dan peranannya dipegang oleh perorangan. Sehingga
partai sebagai alat sudah hilang, karena itu diusulkan agar NU kembali
pada tahun 1926
Dalam menanggapi pernyataan tersebut, KH Idham Chalid
sebagai ketua umum PBNU memberikan pandangan umum dengan
mengatakan: Kita kembali kepada semangat dan jiwa ta`abudiyyah tahun
1926, tapi dalam perjuangan, kita berjuang di tahun 1952
Gagasan kembali ke khittah 1926 kemudian muncul kembali dalam
Muktamar ke-25 NU tahun 1974 di Surabaya, gagasan ini diungkapkan
oleh KH. Dahlan, salah seorang Presidium kabinet dan Menteri Agama
dari unsur NU, gagasan serupa juga disampaikan oleh rais amm PBNU,
KH. Wahab Hasbullah yang menekankan pentingnya kembali ke khittah
1926. Namun
gagasan tersebut belum mendapatkan respon secara serius.
Pada Muktamar ke-26 NU tahun 1979 di Semarang kembali muncul
ke permukaan, yang menginginkan agar NU sebagai organisasi yang
berorientasi pada bidang sosial keagamaan bukan pada bidang politik. Hal
ini didasarkan pada perkembangan politik yang tidak menguntungkan bagi
-
30
NU dan sekaligus peranan NU dalam urusan sosial keagamaan mulai
terbengkalai.
Pada tahun 1983 dewan syuriah PBNU membentuk sebuah komite
yang diketuai oleh KH. Ahmad Shiddiq dan sekretarisnya adalah Gus Dur,
salah satu pembahasan dalam komite tersebut adalah mengenai keharusan
NU untuk kembali ke khittah 1926 dengan menjadikan NU sebagai
organisasi sosial keagamaan.44
Dalam tataran konsepsional, menjadikan NU sebagai organisasi
sosial keagamaan telah berhasil namun dalam tataran operasional belum
bisa dikatakan berhasil karena masih terikat dengan PPP, memulihkan
khittah 1926 berhasil secara konsepsional dan operasional terjadi pada
muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo yang sebelumnya dibahas dalam
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang dilaksanakan pada tahun
1983,45 sebuah momentum yang cukup mempopulerkan Gus Dur karena
dalam Munas Alim Ulama tersebut Gus Dur ditunjuk sebagai ketua
panitianya.
Dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU
tahun 1983 bermula ketika persoalan pelik mulai menimpa NU, yakni
mengenai rencana pemerintah yang akan menyeragamkan ideologi
Pancasila terhadap semua ormas yang ada di Indonesia. Jika ada ormas
yang menolak terhadap penyeragaman ideologi ini ormas tersebut akan
langsung dibubarkan oleh pemerintah. Persoalan ini kemudian dibawa ke
44 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 161 45 Bahrul Ulum, BODOHNYA NU APA NU DIBODOHI" ?..., h. 87-89
-
31
Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 46 yang dilaksanakan pada tahun
1983 di Situbondo.
Sebelum Munas Alim Ulama pada tahun 1983 dilaksanakan para
tokoh senior menunjuk Gus Dur menjadi ketua panitianya, dan munas
tersebut merupakan sebuah momentum yang cukup mempopulerkan Gus
Dur, karena Gus Dur banyak berinteraksi dengan banyak pihak baik
dengan internal maupun ekternal NU.
Dalam Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama tersebut, Gus
Dur mengemukakan pandangannya tentang Pancasila dengan
argumentatif, dan tidak sedikit peserta Munas yang menentang pandangan-
pandangannya tersebut, namun setelah debat berjalan secara serius, pada
akhirnya peserta munas dapat menerima pandangan Gus Dur tentang
Pancasila.
Setelah debat selesai para tokoh senior NU memberikan apresiasi
kepada Gus Dur, karena Gus Dur berhasil meyakinkan peserta Munas
dalam menerima Pancasila sebagai asas organisasi, bahkan ada sebagian
yang menginginkan agar Gus Dur menjadi ketua umum PBNU berikutnya
menggantikan Idham Chalid.47
2. Menjadi Kader dan Ketua Umum PBNU
Pada tahun 1970-an Gus Dur berpartisipasi aktif dalam sejumlah
seminar, simposium dan konferensi tentang pembangunan nasional dan
46 Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum tertinggi dalam NU di bawah Muktamar, kegiatan ini dilaksanakan setidaknya setiap lima tahun sekali di antara dua muktamar. Kegiatan Musyawarah Nasional berisi pembahasan masalah-masalah keagamaan yang menjadi porsi syuriah. H. Sulaiman Fadeli & Muhammad Subhan, ANTOLOGI NU...h. 82
47 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 163-166
-
32
melalui kesempatan inilah ia menarik perhatian publik pada peran
pesantren sebagai agen pembangunan komunitas pedesaan dan
pengembangan masyarakat demokratis di tingkat pedesaan.48
Melihat potensi yang dimiliki oleh Gus Dur kemudian Kakeknya
dari pihak ibu, KH. Bisri Syansuri - yang pada saat itu menjabat sebagai
Rais `am PBNU - mengajak Gus Dur untuk terlibat dalam kepengurusan
Syuriah PBNU, Gus Dur baru menerima ajakan kakeknya tersebut pada
tawaran yang ketiga, itu pun atas nasehat ibunya, dan Gus Dur pun masuk
dalam jajaran kepengurusan PBNU, ia duduk sebagai sekretaris muda
syuriah.49
Gus Dur mulai populer baik di lingkungan NU maupun Pemerintah
setelah dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU
di Situbondo, kepopuleran ini kemudian menjadikan Gus Dur terpilih
menjadi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo.
Proses pemilihan kepemimpinan pada Muktamar ke-27 NU di
Situbondo adalah dengan membentuk komisi khusus yang akan
memutuskan
komposisi pemimpin baru, dalam tradisi sunni disebut dengan ahl al-halli
wa al-`aqdi, komisi ini dibentuk oleh KH. As`ad Syamsul Arifin dan
terdiri dari enam orang lainnya. Komisi tersebut kemudian mengangkat
Gus Dur dan KH. Achmad Siddiq masing-masing menjadi ketua umum
48 ENSIKLOPEDI OXFORD DUNIA ISLAM MODERN, Penj. Eva Y. N, dkk,
(Bandung: Mizan; 2001), Jilid I, cet. I, h. 16 49 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 120-121
-
33
dan Rais `Amm PBNU Periode 1984-1989.50
Gus Dur menjabat Ketua umum PBNU selama tiga periode berturut-
turut, periode pertama dari tahun 1984-1989, periode kedua dari tahun
1989-1994 dan periode ketiga dari tahun 1984 sampai 1999, pada
Muktamar ke-30 NU tahun 1999 di Lirboyo Gus Dur adalah Presiden RI,
dengan demikian Gus Dur mesti turun dari jabatan ketua umum PBNU,
hal ini bisa dikatakan ironis karena pada saat Gus Dur menjadi Presiden
Gus Dur masih menjabat sebagai ketua umum PBNU.51
B. HASYIM MUZADI
Nama lengkap Hasyim Muzadi adalah Ahmad Hasyim Muzadi, ia
dilahirkan di Bangilan, Tuban, Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus 1944.
Ayahnya adalah seorang pengusaha yang terhitung sukses, walau pun secara
genealogis-biologis ayahnya bukan seorang Kiai yang memiiki pondok
pesantren, namun ayahnya Hasyim adalah seseorang yang memiliki kecintaan
dan ke-takdzim-an kepada ulama,52 anak yatim dan anak-anak yang tidak
mampu.53
Kecukupan secara materi dari keluarga menjadikan Hasyim mudah
dalam mengenyam pendidikan formal, hingga Hasyim dapat mengikuti
50 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 167-169 51 Disebut ironis karena hal ini jelas mencederai hasil Muktamar NU di Situbondo tahun
1984. 52 Sifat dan sikap sang ayah ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk
menilai pengaruhnya terhadap sosok Hasyim Muzadi, karena dalam kitab talim al-muta`allim dijelaskan bahwa barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang alim, maka seyogyanya ia menjaga, memuliakan, menghormati dan memberi segala sesuatu kepada alim ulama (fuqaaha). Syekh Azzarnuji, Ta`lim al-Muta`llim; thariqat al-ta`allum, (Semarang: Karya Thaha Putra; tt), h.17
53 Drs. Ibnu Asrori, Sh., MA., KH. Hasyim Muzadi; Religiusitas & Cita-cita Good Governance, ( Sidoarjo: Citra Media; 2004), cet. I, h. 15-16
-
34
pendidikan di Kuliyyatul Mu`allimin Islamiyyah (KMI) Pondok Modern
Gontor Ponorogo, sebuah lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan
khazanah pemahaman Islam yang berbasis pada modernisasi ajaran, dan
lembaga ini pun dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi
kedisplinan dan profesionalitas.
Setelah menamatkan pendidikan dan mengabdi di Gontor, pada tahun
1964 Hasyim melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel Malang
dan tinggal bersama kakaknya KH. Muchid Muzadi, dari sinilah ia
mendapatkan bimbingan dan arahan dari kakaknya yang pada saat itu telah
menjadi seorang tokoh NU yang disegani oleh warga nahdliyyin karena
kedalaman ilmu yang dimilikinya.54
Jiwa kepemimpinan Hasyim tumbuh ketika ia mulai aktif di organisasi
yang berbasiskan NU, karena ia selalu terpilih menjadi ketua di beberapa
organisasi tersebut, yakni Gerakan Pemuda Ansor, Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMI),
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tentunya Nahdlatul Ulama.55
1. Kondisi Sosio-politik
Menjelang Hasyim Muzadi terpilih sebagai ketua umum PBNU, ada
beberapa kondisi yang sedikit banyaknya turut mempengaruhi karirnya
dalam kepemimpinan nasional NU, di antaranya adalah momentum
gerakan reformasi pada tahun 1998.
54 Drs. Ibnu Asrori, Sh., MA., KH. Hasyim Muzadi;.., h. 19-21 55 Drs. Ibnu Asrori, Sh., MA., KH. Hasyim Muzadi;.., h. 21- 23
-
35
Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada tahun 1998 Soeharto
dijatuhkan oleh people power yang tergabung dalam gerakan reformasi
karena salah satu agenda utama reformasi adalah menurunkan Soeharto
dari tampuk kekuasaan.
Tokoh reformasi yang dikenal mendukung terhadap gerakan ini
salah satunya adalah Gus Dur yang pada saat itu menjabat sebagai ketua
umum PBNU, Gus Dur beserta tokoh-tokoh nasional lainnya membentuk
kelompok yang dikenal dengan kelompok Ciganjur, tokoh-tokoh tersebut
adalah Megawati Soekarno Putri, Amin Rais dan Sri Sultan
Hamengkubuwono.
Pada perkembangan selanjutnya PBNU menghimbau kepada seluruh
jamiyah dan jama`ah NU agar dapat mengikuti agenda reformasi secara
aktif, yang kemudian ditunjukkan dengan digelarnya istighosah56 oleh
warga NU di
berbagai daerah di Indonesia, istighosah ini dalam rangka memohon
kepada
Allah Swt. agar menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis dan musibah
yang sedang terjadi,57 yakni krisis moneter dan instabilitas politik yang
berdampak pada kerusuhan dan penjarahan di berbagai tempat.
Kejadian yang tidak kalah fenomenal pada saat itu adalah kasus
ninja dan dukun santet di Banyuwangi Jawa Timur, Hasyim yang ketika
56 Istighosah artinya memohon pertolongan kepada Allah Swt. Istighosah dianjurkan
oleh agama terutama ketika sedang menghadapi permasalahan yang rumit. H. Sulaiman Fadeli & Muhammad Subhan, ANTOLOGI NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah.., h. 122
57 Bahrul Ulum, BODOHNYA NU APA NU DIBODOHI" ?..., h. 132
-
36
itu menjabat Ketua Umum Pengurus Wilayah NU Jawa Timur berhasil
meredam gejolak ini terutama kepada warga NU yang ada di daerah-
daerah,58 dan nama Hasyim Muzadi mulai banyak dikenal ketika berhasil
menyelesaikan kasus tersebut.59
Setelah Rezim Orde baru tumbang dari kekuasaan di Indonesia,
partai-partai politik mulai bermunculan, termasuk partai politik yang
mengidentifikasikan dirinya sebagai partai politik NU dan partai
politik yang pembentukannya difasilitasi oleh PBNU.
Hal ini bermula ketika usulan yang masuk ke PBNU tentang partai
politik sangat beragam, ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk
partai politik (parpol), ada juga yang mengusulkan agar PBNU menjadi
partai politik, dan dari berbagai usulan yang masuk ke PBNU tersebut
tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan dan nama parpol yang paling
banyak muncul adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Ummat dan
Kebangkitan Bangsa.60
Setelah melalui berbagai rapat internal yang panjang, PBNU pada
akhirnya mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Gus
Dur yang pada saat itu masih menjabat sebagai ketua umum beberapa kali
memberikan statement bahwa PKB adalah satu-satunya partai politik yang
mendapat legitimasi dari NU.
58 Drs. Ibnu Asrori, Sh., MA., KH. Hasyim Muzadi..., h. 24 59 Risalah Nahdlatul Ulama, Edisi 14/Tahun III/1431 H, h. 11 60 Musa Khazim dan Alfian H.amzah., 5 Partai Dalam Timbangan, (Bandung: Pustaka
H.idayah.; 1999), Cet. I, h. 237-238
-
37
Setelah PKB berdiri, kontroversi mulai mencuat, karena
menganggap PBNU telah mencederai hasil muktamar ke-27 NU ditambah
lagi dengan haluan partai yang menginginkan Negara sekuler, dari pro-
kontra terhadap pembentukan PKB tersebut Hasyim Muzadi yang pada
saat itu menjabat sebagai ketua Umum PWNU Jawa Timur berada pada
posisi yang pro, karena menurutnya di era multi partai ini NU harus
memiliki kendaraan politik yang under control NU karena kepentingan
NU tidak mungkin tumbuh dalam sebuah aliran politik yang
kepentingannya berbeda secara diametral.61
Pasca Soeharto turun dari kursi kepresidenan, ia melantik wakilnya
B. J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, namun
beberapa kalangan merasa bahwa Habibie merupakan pendukung rezim
orde baru yang akan menjadi penghambat dalam proses reformasi di
Indonesia, oleh sebab itu mesti dilakukan Pemilihan umum.
Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum pemerintah membentuk
KPU yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres)
No. 77/M/1999,62 setelah pemilihan umum dilaksanakan, PKB berada di
posisi ketiga dengan persentasi suara 10, 2 % setelah PDIP yang
memperoleh 30, 8 %, Partai Golkar 24 % dan PPP 11, 8 %.63
Koalisi partai dalam parlemen untuk memilih Presiden diprediksikan
akan terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu PDIP yang menjagokan
Megawati sebagai calon Presidennya dan kubu Golkar yang menjadikan
61 Bahrul Ulum, BODOH.NYA NU APA NU DIBODOH.I..., h. 136-141 62 Bahrul Ulum, BODOH.NYA NU APA NU DIBODOH.I..., h. 154 63 Bahrul Ulum, BODOH.NYA NU APA NU DIBODOH.I..., h. 155
-
38
Habibie sebagai calon Presidennya, namun beberapa waktu kemudian
untuk mengimbangi kedua kekuatan tersebut Amien Rais membentuk
kekuatan ketiga yang disebut dengan poros tengah, poros tengah ini
merupakan koalisi partai-partai politik Islam yang ada di parlemen dan
Gus Dur adalah calon presiden dari poros tengah.64
Pada perkembangan selanjutnya Habibie mengundurkan diri sebagai
calon Presiden, dengan demikian yang menjadi kontestan dalam pemilihan
Presiden adalah Gus Dur dan Megawati. Pemilihan Presiden dilaksanakan
pada pada tanggal 20 Oktober 1999 dan menjelang detik-detik akhir
pemungutan suara gemuruh lantunan shalawat mulai menggema di dalam
gedung DPR/MPR hal ini merupakan simbol bahwa Gus Dur sudah bisa
dipastikan akan menjadi Presiden Republik Indonesia,65 pada saat Gus Dur
terpilih menjadi Presiden Gus Dur masih menjabat ketua umum PBNU.
Tahun 1999 adalah masa berakhirnya kepemimpinan Gus Dur di
PBNU, Gus Dur tidak mungkin maju lagi menjadi ketua umum atau rais
`amm PBNU karena posisinya adalah Presiden Republik Indonesia.
Jabatan ketua umum tersebut akan dilepaskan oleh Gus Dur pada
Muktamar ke-30 NU, tempat yang dipilih dalam muktamar tersebut adalah
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur.
Tempat dilaksanakannya muktamar ke-30 NU adalah di Jawa Timur,
dan pada saat itu Hasyim Muzadi adalah ketua umum PWNU Jawa Timur,
dan tentu Hasyim memiliki keterlibatan dalam menyiapkan agenda lima
64 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 360-363 65 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 166
-
39
tahunan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pemilihan ketua umum
PBNU.
2. Menjadi Kader dan Ketua Umum PBNU
Hasyim Muzadi adalah kader NU yang merintis karir dan
kepemimpinannya dari bawah, sejak tahun 1966 ia telah menjadi kader
sekaligus ketua NU, pengalamannya dalam berorganisasi yang cukup
panjang lambat laun mengantarkan karirnya terus menanjak.
Berikut ini adalah profil singkat karir Hasyim dalam NU yang terus
menanjak dari waktu ke waktu; Ketua Ranting NU Bululawang-Malang,
(1964), Ketua Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bululawang-Malang
(1965), Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Malang (1966), Ketua kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)
Malang (1966), Ketua Cabang GP Ansor Malang (1967-1971), Wakil
Ketua Pengurus Cabang NU Malang (1971-1973), Ketua Pengurus
Cabang PPP Malang (1973-1977), Ketua Pengurus Cabang NU Malang
(1973-1977), Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Timur (1983-
1987), Ketua Pengurus Pusat GP Ansor (1987-1991), Sekretaris Pengurus
Wilayah NU Jawa Timur (1987-1988), Wakil Ketua Pengurus Wilayah
NU Jawa Timur (1988-1992), Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur
(1992-1999).66
Pada tahun 1999, NU mengadakan muktamar ke-30 yang
bertempat di Lirboyo Jawa Timur, dalam muktamar tersebut Hasyim maju
66 Drs. Ibnu Asrori, SH., MA., KH. Hasyim Muzadi, h. 21-23
-
40
sebagai calon ketua umum PBNU periode 1999-2004, bersaing dengan
beberapa kandidat lain, namun saingan yang paling berat untuk Hasyim
adalah Said Aqil Siradj, yang pada saat itu menjabat sebagai katib `amm
Syuriah PBNU dan sekaligus sebagai ketua panitia pusat muktamar ke-30
NU, hasil perolehan suara dari pemilihan tersebut Hasyim memperoleh
205 suara dan disusul oleh Said Aqil Siradj yang mengantongi 105 suara,67
dengan demikian Hasyim resmi terpilih menjadi ketua umum PBNU untuk
periode 1999-2004.
Hasyim menjabat sebagai ketua umum PBNU selama dua periode,
periode pertama dari tahun 1999 sampai 2004, pada periode ini Hasyim
masuk dalam bursa calon wakil Presiden RI bergandengan dengan
Megawati Soekarno Putri, ironisnya pada saat yang sama Hasyim masih
menjabat ketua umum PBNU walau pun dengan status non-aktif,68 periode
kedua kepemimpinan Hasyim di PBNU adalah dari tahun 2004 sampai
tahun 2009 dan pada Muktamar ke-32 NU tahun 2009 di Makassar
Hasyim turun dari jabatan ketua umum PBNU dan memilih untuk tidak
maju lagi dalam bursa calon ketua umum PBNU periode 2009-2014.
67 Muhammad Shodiq, Dinamika Kepemimpinan NU; Refleksi Perjalanan KH. Hasyim
Muzadi, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur; 2004), cet. I, h. 181 68 Disebut ironis karena hal ini jelas mencederai hasil Muktamar NU di Situbondo tahun
1984.
-
41
BAB IV
PERILAKU POLITIK ABDURRAHMAN WAHID
DAN HASYIM MUZADI
A. Perilaku Politik Abdurrahman Wahid
Gus Dur menjabat ketua umum PBNU sejak terpilih dalam muktamar
Situbondo tahun 1984, ia terpilih menjadi pemimpin NU karena sebelumnya
ia sering berinteraksi dengan beberapa kalangan, baik dengan kalangan
internal NU maupun eksternal NU, sehingga baik langsung maupun tidak
langsung Gus Dur mendapatkan dukungan untuk menjadi pemimpin NU
periode berikutnya.
Selain itu, menjelang muktamar NU di Situbondo dilaksanakan Gus
Dur ditunjuk sebagai ketua panitia musyawarah nasional alim ulama NU,
dalam musyawarah nasional alim ulama tersebut seakan turut
mempromosikan pemikiran dan intelektualitas Gus Dur yang dinamis dan
progresif, sehingga mengundang decak kagum baik dari kyai sepuh maupun
para peserta Munas.
Gus Dur menjabat ketua umum PBNU selama tiga periode (dari tahun
1984 sampai 1999; masing-masing periode selama lima tahun), dan perilaku
politik Gus Dur selama memimpin NU yang akan dijadikan objek penelitian
adalah menyangkut gaya kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi gaya
kepemimpinan, gerakan politik serta pengaruh dan wibawanya.
-
42
1. Gaya Kepemimpinan
Sejak Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU, ia dikenal
sebagai sosok yang kontroversial, kontroversi ini adalah sebagai ekses
dari sikap Gus Dur yang mengambil kebijakan dan keputusan
cenderung tidak melibatkan anggota yang lain.
Menurut tipologi kepemimpinan yang dilihat dari proses
kepemimpinan, hal ini tidak bisa lepas dari seorang Gus Dur yang
memiliki tipologi pemimpin yang autokratis, yakni sebuah tipologi
pemimpin yang identik dengan pemusatan otoritas pada pemimpin
dan dalam pengambilan keputusan lembaga sangat bergantung
padanya.1 Menurut Greg Barton, Gus Dur memang memiliki gaya
kepemimpinan seperti ini apalagi setelah KH. Ahmad Siddiq
meninggal dunia.2
KH. Ahmad Siddiq sendiri merupakan sosok yang dikagumi dan
disegani oleh Gus Dur, selain karena secara struktural KH. Ahmad
Siddiq adalah atasannya di PBNU yang menjabat sebagai Rais `amm,
KH. Ahmad Siddiq juga memiliki karisma dan wibawa tersendiri bagi
Gus Dur, sebagaimana yang ia ungkapkan dalam sebuah tulisannya di
Kompas.3
Masih menurut Greg Barton, selama Gus Dur menjabat ketua
1 S.G. Hunneryager & I. L. Heckman, ed. Kepemimpinan (Semarang: Dahara Prize:
1992), cet. I, h. 10 2 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 227 3 Abdurrahman Wahid, In Memoriam: Kiai Achmad Shiddiq, dalam Frans M. Parera&T.
Jakob Koekerits (Peny.), Gus Dur Menjawab Perubahan: Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, (Jakarta: Kompas: 2000), cet. II, h. 95-101
-
43
umum PBNU ia selalu bertindak sendiri, hal ini bukan dikarenakan
Gus Dur tidak dapat bergaul dengan orang lain atau tidak mampu
membuat aliansi, melainkan hal ini dikarenakan beberapa alasan, salah
satunya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia.4 Gus Dur sering
melakukan tindakan yang menurutnya dianggap benar.
Tipologi kepemimpinan Gus Dur ini misalnya adalah Gus Dur
mendirikan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma,5
padahal sebagian besar ulama NU mempersoalkan BPR Nusumma
karena selain program tersebut bekerjasama dengan konglomerat Cina,
yakni Edward Suryadjaja, BPR tersebut juga menganut sistem bunga
bank dan menurut para ulama NU bunga tersebut adalah haram, namun
Gus Dur tidak mempedulikan kritikan tersebut dan tetap melangkah
sehingga BPR Nusumma tumbuh di berbagai daerah.6
Gus Dur mengakui bahwa dalam tradisi NU, kaidah fiqh
merupakan hal utama dalam mengambil kebijakan dan menurut Gus
Dur fiqh sendiri dalam memandang sesuatu terdapat aneka ragam
pilihan hukum yang bisa disesuaikan dengan berbagai kondisi.7
Contoh lainnya adalah dalam melakukan rapat akbar untuk
merayakan ulang tahun yang ke-66 berdirinya NU, Gus Dur hampir
tidak melakukan konsultasi dengan rekan-rekannya, menurut Greg
4 Greg Barton, Biografi Gus Dur, hal. 346-347 5 BPR ini merupakan hasil kerjasama antara NU dan Bank Summa, sehingga dinamai
BPR Nusumma. 6 Drs. H. A. Nasir Yusuf, ed. NU dan Gus Dur, h. 36-37. 7 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia&Transformasi
Kebudayaan, (Jakarta: The Wahid Institute; 2007), cet. I, h. 219
-
44
Barton hal ini merupakan gaya khasnya Gus Dur.8
Selain itu, jika dilihat dari hasil proses kepemimpinan, Gus Dur
masuk dalam kategori pemimpin moderat, karena ketika memimpin
NU, dalam mencapai tujuannya Gus Dur lebih memilih menggunakan
dialog dari pada dengan tindakan-tindakan kekerasan serta masih
menggunakan unsur-unsur dan sistem-sistem rezim lama dalam
kepengurusan NU.
Hal ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi prinsip dalam
lingkungan NU, prinsip tersebut adalah al-muhafadzah ala qodim al-
shalih wa akhdzu bil jadid al-aslah (mempertahankan tradisi lama
yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik), prinsip ini bisa
diibaratkan seperti sebuah rel kereta api, NU adalah keretanya dan
masinisnya adalah ketua umum, jadi siapa pun ketua umumnya akan
selalu berada pada jalur rel tersebut.
Indikatornya adalah ketika menjadi ketua umum PBNU Gus Dur
tidak tercatat melakukan sebuah tindakan yang menjadi ciri khas dari
pemimpin ekstrem, yaitu tindakan-tindakan kekerasan untuk mencapai
tujuannya.
Jika dilihat dari hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin,
Gus Dur masuk dalam kategori pemimpin transformatif, karena Gus
Dur mencoba melakukan peningkatan gairah berpikir dalam tubuh NU
dengan cara memberikan restu serta mendukung gerakan halaqah dan
8 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 227
-
45
forum-forum kajian untuk mengeksplorasi berbagai pemikiran, hal ini
dilakukan agar pemikiran-pemikiran NU bisa dinamis dan fleksibel
sesuai dengan konteks kekinian. Dengan demikian Gus Dur bisa
dikatakan sebagai pemimpin transformatif.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, tipologi
kepemimpinan Gus Dur yang dilihat dari proses kepemimpinan, Gus
Dur masuk dalam kategori autokratis, namun jika dilihat dari karakter
kepemimpinan, Gus Dur masuk dalam kategori pemimpin yang aktif-
positif, karena ia sering terlibat dalam beberapa keputusan yang dibuat
sendiri dan kemudian Gus Dur melaksanakan keputusan tersebut serta
menganggap bahwa apa yang ia lakukan bernilai positif.
Karakter kepemimpinan ini mulai terlihat ketika Gus Dur
menjabat ketua umum pada akhir periode pertama, sikap Gus Dur yang
seolah melangkah sendiri dan tanpa menghiraukan kritik apalagi
masukan dari orang lain menunjukkan bahwa ia merupakan pemimpin
yang aktif-positif.
Misalnya ketika menjabat sebagai ketua umum PBNU Gus Dur
memberikan apresiasasi dan menyokong terhadap rasionalitas yang
diperkenalkan oleh Mu`tazilah dan usahanya dalam pribumisasi Islam
di Indonesia, hal ini membuat resah kiai konservatif yang telah lanjut
usia, namun Gus Dur memberikan dalih bahwa Jika NU ingin
mendapatkan tempat di dunia modern maka NU harus melakukan hal
-
46
tersebut.9
Adapun Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Gus Dur adalah
lebih bersumber dari kepemimpinan karismatik, karena walaupun
secara legal-formal Gus Dur adalah ketua umum PBNU yang mendapat
legitimasi secara konstitusi, namun sumber kekuasaan yang dimilikinya
lebih pada asumsi bahwa Gus Dur adalah seorang yang mempunyai
sebuah karisma tersendiri. Kekarismatikannya Gus Dur ini lahir
sebagaimana yang disebutkan oleh Greg Barton mengatakan bahwa:
Walaupun Gus Dur, dalam banyak hal, adalah seorang manajer yang buruk dan hampir tidak melakukan reformasi apa pun dalam bidang administrasi organisasi, ia telah memberikan kontribusi besar dalam mengubah kultur kaum cendekiawan. Barangkali kontribusi Gus Dur yang terbesar kepada warga NU, dan khususnya yang muda-muda, adalah bahwa ia memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjelajahi ide-ide baru dan juga melakukan usaha-usaha baru. Walaupun popularitas Gus Dur di antara orang-orang muda NU sangat besar, ia tidak mau membina hubungan mentor-protege antara dirinya dan pemimpin-pemimpin muda. Tampaknya ia sengaja menciptakan suatu kondisi agar orang-orang muda ini dapat berkiprah dalam diskusi-diskusi kritis, tanpa dirinya harus secara langsung memberikan bimbingan. Lantas generasi muda NU menganggapnya sebagai tokoh karismatik dan bisa memberikan inspirasi. Gus Dur menurut mereka memberikan semacam izin untuk mencoba hal-hal baru dan menjelalahi ide-ide baru. 10
Bukan hanya itu saja, kekarismatikannya Gus Dur pun lahir dari
sisi genealogis, karena secara genealogis Gus Dur merupakan cucu dari
pendiri NU, baik dari pihak ibu maupun ayah, dalam tradisi NU para
santri dan mantan santri harus menghormati kyai berikut keluarganya
kyai, ini dilakukan agar bisa mendapatkan barokah dari kyai tersebut.
9 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 211-212 10 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 190-191
-
47
2. Pengaruh dan Wibawa
Gus Dur adalah seorang intelektual yang memiliki pengetahuan
dari dua dunia, yakni timur dan barat, ketika memimpin NU Gus Dur
mencoba menularkan intelektualitasnya ini kepada warga NU khususnya
anak-anak muda NU yang memiliki gairah untuk menjelajahi aneka
ragam pemikiran, dengan sendirinya intelektualitas yang dimiliki oleh
Gus Dur ini kemudian menjadi sebuah media untuk mendapatkan sumber
kekuasaan karismatik, ke-karismatik-annya ini dengan sendirinya
menjadikan Gus Dur cukup berpengaruh dalam lingkungan warga NU.
Pada perkembangan selanjutnya, saking kuatnya pengaruh Gus Dur
dalam NU, ada sebuah anekdot yang mengatakan bahwa Gus Dur + NU
= Gus Dur dan NU + Gus Dur = Gus Dur,11 anekdot tersebut dapat
menunjukkan bahwa pengaruh Gus Dur dalam NU begitu dominan,
karena antara NU dan Gus Dur seolah bisa dikatakan seperti dua sisi
mata uang.
Pengaruh Gus Dur dalam NU kemudian sekaligus menjadikannya
berwibawa,12 wibawa ini bukan hanya karena keintelektualan yang
dimilikinya, melainkan juga karena Gus Dur adalah cucu dari pendiri NU
baik dari pihak ibu maupun ayah, bahkan KH. As`ad Syamsul Arifin,
seorang tokoh senior NU yang cukup berkarisma mengakui bahwa ia
tidak dapat memarahi Gus Dur dengan alasan bahwa ia adalah cucu dari
11 Musa Khazim&Alfian Hamzah, ed. Lima Partai dalam timbangan , h. 234 12 Namun rupanya wibawa Gus Dur lebih kuat pada kelompok kultural NU (terutama
dalam kalangan muda NU yang mendapat pencerahan pemikiran dari Gus Dur) dari pada kelompok yang ada dalam struktural NU. Mungkin hal ini sebagai ekses dari gaya kepemimpinan Gus Dur yang autokratis.
-
48
gurunya, yakni KH. Hasyim Asy`ari, karena dalam tradisi pesantren
dituntut untuk menghormati kyai dan keluarganya kyai.
3. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik
Gus Dur adalah seorang intelektual yang memiliki dunia dimensi
keilmuan, yakni Islam dan Barat, kapasitas keintelektualannya ini
kemudian dijadikan sebagai landasan Gus Dur dalam mengelola NU,
Kacung Marijan mengatakan bahwa selama memimpin NU, Gus Dur lebih
menggunakan kapasitas keintelektualannya ketimbang sebagai
administrator.13
Sebagaimana ciri intelektual, yang selalu memproduksi gagasan,
Gus Dur pun memimpin NU dengan berbagai gagasan, mulai dari
masalah-masalah politik, sosial dan keagamaan, gagasan tersebut
kemudian diaktualisasikan dalam sebuah tindakan atau perilaku, termasuk
di dalamnya adalah perilaku politik.
Perilaku politik tersebut di antaranya adalah konsistensi Gus Dur
dengan Pancasila yang dipahami oleh Gus Dur, konsistensi Gus Dur ini
terlihat ketika Gus Dur dalam memandang pancasila di satu sisi terkadang
pro status quo dengan pemerintah, namun di sisi lain menjadi oposan
pemerintah, atau dengan kata lain terkadang Gus Dur menjadikan
Pancasila sebagai tameng ketika berhadapan dengan pemerintah, dan
terkadang pula Gus Dur menjadikan pancasila sebagai senjata untuk
melawan Pemerintah.
13 Drs. A. A. Nasir Yusuf, ed. NU dan Suksesi, (Bandung: Humaniora Utama Press;
1994), cet. I, h. 94
-
49
Pancasila dijadikan sebagai tameng oleh Gus Dur ketika ia - pasca
Muktamar ke-27 NU di Situbondo - menunjukkan komitmennya dengan
ideologi pancasila, sehingga ia diangkat oleh Soeharto menjadi
indoktrinator resmi pancasila yang dikenal dengan nama Manggala
Nasional.14
Menurut Gus Dur bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural,
sehingga sulit untuk menerima negara agama (teokrasi), tapi bangsa
Indonesia juga adalah bangsa yang relijius, sehingga sulit untuk menerima
sekularisme, maka alternatif yang tepat adalah Pancasila, karena ia berada
di antara keduanya.15
Sementara pancasila dijadikan senjata oleh Gus Dur ketika ia hendak
menolak pencalonan Soeharto menjadi Presiden berikutnya pada tahun
1991, bentuk penolakan ini dengan melakukan Rapat Akbar NU yang
bertempat di Senayan dengan tema yang diusung adalah tentang
komitmen NU dalam mendukung Pancasila, hal ini dilakukan untuk
mencegah Soeharto dalam memonopoli makna pancasila, karena Soeharto
sering memberikan legitimasi terhadap tindakan-tindakan intimidasinya
dengan menggunakan dalih pancasila.16
Menurut Gus Dur, harus ada alternatif lain atas penafsiran pancasila
selain untuk mencegah monopoli atas pemaknaan pancasila oleh
pemerintah, juga untuk meminimalisir munculnya ideologi lain yang akan
14 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h.182 15 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara
Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute: 2006), cet I, h. 116-118 16 Darwis, Elyasa KH, ed., Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, (Yogyakarta: LKiS,
2010), cet. III, h. 108
-
50
menggantikan pancasila yang telah dikebiri oleh pemerintah, yakni dengan
ideologi Islam.17
4. Gerakan Politik
Sejak terpilih sebagai ketua umum PBNU Gus Dur memilih untuk
membina hubungan baik dengan Soeharto, pada periode
kepemimpinannya ini (1984-1989) NU mendapatkan perlakuan istimewa
dari pemerintah, menurut Greg Barton, setelah hubungan NU dan
pemerintah membaik sejumlah keuntungan besar masuk kepada NU,
misalnya kerja sama yang erat dengan departemen Agama,18 diangkatnya
Gus Dur menjadi anggota MPR mewakili Golkar,19 diangkatnya orang-
orang NU masuk dalam birokrasi dan Golkar serta madrasah-madrasah
dan guru-gurunya yang merupakan basis NU mendapatkan perhatian
khusus dari pemerintah,20 namun hubungan baik tersebut tidak
menjadikan Gus Dur lemah dalam mengkritisi Soeharto, sebaliknya
Gus Dur tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap
Soeharto.21
Sikap Gus Dur tersebut dapat menunjukkan bahwa Gus Dur adalah
seorang yang masuk dalam Presurre Group/Interest Group (kelompok
penekan/kelompok kepentingan), yang mempunyai kepentingan untuk
mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
17 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 89-90 18 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h.180 19 Pengangkatannya ini hanya sekedar simbolik saja untuk melegitimasi pengangkatan
Soeharto menjadi Presiden, namun menurut Greg Barton simbolisme inilah yang justru dianggap penting. Greg Barton, Biografi Gus Dur, h.183
20 Bahrul Ulum, BODOHNYA NU APA NU DIBODOHI" ?..., h. 102 21 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h.183
-
51
Misalnya dalam kontroversi pembuatan waduk kedung ombo di
Jawa tengah, Gus Dur mengkritisi pemerintah dengan lantang, karena ada
beberapa kerugian yang harus ditanggung dalam proyek tersebut, di
antaranya adalah proyek tersebut akan merusak lingkungan, selain itu
pemerintah tidak adil dalam mengganti tanah para petani di daerah
tersebut, alasan lainnya adalah sisa lahan dari proyek tersebut dijadikan
lapangan golf yang mewah, hal tersebut menunjukkan sikap Soeharto
yang mementingkan diri sendiri.22
Perilaku politik Gus Dur yang lantang dalam mengkritisi
pemerintah merupakan hasil dari pertimbangan dan perhitungan Gus Dur
yang mempunyai paling tidak dua modal, pertama kedekatan Gus Dur
dengan Benny Moerdani yang pada saat itu menjabat sebagai kepala
badan intelejen, selain untuk mempengaruhi pikiran dalam tubuh militer,
kedekatan ini dapat memberikan masukan yang berguna kepada Gus Dur
sehingga Gus Dur dapat mengukur sejauh mana ia dapat mengkritik
pemerintah tanpa menimbulkan reaksi amarah,23 kedua, menurut
perhitungan Gus Dur, Soeharto enggan menentangnya untuk
menghindari kemarahan warga NU yang jumlahnya mencapai puluhan
juta jiwa.24
B. Perilaku Politik Hasyim Muzadi
22 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 188 23 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 182-183 24 Greg Barton, Biografi Gus Dur, h. 187
-
52
Hasyim Muzadi menjabat ketua umum PBNU sejak ia terpilih dalam
muktamar di Lirboyo tahun 1999, Hasyim terpilih menjadi pemimpin NU
karena ia dikenal sebagai seorang yang setia dan teguh membela Gus Dur25
terutama dalam muktamar NU di Tasikmalaya pada tahun 1994, sebuah
Muktamar NU yang benar-benar mendapatkan intervensi dari pemerintah26
untuk menjegal Gus Dur agar Gus Dur tidak terpilih kembali menjadi ketua
umum PBNU.27
Hal lain yang memberikan pengaruh dalam terpilihnya Hasyim
adalah ketika menjelang muktamar NU di Lirboyo dilaksanakan, Hasyim
memberikan kontribusi yang besar dalam mendulang suara PKB di Jawa
Timur,28 sebagaimana diketahui, PKB adalah anak emas partai politik NU,
karena PKB merupakan sebuah partai politik yang dibentuk dan
25 Hasyim adalah pendamping Gus Dur di NU, karena selama kurang lebih 20 tahun
(yakni sejak Gus Dur masuk dalam jajaran PBNU pada tahun 1979 sampai Gus Dur turun dari jabatan ketua umum PBNU pada tahun 1999) Hasyim selalu mengikuti dan sharing dengan Gus Dur mengenai langkah dan pemikiran Gus Dur di NU, dan ketika Gus Dur menjabat ketua umum PBNU Hasyim adalah justifikator Gus Dur yang selalu memberikan penjelasan kepada grass root NU atas pernyataan-pernyataan Gus Dur yang dianggap kontroversial, seperti mengenai kontroversi pandangan Gus Dur tentang ucapan assalamu`alaikum yang boleh diganti dengan selamat pagi dan kontroversi atas masuknya Gus Dur dalam yayasan Simon Perez di Israel. Wawancara dengan Hasyim Muzadi, Depok, 27 Oktober 2010
26 Menurut Hasyim Muzadi, dari dahulu sampai saat ini tidak akan pernah ada kekuasaan di Indonesia yang menginginkan NU bersatu menjadi kekuatan politik di Indonesia, karena jika itu terjadi akan menganggu dan menghambat kekuasaan yang dimilikinya, dan ketika perpecahan itu terjadi pemerintah akan selalu membela dan mendukung pihak yang lebih kecil, dan dalam muktamar NU di Tasikmalaya pemerintah mendukung Abu Hasan menjadi ketua umum PBNU. Wawancara dengan Hasyim Muzadi, Depok, 27 Oktober 2010.
27 Menurut Andree Feillard (seorang peneliti NU asal Perancis), Hasyim Muzadi adalah salah seorang yang akti













![[Skripsi] SMS Gateway Trayek - Achmad Luthfi](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cf9372550346f57b9d8a1b/skripsi-sms-gateway-trayek-achmad-luthfi-569ca6feb2791.jpg)