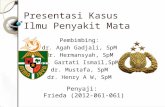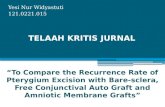lp pterigium
-
Upload
haikjismail -
Category
Documents
-
view
203 -
download
5
description
Transcript of lp pterigium

1
BAB IPENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pterigium merupakan pertumbuhan fibrovaskular konjungtiva yang bersifat
degeneratif dan invasif. Seperti daging berbentuk segitiga, dan umumnya bilateral
di sisi nasal. Keadaan ini diduga merupakan suatu fenomena iritatif akibat sinar
ultraviolet, daerah yang kering dan lingkungan yang banyak angin, karena sering
terdapat pada orang yang sebagian besar hidupnya berada di lingkungan yang
berangin, penuh sinar matahari, berdebu atau berpasir. Temuan patologik pada
konjungtiva, lapisan bowman kornea digantikan oleh jaringan hialin dan elastik.
Jika pterigium membesar dan meluas sampai ke daerah pupil, lesi harus
diangkat secara bedah bersama sebagian kecil kornea superfisial di luar daerah
perluasannya. Kombinasi autograft konjungtiva dan eksisi lesi terbukti
mengurangi resiko kekambuhan.
Uveitis adalah suatu inflamasi pada traktus uvea. Uveitis banyak
penyebabnya dan dapat terjadi pada satu atau semua bagian jaringan uvea. Pada
kebanyakan kasus, penyebabnya tidak diketahui.
Penyakit peradangan pada traktus uvealis umumnya unilateral. Di dunia,
rata-rata insiden penyakit ini sekitar 15 dari 100.000 jiwa. Biasanya terjadi pada
dewasa muda dan usia pertengahan (20-50 tahun). Uveitis jarang terjadi pada
anak dibawah umur 16 tahun, hanya sekitar 5% sampai 8% dari jumlah total.
Kira-kira setengah dari jumlah anak yang mendreita uveitis umumnya uveitis
posterior dan panuveitis. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam angka
kesakitan.
Penatalaksanaan uveitis tergantung pada penyebabnya. Biasanya disertakan
kortikosteroid topikal atau sistemik dengan obat-obatan sikloplegik-midriatik
dan/atau imunosupresan non kortikosteroid. Jika penyebabnya adalah infeksi
diperlukan terapi antibiotik.

2
I.2 Rumusan Masalah
I.2.1 Bagaimana etiologi, patogenesis, diagnosis dan penatalaksanaan Pterigium?
1.2.2 Bagaimana etiologi, patogenesis, diagnosis dan penatalaksanaan Uveitis?
I.3 Tujuan
I.3.1 Mengetahui etiologi, patogenesis, diagnosis dan penatalaksanaan Pterigium.
I.3.2 Mengetahui etiologi, patogenesis, diagnosis dan penatalaksanaan Uveitis.
I.4 Manfaat
I.4.1 Menambah wawasan mengenai penyakit mata khususnya Pterigium dan
Uveitis.
I.4.2 Sebagai proses pembelajaran bagi dokter muda yang sedang mengikuti
kepaniteraan klinik bagian ilmu penyakit mata.

3
BAB IISTATUS PASIEN
2.1 Identitas Pasien
Nama : Ny.W
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 73 tahun
Alamat : Kanigoro
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : Petani
Status : Janda (meninggal)
Suku Bangsa : Jawa
Tanggal Periksa : 10 Agustus 2011
No. RM :296994
2.2 Anamnesa
1. Keluhan Utama : mata kanan dan kiri terasa mengganjal.
2. Riwayat Penyakit Sekarang : Seorang pasien perempuan umur 73 tahun
datang ke poliklinik Mata RSUD Kepanjen dengan keluhan mata kanan dan
kiri terasa ngganjel. Kedua mata dirasakan mengganjal sejak 1 minggu yang
lalu tetapi yang lebih parah pada mata kanan, sejak satu minggu ini
penglihatan juga dirasakan menurun dan bila terkena air mata terasa perih.
Selain itu pasien mengeluhkan mata kirinya terasa ngeres dan sering silau,
pasien juga mengatakan bahwa matanya sering merah, keluhan ini dirasakan
sejak dua hari yang lalu.
3. Riwayat Penyakit Dahulu: riwayat penyakit serupa (-), kencing manis (-),
darah tinggi (-), alergi makanan & obat (-), trauma (-), mata merah (-)

4
4. Riwayat Penyakit Keluarga: riwayat penyakit serupa (-), kencing manis (-),
darah tinggi (-),alergi makanan & obat (-)
5. Riwayat Pengobatan: (-)
6. Riwayat Kebiasaan: setiap hari pergi ke sawah
2.3 Status Generalis
Kesadaran : compos mentis (GCS 456)
Vital sign : Tensi : 140/80 mmHg
Nadi : 76 x/mnt
RR : 20 x/mnt
Suhu : 36,8°C
2.4 Status Oftalmologi
Pemeriksaan OD OSAVTanpa koreksiDengan koreksi
2/60Tidak dilakukan
5/20Tidak dilakukan
TIO N/P N/PKedudukan Orthophoria OthophoriaPergerakan
Palpebra- Odem- Hiperemi- Trikiasis
---
---
Konjungtiva- Tarsal - Bulbi
Hiperemi (-)Selaput putih ∆ di sisi nasal melewati limbus < 2 mm, dan dari sisi lateral melewati limbus < 2mm
Hiperemi (+)Selaput putih ∆ di sisi nasal belum melewati limbus
Kornea- warna Jernih Jernih

5
- permukaan- infiltrate
Cembung-
Cembung-
Bilik mata depan- kedalaman- hifema- hipopion- flare
Cukup---
Dalam--+
Iris Hitam, kripte (+) Hitam, kripte (+), sinekia posterior (+)
Pupil Bulat, central, RC (+) Bulat, central, RC (+)Lensa
- warna - Iris shadow
Sulit dievaluasi-
jernih-
Vitreus Tidak dilakukan Tidak dilakukanRetina Tidak dilakukan Tidak dilakukan
2.5 Diagnosa
Working diagnosis : OD Pterigium Duplex
OS Pterigium Stadium I dengan Uveitis
Differential Diagnosis : Pseudopterigium, Pengikula
2.6 Penatalaksanaan
- Planning Diagnosis : Slit Lamp
- Planning Therapy :
1. C Lyteers ED 6 dd gtt 1 ODS
2. C Atropin ED 1 dd gtt 1 ODS
3. Prednison 3 dd tab I.
4. OD CLG
2.7 Prognosa
Ad vitam: ad bonam
Ad Functionam: dubia ad malam
Ad Sanationam: dubia ad malam
2.8 Follow Up:
Tanggal 13 Agustus 2012
S : mata mengganjal menurun, silau menurun, dan kabur pada mata kiri menurun.
O: Status Ophtalmologis

6
Pemeriksaan OD OSAVTanpa koreksiDengan koreksi
2/60Tidak dilakukan
5/20Tidak dilakukan
TIO N/P N/PKedudukan orthophoria OrthophoriaPergerakan
Palpebra- edema- hiperemi- trikiasis
---
---
Konjungtiva- tarsal- bulbi
Hiperemi (-)Selaput putih ∆ di sisi nasal melewati limbus < 2 mm, dan dari sisi lateral melewati limbus < 2mm
Hiperemi (+)↓Selaput putih ∆ di sisi nasal belum melewati
Kornea- warna- permukaan- infiltrate
JernihCembung
-
JernihCembung
-Bilik mata depan
- kedalaman- hifema- hipopion- flare
Cukup--+
Dalam↓--+
Iris Hitam, kripte (+) Hitam, kripte (+), sinekia posterior (+)
Pupil Bulat, central, RC (↓) Bulat, central, RC (↓)Lensa
- warna - Iris shadow
Sulit dievaluasi-
Jernih-
Vitreus Tidak dilakukan Tidak dilakukanRetina Tidak dilakukan Tidak dilakukan
A : OD Pterigium Duplex dengan uveitis
OS Pterigium Stadium I dengan Uveitis
P : Planning Diagnosis : Slit Lamp

7
Planning Therapy :
1. C Lyteers ED 6 dd gtt 1 ODS
2. C Atropin ED 1 dd gtt 1 ODS
3. C Tobroson ED 6 dd gtt ODS
4. Prednison 3 dd tab I.
5. OD CLG
Bila dilakukan operasi:
Laporan operasi
Diagnose prabedah: OD Pterigium Stadium III
Diagnose pasca bedah: OD post CLG
Tindakan pembedahan: CLG
Laporan pembedahan:
- anastesi subconjunctiva
- Tes sondenasi
- incise kecil pada konjungtiva menuju medial head dari
pterigium
- ambil pterigium dengan dikerok untuk mengangkat lapisan
tipis epithelium dengan kombinasi deseksi tumpul dan traksi
- Diambil konjungtiva dari bagian superior dari mata yang sama,
sebelumnya diinjeksikan dengan lidokain, agar mudah
mendiseksi konjungtiva dari tenon selama pengambilan
autograft.
- Bagian limbal dari autograft ditempatkan pada area limbal dari
area yang akan digraft.
- Autograft kemudian dijahit ke konjungtiva disekitarnya dengan
menggunakan nylon
- olesi mata dengan salep kloramfenicol kemudian tutup dengan
kassa steril
Instruksi pasca bedah :
- medikamentosa:

8
Ciproflokcacin 500 mg tetes/hari2x1
Asam Mefenamat 500mg 3x1
Gentamycin ED 6
- KIE

9
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Anatomi & Fisiologi
3.1.1 Anatomi Konjungtiva
Konjungtiva merupakan membran yang menutupi sclera dan kelopak mata
bagian belakang. Berbagai macam obat mata dapat diserap melalui konjungtiva.
Konjungtiva ini mengandung sel musin yang dihasilkan oleh sel goblet. 2
Konjungtiva terdiri atas tiga bagian, yaitu :
- Konjungtiva tarsal yang menutupi tarsus, konjungtiva tarsal ini sukar
digerakkan dari tarsus.
- Konjungtiva bulbi, menutupi sclera dan mudah digerakan dari sclera
dibawahnya.
- Konjungtiva forniks, merupakan tempat peralihan konjungtiva tarsal
dengan konjungtiva bulbi 2
Konjungtiva bulbi dan forniks berhubungan sangat longgar dengan jaringan
di bawahnya sehingga bola mata mudah bergerak 2
GAMBAR 1. KONJUNGTIVA
3.1.2 Anatomi kornea

10
Kornea adalah selaput bening mata, bagian selaput mata yang tembus
cahaya, merupakan lapis jaringan yang menutup bola mata bagian depan. 2
Kornea terdiri dari lima lapis, yaitu :
1. Epitel
• Tebalnya 50 μm, terdiri atas 5 lapis sel epitel tidak bertanduk yang saling
tumpang tindih; satu lapis sel basal, sel poligonal dan sel gepeng.
• Pada sel basal sering terlihat mitosis sel, dan sel muda ini terdorong ke
depan menjadi lapis sel sayap dan semakin maju ke depan menjadi sel
gepeng, sel basal berikatan erat dengan sel basal di sampingnya dan sel
poligonal di depanya melalui desmosom dan makula okluden; ikatan ini
menghambat pengaliran air, elektrolit, dan glukosa yang merupakan
barrier.
2. Membran Bowman
• Terletak dibawah membran basal epitel kornea yang merupakan kolagen
yang tersusun tidak teratur seperti stroma dan berasal dari bagian depan
stroma.
3. Stroma
• Terdiri atas lamel yang merupakan susunan kolagen yang sejajar satu
dengan lainnya, pada permukaan terlihat anyaman yang teratur sedang di
bagian perifer serat kolagen ini bercabang; terbentuknya kembali serat
kolagen memakan waktu yang lama yang kadang-kadang sampai 15
bulan. Keratosit merupakan sel stroma kornea yang merupakan fibroblas
terletak di antara serat kolagen stroma. Diduga keratosit membentuk
bahan dasar dan serat kolagen dalam perkembangan embrio atau sesudah
trauma. 2
4. membrane descement
• merupakan membran aselular dan merupakan batas belakang stroma
kornea dihasilkan sel endotel dan merupakan membran basalnya.
• bersifat sangat elastik dan berkembang terus seumur hidup, mempunyai
tebal 40µm.2

11
5. Endotel
• berasal dari mesotellium, berlapis satu, bentuk heksagonal, besar 20-
40µm. endotel melekat pada membrane descement melalui
hemidesmosom dan zonula okluden. 2
Kornea dipersyarafi oleh banyak saraf sensoris terutama berasal dari saraf
siliar longus, saraf nasosiliar, saraf ke V saraf siliar longus berjalan suprakoroid,
masuk ke dalam stroma kornea, menembus membrane bowman melepaskan
selubung schwannya. Seluruh lapis epitel dipersarafi sampai pada kedua lapis
terdepan tanpa ada akhir saraf. Bulbus Krause untuk sensasi dingin ditemukan
di daerah limbus. Daya regenerasi saraf sesudah dipotong di daerah limbus
terjadi dalam waktu 3 bulan. 2
Trauma atau penyakit yang merusak endotel akan mengakibatkan system
pompa endotel terganggu sehingga dekompensasi endotel dan terjadi edema
kornea. Endotel tidak mempunyai daya regenarasi.2
Kornea merupakan bagian mata yang tembus cahaya dan menutup bola
mata di sebelah depan. Pembiasan sinar terkuat dilakukan oleh kornea dimana
40 dioptri dari 50 dioptri pembiasan sinar masuk kornea dilakukan oleh kornea.2
GAMBAR 2. SUSUNAN LAPISAN KORNEA
3.1.3 Anatomi Uvea

12
Uvea terdiri dari iris, korpus siliary dan khoroid. Bagian ini adalah lapisan
vaskular tengah mata dan dilindungi oleh kornea dan sklera. Uvea ini ikut
mengalirkan darah ke retina.
GAMBAR 3. ANATOMI MATA
1. Iris
Iris adalah perpanjangan korpus siliare ke anterior. Iris berupa suatu
permukaan pipih dengan apertura bulat yang terletak di tengah pupil. Iris
terletak bersambungan dengan permukaan anterior lensa, yang memisahkan
kamera anterior dari kamera posterior, yang masing-masing berisi aqueus
humor. Di dalam stroma iris terdapat sfingter dan otot-otot dilator. Kedua
lapisan berpigmen pekat pada permukaan posterior iris merupakan perluasan
neuroretina dan lapisan epitel pigmen retina ke arah anterior. Pasokan darah ke
iris adalah dari sirkulus major iris. Kapiler-kapiler iris mempunyai lapisan
endotel yang tidak berlubang sehingga normalnya tidak membocorkan
fluoresein yang disuntikkan secara intravena. Persarafan iris adalah melalui
serat-serat di dalam nervus siliares. Iris mengendalikan banyaknya cahaya yang
masuk ke dalam mata. Ukuran pupil pada prinsipnya ditentukan oleh
keseimbangan antara konstriksi akibat aktivitas parasimpatis yang dihantarkan

13
melalui nervus kranialis III dan dilatasi yang ditimbulkan oleh aktivitas
simpatik.
2. Korpus Siliaris
Korpus siliaris yang secara kasar berbentuk segitiga pada potongan
melintang, membentang ke depan dari ujung anterior khoroid ke pangkal iris
(sekitar 6 mm). Korpus siliaris terdiri dari suatu zona anterior yang berombak-
ombak, pars plikata dan zona posterior yang datar, pars plana. Prosesus siliaris
berasal dari pars plikata. Prosesus siliaris ini terutama terbentuk dari kapiler-
kapiler dan vena yang bermuara ke vena-vena vortex. Kapiler-kapilernya besar
dan berlobang-lobang sehingga membocorkan floresein yang disuntikkan
secara intravena. Ada 2 lapisan epitel siliaris, satu lapisan tanpa pigmen di
sebelah dalam, yang merupakan perluasan neuroretina ke anterior, dan lapisan
berpigmen di sebelah luar, yang merupakan perluasan dari lapisan epitel
pigmen retina. Prosesus siliaris dan epitel siliaris pembungkusnya berfungsi
sebagai pembentuk aqueus humor.
3. Khoroid
Khoroid adalah segmen posterior uvea, di antara retina dan sklera.
Khoroid tersusun dari tiga lapisan pembuluh darah khoroid; besar, sedang dan
kecil. Semakin dalam pembuluh terletak di dalam khoroid, semakin lebar
lumennya. Bagian dalam pembuluh darah khoroid dikenal sebagai
khoriokapilaris. Darah dari pembuluh darah khoroid dialirkan melalui empat
vena vortex, satu di masing-masing kuadran posterior. Khoroid di sebelah
dalam dibatasi oleh membran Bruch dan di sebelah luar oleh sklera. Ruang
suprakoroid terletak diantara khoroid dan sklera. Khoroid melekat erat ke
posterior ke tepi-tepi nervus optikus. Ke anterior, khoroid bersambung dengan
korpus siliare. Agregat pembuluh darah khoroid memperdarahi bagian luar
retina yang mendasarinya

14
3.2 Pterigium
3.2.1 Definisi Pterigium
Pterygium merupakan suatu pertumbuhan fibrovaskular konjungtiva yang
bersifat degeneratif dan invasif. Pertumbuhan ini biasanya terletak pada celah
kelopak bagian nasal ataupun temporal konjungtiva yang meluas ke daerah
kornea.2
GAMBAR 4. PTERIGIUM
3.2.2 Epidemologi Pterigium
Di Amerika Serikat, kasus pterigium sangat bervariasi tergantung pada
lokasi geografisnya. Di daratan Amerika serikat, Prevalensinya berkisar kurang
dari 2% untuk daerah di atas 40o lintang utara sampai 5-15% untuk daerah
garis lintang 28-36o. Sebuah hubungan terdapat antara peningkatan prevalensi
dan daerah yang terkena paparan ultraviolet lebih tinggi di bawah garis
lintang. Sehingga dapat disimpulkan penurunan angka kejadian di lintang atas
dan peningkatan relatif angka kejadian di lintang bawah.8
Di Indonesia, hasil survei Departemen Kesehatan RI Tahun 1982 pterigium
menempati urutan ketiga terbesar (8,79 %) dari penyakit mata. Hasil survei
nasional tahun 1993-1996 tentang angka kesakitan mata di 8 propinsi di

15
Indonesia menempatkan pterigium pada urutan kedua (13,9 %).3 Gizzard dkk
dalam penelitian di Indonesia menemukan bahwa angka prevalensi tertinggi
ditemukan di propinsi Sumatra.4 Sedangkan dari survei kesehatan indra
penglihatan dan pendengaran tahun 1995 prevalensi penyakit mata di Sulawesi
Utara menempatkan pterigium pada urutan pertama (17,9 %).5 Mandang pada
tahun 1970 menemukan 14,69 % pterigium khususnya di 19 desa dan 17,50 %
pterigium di 3 ibukota kecamatan di Kabupaten Minahasa. Di Minahasa,
pterigium merupakan penyakit mata nomor 3 sesudah kelainan refraksi dan
penyakit infeksi luar. Mangindaan IAN, Bustani NM melaporkan 21,35 %
pterigium di 2 desa di Kabupaten Minahasa Utara, hasil 12,92 % pada pria dan
8,43 % pada wanita, 9,55 % berusia di atas 50 tahun, dengan pekerjaan petani
sebesar 10,11 % terbanyak adalah pterigium stadium 3 yaitu 42,11 % yang
tumbuh di bagian nasal sebesar 55,26 %.6,7
3.2.3 Etiologi Pterigium
Etiologi pterigium tidak diketahui dengan jelas. Diduga merupakan suatu
neoplasma, radang dan degenerasi yang disebabkan oleh iritasi kronis akibat
debu, pasir, cahaya matahari, lingkungan dengan angin yang banyak dan udara
yang panas selain itu faktor genetik dicurigai sebagai faktor predisposisi.9,10
Faktor resiko yang mempengaruhi pterygium adalah lingkungan yakni
radiasi ultraviolet sinar matahari, iritasi kronik dari bahan tertentu di udara dan
faktor herediter.
1. Radiasi ultraviolet
Faktor resiko lingkungan yang utama sebagai penyebab timbulnya
pterygium adalah terpapar sinar matahari. Sinar ultraviolet diabsorbsi kornea
dan konjungtiva yang dapat mengakibatkan kerusakan sel dan proliferasi
sel.
2. Iritasi kronik atau inflamasi terjadi pada area limbus atau perifer kornea
merupakan pendukung terjadinya teori keratitis kronik dan terjadinya
limbal.

16
3.2.4 Patofisiologi Pterigium
Etiologi pterygium tidak diketahui dengan jelas. Tetapi penyakit ini lebih
sering pada orang yang tinggal di daerah iklim panas. Oleh karena itu
gambaran yang paling diterima tentang hal tersebut adalah respon terhadap
faktor-faktor lingkungan seperti paparan terhadap matahari (ultraviolet), daerah
kering, inflamasi, daerah angin kencang dan debu atau faktor iritan lainnya.
Pengeringan lokal dari kornea dan konjungtiva yang disebabkan kelainan tear
film menimbulkan pertumbuhan fibroplastik baru merupakan salah satu teori.
Tingginya insiden pterygium pada daerah dingin, iklim kering mendukung
teori ini.12
Ultraviolet adalah mutagen untuk p53 tumor supresor gene pada limbal
basal stem cell. Tanpa apoptosis, transforming growth factor-beta diproduksi
dalam jumlah berlebihan dan menimbulkan proses kolagenase meningkat. Sel-
sel bermigrasi dan angiogenesis. Akibatnya terjadi perubahan degenerasi
kolagen dan terlihat jaringan subepitelial fibrovaskular. Jaringan
subkonjungtiva terjadi degenerasi elastoik proliferasi jaringan vaskular bawah
epithelium dan kemudian menembus kornea. Kerusakan pada kornea terdapat
pada lapisan membran bowman oleh pertumbuhan jaringan fibrovaskular,
sering disertai dengan inflamasi ringan. Epitel dapat normal, tebal atau tipis
dan kadang terjadi displasia. 12,13
Limbal stem cell adalah sumber regenerasi epitel kornea. Pada keadaan
defisiensi limbal stem cell, terjadi pembentukan jaringan konjungtiva pada
permukaan kornea. Gejala dari defisiensi limbal adalah pertumbuhan
konjungtiva ke kornea, vaskularisasi, inflamasi kronis, kerusakan membran
basement dan pertumbuhan jaringan fibrotik. Tanda ini juga ditemukan pada
pterygium dan karena itu banyak penelitian menunjukkan bahwa pterygium
merupakan manifestasi dari defisiensi atau disfungsi limbal stem cell.
Kemungkinan akibat sinar ultraviolet terjadi kerusakan limbal stem cell di
daerah interpalpebra.4

17
Pemisahan fibroblast dari jaringan pterygium menunjukkan perubahan
phenotype, pertumbuhan banyak lebih baik pada media mengandung serum
dengan konsentrasi rendah dibanding dengan fibroblast konjungtiva normal.
Lapisan fibroblast pada bagian pterygiun menunjukkan proliferasi sel yang
berlebihan. Pada fibroblast pterygium menunjukkan matrix metalloproteinase,
dimana matriks ekstraselluler berfungsi untuk jaringan yang rusak,
penyembuhan luka, mengubah bentuk. Hal ini menjelaskan kenapa pterygium
cenderung terus tumbuh, invasi ke stroma kornea dan terjadi reaksi
fibrovaskular dan inflamasi. 4
3.2.5 Gejala dan Tanda Pterigium
Gejala klinis pterigium pada tahap awal biasanya ringan bahkan sering
tanpa keluhan sama sekali (asimptomatik). Beberapa keluhan yang sering
dialami pasien antara lain rasa perih, terganjal, sensasi benda asing, silau,
berair, gangguan visus, serta masalah kosmetik.
Dari pemeriksaan didapatkan adanya penonjolan daging, berwarna putih,
tampak jaringan fibrovaskular yang berbentuk segitiga yang terbentang dari
konjungtiva interpalpebrae sampai kornea, jaringan berbatas tegas sebagai
suatu garis yang berwarna coklat kemerahan, umumya tumbuh di daerah nasal
(pada 90% kasus). Dibagian depan dari apek pterigium terdapat infiltrate kecil-
kecil yang disebut “islet of Fuch”. Pterigium yang mengalami iritasi dapat
menjadi merah dan menebal yang kadang-kadang dikeluhkan kemeng oleh
penderita.15,16,17
Klasifikasi Pterigium dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Pterygium Simpleks; jika terjadi hanya di nasal/ temporal saja.
2. Pterygium Dupleks; jika terjadi di nasal dan temporal.
Pterigium berdasarkan perjalanan penyakitnya dibagi 2 tipe yaitu pterigium
progresif dan pterygium regresif: 14

18
Pterigium progresif : tebal dan vascular dengan beberapa infiltrat di
kornea di depan kepala pterygium (disebut cap dari pterygium).
Pterigium regresif : tipis, atrofi, sedikit vascular. Tipe ini akhirnya
akan membentuk membran yang tidak hilang.
Pterigium juga dapat dibagi ke dalam 4 derajat yaitu : 18
• Derajat 1: jika pterygium hanya terbatas pada limbus kornea.
• Derajat 2: jika sudah melewati limbus kornea tetapi tidak lebih dari 2
mm melewati kornea.
• Derajat 3: sudah melebihi derajat 2 tetapi tidak melebihi pinggiran
pupil mata dalam keadaan cahaya normal (pupil dalam keadaan
normal sekitar 3 – 4 mm)
• Derajat 4: pertumbuhan pterygium melewati pupil sehingga
mengganggu penglihatan.
GAMBAR 5. KLASIFIKASI PTERIGIUM BERDASARKAN DERAJATNYA
Pterigium derajat 2 Pterigium derajat 3
Pterigium derajat 4

19
3.2.6 Diagnosa Banding Pterigium
1. Pseudopterigium
Pseudopterigium merupakan perlekatan konjungtiva dengan kornea yang
cacat. Sering pseudopterigium ini terjadi pada proses penyembuhan tukak
kornea, sehingga konjungtiva menutupi kornea.5,6
GAMBAR 6. PSEEUDOPTERIGIUM
Perbedaan pseudopterigium dengan pterigium adalah 5
TABEL 1. PERBEDAAN PTERIGIUM DENGAN PSEUDOPTERIGIUM
PTERIGIUM PSEUDOPTERIGIUM
1.Lokasi Selalu di fissura palpebra Sembarang lokasi
2.Progresifitas Bisa progresif atau stasioner Selalu stasioner
3.Riwayat penyakit
mata
Ulkus kornea(-) Ulkus kornea (+)
4.Tes sondase Negatif positif
2 Pinguekula
Pinguekula merupakan penebalan pada konjungtiva bulbi berbentuk segitiga
dengan puncak di perifer dasar di limbus kornea, berwarna kuning keabu-abuan
dan terletak di celah kelopak mata. Timbul akibat iritasi oleh angin, debu dan
sinar matahari yang berlebihan. Biasanya pada orang dewasa yang berumur
kurang lebih 20 tahun.1

20
GAMBAR 7. PINGUEKULA
Secara histopatologik ditemukan epitel tipis dan gepeng, sering terdapat
hanya dua lapis sel. Lapisan subepitel tipis. Serat-serat kolagen stroma
berdegenerasi hialin yang amorf kadang-kadang terdapat penimbunan serat-
serat yang terputus-putus. Dapat terlihat penimbunan kalsium pada lapisan
permukaan. Pembuluh darah tidak masuk ke dalam Pinguekula akan tetapi bila
meradang atau terjadi iritasi, maka sekitar bercak degenerasi ini akan terlihat
pembuluh darah yang melebar. Tidak ada pengobatan yang khas, tetapi bila
terdapat gangguan kosmetik dapat dilakukan pembedahan pengangkatan.1
3.2.7 Penatalaksanaan Pterigium
1. Non Farmakologi
Secara teoritis, memperkecil terpapar radiasi ultraviolet untuk mengurangi
resiko berkembangnya pterygia pada individu yang mempunyai resiko lebih
tinggi. Pasien di sarankan untuk menggunakan topi yang memiliki pinggiran,
sebagai tambahan terhadap radiasi ultraviolet sebaiknya menggunakan
kacamata pelindung dari cahaya matahari. Tindakan pencegahan ini bahkan
lebih penting untuk pasien yang tinggal di daerah subtropis atau tropis, atau
pada pasien yang memiliki aktifitas di luar, dengan suatu resiko tinggi
terhadap cahaya ultraviolet (misalnya, memancing, ski, berkebun, pekerja
bangunan). Untuk mencegah berulangnya pterigium, sebaiknya para pekerja
lapangan menggunakan kacamata atau topi pelindung.
2. Farmakologi
Pada pterigium yang ringan tidak perlu di obati. Untuk pterigium derajat
1-2 yang mengalami inflamasi, pasien dapat diberikan obat tetes mata
kombinasi antibiotik dan steroid 3 kali sehari selama 5-7 hari. Diperhatikan
juga bahwa penggunaan kortikosteroid tidak dibenarkan pada penderita
dengan tekanan intraokular tinggi atau mengalami kelainan pada kornea.

21
3. Bedah
Pada pterigium derajat 3-4 dilakukan tindakan bedah berupa avulsi
pterigium. Sedapat mungkin setelah avulsi pterigium maka bagian
konjungtiva bekas pterigium tersebut ditutupi dengan cangkok konjungtiva
yang diambil dari konjugntiva bagian superior untuk menurunkan angka
kekambuhan. Tujuan utama pengangkatan pterigium yaitu memberikan hasil
yang baik secara kosmetik, mengupayakan komplikasi seminimal mngkin,
angka kekambuhan yang rendah. Penggunaan Mitomycin C (MMC)
sebaiknya hanya pada kasus pterigium yang rekuren, mengingat komplikasi
dari pemakaian MMC juga cukup berat.
1. Indikasi Operasi
Pterigium yang menjalar ke kornea sampai lebih 3 mm dari limbus
Pterigium mencapai jarak lebih dari separuh antara limbus dan tepi
pupil
Pterigium yang sering memberikan keluhan mata merah, berair dan
silau karena astigmatismus
Kosmetik, terutama untuk penderita wanita.6
2. Teknik Pembedahan
Tantangan utama dari terapi pembedahan pterigium adalah
kekambuhan, dibuktikan dengan pertumbuhan fibrovascular di limbus
ke kornea. Banyak teknik bedah telah digunakan, meskipun tidak ada
yang diterima secara universal karena tingkat kekambuhan yang
variabel. Terlepas dari teknik yang digunakan, eksisi pterigium adalah
langkah pertama untuk perbaikan. Banyak dokter mata lebih memilih
untuk memisahkan ujung pterigium dari kornea yang
mendasarinya. Keuntungan termasuk epithelisasi yang lebih cepat,
jaringan parut yang minimal dan halus dari permukaan kornea.1
Teknik Bare Sclera
Melibatkan eksisi kepala dan tubuh pterygium, sementara
memungkinkan sclera untuk epitelisasi. Tingkat kekambuhan tinggi,

22
antara 24 persen dan 89 persen, telah didokumentasikan dalam
berbagai laporan.1
Teknik Autograft Konjungtiva
Memiliki tingkat kekambuhan dilaporkan serendah 2 persen dan
setinggi 40 persen pada beberapa studi prospektif. Prosedur ini
melibatkan pengambilan autograft, biasanya dari konjungtiva bulbar
superotemporal, dan dijahit di atas sclera yang telah di eksisi
pterygium tersebut. Komplikasi jarang terjadi, dan untuk hasil yang
optimal ditekankan pentingnya pembedahan secara hati-hati jaringan
Tenon's dari graft konjungtiva dan penerima, manipulasi minimal
jaringan dan orientasi akurat dari grafttersebut. Lawrence W. Hirst,
MBBS, dari Australia merekomendasikan menggunakan sayatan besar
untuk eksisi pterygium dan telah dilaporkan angka kekambuhan sangat
rendah dengan teknik ini.1
(a) Pterygium(b) Pterygium diangkat(c) daerah yang diangkat(d) Konjungtiva di daerah yang tidak terkena sinar UV (misal dibawah palpebra superior) diangkat(e) konjungtiva tersebut ditransplant

23
GAMBAR 8. TEHNIK AUTOGRAFT KONJUNGTIVA
Cangkok Membran Amnion
Mencangkok membran amnion juga telah digunakan untuk
mencegah kekambuhan pterigium. Meskipun keuntungkan dari
penggunaan membran amnion ini belum teridentifikasi, sebagian besar
peneliti telah menyatakan bahwa itu adalah membran amnion berisi
faktor penting untuk menghambat peradangan dan fibrosis dan
epithelialisai.Sayangnya, tingkat kekambuhan sangat beragam pada
studi yang ada, diantara 2,6 persen dan 10,7 persen untuk pterygia
primer dan setinggi 37,5 persen untuk kekambuhan pterygia. Sebuah
keuntungan dari teknik ini selama autograft konjungtiva adalah
pelestarian bulbar konjungtiva. Membran Amnion biasanya
ditempatkan di atas sklera , dengan membran basal menghadap ke atas
dan stroma menghadap ke bawah. Beberapa studi terbaru telah
menganjurkan penggunaan lem fibrin untuk membantu cangkok
membran amnion menempel jaringan episcleral dibawahnya. Lem
fibrin juga telah digunakan dalam autografts konjungtiva.1
4. Terapi Tambahan
Tingkat kekambuhan tinggi yang terkait dengan operasi terus menjadi
masalah, dan terapi medis demikian terapi tambahan telah dimasukkan ke
dalam pengelolaan pterigium. Studi telah menunjukkan bahwa tingkat
rekurensi telah jatuh cukup dengan penambahan terapi ini, namun ada
komplikasi dari terapi tersebut.1
MMC telah digunakan sebagai pengobatan tambahan karena
kemampuannya untuk menghambat fibroblas. Efeknya mirip dengan iradiasi
beta. Namun, dosis minimal yang aman dan efektif belum ditentukan. Dua
bentuk MMC saat ini digunakan: aplikasi intraoperative MMC langsung ke

24
sclera setelah eksisi pterygium, dan penggunaan obat tetes mata MMC topikal
setelah operasi. Beberapa penelitian sekarang menganjurkan penggunaan
MMC hanya intraoperatif untuk mengurangi toksisitas.1
Beta iradiasi juga telah digunakan untuk mencegah kekambuhan, karena
menghambat mitosis pada sel-sel dengan cepat dari pterygium, meskipun
tidak ada data yang jelas dari angka kekambuhan yang tersedia. Namun, efek
buruk dari radiasi termasuk nekrosis scleral , endophthalmitis dan
pembentukan katarak, dan ini telah mendorong dokter untuk tidak
merekomendasikan terhadap penggunaannya.1
Untuk mencegah terjadi kekambuhan setelah operasi, dikombinasikan
dengan pemberian:
1. Mitomycin C 0,02% tetes mata (sitostatika) 2x1 tetes/hari selama 5
hari, bersamaan dengan pemberian dexamethasone 0,1% : 4x1
tetes/hari kemudian tappering off sampai 6 minggu.
2. Mitomycin C 0,04% (o,4 mg/ml) : 4x1 tetes/hari selama 14 hari,
diberikan bersamaan dengan salep mata dexamethasone.
3. Sinar Beta
4. Topikal Thiotepa (triethylene thiophosphasmide) tetes mata : 1 tetes/ 3
jam selama 6 minggu, diberikan bersamaan dengan salep antibiotik
Chloramphenicol, dan steroid selama 1 minggu.6
3.2.8 Komplikasi Pterigium
1. Komplikasi dari pterigium meliputi sebagai berikut:
- Gangguan penglihatan
- Mata kemerahan
- Iritasi
- Gangguan pergerakan bola mata.
- Timbul jaringan parut kronis dari konjungtiva dan kornea
- Dry Eye sindrom 3
2. Komplikasi post-operatif bisa sebagai berikut:
- Infeksi

25
- Ulkus kornea
- Graft konjungtiva yang terbuka
- Diplopia
- Adanya jaringan parut di kornea 3
3.2.9 Pencegahan dan Prognosa Pterigium
Pada penduduk di daerah tropik yang bekerja di luar rumah seperti nelayan,
petani yang banyak kontak dengan debu dan sinar ultraviolet dianjurkan
memakai kacamata pelindung sinar matahari.6
Penglihatan dan kosmetik pasien setelah dieksisi adalah baik, rasa tidak
nyaman pada hari pertama postoperasi dapat ditoleransi, kebanyakan pasien
setelah 48 jam post operasi dapat beraktivitas kembali. 6
Rekurensi pterygium setelah operasi masih merupakan suatu masalah
sehingga untuk mengatasinya berbagai metode dilakukan termasuk pengobatan
dengan antimetabolit atau antineoplasia ataupun transplantasi dengan
konjungtiva. Pasien dengan rekuren pterygium dapat dilakukan eksisi ulang
dan graft dengan konjungtiva autograft atau transplantasi membran amnion.
Umumnya rekurensi terjadi pada 3 – 6 bulan pertama setelah operasi. 6
Pasien dengan resiko tinggi timbulnya pterygium seperti riwayat keluarga
atau karena terpapar sinar matahari yang lama dianjurkan memakai kacamata
sunblock dan mengurangi terpapar sinar matahari.
3.3 Uveitis
3.3.1 Definisi
Uveitis didefinisikan sebagai peradangan yang mengenai traktus uvealis
yaitu (iris, badan silisr dan koroid) akibat infeksi, trauma, neoplasia atau proses
autoimmun.
3.3.2 Epidemiologi

26
Penderita umumnya berada pada usia 20-50 tahun. Setelah usia 70 tahun,
angka kejadian uveitis mulai berkurang. Pada penderita berusia tua umumnya
uveitis diakibatkan oleh toksoplasmosis, herpes zoster, dan afakia. Bentuk
uveitis pada laki-laki umumnya oftalmia simpatika akibat tingginya angka
trauma tembus dan uveitis non-granulomatosa anterior akut. Sedangkan pada
wanita umumnya berupa uveitis anterior kronik idiopatik dan toksoplasmosis.
3.3.3 Klasifikasi
Klasifikasi uveitis dibedakan menjadi empat kelompok utama, yaitu
klasifikasi secara anatomis, klinis, etiologis, dan patologis.
1) Klasifikasi secara anatomis (Gambar 8):
a. Uveitis anterior
- Iritis : inflamasi yang dominan pada iris
- Iridosiklitis : inflamasi pada iris dan pars plicata
b. Uveitis intermediet : inflamasi dominan pada posterior dan retina perifer
c. Uveitis posterior : inflamasi bagian uvea di belakang batas basis vitreus
d. Panuveitis : inflamasi pada seluruh uvea
GAMBAR 9. KLASIFIKASI UVEITIS SECARA ANATOMIS
Klasifikasi secara klinis, yaitu:
a. Uveitis akut : Onset simtomatik terjadi tiba-tiba dan berlangsung
selama < 6 minggu
b. Uveitis kronik : Uveitis yang berlangsung selama berbulan-bulan atau

27
bertahun-tahun, seringkali onset tidak jelas dan bersifat asimtomatik
Klasifikasi berdasarkan etiologinya dibagi menjadi:
a. Uveitis eksogen : Trauma, invasi mikroorganisme atau agen lain dari
luar tubuh
b. Uveitis endogen : mikroorganisme atau agen lain dari dalam tubuh
- Berhubungan dengan penyakit sistemik, contoh: ankylosing
spondylitis
- Infeksi Yaitu infeksi bakteri (tuberkulosis), jamur (kandidiasis),
virus (herpes zoster), protozoa (toksoplasmosis), atau roundworm
(toksokariasis)
- Uveitis spesifik idiopatik Yaitu uveitis yang tidak berhubungan
dengan penyakit sistemik, tetapi memiliki karakteristik khusus yang
membedakannya dari bentuk lain (sindrom uveitis Fuch)
- Uveitis non-spesifik idiopatik Yaitu uveitis yang tidak termasuk ke
dalam kelompok di atas.
Klasifikasi berdasarkan patologis, dibagi menjadi:
a. Uveitis non-granulomatosa: infiltrasi dominan limfosit pada koroid
b. Uveitis granulomatosa : koroid dominan sel epiteloid dan sel-sel
raksasa multinukleus
3.3.4 Etiologi
1. Etiologi uveitis anterior adalah:
TABEL 2. ETIOLOGI UVEITIS ANTERIOR
Autoimun Artritis reumatoid juvenilis, Spondilitis ankilosa, Kolitis ulserativa,
Uveitis terinduksi lensa, Sarkoidosis, Penyakit Crohn
Infeksi Sifilis, Tuberkulosis, Morbus Hansen, Herpes Zoster, Herpes
simpleks, Onkoserkiasis, Adenovirus
Keganasan Sindrom Masquerade (Retinoblastoma, Leukimia, Limfoma,

28
Melanoma maligna)
Lain-lain Idiopatik, Uveitis traumatik, Ablatio retina, Iridosiklitis
heterokromik Fuchs, krisis glaukomatosiklitik
2. Etiologi uveitis posterior adalah:
Penyebab dari uveitis posterior dapat dibagi atas dari penyakit infeksi
(uveitis granulomatosa) dan non infeksi (uveitis non granulomatosa).
1. Penyakit infeksi (uveitis granulomatosa)
virus : virus sitomegalo, herpes simpleks, herpes zoster, rubella, rubeola, HIV,
virus Epstein-Barr, virus coxsackie.
bakteri : Mycobacterium tuberculosis, brucellosis, sifilis sporadik dan
endemik, Nocardia, Neisseria meningitides, Mycobacterium avium-
intracellulare, Yersinia, dan Borrelia.
fungus : Candidia, Histoplasma, Cryptococcus, dan Aspergillus.
parasit : Toxoplasma, Toxocara, Cysticercus, dan Onchocerca.
2. penyakit non infeksi (uveitis non granulomatosa)
autoimun : penyakit Behcet, Sindroma Vogt-Koyanagi-Harada,
poliarteritis nodosa, ofthalmia simpatis, vaskulitis retina.
keganasan : sarkoma sel retikulum, melanoma maligna, leukemia, lesi
metastatik.
etiologi tak diketahui : sarkoidosis, koroiditis geografik, epiteliopati
pigmen plakoid multifokal akut, retinopati “birdshot”, epiteliopati pigmen
retina.
3.3.5 Gejala Klinis
1. Uveitis anterior
Gejala utama uveitis anterior akut adalah fotofobia, nyeri, merah,
penglihatan menurun, dan lakrimasi. Sedangkan pada uveitis anterior kronik

29
mata terlihat putih dan gejala minimal meskipun telah terjadi inflamasi yang
berat. Tanda-tanda objektif adanya uveitis anterior adalah injeksi silier,
keratik presipitata (KP), nodul iris, sel-sel akuos, flare, sinekia posterior, dan
sel-sel vitreus anterior. (Gambar 8)
(a) (b)
GAMBAR 10. (a) UVEITIS ANTERIOR ATAU IRITIS DENGAN INJEKSI
SILIER TETAPI TANPA ADANYA SINEKIA
(b) UVEITIS ANTERIOR ATAU IRITIS DENGAN INJEKSI SILIER
DAN IRREGULAR PUPIL
( EBOOK ABC OF EYES 4E 2004 HAL 11)
Kadangkala mata akan tampak putih dan sedikit nyeri. Pemeriksaan COA
dengan mikoroskop slitlamp menampakkan white cells dan flare. Kumpulan
dari white cells yang kecil pada endotel kornea disebut sebagai keratik
presipitat. Kumpulan dari sel mononuklear akan membentuk nodul pada iris .
Pupil yang irregular menunjukkan adanya perlengketan antara tepi iris dan
permukaan anterior dari lensa (sinekia posterior).Sinekia anterior atau
posterior pada uveitis akan menjadi predisposisi dari glaukoma. Sel-sel ini
kadang kala akan berada di vitreus dan kadang kala akan menimbulkan edema
pada retina. (disebut juga udema makular)

30
(a) (b)
GAMBAR 11. UVEITIS ANTERIOR : (A) MUTTON-FAT KERATIC
PRECIPITATES, NODUL KOEPPE DAN BUSACCA; (B) NODUL
BUSACCA PADA IRIS DAN MUTTON-FAT KP DI BAGIAN INFERIOR
2. Uveitis intermediet
Gejala uveitis intermediet biasanya berupa floater, meskipun kadang-
kadang penderita mengeluhkan gangguan penglihatan akibat edema makular
sistoid kronik. Tanda dari uveitis intermediet adalah infiltrasi seluler pada
vitreus (vitritis) dengan beberapa sel di COA dan tanpa lesi inflamasi fundus.
3. Uveitis posterior
Dua gejala utama uveitis posterior adalah floater dan gangguan
penglihatan. Keluhan floater terjadi jika terdapat lesi inflamasi perifer.
Sedangkan koroiditis aktif pada makula atau papillomacular bundle
menyebabkan kehilangan penglihatan sentral. Tanda-tanda adanya uveitis
posterior adalah perubahan pada vitreus (seperti sel, flare, opasitas, dan
seringkali posterior vitreus detachment), koroditis, retinitis, dan vaskulitis.
4. Panuveitis
Panuveitis merupakan kondisi terdapat infiltrasi sel kurang lebih merata di
semua unsur di traktus uvealis. Ciri morfologi khas seperti infiltrat geografik
secara khas tidak ada.
a. Opthalmia Simpatika

31
Adalah uveitis granulomatosa bilateral yang menghancurkan, yang
timbul sepuluh hari sampai beberapa tahun setelah cedera mata tembus di
daerah korpus siliare, atau setelah kemasukan benda asing. 90% kasus
terjadi dalam satu tahun setelah cedara. Penyebabnya tidak diketahui,
namun penyakitnya diduga berkaitan dengan hipersensitifitas terhadap
beberapa unsur berpigmen di uvea. Kondisi ini sangat jarang terjadi setelah
bedah intra okuler tanpa komplikasi terhadap katarak atau glaukoma. Mata
yang cedera (terangsang) mula-mula meradang dan mata sebelahnya (yang
simpatik) meradang kemudian. Secara patologik terdapat uveitis
granulomatosa difus. Sel-sel epiteloid, bersama sel raksasa dan limfosit,
membentuk tuberkel tanpa perkijauan. Dari traktus uvealis proses radang
itu menyebar ke nervus optikus dan ke pia dan arachnoid sekitar nervus
optikus.
Opthalmia simpatika dapat dibedakan dari uveitis granulomatosa lain
karena riwayat trauma atau bedah okuler dan lesinya bilateral, difus, dan
(umumnya) akut, bukannya unilateral, setempat, dan menahun.
b. Uveitis Tuberkulosis
Uveitis tuberkulosis mungkin difus namun khas terlokalisir dalam
bentuk korioretinitis granulomatosa nekrotikan berat. Tuberkel itu sendiri
terdiri atas sel raksasa dan sel epiteloid sehingga sering terjadi nekrosis
perkijauan. Pasien mengeluh penglihatan kabur, mata merah, jika segmen
anterior terkena ditemukan nodul iris, dan KP “Mutton fat” pada
pemeriksaan slit lamp. Jika yang terkena adalah koroid dan retina maka
akan tamapak masa setempat yang menutupi vitreous seperti berkabut.
Sifat terlokalisir dari uveitis tuberkulosis membantu membedakan
dengan opthalmia simpatika. Secara patologik dibedakan dengan nekrosis
perkijauan. Pupil dilebarkan dengan atrofin 1% (1 tetes 2-3 kali perhari),
dan obat anti tuberkulosis diberikan secara sistemik jika cukup yakin
setelah beberapa bulan penyembuhan penyakit ini akan meninggalkan
jaringan rusak permanen dan penglihatan kabur karena parut pada retina.

32
3.2.6 Penatalaksanaan
Tujuan terapi uveitis adalah mencegah komplikasi yang mengancam
penglihatan, menghilangkan keluhan pasien, dan jika mungkin mengobati
penyebabnya. Ada empat kelompok obat yang digunakan dalam terapi uveitis,
yaitu midriatikum, steroid, sitotoksik, dan siklosporin. Sedangkan uveitis
akibat infeksi harus diterapi dengan antibakteri atau antivirus yang sesuai.
Penatalaksanaan uveitis meliputi pemberian obat-obatan dan terapi
operatif, yaitu
1. Kortikosteroid topikal, periokuler, sistemik (oral, subtenon,
intravitreal) dan sikloplegia
2. Pemberian antiinflamasi non steroid
3. Pemberian obat jenis sitotoksik seperti ankylating agent
(siklofosfamid, klorambusil), antimetabolit (azatrioprin,
metotrexat) dan sel T supresor (siklosporin)
4. Terapi operatif untuk evaluasi diagnostik (parasentesis, vitreus tap
dan biopsy korioretinal untuk menyingkirkan neoplasma atau
proses infeksi) bila diperlukan.
5. Terapi untuk memperbaiki dan mengatasi komplikasi seperti
katarak, mengontrol glaukoma dan vitrektomi.
Midriatikum berfungsi untuk memberikan kenyamanan pada pasien,
mencegah pembentukan sinekia posterior, dan menghancurkan sinekia.
Memberikan kenyamanan dengan mengurangi spasme muskulus siliaris
dan sfingter pupil dengan menggunakan atropin. Atropin tidak diberikan
lebih dari 1-2 minggu. Steroid topikal hanya digunakan pada uveitis
anterior dengan pemberian steroid kuat, seperti dexametason, betametason,
dan prednisolon. Komplikasi pemakaian steroid adalah glaukoma, posterior
subcapsular cataract, komplikasi kornea, dan efek samping sistemik.
3.2.7 Komplikasi

33
Komplikasi terpeting yaitu terjadinya peningkatan tekanan intraokuler
(TIO) akut yang terjadi sekunder akibat blok pupil (sinekia posterior),
inflamasi, atau penggunaan kortikosteroid topikal. Peningkatan TIO dapat
menyebabkan atrofi nervus optikus dan kehilangan penglihatan permanen.
Komplikasi lain meliputi corneal band-shape keratopathy, katarak,
pengerutan permukaan makula, edema diskus optikus dan makula, edema
kornea, dan retinal detachment.

34
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien didiagnosa OD Pterigium
stadium duplex dengan uveitis dan OS pterigium Stadium I dengan uveitis.
Planning erapi yang diberikan adalah C. Lyteers, C. Atropin, prednisone serta
OS CLG.
Pterigium merupakan salah satu dari sekian banyak kelainan pada mata dan
merupakan yang tersering nomor dua di indonesia setelah katarak, hal ini di
karenakan oleh letak geografis indonesia di sekitar garis khatulistiwa sehingga
banyak terpapar oleh sinar ultraviolet yang merupakan salah satu faktor
penyebab dari piterigium. Pterigium banyak diderita oleh laki-laki karena
umumnya aktivitas laki-laki lebih banyak di luar ruangan, serta dialami oleh
pasien di atas 40 tahun karena faktor degenerative.
Terapi dari pterigium umumnya tidak perlu diobati, hanya perawatan secara
konservatif seperti memberikan anti inflamasi pada pterigium yang iritatif. Pada
pembedahan akan dilakukan jika piterigium tersebut sudah sangat mengganggu
bagi penderita semisal gangguan visual, dan pembedahan ini pun hasilnya juga
kurang maksimal karena angka kekambuhan yang cukup tinggi mengingat
tingginya kuantitas sinar UV di Indonesia. Walaupun begitu penyakit ini dapat
dicegah dengan menganjurkan untuk memakai kacamata pelindung sinar
matahari.
Uveitis adalah suatu peradangan pada iris (iritis, iridoskilitis), corpus siliare(uveitis
intermediete,siklitis, uveitis perifer atau pars plantis), atau koroid(koroiditis).
Berdasarkan letaknya uveitis diklasifikasikan menjadi dua yaitu uveitis anterior dan
uveitis posterior. Uveitis anterior merupakan bentuk paling umum uveitis biasanya
unilateral dengan onset yang akut. Uveitis anterior dibedakan atau diklasifikasikan lagi
menjadi dua bentuk yaitu non-granulomatosa dan granulomatosa. Uveitis posterior
merupakan peradangan pada iris bisa juga pada retina dan pada nervus optikus. Pada

35
prinsipnya penatalaksanaan pada uveitis adlalah diberikan obat golongan steroid dan
siklopegik.
4.2 Saran
Pemberian KIE kepada masyarakat mengenai cara mencegah timbulnya
pterigium yaitu dengan cara melindungi mata dengan topi dan kaca mata.

36
DAFTAR PUSTAKA
1. Ilyas S. Ilmu Penyakit Mata. Edisi 3. Jakarta : Balai Penerbit FKUI ; 2007.
hal:2-6, 116 – 117
2. Vaughan G, Daniel et al. Konjungtiva dalam Opthalmologi Umum ed 14.
Widya Medika. Jakarta. 2000
3. Sirlan F, Wiyana IGP. Survey morbiditas mata dan kebutaan di Indonesia,
1993-1996. Warta kesehatan mata. 1996 ; VII : 7.
4. Gazzard G, Pterygium in Indonesia : prevalence, severity and risk factors. Br. J
Ophtalmol. 2002 ; 86 : 1341-46.
5. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Puskesmas. Laporan hasil survey kasehatan
indra penglihatan dan pendengaran di propinsi Sumatera Barat dan Sulawesi
Utara tahun 1995. Jakarta.
6. Oka Pn. The pterygium and its management. Dept ofophtalmology Airlangga
university school of medicine dr. soetomo. General Hospital Surabaya,
Indonesia. 1979
7. Mangindaan IAN, Bustani NM. Insiden pterigium di desa bahoi dan serei di
pesisir pantai minahasa utara,2005
8. Ilyas S. Mata Merah dalam Penuntun Ilmu Penyakit Mata. FK UI. Jakarta.
2003
9. Lazuarni. 2009. Prevalensi Pterigium di Kabupaten Langkat 2010. Tesis.
Fakultas kedokteran Universitas Sumatra Utara. Medan
10. American Academy Of Ophthalmology. 2005-2006. Base and Clinical Science
Course ,section 8, External Disease and Corne. P:344,403
11. Khurana A.K. 2007. Community Ophthalmology in Comprehensive
Ophthalmology. Fourth Edition. Chapter 20. New Delhi. New Age
international Limited Publisher.P: 443-457
12. T H Tan Donald et All. 2005. Pterigium.Clinical Ophthalmology. An Asian
Perspective Chapter 3.2. Saunder Elsevier.Singapore. P: 207-214

37
13. Vaughan G, Daniel et al. Konjungtiva dalam Opthalmologi Umum ed 14.
Widya Medika. Jakarta. 2000
14. Wijana N. Ilmu Penyakit Mata. Binarupa Aksara. Jakarta. 1983
15. D. Gondhowiardjo Tjahjono, Simanjuntak W.S Gilbert,2006,
Pterigium,Panduan Management Klinis Perdani, CV Ondo, Jakarta,P: 56-58
16. Ilyas S. Pterigium dalam Sari Ilmu Penyakit Mata. FK UI. Jakarta. 2003
17. Ilyas S. Mata Merah dalam Penuntun Ilmu Penyakit Mata. FK UI. Jakarta.
2003
18. Wisnujono S, dkk. Pterigium dalam Pedoman Diagnosis dan Terapi, RSUD Dr.
Soetomo, Surabaya. 1994
19. Ardalan Aminlari, MD, Ravi Singh, MD, and David Liang, MD. Management
of Pterygium
20. Pedoman Diagnosis dan Terapi. Bag/SMF Ilmu Penyakit Mata. Edisi III
penerbit Airlangga Surabaya. 2006. hal: 102 – 104
21. Schlaegel TF, Pavan-Langston D. Uveal Tract: Iris, Ciliary Body, and Choroid
In: Pavan-Langston D, editors. Manual of Ocular Diagnosis and Therapy. 2nd
Edition, Boston: Little, Brown and Company, 1980. 143-144.
22. Emmett T. Cunningham. Uveal tract In: Riordan-Eva P, Whitcher JP, editors.
General
23. Ophthalmology 17th Ed. London: McGraw Hill, 2007
24. 6. Rao NA, Forster DJ. Basic Principles In: Berliner N, editors. The Uvea
Uveitis and
25. Intraocular Neoplasms Volume 2. New York: Gower Medical Publishing,
1992. 1.1