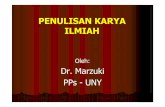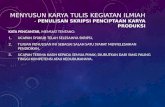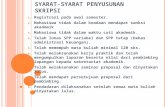Karya Ilmiah 8aa
description
Transcript of Karya Ilmiah 8aa

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang keinginan saya membuat karya ilmiah tentang Kebudayaan
masyarakat batak adalah karena Dewasa ini kebudayaan mengerakkaan pemikiran orang
banyak.Para pemimpin Negara, sarjana ekonomi, penasehat social, ahli pendidikan, dan
semacam itu, diaman-mana selalu menghadapi masalah tersebut. Dalam pelaksanaanya
mereka selalu samapai pada latar belakang kebudayaan, entah sebagai penghambat, entah
sebagai unsur yang harus diintegarsikan agar hasil rencana-rencana tersebut terjamin. Dalam
setiap soal daya kebudayaan menampakan diri sebagai factor yang tidak dapat dielakkan,
yang mau tak mau harus diperhatikan agar usaha-uasah tersebut tidak gagal. Dari dalam
kebuadayaan orang mengali motif dan perangsang untuk menjungjung perkembangan
masyarakat.
Pertanyaan yang sering diajukan kepada banyak orang yang mengumuli antropologi
dan kekudayaan dalam konteks pelayanan. Apakah yang menjadi hubungan antara
antropologi dan kebudayaan. Ada sementara orang yang berpendapat bahwa pelatyanan yang
benar harus didasarkan atas kebenaran Alkitab saja, karena segala sesuatu berbau ilmu
pengetahuan, termsuk antropologi kebudayaan tidak tidak memiliki tenpat dalam pelayanan.
Pendapat ini sepintas kelihatannya benar, sehuingga orang dengan begitu gampang
menrimanya, namaun dalamkenyataan yang sebenarnya ialah bahwa setiap pelayanan yang
berhubungan dengan manusia pastih menyentuh antropolgi. Disisni Antropologi kebudayaan
yang berhubungan dengan manusia, adalah ilmu tentang manusia, akan selalu berhubungan
dengan antropologi kebudayaan itu.
Berdasarkan dari kebenaran tersebut di atas ini, dapatlah dikatakan bahwa setiap
pelayanan yang menyankut manusia perlu memperhatikan antropologi kebudayan secara
serius. Alasan utama untuk kebenaran ini ialah karena antropoli berhubungan erat dengan
manusia dan berbicara tentang manusi, adalah ilmu tentang manusia, asal usul dan
perkembangannya, cara hidup total dan adapt istiadatnya. Alasan yang sejalan ini bahwa
dengan mempelajariantropologi, setiap pembelajar disiapkan untuk menemukan
pendekanatan yang manusiawi untuk mendekati setiap manusia dalam lingkup kehidupannya.
Dari dalamnya juga yang menyebabkan korupsi dan kemacetan. Secara spontan orang merasa
soal kebudayaan merupakan soal actual dan mendesak; penyelesaiannya tidak menyangkut
kepuasan ahli-ahli ilmu melainkan survival kita sendiri dimasa kelak. Jelsa karena bahwa
1

pengatahuan secara refleks lagi sistematis adalah suatu keharusan bagi setiap orang yang
memikul tanggung jawab bagi hari depan.
Kebudayaan merupakan suatu yang khas insani. Lewat kebudayaan manusia membuat
kebudayaan menjadi manusiawi, berate memanusiakan alam, sekaligus dalam kebudayaan itu
manusia meyujudkan diri sehingga mencapai kepenuhan kemanusiaannya. Dengan kata lain
kebudayaan merupakan penciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani. Filsafat
kebudayaan memandang kebudayaan dari segi realisasi kemanusiaan. Tulis J.V.Schall S.J.:
“Philosophy has some very valuable, indeed essential contribution to make before there can
be any adequate knowledge of what is meant by culture. Futhermore, the key to a very
important problem in the field of religion and culture can also be found in philosophy. The
immediate task that confronts the philosopher is a dialectic one, that is , what do modern
historians and social scientist commonly mean by culture, what is the reality that they attempt
to describe?” Dengan demikian menurut perincian tugas yang dipaparkan di atas, maka
hakekat kebudayaan satu persatu akan disoroti menganai: 1) Hakekat., kebudayaan, subjek
dan objeknya. 2) Unsur-unsur kebudayaan. 3) Faktor-faktor kebudayaan.4) Struktur
kebudayaan. 5) Inkulturasi. 6) Akulturasi.
1.2 Rumusan masalah
Menjelaskan Kehidupan social budaya Suku Batak Angkola
Menjelaskan Kehidupan social budaya Suku Batak Mandailing
Menjelaskan Hipotesis Kerajaan Mandala Holing
Memberikan informasi tentang Pengaruh Hindu terhadap batak
Menjelaskan kehidupan social budaya Suku Batak Karo
Menjelaskan kehidupan social budaya Suku Batak Pakpak
2

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Suku Batak
Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma
kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari
Tapanuli, Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak
Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.
Sebagian besar orang Batak menganut agama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam.
Tetapi ada pula yang menganut agama Malim dan juga menganut kepercayaan animisme
(disebut Sipelebegu atau Parbegu), walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah
semakin berkurang.
Sejarah
Topografi dan alam Tapanuli yang subur, telah menarik orang-orang Melayu Tua (Proto
Melayu) untuk bermigrasi ke wilayah Danau Toba sekitar 4.000 - 7.000 tahun lalu. Bahasa
dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang-orang Austronesia dari Taiwan telah
berpindah ke Sumatera dan Filipina sekitar 2.500 tahun lalu, dan kemungkinan orang Batak
termasuk ke dalam rombongan ini.[2]. Selama abad ke-13, orang Batak melakukan hubungan
dengan kerajaan Pagaruyung di Minangkabau yang mana hal ini telah menginspirasikan
pengembangan aksara Batak.[3]. Pada abad ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India
mendirikan kota dagang Barus, di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kamper
yang diusahakan oleh petani-petani Batak di pedalaman. Produksi kamper dari tanah Batak
berkualitas cukup baik, sehingga kamper menjadi komoditi utama pertanian orang Batak, di
samping kemenyan. Pada abad ke-10, Barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan
terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera[4]. Pada masa-masa berikutnya,
perdagangan kamper mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan
koloni di pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari
Barus, Sorkam, hingga Natal[5].
Identitas Batak
3

R.W Liddle mengatakan, bahwa sebelum abad ke-20 di Sumatera bagian utara tidak terdapat
kelompok etnis sebagai satuan sosial yang koheren. Menurutnya sampai abad ke-19, interaksi
sosial di daerah itu hanya terbatas pada hubungan antar individu, antar kelompok
kekerabatan, atau antar kampung. Dan hampir tidak ada kesadaran untuk menjadi bagian dari
satuan-satuan sosial dan politik yang lebih besar.[6] Pendapat lain mengemukakan, bahwa
munculnya kesadaran mengenai sebuah keluarga besar Batak baru terjadi pada zaman
kolonial.[7] Dalam disertasinya J. Pardede mengemukakan bahwa istilah "Tanah Batak" dan
"rakyat Batak" diciptakan oleh pihak asing. Sebaliknya, Siti Omas Manurung, seorang istri
dari putra pendeta Batak Toba menyatakan, bahwa sebelum kedatangan Belanda, semua
orang baik Karo maupun Simalungun mengakui dirinya sebagai Batak, dan Belandalah yang
telah membuat terpisahnya kelompok-kelompok tersebut. Sebuah mitos yang memiliki
berbagai macam versi menyatakan, bahwa Pusuk Bukit, salah satu puncak di barat Danau
Toba, adalah tempat "kelahiran" bangsa Batak. Selain itu mitos-mitos tersebut juga
menyatakan bahwa nenek moyang orang Batak berasal dari Samosir.
Terbentuknya masyarakat Batak yang tersusun dari berbagai macam marga, sebagian
disebabkan karena adanya migrasi keluarga-keluarga dari wilayah lain di Sumatra. Penelitian
penting tentang tradisi Karo dilakukan oleh J.H Neumann, berdasarkan sastra lisan dan
transkripsi dua naskah setempat, yaitu Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting. Menurut
Pustaka Kembaren, daerah asal marga Kembaren dari Pagaruyung di Minangkabau. Orang
Tamil diperkirakan juga menjadi unsur pembentuk masyarakat Karo. Hal ini terlihat dari
banyaknya nama marga Karo yang diturunkan dari Bahasa Tamil. Orang-orang Tamil yang
menjadi pedagang di pantai barat, lari ke pedalaman Sumatera akibat serangan pasukan
Minangkabau yang datang pada abad ke-14 untuk menguasai Barus.
Penyebaran agama
Masuknya Islam
Dalam kunjungannya pada tahun 1292, Marco Polo melaporkan bahwa masyarakat Batak
sebagai orang-orang "liar yang musyrik" dan tidak pernah terpengaruh oleh agama-agama
dari luar. Meskipun Ibn Battuta, mengunjungi Sumatera Utara pada tahun 1345 dan
mengislamkan Sultan Al-Malik Al-Dhahir, masyarakat Batak tidak pernah mengenal Islam
sebelum disebarkan oleh pedagang Minangkabau. Bersamaan dengan usaha dagangnya,
4

banyak pedagang Minangkabau yang melakukan kawin-mawin dengan perempuan Batak.
Hal ini secara perlahan telah meningkatakan pemeluk Islam di tengah-tengah masyarakat
Batak.[9] Pada masa Perang Paderi di awal abad ke-19, pasukan Minangkabau menyerang
tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran atas masyarakat Mandailing dan
Angkola. Namun penyerangan Paderi atas wilayah Toba, tidak dapat mengislamkan
masyarakat tersebut, yang pada akhirnya mereka menganut agama Kristen Protestan.[10]
Kerajaan Aceh di utara, juga banyak berperan dalam mengislamkan masyarakat Karo,
Pakpak, dan Dairi.
Misionaris Kristen
Lihat pula: Sejarah masuknya Kekristenan ke suku Batak
Pada tahun 1824, dua misionaris Baptist asal Inggris, Richard Burton dan Nathaniel Ward
berjalan kaki dari Sibolga menuju pedalaman Batak.[11] Setelah tiga hari berjalan, mereka
sampai di dataran tinggi Silindung dan menetap selama dua minggu di pedalaman. Dari
penjelajahan ini, mereka melakukan observasi dan pengamatan langsung atas kehidupan
masyarakat Batak. Pada tahun 1834, kegiatan ini diikuti oleh Henry Lyman dan Samuel
Munson dari Dewan Komisaris Amerika untuk Misi Luar Negeri.
P
ada tahun 1850, Dewan Injil Belanda menugaskan Herman Neubronner van der Tuuk untuk
menerbitkan buku tata bahasa dan kamus bahasa Batak - Belanda. Hal ini bertujuan untuk
memudahkan misi-misi kelompok Kristen Belanda dan Jerman berbicara dengan masyarakat
Toba dan Simalungun yang menjadi sasaran pengkristenan mereka.[13].
Misionaris pertama asal Jerman tiba di lembah sekitar Danau Toba pada tahun 1861, dan
sebuah misi pengkristenan dijalankan pada tahun 1881 oleh Dr. Ludwig Ingwer Nommensen.
Kitab Perjanjian Baru untuk pertama kalinya diterjemahkan ke bahasa Batak Toba oleh
Nommensen pada tahun 1869 dan penerjemahan Kitab Perjanjian Lama diselesaikan oleh P.
H. Johannsen pada tahun 1891. Teks terjemahan tersebut dicetak dalam huruf latin di Medan
pada tahun 1893. Menurut H. O. Voorma, terjemahan ini tidak mudah dibaca, agak kaku, dan
terdengar aneh dalam bahasa Batak.[14]
5

Masyarakat Toba dan Karo menyerap agama Kristen dengan cepat, dan pada awal abad ke-20
telah menjadikan Kristen sebagai identitas budaya[15]. Pada masa ini merupakan periode
kebangkitan kolonialisme Hindia-Belanda, dimana banyak orang Batak sudah tidak
melakukan perlawanan lagi dengan pemerintahan kolonial. Perlawanan secara gerilya yang
dilakukan oleh orang-orang Batak Toba berakhir pada tahun 1907, setelah pemimpin
kharismatik mereka, Sisingamangaraja XII wafat.
Gereja HKBP
Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah berdiri di Balige pada bulan September
1917. Pada akhir tahun 1920-an, sebuah sekolah perawat memberikan pelatihan perawatan
kepada bidan-bidan disana. Kemudian pada tahun 1941, Gereja Batak Karo Protestan
(GBKP) didirikan
Kepercayaan
Sebelum suku Batak menganut agama Kristen Protestan, mereka mempunyai sistem
kepercayaan dan religi tentang Mulajadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit dan
pancaran kekuasaan-Nya terwujud dalam Debata Natolu.
Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak mengenal tiga konsep, yaitu:
Tondi : adalah jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan, oleh karena itu
tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi di dapat sejak seseorang di dalam
kandungan.Bila tondi meninggalkan badan seseorang, maka orang tersebut akan sakit
atau meninggal, maka diadakan upacara mangalap (menjemput) tondi dari sombaon
yang menawannya.
Sahala : adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang
memiliki tondi, tetapi tidak semua orang memiliki sahala. Sahala sama dengan
sumanta, tuah atau kesaktian yang dimiliki para raja atau hula-hula.
Begu : adalah tondi orang telah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan
tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam.
Demikianlah religi dan kepercayaan suku Batak yang terdapat dalam pustaha. Walaupun
sudah menganut agama Kristen dan berpendidikan tinggi, namun orang Batak belum mau
meninggalkan religi dan kepercayaan yang sudah tertanam di dalam hati sanubari mereka.
6

Kekerabatan
Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada
dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan (genealogi) dan
berdasarkan sosiologis, sementara kekerabatan teritorial tidak ada.
Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan (genealogi) terlihat dari silsilah marga mulai
dari Si Raja Batak, dimana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan
kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian (padan antar marga tertentu)
maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan Adat adalah ikatan
sedarah dalam marga, kemudian Marga. Artinya misalnya Harahap, kesatuan adatnya adalah
Marga Harahap vs Marga lainnya. Berhubung bahwa Adat Batak/Tradisi Batak sifatnya
dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat berpengaruh terhadap
perbedaan corak tradisi antar daerah.
Adanya falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi: Jonok
dongan partubu jonokan do dongan parhundul. merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa
menjaga hubungan baik dengan tetangga, karena merekalah teman terdekat. Namun dalam
pelaksanaan adat, yang pertama dicari adalah yang satu marga, walaupun pada dasarnya
tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan Adat.
Falsafah dan sistem kemasyarakatan
Dalihan na Tolu
Masyarakat Batak memiliki falsafah, azas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam
kemasyarakatannya yakni Tungku nan Tiga atau dalam Bahasa Batak Toba disebut Dalihan
na Tolu, yakni Hula-hula, Dongan Tubu dan Boru ditambah Sihal-sihal. Dalam Bahasa Batak
Angkola Dalihan na Tolu terdiri dari Mora, Kahanggi, dan Anak Boru
Hulahula/Mora adalah pihak keluarga dari isteri. Hula-hula ini menempati posisi yang
paling dihormati dalam pergaulan dan adat-istiadat Batak (semua sub-suku Batak)
sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada Hulahula
(Somba marhula-hula).
7

Dongan Tubu/Hahanggi disebut juga Dongan Sabutuha adalah saudara laki-laki satu
marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon
yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena saking dekatnya kadang-
kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa
terpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi
tetap bersatu. Namun demikian kepada semua orang Batak (berbudaya Batak)
dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, manat mardongan
tubu.
Boru/Anak Boru adalah pihak keluarga yang mengambil isteri dari suatu marga
(keluarga lain). Boru ini menempati posisi paling rendah sebagai 'parhobas' atau
pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun (terutama) dalam setiap upacara
adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan
dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk,
diistilahkan: Elek marboru.
Namun bukan berarti ada kasta dalam sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Dalihan
na Tolu adalah bersifat kontekstual. Sesuai konteksnya, semua masyarakat Batak pasti pernah
menjadi Hulahula, juga sebagai Dongan Tubu, juga sebagai Boru. Jadi setiap orang harus
menempatkan posisinya secara kontekstual.
Sehingga dalam tata kekerabatan, semua orang Batak harus berperilaku 'raja'. Raja dalam tata
kekerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik
sesuai dengan tata krama dalam sistem kekerabatan Batak. Maka dalam setiap pembicaraan
adat selalu disebut Raja ni Hulahula, Raja no Dongan Tubu dan Raja ni Boru.
Ritual kanibalisme
Ritual kanibalisme telah terdokumentasi dengan baik di kalangan orang Batak, yang
bertujuan untuk memperkuat tondi pemakan itu. Secara khusus, darah, jantung, telapak
tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi.
Dalam memoir Marco Polo yang tinggal di pantai timur Sumatera dari bulan April sampai
September 1292, ia menyebutkan pernah berjumpa dengan rakyat bukit yang ia sebut sebagai
"pemakan manusia".
8

Dari sumber-sumber sekunder, Marco Polo mencatat cerita tentang ritual kanibalisme di
antara masyarakat "Battas". Walau Marco Polo hanya tinggal di wilayah pesisir, dan tidak
pernah pergi langsung ke pedalaman untuk memverifikasi cerita tersebut, namun dia bisa
menceritakan ritual tersebut.
Niccolò de 'Conti (1395-1469), seorang Venesia yang menghabiskan sebagian besar tahun
1421 di Sumatra, dalam perjalanan panjangnya untuk misi perdagangan di Asia Tenggara
(1414-1439), mencatat kehidupan masyarakat. Dia menulis sebuah deskripsi singkat tentang
penduduk Batak: "Dalam bagian pulau, disebut Batech kanibal hidup berperang terus-
menerus kepada tetangga mereka "
Thomas Stamford Raffles pada 1820 mempelajari Batak dan ritual mereka, serta undang-
undang mengenai konsumsi daging manusia, menulis secara detail tentang pelanggaran yang
dibenarkan.Raffles menyatakan bahwa: "Suatu hal yang biasa dimana orang-orang memakan
orang tua mereka ketika terlalu tua untuk bekerja, dan untuk kejahatan tertentu penjahat akan
dimakan hidup-hidup".. "daging dimakan mentah atau dipanggang, dengan kapur, garam dan
sedikit nasi"Para dokter Jerman dan ahli geografi Franz Wilhelm Junghuhn, mengunjungi
tanah Batak pada tahun 1840-1841. Junghuhn mengatakan tentang ritual kanibalisme di
antara orang Batak (yang ia sebut "Battaer"). Junghuhn menceritakan bagaimana setelah
penerbangan berbahaya dan lapar, ia tiba di sebuah desa yang ramah. Makanan yang
ditawarkan oleh tuan rumahnya adalah daging dari dua tahanan yang telah disembelih sehari
sebelumnya. Namun hal ini terkadang untuk menakut-nakuti calon penjajah dan sesekali
untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tentara bayaran bagi suku-suku pesisir yang diganggu
oleh bajak laut.[Oscar von Kessel mengunjungi Silindung di tahun 1840-an, dan pada tahun
1844 mungkin orang Eropa pertama yang mengamati ritual kanibalisme Batak di mana suatu
pezina dihukum dan dimakan hidup. Menariknya, terdapat deskripsi paralel dari Marsden
untuk beberapa hal penting, von Kessel menyatakan bahwa kanibalisme dianggap oleh orang
Batak sebagai perbuatan hukum dan aplikasinya dibatasi untuk pelanggaran yang sangat
sempit yakni pencurian, perzinaan, mata-mata, atau pengkhianatan. Garam, cabe merah, dan
lemon harus diberikan oleh keluarga korban sebagai tanda bahwa mereka menerima putusan
masyarakat dan tidak memikirkan balas dendamIda Pfeiffer Laura mengunjungi Batak pada
bulan Agustus 1852, dan meskipun dia tidak mengamati kanibalisme apapun, dia diberitahu
bahwa: "Tahanan perang diikat pada sebuah pohon dan dipenggal sekaligus, tetapi darah
secara hati-hati diawetkan untuk minuman, dan kadang-kadang dibuat menjadi semacam
9

puding dengan nasi. Tubuh kemudian didistribusikan; telinga, hidung, dan telapak kaki
adalah milik eksklusif raja, selain klaim atas sebagian lainnya. Telapak tangan, telapak kaki,
daging kepala, jantung, serta hati, dibuat menjadi hidangan khas. Daging pada umumnya
dipanggang serta dimakan dengan garam. Para perempuan tidak diizinkan untuk mengambil
bagian dalam makan malam publik besar ".Pada 1890, pemerintah kolonial Belanda melarang
kanibalisme di wilayah kendali mereka.Rumor kanibalisme Batak bertahan hingga awal abad
ke-20, dan nampaknya kemungkinan bahwa adat tersebut telah jarang dilakukan sejak tahun
1816. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh Islam dalam masyarakat Batak
Tarombo
Silsilah atau Tarombo merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi
mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak kesasar
(nalilu). Orang Batak khusunya kaum laki-laki diwajibkan mengetahui silsilahnya minimal
nenek moyangnya yang menurunkan marganya dan teman semarganya (dongan tubu). Hal ini
diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya (partuturanna) dalam suatu klan atau
marga.
Kontroversi
Sebagian orang Karo, Angkola, dan Mandailing tidak menyebut dirinya sebagai bagian dari
suku Batak. Wacana itu muncul disebabkan karena pada umumnya kategori "Batak"
dipandang rendah oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, perbedaan agama juga menyebabkan
sebagian orang Tapanuli tidak ingin disebut sebagai Batak. Di pesisir timur laut Sumatera,
khususnya di Kota Medan, perpecahan ini sangat terasa. Terutama dalam hal pemilihan
pemimpin politik dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Sumber lainnya menyatakan kata
Batak ini berasal dari rencana Gubernur Jenderal James Stanford Raffless yang membuat
etnik Kristen yang berada antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Islam Minangkabau, di
wilayah Barus Pedalaman, yang dinamakan Batak. Generalisasi kata Batak terhadap etnik
Mandailing (Angkola) dan Karo, umumnya tak dapat diterima oleh keturunan asli wilayah
itu. Demikian juga di Angkola, yang terdapat banyak pengungsi muslim yang berasal dari
wilayah sekitar Danau Toba dan Samosir, akibat pelaksanaan dari pembuatan afdeeling
Bataklanden oleh pemerintah Hindia Belanda, yang melarang penduduk muslim bermukim di
wilayah tersebut.
10

Konflik terbesar adalah pertentangan antara masyarakat bagian utara Tapanuli dengan selatan
Tapanuli, mengenai identitas Batak dan Mandailing. Bagian utara menuntut identitas Batak
untuk sebagain besar penduduk Tapanuli, bahkan juga wilayah-wilayah di luarnya.
Sedangkan bagian selatan menolak identitas Batak, dengan bertumpu pada unsur-unsur
budaya dan sumber-sumber dari Barat. Penolakan masyarakat Mandailing yang tidak ingin
disebut sebagai bagian dari etnis Batak, sempat mencuat ke permukaan dalam Kasus Syarikat
Tapanuli (1919-1922), Kasus Pekuburan Sungai Mati (1922),[29] dan Kasus Pembentukan
Propinsi Tapanuli (2008-2009).
Dalam sensus penduduk tahun 1930 dan 2000, pemerintah mengklasifikasikan Simalungun,
Karo, Toba, Mandailing, Pakpak dan Angkola sebagai etnis Batak.
Suku Batak Toba
Batak Toba merupakan sub atau bagian dari suku bangsa Batak. Suku Batak Toba meliputi
Kabupaten Toba Samosir sekarang yang wilayahnya meliputi Balige, Laguboti, Parsoburan,
dan sekitarnya.
Toba pada masa Kerajaan Batak
Pada masa Kerajaan Batak yang berpusat di Bakara, Kerajaan Batak yang dalam
pemerintahan dinasti Sisingamangaraja membagi Kerajaan Batak dalam 4 (empat) wilayah
yang disebut Raja Maropat, yaitu:
1. Raja Maropat Silindung
2. Raja Maropat Samosir
3. Raja Maropat Humbang
4. Raja Maropat Toba
Daerah Batak Toba masuk dalam wilayah Raja Maropat Toba. Raja Maropat Toba meliputi
wilayah Toba sekarang hingga pantai Timur dan berbatasan dengan Kerajaan Johor.
Toba pada masa penjajahan Belanda
11

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membentuk Keresidenan Tapanuli pada
tahun 1910. Keresidenan Tapanuli terbagi atas 4 (empat) wilayah yang disebut afdeling dan
saat ini dikenal dengan kabupaten atau kota, yaitu:
1. Afdeling Padang Sidempuan, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas
Utara, dan Kota Padang Sidempuan.
2. Afdeling Nias, yang sekarang menjadi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.
3. Afdeling Sibolga dan Ommnenlanden, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli
Tengah dan Kota Sibolga.
4. Afdeling Bataklanden, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten
Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten
Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Daerah Batak Toba menjadi salah satu bagian dari 5 (lima) onderafdeling pada Afdeling
Bataklanden, yaitu Onderafdeling Toba yang beribukota di Balige.
Onderafdeling Toba dipimpin oleh seorang Controleur van Toba.
Toba pada masa penjajahan Jepang
Pada masa penjajahan Jepang, bentuk pemerintahan di Keresidenan Tapanuli hampir tak
berubah. Namanya saja diubah supaya keren dan kejepang-jepangan.
Toba pada masa awal kemerdekaan RI
Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia pun tetap menjadikan Tapanuli
menjadi sebuah keresidenan. Dr. Ferdinand Lumban Tobing merupakan Residen Tapanuli
yang pertama.
Ada sedikit perubahan dilakukan pada nama. Namun pembagian wilayah tetap sama. Nama
Afdeling Bataklanden misalnya diubah menjadi Luhak Tanah Batak dan luhak pertama yang
diangkat adalah Cornelius Sihombing yang pernah menjabat sebagai Demang Silindung.
Nama onderafdeling pun diganti menjadi urung dan para demang yang memimpin
onderafdeing diangkat menjadi Kepala Urung. Onderdistrik pun menjadi Urung Kecil yang
dipimpin oleh Kepala Urung Kecil yang dulu adalah sebagai Assistent Demang.
12

Seiring dengan perjalanan sejarah, pemerintahan di Keresidenan Tapanuli pernah dibagi
dalam 4 (empat) kabupaten, yaitu:
1. Kabupaten Silindung
2. Kabupaten Samosir
3. Kabupaten Humbang
4. Kabupaten Toba
Batak Toba masuk dalam wilayah Kabupaten Toba.
Toba ketika penyerahan kedaulatan pada permulaan 1950
Ketika penyerahan kedaulatan pada permulaan 1950, Keresidenan Tapanuli yang sudah
disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kabupaten baru, yaitu:
1. Kabupaten Tapanuli Utara (sebelumnya Kabupaten Tanah Batak)
2. Kabupaten Tapanuli Tengah (sebelumnya Kabupaten Sibolga)
3. Kabupaten Tapanuli Selatan (sebelumnya Kabupaten Padang Sidempuan)
4. Kabupaten Nias
Batak Toba pun masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang beribukota di
Tarutung.
Toba pada masa sekarang
Pada Desember 2008 ini, Keresidenan Tapanuli disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara.
Toba saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir yang beribukota di Balige.
Kabupaten Toba Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 12. Tahun 1998 tentang
pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal,
di Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir ini merupakan
pemekaran dari Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara.
Toba dalam pembagian distrik pada HKBP
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dibagi dalam beberapa distrik yang dipimpin oleh
pendeta distrik (praeses). Pembagian distrik tersebut ada sejak tahun 1911. Pada masa itu,
13

Toba telah menjadi salah satu distrik pada HKBP yang disatukan dengan Samosir, yakni
Distrik IV Toba Samosir.
Seiring perkembangan Distrik IV Toba Samosir, Samosir pun dimekarkan menjadi distrik
yang terpisah dari Distrik IV Toba Samosir pada 25 November 1945, yaitu Distrik VII
Samosir. Distrik IV Toba Samosir pun berganti nama menjadi Distrik IV Toba
Pada November 1954, Distrik IV Toba kembali dimekarkan menjadi dua distrik, yaitu Distrik
IV Toba dan Distrik XI Toba Hasundutan.
Hingga Desember 2008 ini, rekapitulasi ressort pada Distrik IV Toba ada sebanyak 28 (dua
puluh delapan) gereja ressort dan 174 (seratus tujuh puluh empat) gedung gereja HKBP.
Distrik IV Toba meliputi Porsea, Sigumpar, Laguboti, Losung Batu, Silaen, Lumban Julu,
Parsoburan, Borbor, Narumonda, Hutahaean, Ajibata, Lumban Nabolon, Parhitean, Pintu
Pohan, Sihubakhubak, dan sekitarnya.
Sedangkan pada Distrik XI Toba Hasundutan, hingga Desember 2008 ini, rekapitulasi ressort
pada Distrik XI Toba Hasundutan ada sebanyak 8 (delapan) gereja ressort dan 28 (dua puluh
delapan) gedung gereja HKBP. Distrik XI Toba Hasundutan meliputi Balige, Tampahan,
Tambunan, Huta Gaol, Hinalang Silalahi, Parik Sabungan, Bonan Dolok, dan sekitarnya.
Seluruh Tapanuli bukan Toba
Kurang dapat diketahui sejak kapan Silindung, Samosir, dan Humbang dinyatakan sebagai
Batak Toba. Padahal Batak Toba hanya meliputi wilayah Balige, Porsea, Laguboti,
Parsoburan, Silaen, Sigumpar, Lumban Julu, Ajibata, Uluan, Pintu Pohan, dan sekitarnya.
Sedangkan seluruh Tapanuli bukan Batak Toba. Melainkan antara Silindung, Samosir,
Humbang, dan Toba telah menjadi wilayah yang berbeda sejak zaman Kerajaan Batak hingga
pembagian distrik pada HKBP.
Bila diperhatikan secara saksama pada buku JAMBAR HATA karangan oleh marga
Sihombing dan PUSTAHA BATAK Tarombo dohot Turiturian ni bangso Batak oleh W. M.
Hutagalung sangat tampak jelas bahwa seluruh Tapanuli bukan Batak Toba.
Melalui orang-orang yang tidak bertanggungjawab menyatukan Silindung, Samosir,
Humbang, dan Toba menjadi Batak Toba.
14

BATAK SISAHUTA (Silindung_Samosir_Humbang_Toba) memiliki wilayah dan contoh
marga yang berbeda pula yang disatukan dalam suku bangsa Batak.
Marga pada suku Batak Toba
Marga atau nama keluarga adalah bagian nama yang merupakan pertanda dari keluarga mana
ia berasal.
Orang Batak selalu memiliki nama marga/keluarga. Nama / marga ini diperoleh dari garis
keturunan ayah (patrilinear) yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara
terus menerus.
Dikatakan sebagai marga pada suku bangsa Batak Toba ialah marga-marga pada suku bangsa
Batak yang berkampung halaman (marbona pasogit) di daerah Toba. Sonak Malela yang
mempunyai 3 (tiga) orang putera dan menurunkan 4 (empat) marga, yaitu: Simangunsong,
Marpaung, Napitupulu, dan Pardede, merupakan salah satu cotoh marga pada suku bangsa
Batak Toba.
Kesimpulan
Batak Toba adalah sub atau bagian dari suku bangsa Batak yang wilayahnya meliputi Balige,
Porsea, Parsoburan, Laguboti, Ajibata, Uluan, Borbor, Lumban Julu, dan sekitarnya.
Silindung, Samosir, dan Humbang bukanlah Toba. Karena 4 (empat) sub atau bagian suku
bangsa Batak (Silindung_Samosir_Humbang_Toba) memiliki wilayah dan contoh marga
yang berbeda. Sonak Malela yang mempunyai 3 (tiga) orang putera dan menurunkan 4
(empat) marga, yaitu: Simangunsong, Marpaung, Napitupulu, dan Pardede, merupakan dan
[nairasaon] yang terdiri dari sitorus,sirait,butar-butar,manurung ini merupakan beberapa
marga dari batak toba.
15

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Sumber data
Dalam penelitian karya tulis ini,digunakan metode penulisan dengan cara peninjauan
dan cara tinjaua kepustakaan menurut buku………………………………tinjauan
kepustakaan disebut juga study kepustakaan yaitu mencari data dari kepustakaan misalnya
dari data buku jurnal masalah dan lain-lain.
Semakin banyak sumber bacaan semakin banyak pula pengetahuan yang diteliti
namun tidak semua buku bacaan dan laporan dapat diolah.
3.2 Cara memperoleh data
a. Mepelajari hasil yang diperoleh dari setiap sumber yang relevan dengan penelitian
yang akan dilakukan.
b. Mempelajari metode penelitian yang dilakukan termasuk metode penelitian
pengambilan sampel pengumpulan data sumber data dan satuan data
c. Mengumpulkan data dari sumber lain yang berhubungan dengan bidang penelitian.
d. Mempelajari analisis deduktif dari problem yang tertera(analisis berpikir secara
kronologis)
3.3 Instrumen penelitian
Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri karena subjek penelitiannya berupa
pustaka yang memerlukan pemahaman dan penafsiran penelitian,penulis mencatat hal-hal
yang berhubungan dengan pesan social budaya dalam menghasilkan generasi muda yang
berkualitas yang digunakan sebagai instruktur penelitian seluruh data dikumpulkan dalam
catatan khusus.
3.4 Analisis data
` Data yang dikumpulkan dalam catatan khusus selanjutnya dianalisis,proses analisis
dilakukan dengan cermat dan dideskripsikan dengan lengkap sehingga menghasilkan analisis
yang representative teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis isi.
16

BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Suku Batak Angkola
Angkola Adalah Nama daerah Di Sumtera Utara tepatnya di Tapanuli Bagian
Selatan.Pada masa dahulu tidak dikenal adanya Angkola .. kampung yang ada pertama kali
adalah sitamiang yang didirikan oleh oppu Jolak Maribu yang bermarga Dalimunthe..dan
memberi nama daerah-daerah diAngkola sekarang seperti : pargarutan (tempatnya mengasah
pedang) Tanggal (tempatnya menaggalkan hari/tempat kalender batak ) sitamiang , dan lain-
nya kemudian kembali ke toba meninggalkan daerah angkola sekarang..dan kembali lagi
disaat suku suku lain seperti suku hindia telah masuk ke-Angkola..dan marga marga lain
seperti harahap,daulay,siregar dan lain-nya``Angkola `` berasal dari sungai sungai batang
Angkola yag diberi nama seorang penguasa yang berasal dari hindia belakang yang beranama
Rajendra Kola (angkola /yang dipertuan kola).masuk melalui padang lawas . dan kemudia
berkuasa disaat itu.. disebelah selatan batang angkola diberi nama angkola jae (hilir) dan
disebelah utara sungai batang angkola diberi nama Angkola julu (hulu)kemudian orang-orang
hindia belakang keluar dari angkola disaat wabah lepra mewabahkemudian masuklah suku
suku lain dari segala penjuru ke wilayah angkolaangkola adalah tempat atau daerah
sedangkan suku diangkola adalah suku2 batakdan suku suku lain kemudian Bukti bukti
berjayanya orang orang batak dan juGa Hindia belakang dihancurkan oleh kekuasaan padri
(1821) dibawah pimpinan Tuanku Lelo dan juga belanda dan penghancuran selanjutnya
dilakukan oleh kekuasaan bangsa jepang. dan apakah kelestarian budaya juga akan
dihancurkan Bangsa sendiri
4.2 Suku Batak Mandailing
Suku Mandailing atau juga disebut Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa
yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara, yang juga dikategorikan sebagai bagian dari suku Batak, yang mempunyai
banyak dialek bahasa, walau masih berkerabat satu dengan yang lain. Pada masyarakat Adat
Minangkabau, Mandailing juga menjadi nama bagi salah satu suku yang ada pada masyarakat
tersebut.
Asal Muasal Nama
17

Mandailing dalam bahasa Minang berasal dari dua kata, mande dan hilang yang
digabung menjadi mandehilang bermaksud ibu yang hilang dan kemudian berubah tutur
menjadi sekarang. Selain itu, Mandailing atau Mandahiling bisa juga berasal dari kata
Mandala dan Hiling atau Holing, yang artinya pusat negeri Kalinga atau Kalingga. Kalingga
sendiri berasal dari kata Sanskrit Lingga, yang berarti lelaki dan imbuhan ka atau ha, menjadi
Kalingga atau Halingga, yang berarti 'kelelakian'.
Adat Istiadat
Adat istiadat suku Mandailing diatur dalam Surat Tumbaga Holing (Serat Tembaga
Kalinga), yang selalu dibacakan dalam upacara-upacara adat. Orang Mandailing mengenal
tulisan yang dinamakan Aksara Tulak-Tulak, yang merupakan varian dari aksara Proto-
Sumatera, yang berasal dari huruf Pallawa, bentuknya tak berbeda dengan aksara asli
[[Minangkabau dan Aksara Rencong dari Aceh, Aksara Sunda Kuna, dan Aksara Nusantara
lainnya. Meskipun bangsa Mandailing mempunyai aksara yang dinamakan urup tulak-tulak
dan dipergunakan untuk menulis kitab-kitab kuno yang disebut pustaha/pustaka, namun amat
sulit menemukan catatan sejarah mengenai Mandailing sebelum abad ke - 19 M. Umumnya
pustaha-pustaha/pustaka-pustaka ini berisi catatan pengobatan tradisional, ilmu-ilmu ghaib,
ramalan2 tentang waktu yang baik dan buruk serta ramalan mimpi dan bukan tentang sejarah.
Kekerabatan
Suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan, baik patrilineal maupun
matrilineal. Dalam sistem patrilineal, orang Mandailing mengenal marga. Di Mandailing
hanya dikenal belasan marga saja berbeda di Batak, yang mengenal hampir 500 marga.
Seperti halnya di Karo, Nias, Gayo, Alas, marga-marga di Mandailing umumnya tak
mempunyai keterkaitan kekerabatan dengan Batak. Marga-marga di Mandailing, antara lain
Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan (Nasibuan),
Rambe, Dalimunthe, Rangkuti (Ra Kuti), Tanjung, Mardia, Daulay (Daulae), Matondang,
Hutasuhut.
Marga-Marga Mandailing, menurut Abdoellah Loebis, di Mandailing Julu dan
Pakantan, seperti berikut: Lubis yang terbahagi kepada Lubis Huta Nopan dan Lubis Singa
Soro, Nasution, Parinduri, Batu Bara, Matondang, Daulay, Nai Monte, Hasibuan, Pulungan.
Marga-marga di Mandailing Godang pula adalah: Nasution yang terbahagi kepada Nasution
18

Panyabungan, Tambangan, Borotan, Lancat, Jior, Tonga, Dolok, Maga, Pidoli, dan lain-lain.
Lubis, Hasibuan, Harahap, Batu Bara, Matondang (keturunan Hasibuan), Rangkuti, Mardia,
Parinduri, Batu na Bolon, Pulungan, Rambe, Mangintir, Nai Monte, Panggabean, Tangga
Ambeng dan Margara. (Rangkuti, Mardia dan Parinduri asalnya satu marga).
Menurut Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan, di Angkola dan Sipirok
terdapat marga-marga Pulungan, Baumi, Harahap, Siregar, Dalimunte dan Daulay. Juga
terdapat marga-marga Harahap, Siregar, Hasibuan, Daulay, Dalimunte, Pulungan, Nasution
dan Lubis di Padang Lawas.
Menurut Basyral Hamidy Harahap dalam buku berjudul Horja, marga-marga di Mandailing
antara lain Babiat, Dabuar, Baumi, Dalimunthe, Dasopang, Daulae, Dongoran, Harahap,
Hasibuan, Hutasuhut, Lubis, Nasution, Pane, Parinduri, Pasaribu, Payung, Pohan, Pulungan,
Rambe, Rangkuti, Ritonga, Sagala, Simbolon, Siregar, Tanjung.
Mandailing versus Batak
Ada juga suku bangsa di Malaysia yang menamakan dirinya sebagai suku Mandailing,
terutama di Negeri Sembilan, tepatnya di Kg. Kerangai, Kg. Lanjut Manis dan Kg.
Tambahtin, mereka juga menolak disebut bagian dari suku Batak dan mereka menganggap
Mandailing merupakan suku bangsa yang terpisah dari suku Batak. Terjadinya perbedaan
pendapat tersebut disebabkan adanya rasa perbedaan agama, dimana mayoritas penduduk
Mandailing adalah Islam, yang diistilahkan melayu dalam bahasa Mandailing, sedangkan
mayoritas agama pada suku bangsa Batak lainnya adalah Kristen Protestan, yang tergabung
dalam Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sementara minoritas Kristen di Mandailing
tergabung dalam Gereja Kristen Angkola (GKA).
Di samping itu, penolakan masyarakat Mandailing disebut batak salah satunya juga
disebabkan sejarah persebaran manusia di Sumatera. Semisal, tidak ada satupun artefak atau
situs sejarah yang bisa membuktikan bahwa suku Mandailing berasal dari Pusu Buhit dan
sekitarnya. Di mana, dalam mitologi Batak, inilah daerah asal muasal orang Batak. Dalam
perspektif persebaran manusia di Mandailing, masyarakat Mandailing tua lebih menyukai
tinggal di lereng gunung yang berpepohonan lebat dibandingkan dengan di daerah dataran
tandus seperti pulau Samosir.
19

Selain itu, ungkapan kata Batak dalam termiologi Minangkabau tua adalah stereotype untuk
para pengelana berkuda. Mereka berkenalan dari sebuah daerah potensial tinggi ke dataran
tinggi tandus yang dilatarbelakangi sebuah perisitwa sosial. Sebut saja seperti lari dari
majikan, begal, rampok dan sebagainya. Pelarian ke dataran tinggi tandus, di mana kehidupan
menjadi begitu sulit adalah sebuah upaya proteksi dari ancaman konflik sosial maupun
politik. Perisitiwa ini sendiri terjadi jauh sebelum bangsa-bangsa dari Eropa melakukan invasi
ke Pulau Sumatera.
Namun, sebutan etnis Batak itu dipopulerkan oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas
Stanford Raffless pada Tahun 1823 M, dalam rangka membuat suku Kristen, yang berada di
antara Kesultanan Islam Aceh dan Kerajaan Islam Minangkabau, yaitu di pedalaman Barus,
yang kala itu masuk dalam Kesultanan Barus bawahan Kesultanan Aceh. Dalam bahasa
Belanda policy (kebijakan) itu berbunyi, "Een wig te drijen tusschen het mohamedaansche
Atjeh en het eveneens mohammadansche Sumatra's West Kust. Een wig in de vorm van de
Bataklanden (Aceh yang Islam serta Minangkabau (Pantai Barat Sumatra) yang Islam dipisah
dengan blok Batak (Barus Tanah Kristen)." Perintah ini meniru perintah Gubernur Jenderal
Inggris di Calcutta, yaitu "Burma yang Buddha serta Siam yang Buddha dipisah dengan blok
Karen yang kristen." Pelaksanaannya, 3 pendeta British Baptist Mission, yaitu Pendeta
Burton, Pendeta Ward, Pendeta Evans ke Kota Tapian Na Uli, tempat Raffless beribukota
saat itu. Pada tahun 1834 M, melalui Londonsche Tractaat, Sumatera bagian utara ditukar
dengan Belanda dengan Kalimantan Utara (Sarawak dan Sabah), perintah Raffless diteruskan
pemerintah Hindia Belanda.Upaya membentuk suku dan wilayah khusus Kristen di Sumatera
baru dimulai tahun 1873 M, dengan berhasilnya Belanda menakhlukkan wilayah Aceh, yaitu
Silindung, dan menghancurkan masjid di Tarutung, setelah Pendeta Nommensen pada tahun
1863 M dari Sipirok pindah ke Silindung ditemani 2 perwira Paderi yang telah dibaptist
Pendeta Verhouven pada tahun 1834 M, yaitu Ja Mandatar Lubis dan Kali (Qadli) Rancak
Lubis di Pakantan. Daerah Silindung kemudian dimasukkan dalam Karesidenan Air Bangis,
di bawah Gouvernemen Sumatra's West Kust. Selanjutnya, pada tahun 1881 M, daerah Toba
berhasil ditakhlukkan Belanda, dan dilanjutkan dengan pengkristenan. Hal ini membuat wali
negeri Bakkara (Bangkara), yang berada di bawah Kesultanan Aceh, yaitu Si Singam Manga
Raja (Sri Singa Maha Raja) XII yang merupakan keturunan Sultan Aceh melalui Kesultanan
Barus, melakukan perlawanan sengit dari tahun 1882 - 1884 M, yang dibantu Tentara Aceh.
Selain itu juga, penamaan suku Kristen di Kalimantan, yaitu Dayak oleh Belanda, dan
Malayik oleh Inggris. Semenjak itu orang Mandailing, baik yang tinggal di afdeeling
20

Padangsidempuan (Tapanuli Selatan), Labuhan Batu, Asahan, Sumatera Barat dan Riau
menolak disebut sebagai orang Batak.Peristiwa di atas dikuatkan pada tahun 1922-1926 M,
setelah terjadi perdebatan di Medan tentang hak orang muslim bermarga Siregar yang semula
mengaku Mandailing kemudian mengaku sebagai Batak, ingin dikuburkan di tanah wakaf
Mandailing di Sungai Mati, Medan. Dalam hal ini, Mahkamah Syariah Deli memutuskan
hanya orang yang mengaku Mandailing yang berhak dikuburkan pada tanah wakaf tersebut.
Peristiwa ini dianggap oleh sebagian orang, sebagai salah satu pengukuhan terhadap
perbedaan identitas orang Mandailing dengan Batak.[
Sejarah
Dalam tulisan MANDAILING DALAM LINTASAN SEJARAH oleh Drs.
Pengaduan Lubis, yang dikabarkan dalam Mandailing.org, dinyatakan Suku bangsa atau
kelompok etnis Mandailing. Suku bangsa atau kelompok etnis Mandailing memang
mempuyai aksara sendiri yang dinamakan Surat Tulak-Tulak. Tetapi ternyata orang-orang
Mandailing pada zaman dahulu tidak menggunakan aksara tersebut untuk menuliskan
sejarah. Pada umumnya yang dituliskan adalah mengenai ilmu pengobatan tradisional,
astronomi tradisional, ilmu ghaib, andung-andung dan tarombo atau silsilah keturunan
keluarga-keluarga tertentu. Setelah sekolah berkembang di Mandailing, Surat Tulak-Tulak
mulai dipergunakan oleh guru-guru untuk menuliskan cerita-cerita rakyat Mandailing sebagai
bacaan murid-murid sekolah.
Beberapa legenda yang mengandungi unsur sejarah dan berkaitan dengan asal-usul
marga orang Mandailing masih hidup di tengah masyarakat Mandailing. Seperti legenda
Namora Pande Bosi dan legenda Si Baroar yang dtulis oleh Willem Iskandar pada abad ke-18
M. Tetapi legenda yang demikian itu tidak memberi keterangan yang cukup berarti mengenai
sejarah Mandailing. Dalam beberapa catatan sejarah seperti sejarah Perang Paderi yang
disusun oleh M. Radjab, disebut-sebut mengenai Mandailing dan keterlibatan orang
Mandailing dalam Perang Paderi. Catatan sejarah ini hanya berhubungan dengan masyarakat
Mandailing pada abad ke-18 dan awal masuknya orang Belanda ke Mandailing. Bagaimana
sejarah atau keadaan masyarakat Mandailing pada abad-abad sebelumnya tidak terdapat
tulisan yang mencatatnya.
Mpu Prapanca, seorang pujangga Kerajaan Majapahit menulis satu kitab yang
berjudul Negarakertagama sekitar tahun 1365 M. kitab tersebut ditulisnya dalam bentuk syair
21

yang berisi keterangan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Menurut Prof. Slamet Mulyana
(1979:9), Kitab Negarakertagama adalah sebuah karya paduan sejarah dan sastra yang
bermutu tinggi dari zaman Majapahit. Berabad-abad setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit,
keberadaan dimana kitab ini tidak diketahui. Baru pada tahun 1894, satu Kitab
Negarakertagama ditemukan di Puri Cakranegara di Pulau Lombok. Kemudian pada Juli
1979 ditemukan lagi satu Kitab Negarakertagama di Amlapura, Lombok.
Dalam Pupuh XIII Kitab Negarakertagama, nama Mandailing bersama nama banyak
negeri di Sumatera dituliskan oleh Mpu Prapanca sebagai negara bawahan Kerajaan
Majapahit. Tidak ada keterangan lain mengenai Mandailing, kecuali sebagai salah satu
negara bawahan Kerajaan Majapahit. Namun demikian, dengan dituliskan nama Mandailing
terdapatlah bukti sejarah yang otentik bahwa pada abad ke-14 M telah diakui keberadaannya
sebagai salah satu negara bawahan Kerajaan Majapahit. Pengertian negara bawahan dalam
hal ini tidak jelas artinya, karena tidak ada keterangan berikutnya.
Jadi dapatlah dikatakan bahwa Negeri Mandailing sudah ada sebelum abad ke-14 M.
Karena sebelum keberadaannya dicatat tentunya Mandailing sudah terlebih dahulu ada.
Kapan Negeri Mandailing mulai berdiri tidak diketahui secara persis. Tetapi karena nama
Mandailing dalam kitab ini disebut-sebut bersama nama banyak negeri di Sumatera termasuk
Pane dan Padang Lawas, kemungkinan sekali negeri Mandailing sudah mulai ada pada abad
ke-5 M atau sebelumya. Karena Kerajaan Pane sudah disebut-sebut dalam catatan Cina pada
abad ke-6 M. Dugaan yang demikian ini dapat dihubungkan dengan bukti sejarah berupa
reruntuhan candi yang terdapat di Simangambat dekat Siabu. Candi tersebut adalah Candi
Siwa yang dibangun sekitar abad ke-8 M.
Apakah pada abad ke-14 M, Mandailing merupakan satu kerajaan tidak diketahui.
Karena dalam Kitab Negarakertagama, Mandailing tidak disebut-sebut sebagai kerajaan
tetapi sebagai negara bawahan Kerajaan Majapahit. Tetapi dengan disebutkan negeri
Mandailing sebagai negara, ada kemungkinan pada masa itu Mandailing merupakan satu
kerajaan. Keterangan mengenai keadaaan Mandailing sebelum abad ke-14 M, tidak ada sama
sekali kecuali keberadaan Candi Siwa di Simangambat. Namun demikian, berdasarkan
berbagai peninggalan dari zaman pra sejarah dan peninggalan dari zaman Hindu/Buddha
yang terdapat di Mandailing kita dapat mengemukakan keterangan yang bersifat hipotesis.
4.3 Hipotesis Kerajaan Mandala Holing
22

Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa di Simangambat terdapat
reruntuhan Candi Siwa (Hindu) dari abad ke-8. Candi tersebut jauh lebih tua dari candi-candi
di Portibi (Padang Lawas) yang menurut perkiraan para pakar dibangun pada abad ke-11.
Dengan adanya candi ini bisa menimbulkan pertanyaan mengapa dan kapan ummat Hindu
yang selanjutnya saya sebut orang Hindu dari India datang ke Mandailing yang terletak di
Sumatera yang mereka namakan Swarna Dwipa (Pulau Emas).
Besar kemungkinan orang Hindu datang ke Mandailing yang terletak di Svarna
Dwipa adalah untuk mencari emas. Dalam sejarah India, terdapat keterangan yang
menyebutkan bahwa sekitar abad pertama Masehi, pasokan emas ke India yang didatangi dari
Asia Tengah terhenti. Karena di Asia Tengah terjadi berbagai peperangan.Oleh karena itu
kerajaan-kerajaan yang terdapat di India berusaha mendapatkan emas dari tempat lain, yaitu
dari Sumatera/Swarna Dwipa. Dalam hubungan ini kita mengerti bahwa di wilayah
Mandailing yang pada masa lalu hingga kini di dalamnya termasuk kawasan Pasaman
terdapat banyak emas. Bukti-bukti mengenai hal ini banyak sekali. Jadi besar sekali
kemungkinan bahwa tempat yang dituju oleh orang Hindu dari India untuk mencari emas di
Swarna Dwipa adalah daerah Mandailing.
Orang Hindu yang datang ke wilayah Mandailing adalah yang berasal dari negeri atau
Kerajaan Kalingga di India. Oleh karena itu mereka disebut orang Holing atau orang Koling.
Ada kemungkinan mereka masuk dari daerah Singkuang (tambahan: Pelabuhan Natal).
Karena Singkuang yang merupakan tempat bermuaranya Sungai Batang Gadis cukup terkenal
sebagai pelabuhan. Itulah sebabnya tempat tersebut dinamakan Singkuan oleh pedagang Cina
(Singkuang dibuat pada masa Dinasti Ming, yang merupakan koloni dari keturunan orang-
orang dari ekspedisi Panglima Ceng Ho) yang berarti 'harapan baru'. Karena melalui
pelabuhan ini mereka biasa memperoleh berbagai barang dagangan yang penting yang
berasal dari Sumatera seperti damar, gitan, gading dsb.
Menurut dugaan setelah orang Holing/Koling tiba di Singkuang, selanjutnya mereka
menyusuri Sungai Batang Gadis ke arah hulunya. Dengan demikian maka akhirnya mereka
sampai di satu dataran rendah yang subur yaitu di kawasan Mandailing Godang yang
sekarang. Sejak zaman pra sejarah di kawasan tersebut dan di berbagai tempat di Mandailing
sudah terdapat penduduk pribumi (tambahan: Suku Lubu, yang memakai sistem matriarkhat
dan matrilineal). Hal ini dibuktikan oleh adanya peninggalan dari zaman pra sejarah berupa
23

lumpang-lumpang batu besar di tengah hutan di sekitar Desa Runding di seberang Sungai
Batang Gadis dan bukti-bukti lainnya di berbagai tempat.
Pada waktu orang Holing/Koling sampai di kawasan Mandailing Godang (waktu itu
kita tidak tahu nama kawasan ini), maka mereka bertemu dengan penduduk pribumi
setempat. Penamaan orang Holing/Koling digunakan untuk menyebutkan orang Hindu yang
berasal dari Negeri Kalingga tersebut dibuat oleh penduduk pribumi. Setibanya di wilayah
Mandailing, orang-orang Holing/Koling tersebut menemukan apa yang mereka cari yaitu
emas. Kita mengetahui melalui sejarah bahwa emas tercatat sebagai salah satu modal utama
dalam berdirinya kerajaan-kerajaan besar dan emas juga merupakan sumber kemakmuran.
Setelah orang-orang Hindu menemukan banyak emas di kawasan Mandailing yang sekarang
ini, mereka kemudian menetap di kawasan tersebut. Karena orang-orang Holing/Koling
menetap di kawasan itu maka dinamakan Mandala Holing/Koling. Mandala artinya
lingkungan atau kawasan. Mandala Holing/Koling berarti lingkungan atau kawasan tempat
tinggal orang-orang Holing/Koling. Sampai sekarang kita sering mendengar disebut-sebut
adanya Banua Holing/Koling. Tetapi orang-orang tidak mengetahui dimana tempat yang
dinamakan Banua Holing/Koling itu.Berdasarkan hipotesis ini kita dapat mengatakan bahwa
yang disebut Banua Holing/Koling itu adalah wilayah Mandailing yang dahulu ditempati oleh
orang-orang Holing/Koling. Dengan kata lain Banua Holing/Koling adalah Mandala
Holing/Koling. Berabad-abad kemudian Mandala Holing/Koling dikenal sebagai Kerajaan
Holing. Dalam hubungan ini Slamet Mulyana (1979:59) mengemukakan bahwa hubungan
dagang dan diplomat antara Cina dan Jawa berlangsung, mulai dari berdirinya Kerajaan
Holing pada permulaan abad ke-7 sampai runtuhnya Kerajaan Majapahit pada permulaan
abad ke-16. Sejalan dengan keterangan Slamet Mulyana ini kita dapat melihat hubungan
antara Kerajaan Holing dengan adanya Candi Siwa Di Simangambat yang dibangunkan pada
abad ke-8. Dalam hubungan ini dapat pula dikemukan bahwa dari berbagai catatan sejarah
disebut-sebut adanya Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Holing. Tetapi sampai sekarang para
sejarah belum menentukan dimana sebenarnya lokasinya yang pasti. Ada pakar sejarah yang
menduga bahwa Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Timur tetapi Kerajaan Holing yang
disebut-sebut dalam catatan Cina tidak diketahui lokasinya yang pasti. Dan dapat pula
dipertanyakan apakah Kerajaan Kalingga adalah yang disebut juga sebagai Kerajaan Holing.
Dengan argumentasi yang telah dikemukan di atas, kita mengajukan dugaan
(hipotesis) bahwa yang disebut Kerajaan Holing itu dahulu terletak di wilayah Mandailing
yang juga disebut sebagai Kerajaan Mandala Holing/Koling. Kiranya cukup beralasan untuk
24

menduga bahwa nama Mandahiling (Mandailing) yang disebut oleh Mpu Prapanca dalam
Kitan Negarakertagama pada abad ke-14 berasal dari nama Mandalaholing yang kemudian
mengalami perubahan penyebutan menjadi Mandahiling dan akhirnya kini menjadi
Mandailing. Untuk membuktikan kebenaran dugaan atau hipotesis ini tentu masih perlu
dilakukan penelitian. Dan ini merupakan tantangan bagi orang Mandailing yang
berkedudukan sebagai pakar sejarah
Diperkiranya orang-orang Hindu menetap di Kerajaan Mandalaholing (Kerajaan
Holing/ Banua Holing) yang kaya dengan emas berabad-abad lamanya. Yaitu sejak mereka
datang pertama kali pada abad-abad pertama Masehi. Sampai abad ke-13 orang-orang Hindu
masih ada yang menetap di Mandailing yang sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan
ditemukannya cukup banyak peninggalan Hindu/Buddha di wilayah Mandailing. Salah satu
diantaranya adalah tiang batu di Gunung Sorik Merapi yang bertarikh abad ke-13 M di
kawasan Mandailing Godang (Pidoli) terdapat lokasi persawahan yang bernama Saba Biara.
Yang disebut biara atau vihara adalah tempat orang-orang Hindu-Buddha melakukan
kegiatan keagamaan.
Menurut dugaan Kerajaan Mandalaholing yang dahulu pernah terdapat di Mandailing
yang sekarang meluas sampai ke kawasan Pasaman (yang dahulu merupakan bagian dari
Mandailing). Menurut keterangan yang pernah saya peroleh di Pasaman, batas antara wilayah
Mandailing dan wilayah Minangkabau terletak di Si Pisang lewat Palupuh. Sekarang batas
antara Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Di kawasan Pasaman, yaitu di
tempat yang bernama Tanjung Medan dekat Rao terdapat juga candi yang mirip keadaannya
dengan candi di Portibi. Dan kita tahu bahwa di kawasan Pasaman juga terdapat emas yang
dibutuhkan oleh orang-orang Hindu. Kalau tidak salah di kawasan yang bernama Manggani.
Di kawasan itu juga terdapat tambang emas Belanda pada masa penjajahan.
4.4 Pengaruh Hindu
Peninggalan-peninggalan bersejarah seperti disebutkan di atas, membuktikan bahwa
sudah ada manusia yang mendiami wilayah Mandailing pada masa tersebut. Sebagai pribumi
Mandailing, mereka terus berkembang sampai orang-orang Hindu datang dan menetap di
Mandailing. Besar kemungkinan antara penduduk pribumi hidp berdampingan secara damai
dengan orang-orang Hindu yang menetap dan kemudian membangun kerajaan di wilayah
Mandailing. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun banyak ditemukan
peninggalan dari zaman Hindu di wilayah Mandailing, tapi ditemukan juga peninggalan
kebudayaan pribumi Mandailing yang berkembang sendiri tanpa didominasi oleh pengaruh
25

Hindu. Misalnya, patung-patung batu seperti yang terdapat di halaman Bagas Godang
Panyabungan Tonga-Tonga dan patung-patung kayu yang terdapat di Huta (Kuta) Godang.
Demikian juga ornamen-ornamen tradisional yang terdapat pada Bagas Godang dan Sopo
Godang yang hanya sedikit sekali memperlihatkan pengaruh Hindu. Yakni pada ornamen
berbentuk segitiga yang disebut bindu (pusuk robung) yang merupakan lambang dari Dalian
Na Tolu. Dalam kebudayaan Hindu, bindu (bentuk segitiga) merupakan lambang mistik
hubungan manusia dengan dewa trimurti. Bagian-bagian lain dari ornamen tradisional tidak
memperlihatkan adanya pengaruh Hindu. Dari bentuknya, ornamen-ornamen yang ada
sampai sekarang ini hanya menggunakan garis-garis geometris (garis lurus), kecuali ornamen
benda alam, buatan dan hewan seperti matahari, bulan, bintang, pedang, ular dll. Bentuk
ornamen yang hanya menggunakan garis-garis geometris ini membuktikan ornamen tersebut
berasal dari zaman yang sudah lama sekali (primitif).
Pengaruh Hindu juga terdapat pada budaya tradisional Mandailing, antara lain pada
penamaan desa na ualu (walu) (mata angin)dan pada gelar kebangsawanan seperti Mangaraja
(Maharaja), Soripada (Sripaduka/Sripaduha), Batara Guru serta nama gunung seperti Dolok
Malea. Keaneragaman bahasa Mandailing yang terdiri dari hata (kata) somal, hata sibaso,
hata parkapur, hata teas dohot jampolak dan hata andung, yang kosa katanya masing-masing
berlainan menunjukkan budaya pribumi Mandailing sudah lama berkembang yang tentunya
dihasilkan dari peradaban yang sudah tinggi yang tidak banyak dipengaruhi oleh budaya
Hindu. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun orang Hindu lama menetap dan
mengembangkan budayanya tetapi pribumi Mandailing tidak didominasi oleh orang-orang
Hindu, dan bebas mengembangkan budayanya sendiri.
Adanya dua masyarakat, yaitu pribumi Mandailing dan orang Hindu yang masing-
masing mengembangkan budayanya pada masa yang lalu di lingkungan alam yang subur dan
kaya dengan emas. Diduga kemungkinan besar Mandailing merupakan pusat peradaban di
Sumatera pada masa awal abad-abad Masehi. Salah satu bukti mengenai hal ini adalah
adanya ragam bahasa yang sudah disebutkan di atas dan adanya aksara yang dinamakan
[[Surat Tulak-Tulak (yang berasal dari huruf Pallawa), yang kemudian berkembang ke arah
utara mulai dari Toba, Simalungun sampai Karo dan Pakpak. Penelitian para pakar sudah
membuktikan bahwa aksara Mandailing (Surat Tulak-Tulak). Bahasa yang halus dan aksara
yang dimiliki oleh sesuatu bangsa menunjukkan bahwa bangsa tersebut sudah mempunyai
peradaban yang tinggi.
26

Ada permasalahan yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu kapan orang
Hindu lenyap dari wilayah Mandailing dan apa yang menyebabkan mereka hilang dari
Mandailing. Setelah orang Hindu lenyap dari Mandailing, pribumi Mandailing terus
mengembangkan kebudayaannya. Budaya Mandailing berkembang tanpa memperlihatkan
pengaruh budaya Hindu yang esensial, walau pun masyarakat Mandailing terbagi dalam 5
kasta, yaitu Namora-mora, Datu-datu, Kalak Somal, Ampong Dalam, dan Hatoban. Dalam
kebudayaan Hindu salah satu esensial adalah konsep bahwa raja adalah wakil dewa di bumi
yang mendasari feodalisme dalam pelaksanaan pemerintahan kerajaan. Masyarakat
Mandailing tidak menganut konsep yang demikian itu, dan pemerintahan yang demokratis
yang dijalankan bersama-sama oleh Namora Natoras dan Raja. Hal ini dilambangkan oleh
bangunan Sopo Godang sebagai balai sidang adat (pemerintahan) yang sengaja dibuat tidak
berdinding, agar rakyat dapat secara langsung melihat dan mendengar segala hal yang
dibicarakan oleh para pemimpin mereka. Semuanya berlangsung secara transparan yang
langsung disaksikan sendiri oleh rakyat.
Setelah Belanda menjajah Mandailing, keadaan yang demikian itu mengalami banyak
perubahan sehingga akhirnya muncul hal-hal yang feodalistis. Karena untuk memperkuat
kedudukannya di Mandailing, Belanda berusaha mengembangkan hal-hal yang feodalistis
untuk dapat menguasai rakyat Mandailing yang demokratis. Sifat rakyat Mandailing yang
demokratis itu, pada akhirnya mendorong munculnya pergerakan nasional di Mandailing
sebagai pelopor pergerakan di Sumatera Utara.
4.5 Suku Batak Karo
Suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia.
Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami
(dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut
Bahasa Karo. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh
dengan perhiasan emas.
Eksistensi Kerajaan Haru-Karo
Kerajaan Haru-Karo (Kerajaan Aru) mulai menjadi kerajaan besar di Sumatera, namun tidak
diketahui secara pasti kapan berdirinya. Namun demikian, Brahma Putra, dalam bukunya
"Karo dari Zaman ke Zaman" mengatakan bahwa pada abad 1 Masehi sudah ada kerajaan di
27

Sumatera Utara yang rajanya bernama "Pa Lagan". Menilik dari nama itu merupakan bahasa
yang berasal dari suku Karo. Mungkinkah pada masa itu kerajaan haru sudah ada?, hal ini
masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.(Darman Prinst, SH :2004)
Kerajaan Haru-Karo diketahui tumbuh dan berkembang bersamaan waktunya dengan
kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Johor, Malaka dan Aceh. Terbukti karena kerajaan Haru
pernah berperang dengan kerajaan-kerajaan tersebut.
Kerajaan Haru pada masa keemasannya, pengaruhnya tersebar mulai dari Aceh Besar hingga
ke sungai Siak di Riau.
Terdapat suku Karo di Aceh Besar yang dalam logat Aceh disebut Karee. Keberadaan suku
Haru-Karo di Aceh ini diakui oleh H. Muhammad Said dalam bukunya "Aceh Sepanjang
Abad", (1981). Ia menekankan bahwa penduduk asli Aceh Besar adalah keturunan mirip
Batak. Namun tidak dijelaskan keturunan dari batak mana penduduk asli tersebut. Sementara
itu, H. M. Zainuddin dalam bukunya "Tarikh Aceh dan Nusantara" (1961) dikatakan bahwa
di lembah Aceh Besar disamping Kerajaan Islam ada kerajaan Karo. Selanjunya disebutkan
bahwa penduduk asli atau bumi putera dari Ke-20 Mukim bercampur dengan suku Karo yang
dalam bahasa Aceh disebut Karee. Brahma Putra, dalam bukunya "Karo Sepanjang Zaman"
mengatakan bahwa raja terakhir suku Karo di Aceh Besar adalah Manang Ginting Suka.
Kelompok karo di Aceh kemudian berubah nama menjadi "Kaum Lhee Reutoih" atau kaum
tiga ratus. Penamaan demikian terkait dengan peristiwa perselisihan antara suku Karo dengan
suku Hindu di sana yang disepakati diselesaikan dengan perang tanding. Sebanyak tiga ratus
(300) orang suku Karo akan berkelahi dengan empat ratus (400) orang suku Hindu di suatu
lapangan terbuka. Perang tanding ini dapat didamaikan dan sejak saat itu suku Karo disebut
sebagai kaum tiga ratus dan kaum Hindu disebut kaum empat ratus.
Dikemudian hari terjadi pencampuran antar suku Karo dengan suku Hindu dan mereka
disebut sebagai kaum Jasandang. Golongan lainnya adalah Kaum Imam Pewet dan Kaum
Tok Batee yang merupakan campuran suku pendatang, seperti: Kaum Hindu, Arab, Persia,
dan lainnya.
Wilayah Pengaruh Suku Karo
28

Sering terjadi kekeliruan dalam percakapan sehari-hari di masyarakat bahwa Taneh Karo
diidentikkan dengan Kabupaten Karo. Padahal, Taneh Karo jauh lebih luas daripada
Kabupaten Karo karena meliputi:
Kabupaten Tanah Karo
Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Tanah Karo. Kota yang terkenal dengan di wilayah
ini adalah Brastagi dan Kabanjahe. Brastagi merupakan salah satu kota turis di Sumatera
Utara yang sangat terkenal dengan produk pertaniannya yang unggul. Salah satunya adalah
buah jeruk dan produk minuman yang terkenal yaitu sebagai penghasil Markisa Jus yang
terkenal hingga seluruh nusantara. Mayoritas suku Karo bermukim di daerah pegunungan ini,
tepatnya di daerah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak yang sering disebut sebagai atau
"Taneh Karo Simalem". Banyak keunikan-keunikan terdapat pada masyarakat Karo, baik dari
geografis, alam, maupun bentuk masakan. Masakan Karo, salah satu yang unik adalah disebut
trites.Trites ini disajikan pada saat pesta budaya, seperti pesta pernikahan, pesta memasuki
rumah baru, dan pesta tahunan yang dinamakan -kerja tahun-. Trites ini bahannya diambil
dari isilambung sapi/kerbau, yang belum dikeluarkan sebagai kotoran.Bahan inilah yang
diolah sedemikian rupa dicampur dengan bahan rempah-rempah sehingga aroma tajam pada
isi lambung berkurang dan dapat dinikmati. Masakan ini merupakan makanan favorit yang
suguhan pertama diberikan kepada yang dihormati.
Kota Medan
Pendiri kota Medan adalah seorang putra Karo yaitu Guru Patimpus Sembiring Pelawi.
Kota Binjai
Kota Binjai merupakan daerah yang memiliki interaksi paling kuat dengan kota Medan
disebabkan oleh jaraknya yang relatif sangat dekat dari kota Medan sebagai Ibu kota provinsi
Sumatera Utara.
Kabupaten Dairi
Wilayah kabupaten Dairi pada umumnya sangat subur dengan kemakmuran masyarakatnya
melalui perkebunan kopinya yang sangat berkualitas. Sebagian kabupaten Dairi yang
merupakan Taneh Karo:
29

Kecamatan Taneh Pinem
Kecamatan Tiga Lingga
Kecamatan Gunung Sitember
[sunting] Kabupaten Aceh Tenggara
Taneh Karo di kabupaten Aceh Tenggara meliputi:
Kecamatan Lau Sigala-gala (Desa Lau Deski, Lau Perbunga, Lau Kinga)
Kecamatan Simpang Simadam
Marga
Suku Karo memiliki sistem kemasyarakatan atau adat yang dikenal dengan nama merga
silima, tutur siwaluh, dan rakut sitelu. Masyarakat Karo mempunyai sistem marga (klan).
Marga atau dalam bahasa Karo disebut merga tersebut disebut untuk laki-laki, sedangkan
untuk perempuan yang disebut beru. Merga atau beru ini disandang di belakang nama
seseorang. Merga dalam masyarakat Karo terdiri dari lima kelompok, yang disebut dengan
merga silima, yang berarti marga yang lima. Kelima merga tersebut adalah:
1. Karo-karo
2. Tarigan
3. Ginting
4. Sembiring
5. Perangin-angin
Kelima merga ini masih mempunyai submerga masing-masing. Setiap orang Karo
mempunyai salah satu dari merga tersebut. Merga diperoleh secara otomatis dari ayah. Merga
ayah juga merga anak. Orang yang mempunyai merga atau beru yang sama, dianggap
bersaudara dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama. Kalau laki-laki bermarga sama,
maka mereka disebut (b)ersenina, demikian juga antara perempuan dengan perempuan yang
mempunyai beru sama, maka mereka disebut juga (b)ersenina. Namun antara seorang laki-
laki dengan perempuan yang bermerga sama, mereka disebut erturang, sehingga dilarang
melakukan perkawinan, kecuali pada merga Sembiring dan Peranginangin ada yang dapat
menikah diantara mereka.
30

Rakut Sitelu
Hal lain yang penting dalam susunan masyarakat Karo adalah rakut sitelu atau daliken sitelu
(artinya secara metaforik adalah tungku nan tiga), yang berarti ikatan yang tiga. Arti rakut
sitelu tersebut adalah sangkep nggeluh (kelengkapan hidup) bagi orang Karo. Kelengkapan
yang dimaksud adalah lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat Karo yang terdiri dari
tiga kelompok, yaitu:
1. kalimbubu
2. anak beru
3. senina
1.
Kalimbubu dapat didefinisikan sebagai keluarga pemberi isteri, anak beru keluarga yang
mengambil atau menerima isteri, dan senina keluarga satu galur keturunan merga atau
keluarga inti.
Tutur Siwaluh
Tutur siwaluh adalah konsep kekerabatan masyarakat Karo, yang berhubungan dengan
penuturan, yaitu terdiri dari delapan golongan:
1. puang kalimbubu
2. kalimbubu
3. senina
4. sembuyak
5. senina sipemeren
6. senina sepengalon/sedalanen
7. anak beru
8. anak beru menteri
Dalam pelaksanaan upacara adat, tutur siwaluh ini masih dapat dibagi lagi dalam kelompok-
kelompok lebih khusus sesuai dengan keperluan dalam pelaksanaan upacara yang
dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:
31

1. Puang kalimbubu adalah kalimbubu dari kalimbubu seseorang
2. Kalimbubu adalah kelompok pemberi isteri kepada keluarga tertentu, kalimbubu ini
dapat dikelompokkan lagi menjadi:
o Kalimbubu bena-bena atau kalimbubu tua, yaitu kelompok pemberiisteri
kepada kelompok tertentu yang dianggap sebagai kelompok pemberi isteri
adal dari keluarga tersebut. Misalnya A bermerga Sembiring bere-bere
Tarigan, maka Tarigan adalah kalimbubu Si A. Jika A mempunyai anak, maka
merga Tarigan adalah kalimbubu bena-bena/kalimbubu tua dari anak A. Jadi
kalimbubu bena-bena atau kalimbubu tua adalah kalimbubu dari ayah
kandung.
o Kalimbubu simada dareh adalah berasal dari ibu kandung seseorang.
Kalimbubu simada dareh adalah saudara laki-laki dari ibu kandung seseorang.
Disebut kalimbubu simada dareh karena merekalah yang dianggap mempunyai
darah, karena dianggap darah merekalah yang terdapat dalam diri
keponakannya.
o Kalimbubu iperdemui, berarti kalimbubu yang dijadikan kalimbubu oleh
karena seseorang mengawini putri dari satu keluarga untuk pertama kalinya.
Jadi seseorang itu menjadi kalimbubu
adalah berdasarkan perkawinan.
Senina, yaitu mereka yang bersadara karena mempunyai merga dan submerga yang sama.
Sembuyak, secara harfiah se artinya satu dan mbuyak artinya kandungan, jadi artinya
adalah orang-orang yang lahir dari kandungan atau rahim yang sama. Namun dalam
masyarakat Karo istilah ini digunakan untuk senina yang berlainan submerga juga, dalam
bahasa Karo disebut sindauh ipedeher (yang jauh menjadi dekat).
Sipemeren, yaitu orang-orang yang ibu-ibu mereka bersaudara kandung. Bagian ini
didukung lagi oleh pihak siparibanen, yaitu orang-orang yang mempunyai isteri yang
bersaudara.
Senina Sepengalon atau Sendalanen, yaitu orang yang bersaudara karena mempunyai
anak-anak yang memperisteri dari beru yang sama.
Anak beru, berarti pihak yang mengambil isteri dari suatu keluarga tertentu untuk
diperistri. Anak beru dapat terjadi secara langsung karena mengawini wanita keluarga
32

tertentu, dan secara tidak langsung melalui perantaraan orang lain, seperti anak beru menteri
dan anak beru singikuri.Anak beru ini terdiri lagi atas:
anak beru tua, adalah anak beru dalam satu keluarga turun temurun. Paling tidak tiga
generasi telah mengambil isteri dari keluarga tertentu (kalimbubunya). Anak beru tua
adalah anak beru yang utama, karena tanpa kehadirannya dalam suatu upacara adat
yang dibuat oleh pihak kalimbubunya, maka upacara tersebut tidak dapat dimulai.
Anak beru tua juga berfungsi sebagai anak beru singerana (sebagai pembicara),
karena fungsinya dalam upacara adat sebagai pembicara dan pemimpin keluarga
dalam keluarga kalimbubu dalam konteks upacara adat.
Anak beru cekoh baka tutup, yaitu anak beru yang secara langsung dapat mengetahui
segala sesuatu di dalam keluarga kalimbubunya. Anak beru sekoh baka tutup adalah
anak saudara perempuan dari seorang kepala keluarga. Misalnya Si A seorang laki-
laki, mempunyai saudara perempuan Si B, maka anak Si B adalah anak beru cekoh
baka tutup dari Si A. Dalam panggilan sehari-hari anak beru disebut juga bere-bere
mama.
Anak beru menteri, yaitu anak berunya anak beru. Asal kata menteri adalah dari kata
minteri yang berarti meluruskan. Jadi anak beru minteri mempunyai pengertian yang lebih
luas sebagai petunjuk, mengawasi serta membantu tugas kalimbubunya dalam suatu
kewajiban dalam upacara adat. Ada pula yang disebut anak beru singkuri, yaitu anak berunya
anak beru menteri. Anak beru ini mempersiapkan hidangan dalam konteks upacara adat.
Aksara
Aksara KaroAksara Karo ini adalah aksara kuno yang dipergunakan oleh masyarakat Karo,
akan tetapi pada saat ini penggunaannya sangat terbatas sekali bahkan hampir tidak pernah
digunakan lagi.guna melengkapi cara penulisan perlu dilengkapi dengan anak huruf seperti
o= ketolongen, x= sikurun, ketelengen dan pemantek
Tari tradisional
Suku Karo mempunyai beberapa tari tradisional, di antaranya:
Piso Surit
Lima Serangkai
33

Terang Bulan
Kegiatan Budaya
Merdang merdem = "kerja tahun" yang disertai "Gendang guro-guro aron".
Mahpah = "kerja tahun" yang disertai "Gendang guro-guro aron".
Mengket Rumah Mbaru - Pesta memasuki rumah (adat - ibadat) baru.
Mbesur-mbesuri - "Ngerires" - membuat lemang waktu padi mulai bunting.
Ndilo Udan - memanggil hujan.
Rebu-rebu - mirip pesta "kerja tahun".
Ngumbung - hari jeda "aron" (kumpulan pekerja di desa).
Erpangir Ku Lau - penyucian diri (untuk membuang sial).
Raleng Tendi - "Ngicik Tendi" = memanggil jiwa setelah seseorang kurang tenang
karena terkejut secara suatu kejadian yang tidak disangka-sangka.
Motong Rambai - Pesta kecil keluarga - handai taulan untuk memanggkas habis
rambut bayi (balita) yang terjalin dan tidak rapi.
Ngaloken Cincin Upah Tendi - Upacara keluarga pemberian cincin permintaan dari
keponakan (dari Mama ke Bere-bere atau dari Bibi ke Permain).
Ngaloken Rawit - Upacara keluarga pemberian pisau (tumbuk lada) atau belati atau
celurit kecil yang berupa permintaan dari keponakan (dari Mama ke Bere-bere) -
keponakan laki-laki.
Suku Batak Pakpak
Suku Pakpak adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatera Indonesia dan
tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh, yaki di Kabupaten
Dairi,Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan( Sumatera Utara),
Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabulusalam (Prov.Aceh.
Suku Pakpak terdiri atas 5 subsuku, dalam istilah setempat sering disebut dengan istilah
Pakpak Silima suak yang terdiri dari :
34

1. [[Pakpak Klasen](Kab. Humbang Hasundutan Sumut]
2. Pakpak Simsim (Kab.Pakpak Bharat-sumut)
3. Pakpak Boang (Kab.Singil dan kota Sabulusalam-Aceh)
4. Pakpak Pegagan (Kab.Dairi-sumut)
5. Pakpak Keppas (Kab.Dairi sumut)
Dalam administrasi pemerintahan Suku Pakpak banyak bermukim di wilayah Kabupaten
Dairi di Sumatera Utara yang kemudian dimekarkan pada tahun 2003 menjadi dua kabupaten,
yakni:
1. Kabupaten Dairi (ibu kota: Sidikalang)
2. Kabupaten Pakpak Bharat (ibu kota: Salak)
Suku Pakpak juga berdomisili di wilayah Parlilitan yang masuk wilayah Kabupaten
Humbang Hasundutan dan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari Kabupaten
Tapanuli Tengah. Suku Pakpak yang tinggal di wilayah tersebut menamakan diri sebagai
Pakpak Klasen.
Suku Pakpak juga bermukim di wilayah Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Singkil dan
kota Sabulusalam yang disebut sebagai Pakpak Boang.
Suku Pakpak yang berdiam di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Pakpak Simsim, sedangkan
yang tinggal di kota Sidikalang dan sekitarnya merupakan suku Pakpak Keppas dan yang
bermukim di Sumbul sekitarnya adalah Pakpak Pegagan.
Suku bangsa Pakpak mendiami bagian Utara, Barat Laut Danau Toba sampai perbatasan
Sumatra Utara dengan provinsi Aceh (selatan).
Suku bangsa Pakpak kemungkinan besar berasal dari keturunan tentara kerajaan Chola di
Indiayang menyerang kerajaan Sriwijaya pada abad 11 Masehi.
Marga Pakpak
Anakampun
Angkat
Bako
35

Bancin
Banurea
Berampu
Berasa
Beringin
Berutu
Bintang
Boang Manalu
Capah
Dabutar
Cibro
Gajah Manik
Gajah
Kabeaken
Kesogihen
Kaloko
Kombih
Kudadiri
Lembeng
Lingga
Maha
Maharaja
Manik
Matanari
Meka
Maibang
Padang
Padang Batanghari (BTH)
Pasi
Penarik Pinayungan
Sambo
SARAAN
Sikettang
Sinamo
36

Sitakar
Sitongkir
Solin
Saing
Tendang
Tinambunan
Tinendung
Tumangger
Turutan
Ujung
BAB V
PENUTUP
Bangsa Indonesia mengakui atas keluhuran budaya bangsanya adalah satu hal yang
37

tidak dapat diragukan. Namun pantas disayangkan, perhatian dan penghormatan terhadap
budaya bangsa masih berada pada level yang meragukan. Terhadap budayanya, bangsa ini
terkesan pokoknya masih ada yang mengurusi. Dalam kondisi seperti ini perlahan dan pasti
suatu saat nanti bangsa ini pasti lupa akan budayanya sendiri. Situasi ini menunjukan betapa
krisis budaya telah melanda negeri ini. Maka marilah kita menjaga dan saling menghormati
kebudayaan kita.
Daftar Pustaka
Daftar Pustaka
Bangun, P. 1999. Kebudayaan Batak. Dalam Koentaraningrat (ed.), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djamabatan.
38

Campbell, D.T. 1976. Stereotypes and the Perception of Group Differences. Dalam Hollander, E.P. & Hunt, R.G. (eds.), Current Perspectives in Social Psychology. London: University Press.
Deaux, W. 1981. Social Psychology in the 80th. Monterey: Brooks/Cole Publishing Co.
Ihromi, T. 1980. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: PT Gramedia.
Koeswara, E. 1988. Agresi Manusia. Bandung: PT Eresco.
Koentaraningrat (ed.). 1999. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djamabatan.
Kodiran. 1999. Kebudayaan Jawa. Dalam Koentaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djamabatan.
Masrun, Martono, Haryanto, Hardjito, P., Utami, M.S., Bawani, N., Aritonang, L., & Soetjipto, H.P. 1986. Studi Mengenai Kemandirian pada Penduduk Tiga Suku Bangsa (Jawa, Batak, Bugis). Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
39