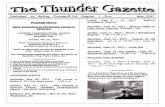jhptump-a-ernawatikh-225-2-babii.pdf
-
Upload
justin-summers -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of jhptump-a-ernawatikh-225-2-babii.pdf
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kulit
Kulit mentah adalah segala macam bentuk kulit yang berasal dari hewan baik yang
diternakkan maupun hewan liar. Kulit yang belum diolah disebut kulit mentah yang dibedakan
menjadi dua kelompok yaitu kulit yang berasal dari hewan besar seperti sapi, kerbau dan hewan
kecil misalnya kambing, domba, kelinci (Daniar 2008 cit Oktafiyani 2009).
Kerusakan-kerusakan yang mempengaruhi kualitas kulit mentah dapat diklasifikasikan
dalam dua golongan yaitu kerusakan yang tinggi pada hewan hidup seperti parasit, umur tua dan
sebab mekanik serta kerusakan pada waktu pengulitan, pengawetan, penyimpanan dan
transportasi. Kulit yang masih segar mudah rusak bila terkena bahan-bahan kimia atau
mikroorganisme. Hal ini disebabkan oleh kandungan air, lemak, mineral serta protein pada kulit
segar tersebut (Daniar 2008 cit Oktafiyani 2009).
Segala cara atau proses untuk mencegah terjadinya lisis atau degradasi komponen-
komponen dalam jaringan kulit secara umum disebut dengan pengawetan kulit. Kulit sebagai
sisa dari pemotongan binatang, mengandung zat-zat makanan atau nutrisi yang sangat tinggi
untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba yang mencemari kulit tersebut akan berkembang biak dan
menghasilkan enzim yang dapat mencerna zat-zat makanan yang ada dalam kulit, akibatnya
beberapa komponen yang ada dalam kulit seperti protein, lemak dan karbohidrat akan
mengalami degradasi (Deasy dan Tancous 1977 cit Bhekti 1988).
B. Pembuatan Rambak
Menurut Oktafiyani (2009) kulit yang digunakan untuk krecek atau rambak adalah kulit
yang sudah tidak dapat digunakan atau sisa-sisa misalnya potongan kulit bagian tepi. Rambak
yang berasal dari kulit kerbau lebih disukai konsumen dibandingkan dengan rambak yang berasal
dari kulit sapi atau kambing. Proses pembuatan rambak baik rambak sayur maupun kerupuk
rambak pada prinsipnya hampir sama yaitu perendaman, proses pengolahan meliputi pencucian,
pengempukan, pengirisan, pemberian bumbu, penjemuran, pengungkepan, penggorengan, dan
proses pembungkusan.
Menurut Bhekti (1988) kerupuk rambak dibuat dengan cara kulit dikeringkan dibawah
sinar matahari dengan lama penjemuran kurang lebih 7 hari. Jika sudah kering kulit disimpan
atau diangkut ke bagian pembuatan. Pada bagian ini, kulit dipotong-potong dengan ukuran besar
dan kemudian direbus dengan air selama kurang lebih 4 sampai 5 jam. Perebusan dapat juga
dilakukan dengan autoclave kurang lebih 1-2 jam. Setelah perebusan kulit selesai, kulit
dibersihkan dari bulu-bulu binatang dan kemudian dipotong-potong dalam ukuran yang lebih
kecil. Selanjutnya kulit dicuci dengan air sampai bersih, dan kemudian dikeringkan. Jika sudah
kering maka kulit direbus (diungkep) dengan lama perebusan 12-15 jam dan kemudian dijemur.
Dari proses yang terakhir diperoleh rambak mentah atau kemudian digoreng untuk memperoleh
rambak matang. Kedua produk ini dikemas dan dijual di pasar dan swalayan.
Menurut Sihombing (1996), kerupuk kulit/rambak mengandung:
1. Energi = 362 Kkal per 100 g
2. Protein = 82,91%
3. Karbohidrat = 0,43%
4. Mineral = 0,04%
5. Natrium Glutamat = 0,8%
C. Timbal (Pb)
Timbal atau lebih dikenal dengan nama timah hitam, dalam bahasa ilmiahnya dinamakan
plumbum, dan logam ini disimbolkan dengan Pb (Palar, 2008). Logam ini sangat popular dan
banyak dikenal karena banyak digunakan di pabrik dan juga banyak menimbulkan keracunan
pada makhluk hidup (Darmono, 1995).
Palar (2008) menyatakan bahwa sifat-sifat khusus timbal yaitu :
a. Merupakan logam lunak, sehingga dapat dipotong dengan pisau atau dengan tangan dan
dapat dibentuk dengan mudah,
b. Merupakan logam yang tahan terhadap korosi atau karat, sehingga sering digunakan
sebagai bahan coating,
c. Mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2,
d. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dari logam biasa,
e. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik,
f. Bila dicampur dengan logam lain akan membentuk logam campuran yang lebih bagus
dari logam murninya.
Pencemaran logam berat dapat terjadi pada daerah lingkungan yang bermacam-macam
dan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu udara, daratan atau tanah, air atau lautan.
Pencemaran udara biasanya terjadi pada proses-proses industri yang menggunakan suhu tinggi,
sedangkan logam seperti Arsen, Cadmium, Raksa, dan Plumbum, adalah logam yang relatif
mudah menguap. Pencemaran daratan dan air biasanaya terjadi karena pembuangan limbah dari
penggunaan logam yang bersangkutan secara tidak terkontrol atau penggunaan bahan yang
mengandung logam itu sendiri (Darmono, 1995).
Timah hitam atau Pb yang ada dalam tatanan udara, terutama sekali bersumber dari
buangan (asap) kendaraan bermotor. Logam ini merupakan sisa pembakaran dari kendaraan
bermotor. Melalui buangan mesin kendaraan tersebut, unsur Pb terlepas sebagian diantaranya
akan membentuk partikulat di udara bebas dengan unsur-unsur lain, sedangkan sebagian lainnya
akan menempel dan diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang jalan (Palar, 2008).
Timbal banyak ditemukan pada tambahan bensin, yaitu tetra ethyl lead (TEL) dan hasil
pembakarannya, baterai, cat, beberapa insektisida, asap rokok, serta limbah industri. Pada asap
rokok ditemukan timbal sekitar 0,017-0,98 mikrogram. Disamping itu, dalam bahan bakar
kendaraan bermotor biasanya ditambahkan pula bahan scavenger, yaitu etilendibromida
(C4H4Br2) dan etilendiklorida (C2H4Cl2). Senyawa ini dapat mengikat residu Pb yang dihasilkan
setelah pembakaran, sehingga di dalam gas buangan terdapat senyawa Pb dengan halogen (Palar,
2008).
Absorbsi timbal paling banyak melalui saluran cerna dan saluran nafas. Timbal dan
kalsium dapat berkompetisi dalam transport lewat mukosa usus karena ada suatu hubungan
timbal balik antara kalsium makanan dan absorbsi timbal. Kekurangan zat besi dilaporkan
meningkatkan absorbsi timbal melalui saluran cerna. Absorbsi timbal yang dihirup berbeda-beda
tergantung dari kadar dan bentuk partikelnya. Kira-kira 90% partikel di udara diabsorbsi melalui
saluran nafas. Keracunan langsung yang terjadi biasanya disebabkan oleh masuknya senyawa Pb
yang larut dalam asam dan inhalasi uap timbal. (Sjamsudin, 1995).
Udara yang mengandung timbal jika dihirup sekitar 50% akan diabsorbsi dari saluran
cerna sekitar 8-10%. Timbal yang diabsorbsi dari saluran cerna, sebagian akan keluar melalui
empedu, sedangkan di dalam usus akan membentuk timbal sulfid yang akan keluar bersama
feses, sebagian dari timbal sulfida yang keluar bersama feses akan mengalami reabsorbsi
kembali ke dalam peredaran darah. Timbal yang beredar dalam darah sebagian besar terikat pada
eritrosit, sedangkan timbal yang masuk dalam tubuh terutama akan diekskresi melalui feses dan
ginjal (Mutschler, 1991).
Keracunan Pb dapat menimbulkan suatu gejala pada setiap orang baik pada anak-anak
maupun dewasa. Gejala keracunan biasanya berbeda antara anak dan orang dewasa, begitu juga
asal dan kontaminasi Pb tersebut. Kerusakan saraf perifer orang dewasa lebih parah daripada
kerusakan saraf pusat yang dialami oleh anak-anak. Gejala pada anak-anak ialah nafsu makan
berkurang, sakit perut, muntah-muntah, kelemahan, sulit berbicara, peka terhadap rangsang, tes
psikologi sangat rendah dan gangguan pertumbuhan. Keracunan Pb pada orang dewasa biasanya
terjadi di tempat mereka bekerja. Tingkat keracunannya berbeda tergantung pada jenis
industrinya. Gejala yang sering ditemukan ialah kepucatan, sakit perut, anemia, hipertensi,
gangguan tidur, adanya garis hitam pada gusi, mual, diare, konstipasi dan sakit kepala (Darmono,
1995).
Palar (2008) mengatakan bahwa timbal dan persenyawaannya banyak digunanakan dalam
berbagai bidang. Dalam industri baterai digunakan sebagai grid yang merupakan suatu
persenyawaan dengan logam bismuth (Pb-Bi) dengan perbandingan (93:7). Timbal juga
digunakan sebagai sekering dan alat listrik. Dalam industri percetakan dan sebagai komponen
aktif pada pambangkit listrik tenaga panas dalam bentuk persenyawaan Pb dengan Te
(Tellurium).
Batas maksimum timbal dalam makanan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi
Nasional No. SNI 7387:2009 tentang batas maksimum cemaran logam dalam makanan adalah
2,0 mg/kg (Anonim, 2009).
D. Spektrofotometri Serapan Atom
Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) merupakan suatu metode pengukuran yang
didasarkan pada jumlah radiasi yang diserap oleh atom-atom bebas bila jumlah radiasi yang
diserap oleh atom-atom bebas dilewatkan melalui sistem yang mengandung atom-atom itu
(Narsito 1992 cit Handayani 2005). Metode serapan sangatlah spesifik dan selektif. Logam-
logam yang membentuk campuran kompleks dapat dianalisis dan selain itu tidak selalu
diperlukan sumber energi yang besar (Khopkar, 1990).
Menurut Hendayana (1994) umumnya bahan bakar yang digunakan adalah propana,
butana, hidrogen dan asetilen, sedang oksidatornya adalah udara, oksigen, N2O dan asetilen.
Logam-logam yang mudah diuapkan seperti Cu, Pb, Zn, Cd, umumnya ditentukan pada suhu
rendah sedangkan unsur-unsur yang tak mudah diatomisasi diperlukan suhu tinggi.
Pada SSA memerlukan lampu katoda spesifik (hollow cathode lamp). Lampu pijar katoda
berongga ini digunakan pada alat SSA karena dapat memberikan garis emisi yang tajam dari
suatu unsur yang sama dengan unsur spesifik tertentu. Lampu ini mempunyai dua elektroda, satu
diantaranya berbentuk silinder dan terbuat dari unsur yang sama dengan unsur yang dianalisis
dan diisi dengan gas mulia bertekanan rendah. Pemberian tegangan pada arus tertentu, maka
logam mulai memijar dan atom-atom logam katodanya akan teruapkan dengan pemercikan.
Elektron pada atom akan tereksitasi kemudian mengemisikan radiasi pada panjang gelombang
tertentu. Tinggi pucak diukur pada garis absorpsi dan garis emisi mempunyai lebar yang sama.
Lampu hollow cathode disebut multi unsur karena dibuat dari bermacam-macam unsur sehingga
memudahkan pekerjaan karena tidak perlu lagi menukar lampu. Misalkan saja (Ca, Mg, Al); (Fe,
Cu, Mn); (Cu, Zn, Pb, Sn); dan (Cr, Co, Cu, Fe, Mn serta Ni) (Khopkar, 1990).
Cara kerja Spektrofotometri Serapan Atom ini adalah berdasarkan atas penguapan larutan
sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom
tersebut mengapsorbsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda (Hollow
Cathode Lamp) yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi
kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya (Khopkar, 1990).
Jika radiasi elektromagnetik dikenakan kepada suatu atom, maka akan terjadi eksitasi
elektron dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi. Maka setiap panjang gelombang memiliki
energi yang spesifik untuk dapat tereksitasi ke tingkat yang lebih tingggi (Anonim 2003 cit Aziz
2007).
Atomisasi
Ada 3 proses metode atomisasi pada SSA antara lain :
a. Atomisasi dengan Nyala
Pada spektrofotometer nyala serapan atom (FAAS=Flame Atomic Absorption
Spectrophotometry), cuplikan disediakan dalam bentuk larutan dan atomisasi dilakukan
dengan memasukkan larutan atau cuplikan ke dalam nyala gas bakar.
Populasi atom di dalam nyala bergantung pada suhu nyala, sedang suhu nyala
bergantung pada jenis dan perbandingan gas bahan bakar dan gas oksidan.
b. Atomisasi dengan Metode Penguapan (Vapor Generation Method).
Metode ini hanya digunakan untuk analisis As (arsen), Bi (bismuth), Sn (timah
putih), Te (tellurium), Ge dan Hg (merkuri). Metode ini menggunakan beberapa pereaksi
kimia dalam prosedur atomisasinya.
c. Atomisasi dengan Furnace
Atomisasi dengan tanur (furnace atomization) dilakukan dengan mengukur batang
listrik karbon (CRA = Carbon Red Atomizer) yang biasanya berbentuk tabung grafit.
Cuplikan diletakkan pada tabung grafit dan arus listrik dialirkan melalui tabung tersebut,
kemudian tabung dipanaskan sampai suhu tinggi sehingga cuplikan akan teratomisasi
(Gunandjar 1985 cit Laely 2007).
Pada atomisasi dengan nyala, larutan sampel diaspirasikan ke suatu nyala dan unsur-
unsur di dalam sampel diubah menjadi uap atom sehingga nyala mengandung atom unsur-unsur
yang dianalisis. Beberapa diantara atom akan tereksitasi secara termal oleh nyala, tetapi
kebanyakan atom tetap tinggal sebagai atom netral dalam keadaan dasar (ground state). Atom-
atom ground state ini kemudian menyerap radiasi yang diberikan oleh sumber radiasi yang
terbuat oleh unsur-unsur yang bersangkutan. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh sumber
radiasi adalah sama dengan panjang gelombang yang diabsorbsi oleh atom dalam nyala.
Absorbsi ini mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan panjang
nyala yang dilalui sinar dan konsentrasi uap atom dalam nyala. Kedua variabel ini sulit untuk
ditentukan tetapi panjang nyala dapat dibuat konstan sehingga absorbansi hanya berbanding
langsung dengan konsentrasi analit dalam larutan sampel (Anonim 2003 cit Aziz 2007).
Aspek kuantitatif dari metode spektrofotometri diterangkan oleh hukum Lambert-Beer,
yaitu:
A = ε . b . c atau A = a . b . c ...........................................(1)
Dimana :
A = Absorbansi
ε = Absorptivitas molar (mol/L)
a = Absorptivitas (g/L)
b = Tebal nyala (nm)
c = Konsentrasi (ppm)
Absorptivitas molar (ε) dan absorptivitas (a) adalah suatu konstanta dan nilainya spesifik
untuk jenis zat dan panjang gelombang tertentu, sedangkan tebal media (sel) dalam prakteknya
tetap (Anonim 2003 cit Aziz 2007).
Instrumentasi Spektrofotometri Serapan Atom
Alat spektrofotometer serapan atom terdiri dari rangkaian dalam diagram skematik
berikut:
Gambar 1. Diagram Spektrometer Serapan Atom atau SSA (Syahputra 2004 cit Aziz 2007).
Keterangan : 1. Sumber sinar
2. Pemilah (Chopper)
3. Nyala
4. Monokromator
5. Detektor
6. Amplifier
7. Meter atau recorder
Komponen-komponen Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) adalah:
1. Sumber Sinar
Sumber radiasi SSA adalah Hollow Cathode Lamp (HCL). Setiap pengukuran dengan
SSA kita harus menggunakan Hollow Cathode Lamp khusus misalnya akan menentukan
konsentrasi tembaga dari suatu cuplikan. Hollow Cathode akan memancarkan energi radiasi
yang sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom.
Hollow cathode lamp (HCL), merupakan sumber radiasi dengan spektra yang tajam dan
mengemisikan gelombang monokromatis. Lampu ini terdiri dari katoda cekung yang silindris
yang terbuat dari unsur yang akan ditentukan atau campurannya (alloy) dan anoda yang terbuat
dari tungsten. Elektroda-elektroda ini berasal dari tabung gelas dengan jendela quartz karena
panjang gelombang emisinya sering berada pada daerah ultraviolet. Tabung gelas tersebut dibuat
bertekanan rendah dan diisi dengan gas inert Ar atau Ne. Beda voltase yang cukup tinggi
dikenakan pada kedua elektroda tersebut sehingga atom gas pada elektoda terionisasi. Ion positif
ini dipercepat ke arah katoda dan ketika menabrak logam yang ada pada katoda dan
menyebabkan elektron terluar pada atom akan tereksitasi ke tingkat elektron yang lebih tinggi.
(Khopkar, 1990). Secara jelas dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram skematik lampu katoda cekung (Khopkar 1990).
Socket
Anode
Hollow Cathode Lamp
Fill Gas Ne or Ar (1-5 torr)
Glass Envelope
2. Atomizer
Sumber atomisasi dibagi menjadi dua yaitu sistem nyala dan sistem tanpa nyala.
Kebanyakan instrumen sumber atomisasinya adalah nyala dan sampel diaspirasikan dalam
bentuk larutan. Sampel masuk ke nyala dalam bentuk aerosol. Aerosol biasa dihasilkan oleh
nebulizer (pengabut) yang dihubungkan ke nyala oleh ruang penyemprot (chamber spray). Jenis
nyala yang digunakan secara luas untuk pengukuran analitik adalah udara-asetilen dan nitrous
oksida-asetilen. Dengan kedua jenis nyala ini, kondisi analisis yang sesuai untuk kebanyakan
analit dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode emisi, absorbsi dan juga
fluorosensi.
3. Monokromator
Monokromator merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan radiasi yang tidak
diperlukan dari spektrum radiasi lain yang dihasilkan oleh Hollow Cathode Lamp.
4. Detektor
Detektor merupakan alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, yang
memberikan suatu isyarat listrik berhubungan dengan daya radiasi yang diserap oleh permukaan
yang peka.
5. Sistem pengolah
Sistem pengolah berfungsi untuk mengolah kuat arus dari detektor menjadi besaran daya
serap atom transmisi yang selanjutnya diubah menjadi data dalam sistem pembacaan.
6. Sistem pembacaan
Sistem pembacaan merupakan bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang
dapat dibaca oleh mata.
Gangguan dalam Spektrofotometri Serapan Atom
Berbagai faktor dapat mempengaruhi pancaran nyala suatu unsur tertentu dan
menyebabkan gangguan pada penetapan konsentrasi unsur (Syahputra 2004 cit Aziz 2007).
1. Gangguan akibat pembentukan senyawa refraktori
Gangguan ini dapat diakibatkan oleh reaksi antara analit dengan senyawa kimia, biasanya
anion, yang ada dalam larutan sampel sehingga terbentuk senyawa yang tahan panas
(refractory). Sebagai contoh fospat akan bereaksi dengan kalsium dalam nyala menghasilkan
pirofospat (Ca2P2O7). Hal ini menyebabkan absorpsi ataupun emisi atom kalsium dalam
nyala menjadi berkurang. Gangguan ini dapat diatasi dengan menambahkan stronsium
klorida atau lanthanum nitrat ke dalam larutan. Kedua logam ini mudah bereaksi dengan
fospat dibanding dengan kalsium sehingga reaksi antara kalsium dengan fospat dapat dicegah
atau diminimalkan. Gangguan ini dapat juga dihindari dengan menambahkan Ethylene
Diamine Tetra Acetic (EDTA) berlebih. EDTA akan membentuk kompleks kelat dengan
kalsium, sehingga pembentukan senyawa refraktori dengan fospat dapat dihindarkan.
Selanjutnya kompleks Ca-EDTA akan terdisosiasi dalam nyala menjadi atom netral Ca yang
menyerap sinar. Gangguan yang lebih serius terjadi apabila unsur-unsur seperti: Al, Ti, Mo,
V dan lain-lain bereaksi dengan O dan OH dalam nyala menghasilkan logam oksida dan
hidroksida yang tahan panas. Gangguan ini hanya dapat diatasi dengan menaikkan
temperatur nyala, sehingga nyala yang umum digunakan dalam kasus semacam ini adalah
nitrous oksida-asetilen.
2. Gangguan ionisasi
Gangguan ionisasi ini biasa terjadi pada unsur-unsur alkali tanah dan beberapa unsur yang
lain. Karena unsur-unsur tersebut mudah terionisasi dalam nyala. Dalam analisis dengan
SSA yang diukur adalah emisi dan serapan atom yang tak terionisasi. Oleh sebab itu dengan
adanya atom-atom yang terionisasi dalam nyala akan mengakibatkan sinyal yang ditangkap
detektor menjadi berkurang. Gangguan ini dapat diatasi dengan menambahkan unsur-unsur
yang mudah terionisasi ke dalam sampel sehingga akan menahan proses ionisasi dari unsur
yang dianalisis.
3. Gangguan fisik alat
Gangguan fisik adalah semua parameter yang dapat mempengaruhi kecepatan sampel sampai
ke nyala dan sempurnanya atomisasi. Parameter-parameter tersebut adalah kecepatan alir
gas. Gangguan ini biasanya diatasi dengan lebih sering membuat kalibrasi atau standarisasi.
Penerapan Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)
Teknik SSA menjadi alat canggih dalam analisis karena ketelitiannya sampai tingkat
runut dan tidak memerlukan pemisahan pendahuluan. Kelebihan kedua adalah kemungkinan
untuk menentukan konsentrasi semua unsur pada konsentrasi runut. Ketiga, sebelum pengukuran
tidak selalu perlu pemisahan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu unsur
lain dapat dilakukan asalkan katoda berongga yang diperlukan tersedia. Non logam yang dapat
dianalisis adalah fosfor dan boron. Logam alkali dan alkali tanah paling baik ditentukan dengan
metode emisi secara fotometri nyala (Khopkar, 1990).
Khopkar (1990) mengatakan bahwa sensitivitas dan batas deteksi merupakan dua
parameter yang sering digunakan dalam SSA. Sensitivitas didefinisikan sebagai konsentrasi
suatu unsur dalam larutan air yang mengabsorbsi 1% dari intensitas radiasi yang datang. Batas
deteksi adalah konsentrasi suatu unsur dalam larutan yang memberikan signal setara dengan dua
kali deviasi standar dari suatu seri pengukuran standar yang konsentrasinya mendekati blangko
atau signal latar belakang. Baik sensitifitas maupun batas deteksi dapat bervariasi dengan
perubahan temperatur nyala dan lebar pita spektra.
Metode SSA dapat digunakan untuk analisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis
kualitatif dapat digunakan satu demi satu dengan menggunakan lampu katoda berongga sesuai
dengan unsur yang diduga. Pada panjang gelombang radiasi sensori (panjang gelombang
karakteristik) untuk unsur yang diduga, diukur serapannya. Jika pada panjang gelombang
tersebut memberikan serapan maka larutan cuplikan tersebut mengandung unsur yang diduga,
tetapi jika tidak, maka larutan cuplikan tersebut tidak mengandung unsur yang diduga. Untuk
analisis kuantitif, kadar logam yang dianalisis dapat dihitung dengan membandingkan serapan
sampel ke dalam persamaan regresi linear kurva baku logam yang dianalisis (Day & Underwood
2002 cit Laely 2007).
E. Validasi Metode Analisis
Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu,
berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi
persyaratan untuk penggunaannya (Harmita, 2004).
Harmita (2004) menyatakan bahwa beberapa parameter analisis yang harus
dipertimbangkan dalam validasi metode analisis adalah :
1. Kecermatan (accuracy)
Kecermatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis
dengan kadar analit yang sebenarnya. Kecermatan dinyatakan sebagai persen perolehan
kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Untuk mencapai kecermatan yang tinggi
hanya dapat dilakukan dengan cara menggunakan peralatan yang sudah dikalibrasi,
menggunakan pereaksi dan pelarut yang baik, pengontrolan suhu, dan pelaksanaannya
yang cermat dan sesuai prosedur.
Kecermatan dilakukan dengan dua cara yaitu metode simulasi (spiked-placebo
recovery) atau metode panambahan baku (standard addition method). Dalam metode
simulasi, sejumlah analit bahan murni ditambahkan ke dalam campuran bahan pembawa
sediaan farmasi (placebo) lalu campuran tersebut dianalisis dan hasilnya dibandingkan
dengan kadar analit yang ditambahkan (kadar yang sebenarnya). Dalam metode
panambahan baku, sampel dianalisis lalu sejumlah tertentu analit yang diperiksa
ditambahkan ke dalam sampel, dicampur dan dianalisis lagi. Selisih kedua hasil
dibandingkan dengan kadar yang sebenarnya adalah hasil yang diharapkan. Dalam kedua
metode tersebut, persen perolehan kembali dinyatakan sebagai rasio antara hasil yang
diperoleh dengan hasil yang sebenarnya. Persen perolehan kembali dapat ditentukan
dengan cara membuat sampel plasebo kemudian ditambah analit dengan konsentrasi
tertentu (biasanya 80%-120% dari kadar analit yang diperkirakan), kemudian dianalisis
dengan metode yang akan divalidasi.
Perhitungan perolehan kembali dapat juga ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:
% Perolehan kembali = Kadar terukur X 100 %
Kadar sebenarnya
2. Keseksamaan (precision)
Keseksamaan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji
individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika prosedur
diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang
homogen.
Keseksamaan diukur sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif.
Keseksamaan dapat dinyatakan sebagai keterulangan (repeatability) atau ketertiruan
(reproducibility). Keterulangan adalah keseksamaan metode jika ilakukan berulang kali
oleh analis yang sama pada kondisi sama dan dalam interval waktu yang pendek.
Ketertiruan adalah keseksamaan metode jika dikerjakan pada kondisi yang berbeda.
Kriteria seksama diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif atau
koefisien variasi 2% atau kurang. Tetapi kriteria ini sangat fleksibel tergantung pada
konsentrasi analit yang diperiksa, jumlah sampel, dan kondisi laboratorium.
Keseksamaan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
a. Hasil analisis adalah x1, x2, x3, x4, ……. Xn
Maka simpangan bakunya adalah:
SD = 1
)( 2
nXXi
b. Simpangan baku relatif atau koefisien variasi (KV) adalah:
RSD % = ௌ௫ܺ 100%
3. Linearitas dan Rentang
Linearitas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon yang
secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik, proporsional
terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Rentang metode adalah pernyataan batas
terendah dan tertinggi analit yang sudah ditunjukkan dapat ditetapkan dengan
kecermatan, keseksamaan, dan linearitas yang dapat diterima.
Linearitas biasanya dinyatakan dalam istilah variasi sekitar arah garis regresi yang
dihitung berdasarkan persamaan metematik data yang diperoleh dari hasil uji analit dalam
sampel dengan berbagai konsentrasi analit. Pengujian matematik dalam pengujian
linearitas adalah melalui persamaan garis lurus dengan metode kuadrat terkecil antara
hasil analisis terhadap konsentrasi analit. Sebagai parameter adanya hubungan linear
digunakan koefisien korelasi r pada analisis regresi linear y = a + bx.
4. Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi
Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi.
Batas deteksi merupakan parameter uji batas.
Batas kuantitasi merupakan parameter pada analisis sebagai kuantitas terkecil
analit dalam sampel yang masih memenuhi kriteria cermat dan seksama.