ELIMINASI PMWaV (PINEAPPLE MEALYBUG … · Tunas apikal mulai tumbuh dengan membentuk daun sejak 1...
Transcript of ELIMINASI PMWaV (PINEAPPLE MEALYBUG … · Tunas apikal mulai tumbuh dengan membentuk daun sejak 1...

ELIMINASI PMWaV
ASSOCIATED-VIRUS
MELALUI PERLAKUAN AIR PANAS DAN RIBAVIRIN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
ELIMINASI PMWaV (PINEAPPLE MEALYBUG WILT
VIRUS) DARI JARINGAN TANAMAN NANAS
MELALUI PERLAKUAN AIR PANAS DAN RIBAVIRIN
MIMI SUTRAWATI
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2009
EAPPLE MEALYBUG WILT-
) DARI JARINGAN TANAMAN NANAS
MELALUI PERLAKUAN AIR PANAS DAN RIBAVIRIN

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN
SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ELIMINASI PMWaV (PINEAPPLE
MEALYBUG WILT-ASSOCIATED VIRUS) DARI JARINGAN TANAMAN NANAS MELALUI PERLAKUAN AIR PANAS DAN RIBAVIRIN adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Februari 2009
Mimi Sutrawati
NRP A451060061

ABSTRACT
MIMI SUTRAWATI. Elimination of PMWaV (Pineapple Mealybug Wilt-
associated Virus) at Pineapple Tissue by Hot Water Treatment and Ribavirin. Under direction of GEDE SUASTIKA and SOBIR.
Mealybug wilt of pineapple (MWP) is the devastating disease found in all the major pineapple growing regions of the world. The disease is characterized by severe tip dieback, downword curving of the leaf margins, reddening, and wilting of the leaves that can cause total collapse of the plant. Closterovirus particles were detected in both MWP symptomatic and asymptomatic pineapple worldwide. The particles, referred to as Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus-1 and PMWaV-2. Both viruses are mealybug transmitted. Two species of mealybug, the pink mealybug Dysmicoccus brevipes (Cockerell), and the grey mealybug Dysmicoccus neobrevipes
(Beardsley) have been associated with MWP. One method for managing MWP disease is rogue symptomatic plant, but this method remain PMWaV at asymptomatic plant. Use of pesticide to control mealybug and ants is not efficient and high cost. The research was conducted to develop elimination method for PMWaV-free plant by hot water treatment and ribavirin. PMWaV infected plant (leave, stem, crown) were given two hot water treatment consisting of 35 ºC for 24 hour as pre-treatment followed immediately by hot water treatment either 56 ºC for 60 minute or 58 ºC for 40 minute in a water bath. Infected plant without hot water treatment as positive control, and healthy plant without hot water treatment as negative control. Ribavirin were added to medium culture 10 mg/l medium. PMWaV infection can be eliminated from propagative material through hot water treatment 58 ºC 40 minute in a water bath without decrease propagative material viability.
Keyword: Pineapple mealybug wilt-associated virus, heat treatment, ribavirin.

RINGKASAN MIMI SUTRAWATI. Eliminasi PMWaV (Pineapple Mealybug Wilt-associated
Virus) dari Jaringan Tanaman Nanas melalui Perlakuan Air Panas dan Ribavirin. Dibimbing oleh GEDE SUASTIKA dan SOBIR.
Penyakit layu nanas merupakan penyakit yang sangat merugikan di sentra budidaya nanas di seluruh dunia. Gejala penyakit layu berupa mati ujung daun, daun menggulung, kemerahan, dan kelayuan daun dapat menyebabkan penurunan hasil panen, bahkan kematian tanaman. Penyakit layu nanas berasosiasi dengan Pineapple
Mealybug Wilt-associated Virus (PMWaV) dan ditularkan oleh Dysmicoccus brevipes
dan D. neobrepives (Hemiptera: Pseudococcidae). Pengendalian penyakit dengan eradikasi tanaman bergejala tidak menjamin lahan bebas dari sumber inokulum, karena infeksi PMWaV juga dapat terjadi pada tanaman tanpa menimbulkan gejala. Penggunaan pestisida untuk pengendalian kutu putih tidak efisien dan meningkatkan biaya produksi. Penggunaan varietas tahan belum dapat dilakukan karena hingga saat ini belum ada varietas nanas yang tahan terhadap kutu putih dan PMWaV. Salah satu cara pengendalian yang perlu dikaji yaitu dengan penggunaan bibit bebas PMWaV. Penggunaan bibit bebas PMWaV akan menekan jumlah sumber inokulum PMWaV di lapang sehingga menurunkan laju penyebaran penyakit, dan pada akhirnya mengurangi resiko kehilangan hasil, serta meningkatkan peluang bagi petani untuk membudidayakan nanas dengan ratoon crop sampai beberapa generasi. Sistem perbanyakan massal nanas dapat dilakukan dengan cara teknik kultur jaringan in vitro, dan stek. Kedua cara ini dapat menghasilkan bibit nanas dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dan seragam. Penelitian ini bertujuan mengeliminasi PMWaV pada bahan perbanyakan bibit nanas melalui perlakuan air panas dan ribavirin untuk memperoleh bibit bebas PMWaV. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan metode eliminasi PMWaV dari jaringan tanaman nanas untuk memproduksi bibit bebas PMWaV. Perbanyakan bibit nanas bebas PMWaV secara massal dengan metode kultur jaringan dan stek diharapkan dapat menghasilkan bibit bebas PMWaV dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat sehingga memungkinkan untuk dapat segera diaplikasikan di lapang sebagai langkah pengendalian penyakit layu nanas.
Penelitian ini meliputi tiga kegiatan yaitu: (1) Eliminasi PMWaV melalui perlakuan air panas dan ribavirin pada planlet; (2) Eliminasi PMWaV melalui perlakuan air panas dan ribavirin pada eksplan; dan (3) Eliminasi PMWaV melalui perlakuan air panas pada stek nanas.
Pengamatan penyakit layu pada tanaman nanas telah dilakukan di sentra produksi nanas di Jawa Barat yaitu di Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang. Gejala awal penyakit layu dimulai dengan perubahan warna daun terutama pada daun bagian tengah menjadi merah. Perkembangan gejala selanjutnya adalah semakin banyak daun yang berwarna merah, terutama daun bagian bawah sampai pada akhirnya semua daun menjadi merah. Kebugaran daun menurun sehingga tanaman layu dan terlihat nekrotik pada ujung daun. Bila sudah kering, umumnya tepi daun menggulung ke bawah dan layu. Kejadian penyakit layu cenderung lebih tinggi pada

sistem budidaya ratoon crop dibandingkan plant crop. Kutu putih ditemukan baik pada tanaman bergejala layu maupun tanaman sehat. Kutu putih ditemukan baik pada tanaman bergejala layu maupun tanaman sehat. Kutu putih mengkoloni tanaman nanas terutama pada bagian pangkal daun, crown, atau pada akar.
Perlakuan air panas sebagai teknik eliminasi virus tidak dapat diaplikasikan pada planlet karena lemahnya jaringan planlet untuk menerima perlakuan suhu tinggi. Planlet nanas diduga sangat sensitif terhadap ribavirin, sehingga tidak mampu tumbuh pada media dengan ribavirin 10 mg/l.
Tunas apikal mulai tumbuh dengan membentuk daun sejak 1 msi, sedangkan tunas lateral belum menunjukkan tanda pertumbuhan tunas. Pertumbuhan eksplan tunas lateral mulai terjadi sejak 2 msi ditandai dengan terjadinya pembengkakan mata tunas dan penebalan pada mata tunas sehingga terlihat berwarna gelap. Eksplan berumur 4 msi mata tunas dari eksplan tunas lateral mulai pecah dan berwarna hijau menunjukkan calon tunas akan muncul. Selama 12 msi pada media B2N1, eksplan tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti namun mata tunas tetap hijau, menandakan eksplan tersebut hidup. Terhambatnya pertumbuhan eksplan dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain ketidak sesuaian jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh, maupun penurunan viabilitas eksplan. Stek yang disemai pada media sekam bakar mulai memperlihatkan pertumbuhan tunas sejak 2 minggu setelah semai (mss). Perlakuan air panas 56°C selama 60 menit menyebabkan penurunan daya tumbuh stek daun dan batang. Sedangkan perlakuan air panas 58°C 40 menit tidak mengurangi viabilitas stek. Perlakuan air panas 58°C selama 40 menit pada tanaman sakit mampu menekan infeksi PMWaV-2. Perlakuan air panas 56°C selama 60 menit pada tanaman sakit tidak berpengaruh nyata terhadap infeksi PMWaV-1 maupun PMWaV-2. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa perlakuan air panas 58 ºC selama 40 menit memenuhi persyaratan dalam ”treatment window” karena perlakuan tersebut mampu menekan infeksi PMWaV-2 pada stek tanpa daya tumbuh dan vigor stek.

@ Hak cipta milik IPB, tahun 2009
Hak Cipta dilindungi Undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan
atau menyebutkan sumber
a. Penyutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis
dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

ELIMINASI PMWaV (PINEAPPLE MEALYBUG WILT-
ASSOCIATED-VIRUS) DARI JARINGAN TANAMAN NANAS
MELALUI PERLAKUAN AIR PANAS DAN RIBAVIRIN
MIMI SUTRAWATI
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada Program Studi Entomologi-Fitopatologi
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2009

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Ir. Giyanto, M.Si.

Judul Penelitian : Eliminasi PMWaV (Pineapple Mealybug Wilt-associated
Virus) dari Jaringan Tanaman Nanas Melalui Perlakuan Air Panas dan Ribavirin
Nama Mahasiswa : Mimi Sutrawati NRP : A451060061
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Gede Suastika, M.Sc. Dr. Ir. Sobir, M.Si Ketua Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Entomologi-Fitopatologi
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Sri Hendrastuti Hidayat, M.Sc Tanggal Ujian: 18 Februari 2009
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
Tanggal lulus: 23 Februari 2009

PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Eliminasi PMWaV (Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus) dari Jaringan Tanaman Nanas Melalui Perlakuan Air Panas dan Ribavirin”. Penelitian dan penulisan tesis dilaksanakan sejak Agustus 2007 hingga Januari 2009. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program studi Entomologi-Fitopatologi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Gede Suastika, M.Sc. dan Dr. Ir. Sobir, M.Si., selaku komisi pembimbing atas bimbingan, saran, dan masukannya selama penelitian hingga penulisan tesis ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Giyanto, M.Si., selaku penguji luar komisi atas koreksi, saran, dan kritiknya.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Laboratorium Virologi Tumbuhan Departemen Proteksi Tanaman Faperta IPB atas izin penggunaan bahan dan peralatan laboratorium yang digunakan selama penelitian. Terimakasih kepada Kepala Pusat Kajian Buah Tropika (PKBT) IPB atas bantuan dana penelitian dan izin penggunaan Laboratorium Kultur Jaringan Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (PKBT) serta terimakasih kepada Kepala Kebun Percobaan Tajur II atas izin penggunaan rumah kasa di kebun percobaan Tajur II. Terimakasih juga kepada Tuti Legiastuti, Rai Maya Temaja, Irwan Lakani, Endang Opriana, Devi Agustina, Ifa Manzilla dan teman-teman di Laboratorium Virologi Tumbuhan, terimakasih kepada Sulassih, Pipit, dan teman-teman di Laboratorium Kultur Jaringan PKBT, serta kepada Bapak Ibram dan Bu Yuyun di kebun percobaan PKBT Tajur II atas bantuan dan kerjasamanya selama pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga kepada Bu Rita Noveriza yang telah membantu penulis dalam pengolahan data dengan analisis statistik.
Ungkapan terima kasih yang tulus untuk kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sudardjat dan Ibu Dalemawati atas perhatian, kasih sayang, doa yang tak pernah henti, serta dukungan untuk selalu berjuang mengejar impian dan cita-cita putra-putrinya. Terimakasih kepada adik-adikku tersayang Sari, Neli, dan Medi, terima kasih juga pada Kakak-kakakku Renville, Dedi, Anto, Nozy atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang selalu menyertaiku. Ungkapan terima kasih yang tulus untuk Deden Dani, SP. yang selalu membantu selama pelaksanaan penelitian, selalu memberi dukungan, pengertian dan doa selama ini. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama penelitian hingga penulisan tesis ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman semua. Amin.
Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan.
Bogor, Februari 2009
Mimi Sutrawati

RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Curup, Bengkulu pada tanggal 23 Mei 1982 dari ayah Sudardjat dan ibu Dalemawati sebagai putri sulung dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Umum di SMUN 1 Curup pada tahun 2000. Pada tahun yang sama penulis diterima di Departemen Proteksi Tanaman IPB melalui jalur USMI. Pendidikan Sarjana diselesaikan oleh penulis pada September 2004. Sejak Januari 2005 penulis bekerja sebagai staf pengajar di Program Studi Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Tahun 2006 penulis melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Entomologi-Fitopatologi dengan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana dari DIKTI.
Bogor, Februari 2009
Penulis

DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xvi
PENDAHULUAN .................................................................................... 1
Latar Belakang ................................................................................ 1 Tujuan penelitian ............................................................................ 3
Manfaat Penelitian .......................................................................... 3
TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 4
Nanas (Ananas comosus L. (Merr.)) ................................................ 4 Perbanyakan Tanaman Nanas .......................................................... 5 Kultur Jaringan ........................................................................ 6 Stek (sectioning) ..................................................................... 6 Gejala Penyakit Layu dan Kisaran Inang PMWaV ......................... 7 Karakteristik PMWaV ...................................................................... 9 Kutu Putih dan Penularan PMWaV .................................................. 10 Pengendalian Penyakit Layu ............................................................. 11 Eliminasi Virus dengan Perlakuan Panas ............................... 12 Eliminasi Virus dengan Perlakuan Ribavirin .......................... 13
BAHAN DAN METODE ......................................................................... 15
Tempat dan Waktu Penelitian .......................................................... 15 Metode Penelitian ........................................................................... 15 Pengamatan Penyakit Layu dan Kutu Putih di Lapang ............ 15
Eliminasi PMWaV melalui Perlakuan Air Panas dan Ribavirin pada Planlet ............................................................................. 15 Penyiapan Planlet Nanas ............................................... 15 Inokulasi PMWaV pada Planlet ................................... 16 Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas dan Ribavirin ....................................................................... 16
Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas dan Ribavirin pada Eksplan ............................................................................. 17
Penyiapan Bahan Tanaman Nanas ................................ 17 Perlakuan Air Panas ...................................................... 17
Kultur Jaringan Nanas ................................................... 18 Eliminasi PMWaVdengan Perlakuan Air Panas pada Bahan Stek .......................................................................................... 18 Penyiapan Bahan Tanaman Nanas ................................ 18
Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas .......... 18 Penanaman Stek ............................................................ 18 Verifikasi Infeksi PMWaV dengan Tissue Blot Immunoassay . 19

HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................. 21
Penyakit Layu Nanas di Sentra Produksi Nanas Jawa Barat ........... 21 Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas dan Ribavirin pada planlet .............................................................................................. 23 Pengaruh Perlakuan Air Panas terhadap Pertumbuhan Planlet . 23 Pengaruh Perlakuan Ribavirin terhadap Pertumbuhan Planlet .. 24 Pengaruh Perlakuan Air Panas dan Ribavirin terhadap Infektifitas PMWaV pada Planlet ........................................... 26 Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas dan Ribavirin pada eksplan ............................................................................................ 27 Pengaruh Perlakuan Air Panas terhadap Daya Tumbuh Eksplan 27 Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas pada Bahan Stek .. 29 Keadaa Umum .......................................................................... 29 Pengaruh Perlakuan Air Panas terhadap Daya Tumbuh Stek ... 30 Pengaruh Perlakuan Air Panas terhadap Infektifitas PMWaV .. 33 KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 38 Kesimpulan ..................................................................................... 38 Saran ............................................................................................... 38
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 39
LAMPIRAN .............................................................................................. 43

DAFTAR TABEL
Halaman 1 Pengaruh perlakuan air panas terhadap pertumbuhan planlet nanas selama 7 hari setelah perlakuan air panas .............................................. 23 2 Pengaruh perlakuan ribavirin terhadap pertumbuhan planlet nanas
selama 11 hari setelah perlakuan ribavirin ............................................. 25
3 Persentase daya tumbuh stek nanas berumur 7 minggu setelah semai (mss) ...................................................................................................... 33 4 Persentase stek terinfeksi PMWaV setelah mendapat perlakuan air panas . 36

DAFTAR GAMBAR
Halaman
1 Struktur kimia ribavirin........................................................................... 14
2 Stek daun (a) dan stek batang (b) tanaman nanas .................................. 19
3 Gejala penyakit layu pada tanaman nanas di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gejala dicirikan dengan daun berwarna kuning kemerahan (a), kebugaran daun menurun sampai layu (b) ujung daun mengalami nekrotik (c), dan tepi daun menggulung ke bawah (d). ........................................................................................... 21
4 Hasil pengamatan koloni kutu putih (Dysmicoccus brevipes
Cockerell) pada pangkal batang (a) dan perakaran (b) tanaman nanas di Lapang ...................................................................................................... 22 5 Pertumbuhan eksplan tunas apikal (a) dan tunas lateral (b) berumur 1
minggu setelah inisiasi (msi) ................................................................. 27 6 Daun induk pada stek daun dengan perlakuan panas (a) dan tanpa perlakuan panas (b) ................................................................................ 30 7 Stek daun (a), stek batang (b), dan stek crown (c) berumur 2 mst; stek daun (d), stek batang (e), crown (f) berumur 4 mst; stek daun (g), stek batang (h), crown (i) berumur 5 mst. ...................................................... 31 8 Bibit nanas berumur 2 mst (a) dan 3 mst (b) .......................................... 33 9 Membran hasil deteksi PMWaV-1 dengan metode TBIA. Daun stek kontrol positif (K+), daun stek kontrol negatif (K-), daun stek tanaman sakit yang diberi perlakuan suhu 56 ºC (H56), daun dari stek tanaman sakit yang diberi perlakuan air panas 58 ºC (H58). Sinyal berwarna ungu (ditunjuk oleh tanda panah) pada jaringan pembuluh menunjukkan bahwa sampel daun positif terinfeksi PMWaV-1. ........................................... 34 10 Membran hasil deteksi PMWaV-2 dengan metode TBIA. Daun stek kontrol positif (K+), daun stek kontrol negatif (K-), daun stek tanaman sakit yang diberi perlakuan suhu 56 ºC (H56), daun dari stek tanaman sakit yang diberi perlakuan air panas 58 ºC (H58). Sinyal berwarna ungu (ditunjuk oleh tanda panah) pada jaringan pembuluh menunjukkan bahwa sampel daun positif terinfeksi PMWaV-2 .............................................. 35

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1 Komponen Larutan Media Inisiasi .......................................................... 44
2 Komponen Larutan Media B2N1............................................................ 45

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tanaman nanas (Ananas comosus L. (Merrill)) cv. Smooth Cayenne
merupakan tanaman buah tropika yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Produksi
nanas Indonesia pada tahun 2000 yaitu 399,299 ton meningkat menjadi 1.427.781 ton
pada tahun 2003 (Deptan 2008). Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,
nanas merupakan komoditas ekspor yang penting. Volume ekspor nanas kaleng
Indonesia mencapai 11% dari total ekspor dunia dan menempati urutan ketiga setelah
Thailand dan Filipina (CABI 2005). Potensi pengembangan produksi nanas Indonesia
dapat lebih ditingkatkan jika faktor-faktor pembatas produksi nanas dapat
diminimalkan.
Salah satu kendala utama dalam produksi nanas adalah serangan penyakit layu
nanas yang juga telah menjadi masalah serius dalam budidaya nanas di seluruh dunia.
Penyakit layu nanas berasosiasi dengan infeksi Pineapple mealybug wilt-associated
virus (PMWaV) (Tryono 2006; Sether & Hu 2002a). Di lapangan, virus ini dengan
efektif dapat ditularkan oleh dua spesies kutu putih yaitu Dysmicoccus brevipes
Cockerell dan D. neobrevipes Cockerell (Hemiptera : Pseudococcidae) (Sether et al.
1998).
Penyakit layu nanas pertama kali dilaporkan tahun 1910 di Hawaii dan disebut
dengan pineapple mealybug wilt disease karena pada tanaman yang menunjukkan
gejala umumnya terkolonisasi kutu putih (mealybug) (Carter 1933). Namun kemudian
diketahui bahwa gejala layu tersebut terutama akibat infeksi PMWaV (Sether & Hu
2002a). Penyakit layu telah dilaporkan menyebabkan banyak kerugian pada industri
nanas dunia seperti di Hawaii mencapai 35% (Sether & Hu 2002b) atau di Kuba
mencapai 40% (Anonim 1989 dalam Borroto et.al. 2007). Di Indonesia, penyakit ini
telah menjadi masalah serius di sentra-sentra produksi nanas nasional. Kejadian
penyakit layu di beberapa pertanaman nanas di Blitar sudah mencapai 90%, Subang
60-70%, Simalungun 50-60%, dan Bogor 50% (Hutahayan 2006). Penyakit layu
menyebabkan petani mengalami gagal panen, karena buah yang dihasilkan berukuran
sangat kecil dan matang prematur. Rata-rata bobot buah dari tanaman bergejala layu
35% lebih rendah dari pada bobot buah tanaman bebas virus, dan 30% lebih rendah
dari pada tanaman terinfeksi PMWaV-1 (Sether & Hu 2002b).

Beberapa teknik pengendalian telah diterapkan untuk mengurangi kejadian
penyakit layu di lapang, namun belum dapat memberikan hasil yang diharapkan.
Pengendalian penyakit layu dengan eradikasi tanaman sakit di lapang ternyata tidak
menjamin lahan tersebut terbebas dari sumber inokulum karena tidak semua tanaman
terinfeksi PMWaV menunjukkan gejala. Pengendalian populasi kutu putih dan semut
juga kurang berhasil. Simbiosis semut dengan kutu putih (Rohrbach et at. 1988;
Beardsley 1996) dan tempat hidup (nice) kutu putih di bagian yang tertutup dari
tanaman nanas (di ketiak daun dan pangkal batang di bawah tanah) (Beardsley 1996)
menyebabkan parasit atau predator alami (maupun yang diinnundasi) tidak dapat
bekerja optimal dan tetap menyisakan populasi kutu putih yang potensial
menyebarkan PMWaV. Sedangkan pengendalian kutu putih dengan aplikasi
insektisida kimia kurang berhasil karena tubuh serangga ini diselimuti lilin.
Pengendalian dengan varietas tahan juga belum dapat dilakukan karena semua
varietas tanaman nanas di Indonesia rentan terhadap PMWaV maupun kutu putih
(Hidayat 2006). Salah satu cara pengendalian penyakit layu yang memberi harapan
serta perlu dikaji adalah penggunaan bibit bebas virus.
Penggunaan bibit bebas PMWaV akan menekan jumlah sumber inokulum
PMWaV di lahan sehingga peluang penyebarannya menjadi kecil meskipun ada
serangga vektor. Perkembangan penyakit layu pada 3 bulan pertama pertumbuhan
tanaman nanas dapat menyebabkan penurunan bobot buah sampai 55% ( Sether & Hu
2002b). Dengan demikian, penggunaan bibit bebas PMWaV diharapkan dapat
mencegah terjadinya penyakit layu pada fase awal pertumbuhan tanaman nanas
sehingga dapat mengurangi resiko kehilangan hasil akibat penyakit layu. Rendahnya
laju penyebaran penyakit layu akan mengurangi resiko kehilangan hasil dan
memberikan banyak peluang bagi petani untuk membudidayakan nanas dengan
tanaman ratoon sampai beberapa generasi.
Umumnya perbanyakan tanaman nanas dilakukan secara vegetatif
menggunakan tunas akar, tunas batang, tunas tangkai buah, tunas dasar buah, stek
batang, dan mahkota (crown). Petani biasanya menggunakan bibit yang berasal dari
anakan dengan status kesehatan bibit yang tidak diketahui, dan tidak seragam. Selain
itu, ketersediaan bibit dari anakan sangat terbatas yaitu dua sampai sepuluh anakan
per tanaman per tahun.

Sistem perbanyakan massal tanaman nanas dapat dilakukan melalui teknik
kultur jaringan in vitro dan stek. Kedua cara ini dapat menghasilkan bibit nanas yang
seragam dalam jumlah besar dan dalam waktu relatif singkat. Cara perbanyakan
tanaman ini apabila dikombinasikan dengan metode eliminasi PMWaV akan dapat
digunakan untuk menghasilkan bibit nanas bebas virus. Pada penelitian ini dilakukan
eliminasi PMWaV dari jaringan tanaman dengan perlakuan air panas atau ribavirin
pada kultur jaringan dan stek.
Dalam penelitian ini eliminasi PMWaV dilakukan dengan termoterapi yaitu
perlakuan air panas, dan kemoterapi yaitu dengan perlakuan ribavirin. Banyak virus
yang dapat dieliminasi dari tanaman inangnya dengan cara perlakuan panas (heat
treatment). Eliminasi PMWaV-1 dapat dilakukan dengan cara crown tanaman nanas
yang terinfeksi di beri pre-treatment pada suhu 35°C selama 24 jam kemudian
dilanjutkan dengan suhu 58°C selama 40 menit atau 56°C selama 60 menit (Sether et
al. 2001). Selain perlakuan air panas, eliminasi virus dapat dilakukan dengan cara
kemoterapi menggunakan ribavirin. Penambahan 10-50 mg/L ribavirin ke dalam
media kultur efektif mencegah infeksi beberapa virus yaitu PVX, PVY, PVS, dan
PVM pada kentang dan tembakau, juga mencegah CMV pada kultur meristem
Nicotiana rustika (Hadidi et al. 1998).
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeliminasi PMWaV pada bahan
perbanyakan bibit nanas melalui perlakuan air panas dan ribavirin untuk memperoleh
bibit bebas PMWaV.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan metode eliminasi PMWaV
dari jaringan tanaman nanas untuk memproduksi bibit bebas PMWaV. Penggunaan
bibit bebas PMWaV diharapkan dapat menekan kejadian penyakit layu nanas di
lapang dan meningkatkan produksi nanas di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
Nanas (Ananas comosus L. (Merr.))
Nanas dibudidayakan untuk dikonsumsi sebagai buah segar maupun buah
kaleng. Nanas merupakan penghasil bromelein, enzim yang diperlukan dalam industri
farmasi juga sebagai agen pelunak daging dalam proses pengolahan makanan. Buah
ini merupakan komoditas ekspor yang penting bagi Indonesia. Indonesia merupakan
produsen nanas menempati posisi ketiga di Asia Tenggara setelah Thailand dan
Filipina (CABI 2005).
Tanaman nanas berupa herba tahunan atau dua tahunan dengan tinggi 50-150
cm, terdapat tunas merayap pada bagian pangkalnya. Daun berkumpul dalam roset
akar dan pada bagian pangkalnya melebar menjadi pelepah. Helaian daun berbentuk
pedang, tebal, panjang 80-120 cm, lebar 2-6 cm, ujung lancip menyerupai duri. Bunga
majemuk tersusun dalam bulir yang sangat rapat, letaknya terminal dan bertangkai
panjang. Buahnya buah buni majemuk, bulat panjang, berwarna hijau, jika masak
warnanya menjadi kuning. Tanaman nanas (Ananas comosus (L.) Merr. merupakan
anggota family Bromeliaceae dari kelas Angiospermae (Dalimartha, 2004).
Tanaman nanas membentuk suatu roset yang lambat laun daun-daunnya yang
lebih besar mencapai ukuran yang mencerminkan pertumbuhan normal. Setelah itu,
ukuran daun konstan dan jika meristem pucuknya telah menghasilkan 70-80 lembar
daun, dengan kecepatan satu lembar daun per minggu selama perode pertumbuhan
yang cepat itu, meristem pucuk itu berubah menjadi bongkol bunga dan bongkol
tanaman, yaitu poros tengah yang memanjang ke bunga dan buah (Wee &
Thongtham, 1997).
Tanaman nanas merupakan herba perennial monokotil. Setelah pematangan
buah pertama, pada tanaman berkembang tunas baru dari pucuk aksilar, yang
kemudian berkembang dan mampu menghasilkan buah. Pada budidaya nanas
komersial, sebaiknya tanaman nanas dipelihara hanya 2-3 generasi, sehingga petani
dapat memperoleh buah yang seragam dengan kualitas yang baik (Bartholomew et. al
2003). Selanjutnya harus dilakukan penanaman bibit baru secara regular.
Sistem budidaya nanas dengan cara pemeliharaan tanaman sampai pemanenan
kedua dan seterusnya setelah pemanenan pertama disebut ratoon crop. Sedangkan

cara budidaya dengan penggunaan bibit baru pada awal masa tanam disebut plant
crop. Sistem ratoon crop sangat penting dalam manajemen budidaya nanas karena
dapat menekan biaya produksi daripada melakukan penanaman ulang atau plant crop
(Bartholomew et. al 2003).
Perbanyakan Tanaman Nanas
Perbanyakan tanaman nanas umumnya dilakukan dengan menggunakan
mahkota buah (crown), tunas akar (sucker), tunas batang (shoot), tunas tangkai buah
(hapas), tunas dasar buah (slips), dan stek batang (Collin 1960). Petani biasanya
menggunakan bibit dari tunas-tunas tersebut dengan status kesehatan bibit yang tidak
diketahui, dan tidak seragam. Sejumlah besar crown dapat dengan mudah
dikumpulkan bersamaan dengan pemanenan buah. Namun, crown tidak dapat
dijadikan sebagai bibit jika produksi nanas ditujukan untuk pemasaran buah segar.
Hal ini dikarenakan pada produksi nanas untuk pemasaran buah segar buah dijual
utuh dengan mahkota buah yang masih melekat pada buah nanas. Hapas dan slips
merupakan diferensiasi tunas-tunas lateral yang berkembang pada tangkai buah
(peduncle) selama pembentukan buah (Bartholomew et al. 2003). Biasanya hapas
dan slips dipanen dari tanaman beberapa minggu setelah pemanenan buah, sehingga
membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga kerja dibandingkan penanganan crown.
Tidak semua varietas nanas menghasilkan slips, sedangkan keberadaan slips dalam
jmlah besar pada tanaman dapat mereduksi rata-rata bobot buah (Collin 1960);
(Wang & Chang 1960 dalam Bartholomew et al. 2003). Sucker tumbuh pada
tanaman nanas beberapa minggu setelah pemanenan buah, sehingga membutuhkan
tenaga kerja untuk pemanenan dengan cara memotong sucker dari tanaman induk.
Kelemahan lain penggunaan sucker sebagai bibit yaitu adanya diferensiasi
pembungaan sehingga tanaman dari bibit sucker menghasilkan buah yang berukuran
lebih kecil (Bartholomew et al. 2003). Ketersediaan bibit dari mahkota buah (crown),
tunas akar (sucker), tunas batang (shoot), tunas tangkai buah (hapas), tunas dasar
buah (slips) sangat terbatas yaitu dua sampai sepuluh tunas per tanaman per tahun
(Bartholomew et al. 2003); Smith et al. (2002).
Ketersediaan bibit merupakan faktor penting dalam produksi nanas. Sistem
budidaya nanas komersial membutuhkan 60000 bibit nanas per hektar (Bartholomew
et al. 2003). Oleh karena itu, berbagai penelitian dilakukan dalam rangka

pengembangan metode perbanyakan bibit nanas untuk mendapatkan bibit nanas
dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Sistem perbanyakan massal nanas
dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan in vitro dan stek (sectioning)
(Bartholomew et al. 2003).
Kultur Jaringan
Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bahan tanaman yaitu
sel, kelompok sel, jaringan, dan organ serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik
sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi
tanaman lengkap (Gunawan, 1988). Tujuan dari teknik kultur jaringan antara lain
menciptakan tanaman baru bebas penyakit, memperbanyak tanaman yang sukar
diperbanyak secara seksual dan memproduksi tanaman dalam jumlah besar dalam
waktu singkat (Katuuk, 1989). Perbanyakan nanas dengan kultur jaringan dapat
menghasilkan 1 juta tanaman dari satu tunas aksilar selama 2 tahun (Pannetier &
Lanaud 1976 dalam Bartholomew et al. 2003).
Aplikasi kultur jaringan untuk perbanyakan dan pengembangan nanas meliputi
mikropropagasi melalui proliferasi tunas aksilar, proliferasi tunas adventif, regenerasi
dari kultur kalus, konservasi plasma nutfah in vitro serta kultur protoplas, ovule, dan
anter (Bartholomew et al. 2003). Menurut Roostika dan Mariska (2003) sistem
regenerasi tanaman nanas pada kultur in vitro dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu
organogenesis dan embriogenesis.
Eksplan yang umum digunakan untuk inisiasi kultur nanas yaitu tunas aksilar
yang dipotong dari crown (Bartholomew et al. 2003). Tunas aksilar tersebut
kemudian ditanam pada media padat Murashige & Skoog (1962) (MS) dengan
penambahan sitokinin, biasanya berupa benzyladenine (BA) dengan konsentrasi
antara 2-5 mg/l media. Ketika tunas telah tumbuh dan bermultiplikasi, maka eksplan
dipindahkan ke media MS padat yang mengandung auksin, misalnya indole butyric
acid (IBA) dengan konsentrasi 2-5 mg/l media atau ke media tanpa ZPT untuk
pembentukan akar (Bartholomew et al. 2003). Penambahan ZPT eksogen BA (2
mg/L) dan napthalene acetic acid /NAA ( 2 mg/L) merupakan konsentrasi terbaik
untuk menginduksi pembentukan nodul pada bonggol nanas, dan selanjutnya terjadi
akumulasi N6 (2-isopentenyl) adenin (iP) dan IAA untuk menginduksi organogenesis
tunas (Auer et al. 1999).

Stek (Sectioning)
Salah satu alternatif perbanyakan massal bibit nanas yang dapat mengatasi
kebutuhan bibit nanas adalah dengan stek (sectioning) (Bartholomew et al. 2003;
PKBT 2008). Teknik sectioning dalam sistem perbanyakan nanas merupakan cara
baru yang belum umum digunakan. Teknologi perbanyakan massal dengan
sectioning, antara lain dengan stek daun, dan stek batang dapat lebih mudah
ditransfer ke petani, karena tidak membutuhkan keahlian khusus dan biayanya relatif
murah.
Tunas-tunas vegetatif dari tanaman nanas dapat dipotong untuk perbanyakan
bibit dengan stek daun jika setiap potongan mempunyai minimal satu atau dua tunas
aksilar dan sebagian daun tanaman induk. Penggunaan stek batang dapat dilakukan
dengan melepaskan bagian daun dari batang tersebut, kemudian batang dipotong
menjadi empat bagian. Crown juga dapat dipotong menjadi 4 potongan stek atau
lebih. Bahan stek tersebut kemudian diberi perlakuan fungisida, selanjutnya bahan
stek ditanam pada media semai yang telah dipersiapkan (Bartholomew et al. 2003).
Semua bahan stek pada media semai harus ditumbuhkan hingga mencapai
ukuran yang cukup dan vigor yang baik untuk siap dipindah tanam ke lahan. Bibit
stek akan tumbuh dan berkembang dengan baik di lahan jika bibit tersebut
pertumbuhan perakarannya optimal saat dipindah tanam (Bartholomew et al. 2003).
Gejala Penyakit Layu dan Kisaran Inang PMWaV
Penyakit layu nanas melibatkan tiga faktor penting yaitu virus, serangga
vektor yaitu kutu putih (mealybug) dan keadaan lingkungan yang mendukung
munculnya gejala pada tanaman. Virus yang berasosiasi dengan penyakit ini yaitu
pineapple mealybug wilt-associated virus-1 (PMWaV-1) dan PMWaV-2 yang telah
berhasil diekstrak dari tanaman nanas yang menunjukkan gejala penyakit layu
maupun tanaman nanas yang tidak bergejala (Sether & Hu 2001). Hu et al. (1996)
menyatakan bahwa gejala layu tidak akan muncul jika pada tanaman hanya ada virus
saja atau kutu putih saja. Hal ini berbeda dengan penelitian penyakit layu nanas di
Indonesia oleh Hutahayan (2006) bahwa hasil pengamatan baik di rumah kaca
maupun di lahan nanas di Simalungun, Sumatra Utara menunjukkan bahwa tanaman
menunjukkan gejala layu meskipun tidak terkolonisasi oleh kutu putih.

Serangan penyakit layu oleh PMWaV telah dilaporkan menyebabkan kerugian
industri nanas di Hawaii mencapai 35% (Sether & Hu 2002b) serta kehilangan hasil
sampai 40% di Kuba (Anonim 1989 dalam Borroto et.al. 2007). Dalam beberapa
tahun terakhir penyakit layu nanas oleh PMWaV menjadi masalah serius di sentra
budidaya nanas di Indonesia, antara lain di Subang dengan kejadian penyakit layu 60-
70%, Blitar 90%, Simalungun 50-60%, dan Bogor 50% (Hutahayan 2006). Penyakit
layu menyebabkan petani mengalami gagal panen, karena buah yang dihasilkan
berukuran sangat kecil dan matang prematur. Rata-rata bobot buah dari tanaman
bergejala layu 35% lebih rendah daripada bobot buah tanaman bebas virus, dan 30%
lebih rendah daripada tanaman terinfeksi PMWaV-1 (Sether & Hu 2002b).
Tanaman induk yang terlihat sehat belum tentu terbebas dari PMWaV karena
infeksi PMWaV pada nanas tidak selalu menunjukkan gejala. Tryono (2006)
melaporkan hasil deteksi TBIA pada sampel tanaman bergejala maupun tidak
bergejala menunjukkan adanya variasi infeksi PMWaV-1 dan PMWaV-2 di lapang.
Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan Sether et al. (2001) bahwa tanaman nanas yang
tidak bergejala layu umumnya terinfeksi PMWaV-1, dan pada tanaman yang
bergejala layu umumnya terinfeksi PMWaV-2. Walaupun tidak menunjukkan gejala
layu, infeksi PMWaV-1 menyebabkan reduksi hasil tanaman nanas.
Infeksi awal biasanya terjadi pada tanaman di tepi lahan kemudian menyebar
ke tanaman di bagian dalam lahan. Gejala penyakit ini berupa nekrotik di ujung daun,
tepi daun menggulung ke bawah dan warna daun menjadi kemerahan. Kemudian
gejala berkembang menjadi kehilangan kebugaran daun dan menjadi layu. Pada
serangan yang parah, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan akar
terhambat hingga perakaran lemah, kemudian tanaman roboh. Jika tanaman terinfeksi
pada fase awal pertumbuhan maka tanaman tersebut tidak mampu menghasilkan
buah, atau hanya menghasilkan buah berukuran kecil (Sether & Hu 2002b).
Tryono (2006) telah melakukan pengujian terhadap tumbuhan yang berada di
sekitar pertanaman nanas dengan metode uji serologi TBIA. Dua jenis gulma yang
berbeda yaitu Panicum sp. dan Chloris sp. dan beberapa tanaman pisang (Musa spp.)
merupakan tumbuhan yang banyak ditemukan di sekitar pertanaman nanas di
kabupaten Subang. Hasil pengujian terhadap ketiga tumbuhan tersebut menunjukkan
hasil negatif terhadap infeksi PMWaV. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman nanas
merupakan satu-satunya tanaman yang diketahui sebagai inang bagi PMWaV.

Karakteristik PMWaV
Penyakit layu nanas berasosiasi dengan partikel virus dengan asam nukleat
berupa ssRNA, partikel berbentuk batang lentur yang tidak beramplop dengan ukuran
1200-1500 nm x 12 nm. Virus tersebut adalah pineapple mealybug wilt-associated
virus (PMWaV). PMWaV terdiri atas kompleks dua virus yang berbeda yaitu
PMWaV-1 dan PMWaV-2. Berdasarkan morfologi partikel dan karakteristik genom,
PMWaV-1 dan PMWaV-2 termasuk genus Ampelovirus Famili Closteroviridae
(Melzer et. al 2001, Martelli et. al 2005, Sether et. al 2005). Berdasarkan
karakterisasi genom dilaporkan bahwa PMWaV-1 terdiri dari 10,7 kb (7 ORF nomor
aksesi AF4141119), sedangkan PMWaV-2 terdiri dari 14,8 kb (10 ORF nomor aksesi
AF283103) (Melzer et. al 2001). Partikel virus yang diwarnai dengan uranyl formate
jenuh dalam metanol menunjukkan suatu struktur lubang pada sub unit selubung
protein yang merupakan karakteristik Closterovirus (Gunasinghe & German 1989).
Deteksi dan identifikasi virus merupakan langkah penting untuk mengetahui
keberadaan virus dan asosiasinya dengan tanaman inang. Cara terbaik untuk
mendeteksi PMWaV adalah dengan mengisolasi dsRNA yang diikuti dengan separasi
RNA pada gel elektroforesis (Gunasinghe & German 1989). Deteksi dan identifikasi
virus dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain deteksi serologi dan deteksi
asam nukleat. Deteksi serologi dengan Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
dan Serological Spesific Electron Mycroscopy (SSEM) dapat dilakukan, namun
dengan metode Tissue Blot Immunoassay (TBIA) dapat diperoleh hasil deteksi yang
lebih baik. Deteksi asam nukleat dilakukan dengan pengujian reverse transcription-
polymerase chain reaction (RT-PCR). Kedua PMWaV berbeda dengan 50% asam
nukleat yang homolog berdasarkan sekuensi genom yang telah dilakukan.
Berdasarkan hasil deteksi dan identifikasi Tryono (2006) PMWaV yang ada di
Indonesia mirip dengan PMWaV yang ada di Hawaii dan partikel virus ini hanya ada
pada jaringan pembuluh.
PMWaV berhasil diisolasi dari tanaman nanas yang menunjukkan gejala layu
maupun tanaman nanas yang tidak bergejala. Tanaman nanas yang bergejala layu
lebih banyak terinfeksi PMWaV-2, sedangkan tanaman nanas yang tidak bergejala
layu lebih banyak terinfeksi oleh PMWaV-1 (Tryono 2006). Deteksi dengan metode
TBIA menunjukkan bahwa distribusi PMWaV pada jaringan tanaman nanas
terlokalisir pada jaringan tertentu yaitu jaringan pembuluh (Tryono 2006). Kutu putih

mengintroduksikan PMWaV ke jaringan floem tanaman, kemudian virus tersebut
menyebar secara sistemik di dalam tanaman. Sifat virus yang terbatas pada floem
merupakan salah satu karakteristik Closteroviridae. Hu et al. (1997) melaporkan
bahwa antigen PMWaV terdeteksi dengan TBIA daun berumur sedang, juga pada
akar tetapi tidak pada daun muda.
Kutu Putih dan Penularan PMWaV
Kutu putih Dysmicoccus brevipes Cockerell (Hemiptera: Pseudococcidae) dan
Dysmicoccus neobrevipes Cockerell (Hemiptera: Pseudococcidae) merupakan hama
utama tanaman nanas yang menjadi masalah serius dalam budidaya nanas (Sether &
Hu 1998). Selain sebagai hama yang merusak karena aktivitas makannya, serangga
ini juga berperan sebagai vektor PMWaV yang menjadi penyebab penyakit layu nanas
(Sether et al. 1998). Kutu putih ditemukan selalu berasosiasi dengan beberapa jenis
semut (Rohrbach et at. 1988) sehingga mobilitasnya meningkat demikian juga dengan
penyebaran PMWaV di lapangan.
Penyakit layu nanas dilaporkan dapat ditularkan melalui perbanyakan vegetatif
tanaman nanas dan melalui vektornya yaitu Dysmicoccus brevipes (pink mealybug)
(Hemiptera: Pseudococcidae) dan D. neobrevipes (grey mealybug) (Hemiptera:
Pseudococcidae) (Sether et al. 1998). Kutu putih tersebut merupakan hama
kosmopolitan pada tanaman nanas (Rorhbach et al. 1988). D. brevipes bersifat
polifagus dengan kisaran inang lebih dari 100 genus dari 53 famili tanaman, termasuk
beberapa gulma yang tumbuh di sekitar tanaman nanas.
PMWaV dapat ditularkan oleh dua spesies kutu putih sebagai vektor yaitu D.
brevipes dan D. neobrevipes. Kedua kutu putih ini menularkan PMWaV secara semi
persisten, kemampuan menularkan PMWaV akan berkurang beberapa hari setelah
akuisisi. Beberapa spesies semut berasosiasi dengan kutu putih. Semut membantu
kelangsungan hidup koloni kutu putih dengan mengkonsumsi embun madu yang
dihasilkan kutu putih sehingga mencegah kolonisasi cendawan tempat hidup kutu
putih, semut juga melindungi kutu putih dari parasitoid dan predatornya (Lim 1985,
Sether et al. 1998). Keberadaan semut di lahan nanas sangat berpengaruh terhadap
penyebaran kutu putih di lahan tersebut, sekaligus penyebaran PMWaV karena
perpindahan kutu putih dibantu oleh semut.

Perbanyakan tanaman nanas yang umum dilakukan hanya dengan cara
vegetatif. Jika tanaman induk terinfeksi PMWaV maka tanaman anakannya akan ikut
terinfeksi karena penyebaran PMWaV dalam tanaman yaitu secara sistemik pada
pembuluh. Petani menggunakan bibit nanas dari ratoon, jika ratoon tersebut berasal
dari tanaman induk terinfeksi PMWaV maka bibit yang diperoleh juga terinfeksi
PMWaV.
Sether et al. (1998) melaporkan bahwa tidak ada infeksi PMWaV pada
sampel tanaman yang dikumpulkan dari lapang, yaitu gulma, tumbuhan semak, dan
pohon yang tumbuh di sekitar lahan nanas. Sether et. al (2002) juga melaporkan tidak
ada infeksi PMWaV pada Agave, pisang, ketela pohon, Chenopodium, tembakau, dan
rumput-rumputan, di mana tanaman nanasnya sendiri terinfeksi setelah diinokulasi
dengan D. brevipes yang viruliferous, meskipun beberapa dari tanaman non nanas ini
dapat dijadikan inang oleh D. brevipes.
Pengendalian Penyakit Layu
Eradikasi tanaman sakit di lahan dapat menjadi strategi pengendalian penyakit
layu di lapang (Sether & Hu et al. 2002b). Namun, teknik eradikasi tanaman
memerlukan banyak tenaga kerja dan tidak efisien karena tidak semua tanaman sakit
menunjukkan gejala layu, akibatnya tujuan eradikasi untuk menghilangkan inokulum
di lapangan tidak tercapai. Populasi kutu putih yang tinggi sepanjang tahun sangat
mendukung penyebaran inokulum di alam. Penanggulangan penyakit layu melalui
pengendalian populasi kutu putih juga kurang berhasil. Simbiosis semut dengan kutu
putih (Rohrbach et at. 1988; Beardsley 1996) dan tempat hidup (nice) kutu putih di
bagian yang tertutup dari tanaman nanas (di ketiak daun dan di pangkal batang bawah
tanah) (Beardsley 1996) menyebabkan parasit atau predator alami (maupun yang
diinnundasi) tidak dapat bekerja optimal dan tetap menyisakan populasi kutu putih
yang potensial menyebarkan PMWaV. Sedangkan pengendalian kutu putih dan
semut dengan aplikasi insektisida kimia tidak ekonomis karena biaya produksi
semakin tinggi dan juga tidak dapat menjamin populasi kutu putih selalu pada tingkat
aman bagi penyebaran PMWaV.
Semua varietas tanaman nanas di Indonesia rentan terhadap virus maupun kutu
putih (Hidayat 2006) sehingga penanggulangan penyakit ini belum dapat dilakukan

melalui tanaman varietas tahan. Salah satu cara pengendalian penyakit layu yang
sangat menjanjikan dan perlu dikaji adalah penggunaan bibit bebas virus.
Penggunaan bibit bebas PMWaV dapat menekan sumber inokulum sehingga
dapat mengurangi laju infeksi pada tanaman nanas di lahan. Jika infeksi PMWaV
dapat dicegah sampai tanaman melewati fase vegetatif, maka petani dapat
mengurangi resiko penurunan hasil panen. Berdasarkan penelitian Sether & Hu
(2002b), tanaman nanas yang terinfeksi PMWaV lebih awal yaitu saat tanaman
berumur 3-6 bulan (fase vegetatif) maka tanaman akan menghasilkan buah berukuran
relatif lebih kecil dari pada tanaman yang terinfeksi PMWaV setelah berumur lebih
dari 10 bulan (fase generatif).
Eliminasi Virus dengan Perlakuan Panas
Dalam beberapa tahun terakhir, perlakuan panas (heat treatment) menjadi
metode yang umum digunakan untuk memproduksi propagasi tanaman yang bebas
virus, viroid dan fitoplasma (Hadidi et al. 1998). Banyak virus yang dapat dieliminasi
dari tanaman inangnya dengan cara heat treatment. Awalnya perlakuan panas
diperlakukan pada keseluruhan tanaman pada suhu konstan yang berkisar dari 35-
40°C. Meskipun banyak tanaman yang mati setelah mendapatkan perlakuan ini,
beberapa tanaman yang bertahan dapat menjadi tanaman yang bebas virus. Bagian
tanaman dorman yang biasa digunakan adalah biji, umbi dan tunas. Secara umum
bagian tanaman tersebut lebih tahan terhadap suhu tinggi dari pada jaringan tanaman
lainnya. Setelah beberapa tahun, metode heat treatment dimodifikasi, yaitu
dikombinasikan dengan kultur meristem apikal untuk memperbesar peluang
mendapatkan tanaman bebas virus.
Perlakuan panas dapat dilakukan dengan penggunaan air panas (hot wáter
treatment) maupun udara panas (hot air treatment). Perlakuan air panas dengan
waktu yang lebih singkat lebih sering digunakan daripada perlakuan udara panas.
Selain menyebabkan terjadinya dehidrasi tanaman, perlakuan udara panas kurang
efektif dibandingkan perlakuan air panas. Perlakuan air panas umumnya diperlakukan
pada bagian tanaman dorman seperti biji, maupun tunas. Namun untuk tanaman yang
sedang tumbuh lebih sering digunakan perlakuan udara panas pada suhu 35-40°C
selama beberapa hari atau beberapa minggu (Hadidi et al. 1998)

Perlakuan panas in vivo menghambat replikasi virus di dalam tanaman,
translokasi virus, dan proses-proses dalam tanaman. Perlakuan panas dengan suhu di
atas 37 °C mampu menghambat multiplikasi banyak virus, merusak movement
protein yang sangat berperan dalam transportasi virus dalam tanaman, serta merusak
coat protein virus yang juga berperan dalam translokasi sistemik virus dalam tanaman
( Hadidi et.al 1998). Perlakuan panas in vivo tidak hanya berpengaruh terhadap virus
di dalam tanaman, tetapi juga menghambat proses fotosintesis, meningkatkan
respirasi gelap, dan mereduksi translokasi karbohidrat, mempengaruhi sintesis
protein, mempengaruhi pembelahan sel, pertumbuhan sel dan hormon tumbuhan.
Perubahan proses dalam tumbuhan juga dapat mempengaruhi virus dalam tumbuhan
tersebut ( Hadidi et.al 1998).
Salah satu cara mengeliminasi keberadaan PMWaV pada tanaman nanas
adalah dengan perlakuan panas pada bibit nanas yang terinfeksi. Beberapa laporan
menyebutkan PMWaV dapat dieliminasi dengan cara bibit nanas diberi perlakuan air
panas 50°C selama 120 menit (Hadidi et al. 1998). Sedangkan Sether et al. (2001)
menyebutkan bahwa PMWaV dapat dieliminasi melalui perbanyakan vegetatif
dengan kultur jaringan meristem apikal dan meristem lateral dari crown tanaman
nanas yang terinfeksi. Eliminasi PMWaV-1 dapat dilakukan dengan cara crown
tanaman nanas yang terinfeksi di beri perlakuan air panas di dalam penangas air pada
suhu 35°C selama 24 jam kemudian dilanjutkan dengan suhu 58°C selama 40 menit
atau 56°C selama 60 menit (Sether et al. 2001).
Eliminasi Virus dengan Ribavirin
Kemoterapi dapat diaplikasikan baik pada meristem yang dikulturkan secara
in vitro, maupun pada tanaman sebelum pengambilan meristem (Hadidi et al. 1998).
Ribavirin merupakan salah satu bahan kimia yang dapat digunakan untuk
mengeliminasi beberapa jenis virus. Perlakuan kemoterapi pada meristem kultur
bahan kimia langsung diaplikasikan pada medium kultur, dan dapat mempengaruhi
pertumbuhan meristem tersebut. Beberapa bahan kimia telah diuji untuk tujuan
tersebut, namun hanya sedikit yang dapat digunakan. Salah satu bahan kimia sintetik
yang bersifat antiviral berupa substansi yang analog dengan guanosin yaitu ribavirin.
Penambahan 10-50 mg/L ribavirin ke dalam media kultur efektif mencegah infeksi

beberapa virus yaitu PVX, PVY, PVS, dan PVM pada kentang dan tembakau, juga
mencegah CMV pada kultur meristem Nicotiana rustika (Hadidi et al. 1998).
Keberadaan substansi analog guanosin akan mengganggu pembentukan asam
nukleat virus sehingga multiplikasi virus dalam tanaman terhambat. Ribavirin aktif
dalam bentuk trifosfat yang menghambat proses capping pada 5’ RNA virus (Dawson
& Saldana 1984). Selain itu ribavirin menghambat replikasi virus pada fase awal
yaitu dengan mengganggu síntesis RNA-dependent RNA polymerase, dan pada fase
akhir dengan mengganggu síntesis selubung protein (Schuster & Huber 1991 dalam
Sharma et.al 2006). Berikut ini adalah gambar struktur kimia ribavirin (gambar 1).
Gambar 1 Struktur kimia ribavirin

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Virologi Tumbuhan Departemen
Proteksi Tanaman IPB, Laboratorium Kultur Jaringan Pusat Kajian Buah Tropika
(PKBT) IPB, dan Kebun Percobaan Tajur II PKBT IPB sejak Agustus 2007 sampai
Januari 2009.
Metode Penelitian
Penelitian ini meliputi tiga kegiatan yaitu: (1) Eliminasi PMWaV melalui
perlakuan air panas dan ribavirin pada planlet; (2) Eliminasi PMWaV melalui
perlakuan air panas dan ribavirin pada eksplan; dan (3) Eliminasi PMWaV melalui
perlakuan air panas pada bahan stek nanas.
Pengamatan Penyakit Layu dan Kutu Putih di Lapang
Pengamatan penyakit layu dan kutu putih pada tanaman nanas telah dilakukan
di sentra produksi nanas di Jawa Barat yaitu di Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak,
Kab. Subang.
Tanaman nanas cv Smooth Cayenne yang bergejala layu diambil dari
pertanaman nanas Kab. Subang Jawa Barat. Tanaman yang diambil adalah tanaman
nanas yang menunjukkan gejala penyakit layu berwarna merah dan nekrosis pada
ujung daun. Verifikasi PMWaV pada sampel tanaman dilakukan dengan TBIA.
Tanaman nanas yang positif terinfeksi PMWaV ditanam dalam polibag yang berisi
campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Tanaman nanas tersebut
kemudian digunakan sebagai sumber inokulum PMWaV dalam percobaan berikutnya.
Eliminasi PMWaV melalui Perlakuan Air Panas dan Ribavirin pada Planlet
Penyiapan Planlet Nanas. Planlet yang digunakan adalah planlet nanas kultivar
Smooth Cayenne klon Curug Rendeng koleksi Laboratorium Kultur Jaringan PKBT
IPB yang telah ditanam pada MS0 selama 3 bulan (lebih dari 5 kali sub kultur).
Sebagian daun dan akar planlet dibuang kemudian dipotong sepanjang 0,5-1,0 cm
dari pangkal batang. Planlet ditanam pada media MS + 0,5µM NAA selama 30 hari

untuk menginduksi pengakaran pada planlet. Planlet tersebut kemudian diinokulasi
dengan PMWaV menggunakan vektor kutu putih.
Inokulasi PMWaV pada Planlet. Kutu putih (Dysmicoccus sp.) diambil dari pelepah
pangkal batang dan akar tanaman nanas kemudian diperbanyak pada buah kabocha
(Cucurbita maxima). Kutu putih dipindahkan dengan menggunakan kuas basah ke
buah kabocha yang diletakkan dalam kotak kardus dan disimpan pada suhu ruang.
Nimfa-nimfa yang diletakkan oleh imago betina kutu putih tersebut dipelihara pada
kabocha sampai menghasilkan kutu putih generasi ke dua yang selanjutnya digunakan
sebagai vektor penularan PMWaV. Nimfa kutu putih generasi ke dua dibiarkan
makan akuisisi pada tanaman nanas sumber PMWaV selama 72 jam, kemudian
dibiarkan makan inokulasi pada planlet dalam botol kultur selama 7-14 hari. Jumlah
planlet yang diinokulasi adalah sebanyak 10 botol kultur, masing-masing 3
planlet/botol. Jumlah kutu putih yang digunakan sebagai vektor adalah 10
individu/planlet.
Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas dan Ribavirin. Planlet yang
telah diinokulasi PMWaV kemudian diberi perlakuan air panas atau ribavirin. Planlet
terlebih dahulu diberi pre-treatment dalam penangas air (waterbath) pada suhu
konstan 35°C selama 24 jam untuk mengurangi kejutan (shock) terhadap suhu panas
yang diberikan selanjutnya. Segera setelah pre-treatment ini, suhu waterbath
dinaikkan menjadi 58°C kemudian planlet dimasukkan ke waterbath selama 30-40
menit atau 56°C selama 30-60 menit. Selanjutnya planlet ditanam kembali pada
media Murashige & Skoog (MS). Percobaan ini terdiri dari 6 taraf perlakuan suhu
yaitu perlakuan air panas 35 ºC selama 24 jam; perlakuan 35 ºC selama 24 jam
dilanjutkan dengan 56 ºC selama 30 menit; perlakuan 35 ºC selama 24 jam
dilanjutkan 56 ºC selama 60 menit; perlakuan 35 ºC selama 24 jam 58 ºC selama 30
menit; perlakuan 35 ºC selama 24 jam dilanjutkan 58 ºC selama 40 menit; dan tanpa
perlakuan panas sebagai kontrol negatif. Setiap perlakuan terdiri dari 3 botol kultur
sebagai ulangan, dan masing-masing ulangan terdiri dari 4 planlet sehingga terdapat
72 unit percobaan.
Eliminasi PMWaV dengan perlakuan kimia dilakukan dengan cara
penambahan 10 mg/l ribavirin dalam media MS. Ribavirin 10 mg dilarutkan dalam

aquades kemudian ditambahkan pada media MS yang masih cair dalam botol kultur
dan ditutup rapat dengan plastik bening. Selanjutnya media+ ribavirin disimpan pada
suhu ruang sampai media menjadi padat. Percobaan ini terdiri dari 3 macam
perlakuan yaitu planlet terinfeksi PMWaV yang ditumbuhkan pada media ribavirin 10
mg/l, planlet terinfeksi PMWaV pada media MS tanpa ribavirin sebagai kontrol
positif, dan planlet sehat pada media MS tanpa ribavirin sebagai kontrol negatif.
Perlakuan ribavirin 10 mg/l terdiri dari 11 botol kultur sebagai ulangan, setiap
ulangan terdiri dari 4 planlet, sedangkan kontrol positif dan kontrol negatif masing-
masing dilakukan 1 ulangan yang terdiri dari 4 planlet. Sehingga jumlah planlet yang
digunakan dalam percobaan ini adalah 52 planlet.
Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas dan Ribavirin pada Eksplan
Bahan Tanaman Nanas. Bahan tanaman yang digunakan untuk kultur jaringan
adalah mahkota buah (crown) nanas cv Smooth Cayenne terinfeksi PMWaV yang
diambil dari pertanaman nanas di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten
Subang, Provinsi Jawa Barat. Verifikasi infeksi PMWaV pada crown yang digunakan
sebagai bahan kultur jaringan dilakukan dengan tissue blot immunoassay (TBIA)
berdasarkan metode Hu et.al (1997). Sebagai kontrol negatif digunakan crown
tanaman sehat. Eksplan yang digunakan untuk inisiasi kultur nanas yaitu tunas aksilar
dan tunas apikal yang diambil dari crown.
Perlakuan Air Panas. Crown yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi PMWaV
(kontrol negatif) diberi pre-treatment air panas 35 ºC selama 24 jam di dalam
penangas air. Kemudian crown diberi perlakuan air panas. Perlakuanair panas terdiri
dari empat taraf yaitu crown sakit dengan perlakuan air panas 56 °C selama 60 menit;
crown sakit dengan perlakuan air panas 58°C selama 40 menit; crown sakit tanpa
perlakuan pemanasan (kontrol positif); serta crown sehat tanpa perlakuan air panas
(kontrol negatif). Setiap perlakuan diulang 3 kali, setiap ulangan terdiri dari 5 botol
kultur dengan 10 eksplan/botol sehingga terdapat 150 unit percobaan. Peubah yang
diamati adalah pertumbuhan eksplan.

Kultur Jaringan Nanas. Daun crown dilepaskan dari bonggol, kemudian bonggol
direndam dalam larutan detergen selama 30 menit dan dibilas dengan air mengalir
selama 30-60 menit. Mata tunas aksilar dan tunas apikal dari bonggo crown diambil
dengan menggunakan scalpel dan langsung direndam dalam larutan fungisida dan
bakterisida selama 30 menit, dan dibilas dengan aquades steril sebanyak 2 kali.
Selanjutnya, mata tunas tersebut direndam dalam NaOCl 20% dan 10% masing-
masing selama 5 menit, dan dibilas dengan aquades steril. Mata tunas tersebut
kemudian ditanam pada media inisiasi yaitu media MS dasar yang terdiri dari larutan
makro, larutan mikro A, larutan mikro B ditambah NAA 2 mg/l, BA 2 mg/l
(Lampiran 1) dipelihara sampai 12 minggu, selanjutnya tunas dipindahtanam ke
media B2N1 (Lampiran 2) untuk menginduksi pembentukan tunas dan akar.
Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas pada Bahan Stek
Penyiapan Bahan Tanaman. Bahan tanaman diambil dari tanaman nanas induk yang
menunjukkan gejala penyakit layu (diverifikasi dengan TBIA) dan tanaman sehat
sebagai kontrol negatif dari Kebun Percobaan PKBT Tajur II. Bahan stek yang
digunakan adalah daun, batang, dan crown.
Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas. Perendaman bahan stek di dalam
air panas dengan suhu 35°C selama 24 jam sebagai pre-treatment. Perlakuan terdiri
dari dua macam yaitu perlakuan panas dan jenis stek. Perlakuan panas terdiri dari
empat taraf yaitu perlakuan air panas 56 °C selama 60 menit pada tanaman sakit;
perlakuan air panas 58°C 40 menit pada tanaman sakit; tanpa perlakuan air panas
pada tanaman sakit (kontrol positif); serta tanpa perlakuan pemanasan pada tanaman
sehat (kontrol negatif). Perlakuan kedua yaitu jenis stek, terdiri dari 3 taraf antara lain
stek daun, stek batang, dan crown. Sehingga percobaan ini terdiri dari 12 kombinasi
perlakuan. Setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali, setiap ulangan terdiri dari 10
unit percobaan sehingga terdapat 360 unit percobaan.

Penanaman Stek. Bahan stek daun diperoleh dengan cara pemotongan bagian dasar
daun sampai mengenai jaringan meristem kulit batang dengan tunas lateral (Gambar
2a). Sedangkan stek batang didapatkan dengan cara memotong batang secara
longitudinal menjadi 2 bagian potongan (Gambar 2b). Crown digunakan utuh, tanpa
pemotongan karena crown masih sangat muda.
Gambar 2 Stek daun (a) dan stek batang (b) tanaman nanas
Media semai yang digunakan adalah sekam bakar. Sekam bakar dibasahi
sampai basah kapasitas lapang untuk menjaga kelembaban kemudian sekam ditebar
pada meja pesemaian seluas 1-2 m2
dengan ketebalan media tanam 10 cm. Semua
bahan stek direndam dalam larutan fungisida dan bakterisida. Kemudian bahan stek
ditanam pada media semai dengan jarak tanam 5 cm. Selama 2 minggu pertama
penyemaian, meja semai disungkup plastik bening untuk mengurangi laju penguapan
supaya stek tidak cepat mengering.
Bibit stek yang telah berumur 7 minggu dipindah tanam ke media tanam
dalam polibag 15x25 cm. Media tanam yang digunakan adalah sekam bakar dan
kompos (1:1). Bibit dipelihara sampai 4 minggu, dan dilakukan pengamatan jumlah
daun yang tumbuh dan tinggi tanaman. Kemudian daun dipanen untuk deteksi
PMWaV dengan TBIA.
Data daya tumbuh stek dan persentase infeksi PMWaV dianalisis dengan
ANOVA program SAS versi 9.0. Apabila terdapat beda nyata di antara perlakuan
maka dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (α =0,05).
Verifikasi Infeksi PMWaV dengan Tissue Blot Immunoassay (TBIA)
PMWaV pada tanaman dideteksi secara serologi dengan TBIA berdasarkan
metode Hu et al. (1997). Daun dipotong melintang pada bagian dasar daun dengan
a b

potongan yang rata. Potongan ini kemudian diblot pada 0,45 µm Nitro ME
nitrocellulose membrane (Amersham Pharmacia Biotec, USA) selama 60 detik. Pola
jaringan pembuluh daun menempel dan meninggalkan jejak pada membran. Membran
dapat disimpan kering di antara lipatan kertas saring pada suhu ruang sampai siap
dianalisis.
Membran yang telah diblot ditempatkan dalam wadah plastik dan diblocking
dengan 2% (wt/vol) susu skim yang dilarutkan dalam larutan penyangga phosphate
buffer saline (PBS) ( 8g sodium chloride; 1,15g sodium phosphate dibasic; 0,2g
potasium phosphate monobasic; 0,2g potasium chloride; 1000 ml aquades; pH 7,4)
digoyang 50 rpm dengan rotary shaker selama 30 menit pada suhu ruang. Kemudian
membran diinkubasikan dalam wadah plastik atau kantung plastik segel dengan
antibodi monoklonal PMWaV (Agdia Inc., USA) dengan pengenceran 1:10 dalam
PBS digoyang 50 rpm dengan rotary shaker pada suhu ruang selama 1-2 jam, atau
diinkubasi pada suhu 4 ˚C selama satu malam. Kemudian membran dicuci dengan
PBST (PBS + 0,05% Tween 20) digoyang 125 rpm selama 10 menit pada suhu ruang,
pencucian diulang sebanyak 5 kali. Setelah pencucian, membran kemudian
diinkubasikan dengan konjugate alkaline phosphatase (Shigma Chemical Co. St.
Louise, USA) pada pengenceran 1:1000 dalam PBS selama 2-3 jam sambil digoyang
50 rpm pada suhu ruang. Membran kemudian dicuci seperti di atas, diwarnai dengan
substrat 5-bromo-4-chloro-3-Indolyl Phosphate/Nitro Blue Tetrazolium (BCIP/NBT)
(Shigma Chemical Co., USA) mengunakan satu tablet BCIP/NBT yang dilarutkan
dalam 10 ml larutan penyangga Alkaline Phosphatase (AP). Pewarnaan dilakukan
pada suhu ruang sampai terjadi perubahan warna pada membran. Reaksi pewarnaan
dihentikan dengan mencuci membran dengan air mengalir kemudian
dikeringanginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyakit Layu Nanas di Sentra Produksi Nanas Jawa Barat
Pengamatan penyakit layu pada tanaman nanas telah dilakukan di sentra
produksi nanas di Jawa Barat yaitu di Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang.
Tanaman nanas bergejala layu dapat diamati dengan mudah karena terjadi perubahan
warna daun menjadi kemerahan, atau kekuningan. Gejala awal penyakit layu dimulai
dengan perubahan warna daun terutama pada daun bagian tengah menjadi merah
(Gambar 3a). Pada perkembangan selanjutnya semakin banyak daun yang berwarna
merah, terutama daun bagian bawah sampai pada akhirnya semua daun menjadi
merah. Kebugaran daun menurun sehingga tanaman layu (Gambar 3b), dan terlihat
nekrotik pada ujung daun (Gambar 3c). Bila sudah kering, umumnya tepi daun
menggulung ke bawah dan layu (Gambar 3d).
Gambar 3 Gejala penyakit layu pada tanaman nanas di Desa Bunihayu, Kecamatan
Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gejala dicirikan dengan daun berwarna kuning kemerahan (a), kebugaran daun menurun sampai layu (b), ujung daun mengalami nekrotik (c), dan tepi daun menggulung ke bawah (d).
c
a b
d

Hasil pengamatan penyakit layu di lapangan menunjukkan bahwa penyakit
layu yang terjadi pada fase vegetatif sangat mempengaruhi produksi buah pada fase
generatif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sether & Hu (2002b) bahwa rata-rata
bobot buah yang dihasilkan oleh tanaman bergejala layu berkorelasi positif dengan
umur tanaman saat terjadinya gejala penyakit layu. Tanaman yang bergejala layu pada
umur 3-6 bulan menghasilkan bobot buah yang lebih rendah daripada tanaman yang
bergejala layu pada umur 10-14 bulan. Rata-rata bobot buah dari tanaman terinfeksi
PMWaV-2 35% lebih rendah daripada tanaman sehat, dan 30% lebih rendah dari
tanaman yang hanya terinfeksi PMWaV-1 (Sether & Hu 2002b).
Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa kejadian penyakit layu cenderung
lebih tinggi pada sistem budidaya ratoon crop dibandingkan plant crop. Widyanto
(2005) melaporkan bahwa luas serangan penyakit layu nanas di Desa Bunihayu pada
sistem ratoon crop mencapai 50% sedangkan kejadian penyakit layu pada pertanaman
sistem plant crop hanya 15%.
Kutu putih ditemukan baik pada tanaman bergejala layu maupun tanaman
sehat. Serangga ini mengkoloni tanaman nanas terutama pada bagian pangkal daun
(Gambar 4a), crown, atau pada akar (Gambar 4b). Kutu putih yang berasosiasi dengan
tanaman nanas di Subang telah diidentifikasi sebagai Dysmicoccus brevipes
(Hemiptera: Pseudococcidae) (Hutahayan 2006).
Gambar 4 Hasil pengamatan koloni kutu putih (Dysmicoccus brevipes Cockerell)
pada pangkal batang (a) dan perakaran (b) tanaman nanas di lapang
a b

Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas dan Ribavirin pada Planlet
Pengaruh Perlakuan Air Panas terhadap Pertumbuhan Planlet
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan planlet menjadi sangat
terganggu setelah mendapat perlakuan air panas (Tabel 1). Plantlet yang masih hidup
ditandai dengan warna daun tetap hijau, dan terjadi pertumbuhan daun yang baru,
sedangkan planlet yang mati diawali dengan perubahan warna planlet menjadi
berwarna kuning atau kecoklatan, serta tidak terjadi pertumbuhan daun baru. Planlet
yang diberi perlakuan air panas hanya dapat bertahan hidup sampai maksimal hari
ketiga setelah perlakuan dan tanda-tanda kematian telah tampak jelas pada hari-hari
selanjutnya.
Tabel 1 Pengaruh perlakuan air panas terhadap pertumbuhan planlet nanas selama 7 hari setelah perlakuan air panas
No
Perlakuan air panas
Hari setelah perlakuan air panas
1 2 3 4 5 6 7
1 35°C 24 jam + + + + - - -
2 35°C 24 jam; 56°C 30 menit + + + - - - -
3 35°C 24 jam; 56°C 60 menit + - - - - - -
4 35°C 24 jam; 58°C 30 menit + + - - - - -
5 35°C 24 jam; 58°C 40 menit + + - - - - -
6 Kontrol (tanpa perlakuan panas) + + + + + + +
Keterangan: (+) planlet hidup, (-) planlet mati.
Perlakuan air panas tidak hanya berpengaruh terhadap virus di dalam jaringan
tanaman tetapi juga berpengaruh terhadap metabolisme dan fisiologi tanaman.
Perlakuan panas menyebabkan perubahan pada kloroplas dan perubahan sitoplasma
sel sehingga mengganggu proses fotosintesis tanaman. Kerusakan klorofil
menyebabkan tanaman mengalami klorosis sehingga tanaman berwarna hijau
kekuningan bahkan kecoklatan, selanjutnya tanaman mengalami dehidrasi dan absisi.
Perlakuan panas juga dapat mempengaruhi sintesis protein tanaman, meningkatkan
reaksi gelap, dan mereduksi translokasi karbohidrat (Hadidi et. al 1998).
Tanaman atau bagian tanaman mempunyai toleransi yang berbeda terhadap
perlakuan panas (Hadidi et. al 1998). Pada penelitian ini, jaringan planlet

mempunyai ambang toleransi yang rendah terhadap perlakuan air panas sehingga
jaringan planlet mengalami kerusakan jaringan, dan mati. Perlakuan air panas
sebagai teknik eliminasi virus tampaknya tidak dapat diaplikasikan pada planlet
karena lemahnya jaringan planlet untuk menerima perlakuan suhu tinggi. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Hadidi (1998) bahwa perlakuan air panas umumnya
diterapkan pada bagian tanaman dorman seperti biji, maupun tunas. Sedangkan untuk
tanaman yang sedang tumbuh lebih sering digunakan perlakuan udara panas dengan
suhu yang lebih rendah dan waktu aplikasi yang lebih panjang.
Pada penelitian ini, planlet yang diberi perlakuan air panas tidak menunjukkan
pertumbuhan daun baru. Hal ini diduga disebabkan oleh perlakuan panas berpengaruh
langsung terhadap pembelahan sel dan pertumbuhan tanaman. Hadidi et al. (1998)
menyatakan bahwa perlakuan suhu di atas 40 ºC menyebabkan reduksi pembelahan
dan pertumbuhan sel tanaman. Faktor utama yang mempengaruhi pembelahan dan
pertumbuhan sel adalah zat pengatur tumbuh. Beberapa penelitian menunjukkan
bahwa stres suhu tinggi menyebabkan peningkatan level abscisic acid (ABA) dan
menekan aktivitas sitokinin, auksin dan giberelin (Hadidi et al. 1998).
Pengaruh Perlakuan Ribavirin terhadap Pertumbuhan Planlet
Planlet yang ditumbuhkan pada media MS yang telah diberi ribavirin 10 mg/l
telah diamati pertumbuhannya (Tabel 2). Menurut Hadidi et. al (1998) penambahan
10-50 mg/l ribavirin ke dalam media kultur efektif mencegah infeksi beberapa virus
seperti Potato virus X, Potato virus Y, Potato virus S, atau Potato virus M pada
kentang dan tembakau, juga mencegah Cucumber mosaic virus pada kultur meristem
Nicotiana rustika. Namun demikian, dari hasil penelitian ini tampaknya planlet nanas
yang digunakan sangat sensitif terhadap ribavirin, sehingga tidak mampu tumbuh
pada media dengan ribavirin 10 mg/l. Umumnya planlet yang diberi perlakuan
ribavirin 10 mg/l mulai mengalami perubahan warna menjadi menguning dan mati
sejak 7 hari setelah perlakuan (Tabel 2).

Tabel 2 Pengaruh perlakuan ribavirin terhadap pertumbuhan planlet nanas selama 11
hari setelah perlakuan ribavirin
Ulangan (botol kultur)
Hari setelah perlakuan ribavirin
1 7 11
1 + + -
2 + + -
3 + + +
4 + - -
5 + + -
6 + - -
7 + - -
8 + - -
9 + + -
10 + + +
11 + + -
12 (K+) + + +
13 (K-) + + +
Keterangan: K- = kontrol negatif (planlet sehat, tanpa ribavirin), K+ = kontrol positif (planlet sakit tanpa ribavirin), (+) planlet hidup, (-) planlet mati.
Dalam penelitian ini, planlet nanas menunjukkan reaksi yang sangat sensitif
terhadap perlakuan ribavirin 10 mg/l. Bahan aktif ribavirin diketahui dapat
menyebabkan gangguan pada replikasi asam nukleat (Dawson & Saldana 1984)
diduga bahan aktif tersebut juga dapat mengganggu replikasi asam nukleat pada
tanaman. Gangguan dalam replikasi asam nukleat akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlakuan
senyawa antiviral juga dapat menyebabkan fitotoksisitas pada tanaman (Sharma et al.
2007). Hal ini menyebabkan hanya sedikit jenis bahan antiviral yang dapat digunakan
dalam eliminasi virus pada tanaman. Perlakuan beberapa senyawa antiviral antara lain
acylcloguanosine; azidothymidine; 2,4-dioxohexahydro-1; ribavirin serta 2,5-triazine
(DHT); dan 2-thiouracil secara signifikan menyebabkan penurunan pembentukan
tunas pada tanaman kinnow (Sharma et al. 2007).

Pengaruh Perlakuan Air Panas dan Ribavirin terhadap Infektifitas PMWaV
pada Planlet
Pengaruh perlakuan ribavirin terhadap infeksi PMWaV pada planlet akan
dapat diketahui dengan cara verifikasi infeksi PMWaV pada planlet. Deteksi PMWaV
dengan metode TBIA belum memungkinkan untuk dilakukan terhadap daun planlet
karena ukuran jaringan daun yang belum cukup untuk diblot pada membran.
Sehingga kemudian dilakukan verifikasi PMWaV dengan metode DIBA (dot blot
immunoassay). Deteksi PMWaV dengan metode DIBA telah dilakukan pada planlet.
Prinsip deteksi PMWaV dengan metode DIBA secara umum sama dengan TBIA,
hanya berbeda dalam blotting sampel daun pada membran. Penyiapan sampel
tanaman dilakukan dengan penggerusan sampel daun dalam larutan penyangga
phosphate buffer saline (PBS) dengan perbandingan 1:5 (w/v). Namun hasil
pengujian DIBA menunjukkan reaksi negatif terhadap PMWaV-1 dan PMWaV-2.
Beberapa faktor diduga dapat mempengaruhi hasil deteksi PMWaV dari planlet
dengan DIBA antara lain; konsentrasi PMWaV dalam cairan sap tanaman hasil
penggerusan, dan keberadaan PMWaV pada floem planlet. PMWaV mempunyai
konsentrasi yang sangat rendah di dalam jaringan tanaman yang diinfeksinya,
penyiapan sampel uji dengan penggerusan dalam larutan penyangga akan semakin
menurunkan konsentrasi PMWaV dalam sap tanaman sehingga akan lebih sulit
terdeteksi dengan DIBA. Translokasi PMWaV dalam pembuluh floem tanaman in
vitro diduga lebih lambat dari pada translokasi PMWaV pada tanaman lapang.
Tanaman in vitro (planlet) merupakan tanaman heterotrof yang mengambil nutrisi
dari medium, bukan dari hasil fotosintesis, sehingga metabolisme pada jaringan
pembuluh floem tidak sepenuhnya aktif seperti halnya tanaman lapang. Hal ini diduga
menyebabkan rendahnya translokasi virus dalam pembuluh floem planlet sehingga
tidak terdeteksi pada planlet. Deteksi PMWaV pada planlet akan memberikan hasil
yang lebih baik jika dilakukan dengan metode TBIA. Maka planlet harus dipelihara
sampai aklimatisasi sehingga mempunyai ukuran penampang daun yang cukup untuk
dideteksi dengan TBIA. Namun dalam percobaan ini, pengaruh perlakuan air panas
dan ribavirin terhadap infektifitas PMWaV tidak dapat diamati. Planlet nanas sangat
sensitif terhadap suhu tinggi atau ribavirin sehingga planlet mati dan tidak dapat
dipelihara sampai dilakukan deteksi PMWaV pada planlet.

Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas pada Eksplan
Pengaruh Perlakuan Air Panas terhadap Daya Tumbuh Eksplan
Pertumbuhan eksplan di dalam media inisiasi mulai terlihat sejak 1 minggu
setelah inisiasi (msi) pada media inisiasi. Pertumbuhan eksplan tunas apikal
menunjukkan perbedaan dengan eksplan mata tunas lateral. Tunas apikal mulai
tumbuh dengan membentuk daun sejak 1 msi (Gambar 5a), sedangkan tunas lateral
belum menunjukkan tanda pertumbuhan tunas (Gambar 5b). Pertumbuhan eksplan
tunas lateral mulai terjadi sejak 2 msi ditandai dengan terjadinya pembengkakan mata
tunas dan penebalan pada mata tunas sehingga terlihat berwarna gelap. Setelah 4 msi
mata tunas dari eksplan tunas lateral mulai pecah dan berwarna hijau menunjukkan
calon tunas akan muncul. Namun sampai eksplan berumur 12 msi tidak terjadi
perubahan yang signifikan pada mata tunas tersebut. Selanjutnya eksplan dipindah ke
media B2N1 untuk menginduksi pembentukan tunas dan akar. Selama 12 msi pada
media B2N1, eksplan juga tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti namun mata
tunas tetap hijau, menandakan eksplan tersebut hidup.
Gambar 5 Pertumbuhan eksplan tunas apikal (a) dan tunas lateral (b) berumur 1
minggu setelah inisiasi (msi)
Pengamatan eksplan pada medium kultur dilakukan sampai 12 msi, namun
hingga akhir pengamatan pertumbuhan pada eksplan tunas lateral terhambat. Nodul
yang membengkak tetap berwarna hijau dan tidak terlihat adanya pertumbuhan tunas
maupun akar. Terhambatnya pertumbuhan eksplan dapat disebabkan oleh banyak
faktor antara lain perubahan keseimbangan dan konsentrasi zat pengatur tumbuh,
maupun penurunan daya tumbuh eksplan.
a
b

Perbanyakan tanaman dengan kultur jaringan menunjukkan adanya perbedaan
respon antar spesies, klon, maupun varietas tanaman terhadap komposisi media dan
zat pengatur tumbuh. Menurut Gunawan (1988), zat pengatur tumbuh merupakan
komponen yang penting dalam kultur jaringan, namun jenis dan kompisisinya sangat
tergantung pada jenis tanaman dan tujuan kulturnya. Pertumbuhan dan morfogenesis
tanaman in vitro dikendalikan oleh keseimbangan dan konsentrasi zat pengatur
tumbuh di dalam tanaman tersebut. Salah satu zat pengatur tumbuh yang digunakan
dalam percobaan ini adalah benzyl adenin (BA) yang merupakan salah satu sitokinin
sintetik yang cukup efektif dan NAA yang merupakan auksin. BA mampu
menginduksi produksi hormon alami di dalam tanaman dan hormon alami tersebut
bekerja dalam menginduksi organogenesis (Zaers & Mapes 1982). Auksin berperan
dalam pemunculan kalus, suspensi sel, pertumbuhan akar, dan bersama-sama dengan
sitokinin mengatur morfogenesis tanaman. Selain itu, auksin berperan dalam
pembentukan klorofil, embriogenesis, serta morfogenesis tunas dan akar (Wattimena
1988).
Di dalam tanaman terdapat zat pengatur tumbuh endogen antara lain IAA
(indoleacetic acid), dan N6 (2-isopentenyl) adenin (iP), N6 (2-isopentenyl) adenosine
(iPR), Zeatin (Z), Zeatin riboside (ZR), dan N6-benzyladenin (BA) yang berada pada
bagian dasar daun. Penyerapan BA dan NAA dari medium kultur menyebabkan
peningkatan level ZPT endogen yaitu iP dan IAA yang kemudian terlibat dalam
proses organogenesis tunas (Auer et al. 1999).
Penambahan ZPT eksogen BA (2 mg/L) dan NAA ( 2 mg/L) merupakan
konsentrasi terbaik untuk menginduksi pembentukan nodul pada bonggol nanas, dan
selanjutnya terjadi akumulasi iP dan IAA untuk menginduksi organogenesis tunas
(Auer et al. 1999). Dalam penelitian ini media inisiasi yang digunakan diberi ZPT
eksogen berupa BA 2 mg/l dan NAA 2 mg/l namun tidak terjadi pembentukan tunas
dan akar. Perlakuan air panas pada eksplan diduga berpengaruh terhadap zat pengatur
tumbuh endogen pada tanaman nanas dan juga berpengaruh pada daya tumbuh
eksplan. Perlakuan panas diketahui dapat menyebabkan reduksi sitokinin, auksin, dan
giberelin, serta meningkatkan abscisic acid (ABA) dan etilen pada tanaman (Hadidi et
al. 1998). Perubahan keseimbangan zat pengatur tumbuh pada eksplan diduga
berpengaruh terhadap viabilitas eksplan tersebut. Faktor lain yang diduga
menghambat pertumbuhan tunas dan akar pada eksplan tanaman nanas yang terinfeksi

PMWaV adalah penurunan daya tumbuh eksplan akibat perubahan metabolisme pada
tanaman nanas sakit. Tanaman yang terserang penyakit layu mengalami perubahan
metabolisme antara lain peningkatan kadar asam absisat, protein terlarut, prolin dan
fenol, munculnya peroksidase dan aktivitas asam invertase (Nieves et al. (1996)
dalam Borroto et al. 2007). Perubahan metabolisme dalam tanaman sakit tersebut
diduga mempengaruhi daya tumbuh eksplan yang berasal dari tanaman sakit.
Eliminasi PMWaV dengan Perlakuan Air Panas pada Stek
Keadaan Umum
Bahan perbanyakan yang digunakan adalah stek daun, batang, dan crown. Stek
yang disemai pada media sekam bakar mulai memperlihatkan pertumbuhan tunas
sejak 2 minggu setelah semai (mss). Pertumbuhan perakaran pada bibit mulai terlihat
sejak 3 minggu setelah semai (mss). Daya tumbuh stek pada tabel 1 merupakan
pertumbuhan tunas pada 7 mss. Perlakuan panas pada stek menyebabkan daun induk
pada stek daun lebih cepat mengalami perubahan warna menjadi kekuningan,
kemudian mengering (Gambar 6a) berbeda dengan stek daun tanaman sakit tanpa
perlakuan panas (Gambar 6b).
Gambar 6 Daun induk pada stek daun dengan perlakuan panas (a) dan tanpa
perlakuan panas (b)
Stek daun dan stek batang menghasilkan 1-2 tunas per stek. Stek daun ditanam
dengan cara membenamkan bagian stek yang mengandung mata tunas ke dalam
media semai, dengan daun berada di permukaan media semai. Sedangkan cara
penanaman stek batang yang baik yaitu dengan cara batang dibagi menjadi dua bagian
a b

dan permukaan batang yang mengandung tunas berada di atas permukaan media
semai.
Pengaruh Perlakuan Air terhadap Daya Tumbuh Stek
Bahan perbanyakan yang digunakan adalah stek daun, batang, dan crown.
Tunas pada stek mulai tumbuh sejak 2 minggu setelah semai (mss). Pada umumnya
tumbuh satu sampai dua tunas pada stek daun, batang, dan crown. Tunas yang tumbuh
dari crown berukuran relatif lebih besar dari pada tunas dari stek daun dan batang.
Tunas stek daun dan stek batang mulai terlihat sejak 2 mss, namun belum
terlihat tunas dari crown (Gambar 7 a,b,c). Daun mulai terbentuk pada 4 mss namun
belum terbuka sempurna (Gambar 7 d,e,f). Daun dari tunas stek sudah terbuka
sempurna pada 5 mss (Gambar 7 g, h, i).

Gambar 7 Stek daun (a), stek batang (b), dan stek crown (c) berumur 2 minggu setelah semai (mss); stek daun (d), stek batang (e), crown (f) berumur 4 mss; stek daun (g), stek batang (h), crown (i) berumur 5 mss.
Berdasarkan pengamatan selama pesemaian, tidak ada perbedaan warna
maupun bentuk tunas pada stek dari tanaman sakit maupun tanaman sehat, baik yang
diberi perlakuan panas maupun tanpa perlakuan panas. Hal ini menunjukkan bahwa
infeksi PMWaV tidak menimbulkan gejala pada bibit/anakan di pesemaian. Namun
demikian, bibit atau anakan yang terlihat sehat tanpa gejala layu belum tentu bebas
infeksi PMWaV. Persentase daya tumbuh stek diperoleh dengan cara menghitung
jumlah stek yang tumbuh pada 7 mss dibandingkan dengan jumlah total stek yang
ditanam. Daya tumbuh stek pada 7 mss ditampilkan dalam tabel 3.
a c b
d e f
g h i
Stek daun Stek batang Stek crown
Umur 2 mss
Umur 4 mss
Umur 5 mss

Tabel 3 Persentase daya tumbuh stek nanas berumur 7 minggu setelah semai (mss)
Perlakuan air panas jenis stek daya tumbuh stek (%)*)
Perlakuan air panas 56°C selama 60 menit Daun 50,20c
Batang 51,51c
Crown 100a
Perlakuan air panas 58°C selama 40 menit Daun 78, 21abc
Batang 60,83bc
Crown 86,00ab
Tanaman sakit tanpa perlakuan (kontrol positif) Daun 86,03ab
Batang 81,10ab
Crown 100a
Tanaman sehat tanpa perlakuan (kontrol negatif) Daun 100a
Batang 100a
Crown 100a *)Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%
(DMRT)
Perlakuan air panas 56°C selama 60 menit menyebabkan penurunan daya
tumbuh stek daun dan batang. Sedangkan perlakuan air panas 58°C 40 menit tidak
mengurangi viabilitas stek (Tabel 3). Dari penelitian ini diketahui bahwa perlakuan
air panas dengan waktu aplikasi yang lebih panjang menghambat daya tumbuh stek,
sedangkan perlakuan air panas dengan suhu lebih tinggi namun diaplikasikan dalam
waktu yang singkat tidak mempengaruhi daya tumbuh dan vigor stek.
Bibit berumur 7 minggu dipindah tanam ke dalam media kompos dan sekam
bakar di dalam polibag. Secara umum bibit stek menunjukkan pertumbuhan dan vigor
tanaman yang sangat baik setelah dipindah tanam ke dalam pot individu dengan
media sekam bakar dan kompos. Pertumbuhan tajuk tanaman yang baik didukung
oleh pertumbuhan perakaran yang baik. Ketersediaan nutrisi dari pupuk kompos
dalam media tanam mendukung pertumbuhan akar dan tajuk bibit. Bibit berumur 2
mst dan 3 mst ditampilkan pada gambar 8.

Gambar 8 Bibit nanas berumur 2 mst (a) dan 3 mst (b)
Pengaruh Perlakuan Air Panas terhadap Infektifitas PMWaV
Bibit dari stek tanaman sehat maupun tanaman sakit terlihat sehat dan tidak
menunjukkan gejala penyakit layu sampai akhir pengamatan (4 minggu setelah
tanam). Namun hasil deteksi PMWaV pada bibit dengan menggunakan antibodi
monoklonal terhadap PMWaV-1 dan PMWaV-2 menunjukkan bahwa sebagian bibit
positif terinfeksi PMWaV-1, PMWaV-2, maupun infeksi ganda PMWaV-1 dan
PMWaV-2 (Tabel 4).
Antibodi monoklonal spesifik PMWaV-1 dan PMWaV-2 yang digunakan
dalam pengujian TBIA menunjukkan reaksi kuat terhadap antigen PMWaV, dan tidak
terdapat reaksi terhadap tanaman sehat pada blot membran. Reaksi BCIP/NBT
terhadap konjugate-antigen PMWaV ditunjukkan dengan warna ungu (ditunjuk
dengan tanda panah) yang terlihat jelas pada jaringan pembuluh daun tanaman yang
terinfeksi PMWaV (Gambar 9 dan 10). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa
distribusi PMWaV pada jaringan tanaman nampaknya terbatas pada jaringan
pembuluh. Hasil ini mendukung laporan sebelumnya oleh Hu et al. (1997), Sether et
al. (1998), dan Tryono (2006) bahwa antigen PMWaV terdeteksi hanya berada pada
jaringan pembuluh pada daun muda, daun berumur sedang, juga pada akar, tetapi
tidak pada daun tua.
Sinyal berupa titik berwarna ungu menunjukkan bahwa sampel daun positif
terinfeksi oleh PMWaV-1 (Gambar 9) atau PMWaV-2 (Gambar 10). Sinyal ungu
terlihat pada sepanjang jaringan pembuluh daun nanas pada perlakuan kontrol positif
(K+), dan beberapa titik pembuluh pada sampel daun nanas dari stek yang diberi
perlakuan air panas 56 ºC selama 40 menit, serta sampel daun nanas dari stek yang
b a

diberi perlakuan air panas 58 ºC selama 60 menit (Gambar 9). Sinyal titik ungu
terlihat lebih jelas jika dilakukan pengamatan dengan bantuan kaca pembesar.
Gambar 9 Membran hasil deteksi PMWaV-1 dengan metode TBIA. Daun stek kontrol positif (K+), daun stek kontrol negatif (K-), daun stek tanaman sakit yang diberi perlakuan suhu 56 ºC (H56), daun dari stek tanaman sakit yang diberi perlakuan air panas 58 ºC (H58). Sinyal berwarna ungu (ditunjuk oleh tanda panah) pada jaringan pembuluh menunjukkan bahwa sampel daun positif terinfeksi PMWaV-1.
Sinyal ungu terlihat pada sepanjang jaringan pembuluh daun nanas pada
perlakuan kontrol positif (K+), dan beberapa titik pembuluh pada sampel daun nanas
dari stek yang diberi perlakuan air panas 56 ºC selama 40 menit, serta tidak ada
sinyal ungu pada sampel daun nanas dari stek yang diberi perlakuan air panas 58 ºC
selama 60 menit (Gambar 10). Sinyal titik ungu terlihat lebih jelas jika dilakukan
pengamatan dengan bantuan kaca pembesar.
K+ H56 H58 K-

Gambar 10 Membran hasil deteksi PMWaV-2 dengan metode TBIA. Daun stek kontrol positif (K+), daun stek kontrol negatif (K-), daun stek tanaman sakit yang diberi perlakuan suhu 56 ºC (H56), daun dari stek tanaman sakit yang diberi perlakuan air panas 58 ºC (H58). Sinyal berwarna ungu (ditunjuk oleh tanda panah) pada jaringan pembuluh menunjukkan bahwa sampel daun positif terinfeksi PMWaV-2.
Persentase stek terinfeksi PMWaV dihitung berdasarkan jumlah stek terinfeksi
dibagi jumlah stek yang diberi perlakuan. Persentase stek terinfeksi PMWaV-1,
PMWaV-2 dan infeksi ganda kedua virus ditampilkan pada tabel 4.
K+ H56 H58 K-

Tabel 4 Persentase stek terinfeksi PMWaV setelah mendapat perlakuan air panas
Perlakuan Air Panas Persentase stek terinfeksi PMWaV*)
PMWaV-1 PMWaV-2 PMWaV-1 & PMWaV-2
Suhu 56°C selama 60 menit 32,00a 20,00ab 10,00ab
Suhu 58°C selama 40 menit 21,00ab 0,00b 0,00b
Kontrol positif 44,33a 66,77a 18,33a
Kontrol negatif 0,00d 0,00b 0,00b *)Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%
(DMRT)
Berdasarkan persentase infeksi PMWaV-1 dan PMWaV-2 pada stek dari
tanaman sakit diketahui bahwa perlakuan air panas 58°C selama 40 menit pada
tanaman sakit mampu menekan infeksi PMWaV-2. Sedangkan perlakuan air panas
56°C selama 60 menit pada tanaman sakit tidak berpengaruh nyata terhadap infeksi
PMWaV-1 maupun PMWaV-2.
Eliminasi patogen dari bahan tanaman dengan perlakuan panas dapat
dilakukan jika toleransi patogen terhadap panas lebih rendah dibandingkan toleransi
bahan tanaman. Jika kedua syarat tersebut dapat terpenuhi, maka akan terdapat
interval perlakuan suhu perlakuan panas yang dapat mengeliminasi patogen tanpa
mengurangi viabilitas bahan tanaman. Interval suhu yang dapat mengeliminasi
patogen tanpa mengurangi viabilitas bahan tanaman tersebut disebut ”treatment
window” (Forsberg 2001). Dalam penelitian ini, perlakuan air panas 58 ºC selama 40
menit memenuhi persyaratan dalam ”treatment window” karena perlakuan tersebut
mampu menekan infeksi PMWaV-2 pada stek tanpa mengurangi viabilitas stek
tersebut.
Perlakuan panas berpengaruh terhadap transportasi virus di dalam tanaman,
baik transportasi antar sel (cell-to-cell movement) maupun transportasi jarak jauh
antar jaringan (Hadidi et al. 1998). Transportasi virus di dalam tanaman dimediasi
oleh protein yang dikode oleh virus tersebut yang disebut movement protein atau
transport protein. Perlakuan air panas yang diberikan pada tanaman yang terinfeksi
virus dapat menyebabkan gangguan fungsi movement protein di dalam tanaman
sehingga menghambat transportasi virus di dalam jaringan tanaman. Selain itu,
perlakuan panas di atas 37 ºC diketahui menghambat multiplikasi banyak jenis virus

(Hadidi et al. 1998), bahkan suhu 32 ºC dapat menghambat multiplikasi Plum pox
virus (Glasa et al. 2003). Gangguan dalam multiplikasi dan translokasi virus diduga
menyebabkan terhambatnya infeksi dan penyebaran PMWaV pada stek yang telah
diberi perlakuan air panas 58°C selama 40 menit.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Perlakuan air panas 58 °C selama 40 menit pada bahan stek nanas mampu
mengeliminasi PMWaV-2 tanpa mengurangi daya tumbuh dan vigor stek
nanas.
2. Perlakuan air panas dan ribavirin pada perbanyakan kultur jaringan
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan eksplan dan planlet setelah
perlakuan. Sehingga pengaruh perlakuan air panas dan ribavirin dalam
eliminasi PMWaV belum dapat diketahui.
Saran
Perlakuan air panas 58 °C selama 40 menit pada bahan perbanyakan stek
tanaman nanas dapat diaplikasikan untuk perbanyakan massal bibit nanas bebas
PMWaV. Penggunaan bibit nanas bebas PMWaV sangat penting dilakukan untuk
mengurangi resiko gagal panen petani nanas akibat penyakit layu nanas.

DAFTAR PUSTAKA
Auer CA, Motyka V, Brezinová A, Kamínek M. 1999. Endogenous cytokinin accumulation and cytokinin oxidase activity during shoot organogenesis of Petunia hybrida. Physiol. Plant. 105:141-147.
Bartholomew DP, Rohrbach KG, and Evans DO. 2002. Pineapple Cultivation in
Hawaii. Fruits and Nuts. F&N-7. Bartholomew DP, Paul RE, Rohrbach KG, ed. 2003. Pineapple : Botany, Production,
and Uses. CAB international. Beardsley JW. 1996. The pineapple mealybug complex: taxonomy, distribution and
host relationship. Acta Hort. 334: 383-386. Borroto FEG, Torres AJA, Laimer M. 2007. RT-PCR detection and protein-protein
interaction of viral component of pineapple mealybug wilt-associated virus-2
in Cuba. Plant Pathology. 89:435-439. Collin JL. 1960. The Pineapple. Leonard Hill, London. [CABI] Centre in Agricultural and Biological Institute. 2005. Plant protection
compedium. Cab International. Wallingford. United Kingdom. Carter W. 1933. The pineapple mealybug, Pseudococcus brevipes, and wilt of
pineapple. Phytopathology 23: 207-242. Deptan. 2005. Profil Nenas di Kabupaten Subang. http://www.deptan.go.id 23 Maret
2007. Dalimartha, S. 2004. Atlas tumbuhan obat Indonesia. http://www.pdpersi.com. 23
Maret 2006. Dawson WO, Saldana HL. 1984. Examination of mode of action ribavirin against
Tobacco mosaic virus. Intervirology.22:77-84. Forsberg G. 2001. Heat sanitation of cereal seeds with a new, efficient, cheap and
environmentally friendly method. Proceedings from Symposium no. 76 of the British Crop Protection Council “ Seed Treatment, Challenges and Opportunities”, ed. AJ Biddle, pp. 69-72. BCPC, Farnham.
Glasa M, Labonne G, Quiot JB. 2003. Effect of temperature on plum pox virus
infection [abstrak]. Acta Virol 47(1): 49-52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi [13 April 2007].

Gunawan LW. 1988. Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan. Laboratorium Kultur
Jaringan Tumbuhan, Pusat Antar Universitas (PAU) Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor.
Gunasinghe UB, German TL. 1989. Purification and partial characterization of a virus
from pineaplle. Phytopathology 79: 1337-1341. Hadidi A, Khetarpal RK, Koganezawa H. 1998. Plant Virus Diseases Control. USA:
APS. Hidayat D. 2006. Respon lima varietas nanas terhadap infeksi Pineapple mealybug
wilt-associated virus melalui vektor Dysmicoccus brevipes (Cockerrel) (Hemiptera: Pseudococcidae). [skripsi] Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Hu JS, Sether DM, Liu XP, Wang M. 1997. Use of tissue blotting immunoassay to
examine the distribution of pineapple Closterovirus in Hawaii. Phytopathology 88:1150-1154.
Hutahayan AJ. 2006. Peranan strain dan Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus
dan kutu putih (Dysmicoccus spp.) dalam menginduksi gejala layu pada tanaman nanas. [Thesis] Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
Katuuk, J. R. P. 1989. Teknik Kultur Jaringan dalam Mikropropagasi Tanaman.
Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi. Jakarta. 189 hal. Lim WH. 1985. Diseases and disorders of pineapples in peninsular Malaysia.
Malaysian Agricultural Research and Development Institut Report 97: 25-30.
Martelli GP, Agranovsky AA, Bar-Joseph M, Boscia D, Candresse T., et.al. 2003. The family Closteroviridae revised. Negative Strand Viruses 2003. Twelfth
International Conference on Negative Strand Viruses; Pisa, 14-19 Juni 2003. USA: ICTV. hlm 2039-2045.
Melzer MJ, Karasev AV, Sether DM, Hu JS. 2001. Nucleotide sequence, genome
organization, and phylogenetic analysis of pineapple mealybug wilt-associated virus 2. J. Gen. Virol 82:1-7.
[PKBT] Pusat Kajian Buah Tropika. 2008. Perbanyakan Massal Bibit Nenas dengan
Stek Daun. Pusat Kajian Buah Tropika, LPPM. Institut Pertanian Bogor. Rohrbach KG, Beardsley JW, German TL, Reimer NJ, Sanford WG. 1988.
Mealybug wilt, mealybug, and ants of pineapple. Plant Disease 72: 558-565. Roostika, I. And Mariska, I. 2003. In vitro culture of pineapple by organogenesis and
somatic embryogenesis: its utilization and prospect. Bul. AgroBio 6(1):34-40.

Sharma S, Singh B, Rani G, Zaidi AA et. al. 2006. Production of Indian citrus
ringspot virus free plants of Kinnow employing chemotherapy coupled with shoot tip grafting.
Sether DM, Karasev AV, Okumura C, Arakawa C, Zee F, Kislan MM, Busto JL, Hu
JS. 2001. Differentiation, distribution, and elimination of two different pineapple mealybug wilt-associated viruses found in pineapple. Plant Disease 85: 856-864.
Sether DM, Hu JS. 2002a. Closterovirus Infection and Mealybug Exposure are
Necessary for the Development of Mealybug Wilt of Pineapple Disease. Phytopathology 92: 928-935.
Sether DM, Hu JS. 2002b. Yield impact and spread of pineapple mealybug wilt-
associated virus-2 and mealybug wilt of pineapple in Hawaii. Plant Diseases 86: 867-874.
Sether DM, Karasev AV, Okumura C, Arakawa C, Zee F, Kislan MM, Busto JL, Hu
JS. 2001. Differentiation, distribution, and elimination of two different pineapple mealybug wilt-associated virus found in pineapple. Plant Diseases 85: 856-864.
Sether DM, Melzer MJ, Busto J, Hu JS. 2005. Diversity of mealybug transmissibility
of ampelovirus in pineapple. Plant Disease 89: 450-456. Sether DM, Ullman DE, Hu JS. 1998. Transmission of pineapple mealybug wilt-
associated virus by two species of mealybug (Dysmicoccus Spp.). Phytopathology 88:1224-1230.
Smith, M. K. H.-L. Ko, S. D. Hamill, G. M. Sanewski, and M. W. Graham. 2002.
Biotechnology, p 57-68. In D. P. Bartholomew, R. E. Paull, and K. G. Rohrbach (Eds). The Pineapple Botany, Production and Uses. CABI Publishing. New York.
Tryono R. 2006. Deteksi dan identifikasi Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus
penyebab penyakit layu pada tanaman nanas di Indonesia. [Tesis] Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
Wattimena GA. 1988. Zat Pengatur Tumbuh. Pusat Antar Universitas, Institut
Pertanian Bogor, Bogor. 247 hal. Widyanto H. 2005. Pola penyebaran penyakit layu dan kutu putih pada perkebunan
nanas (Ananas comosus (Linn.) Merr.) rakyat di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. [Skripsi] Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Wee, Y. C. dan M. L. C. Thongtham. 1997. Ananas comosus (L.) Merr., p. 68-76.
Dalam E. W. M. Verheij dan R. E. Coronel (Eds). PROSEA Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2 Buah-buahan yang Dapat Dimakan (Terjemahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Zaers, J. B. and M. O. Mapes. 1982. Action of growth regulation. In J. M. Bonga and
D. J. Durzan (Eds). Tissue Culture in Forestry. Martinus Nijhoff Publ. The Hague.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Komponen Larutan Media Inisiasi
No. Komponen Bahan Jml dlm media (mg/l)
Stok Penggunaan stok per liter
1. Makro NH4NO3 1650 10x 1/10x200=20
KNO3 1900
KH2PO4 170
MgSO4.7H2O 370
2. Mikro A MnSO4.4H2O 22,3 100x 1/100x500=5
ZnSO4. H2O 8,6
H3BO3 6.2
3. Mikro B KI 0,83 100x 1/100x500=5
Na2MoO4.2H2O 0,25
CuSO4.5H2O 0,025
CoCl2.6H2O 0,025
Fe-EDTA FeSO4.7H2O 27.8 100x 1/100x500=5
Na2EDTA 37,3
5. Myo-inositol 100 10x 1/10x100=10
6. Vitamin Thiamin-HCl 0,1 100x 1/100x500=5
Nicotinic acid 0,5
Pyridoxin-HCl 0,5
Glycine 2
7. CaCl2.2H2O 440 10x 1/10x100=10
8. Gula (sukrosa)
30000
9. Agar (pure agar)
6000-6500
10. BA 2
11. NAA 1
1 pH 5,8

Lampiran 2 Komponen Larutan Media B2N1
No. Komponen Bahan Jml dlm media (mg/l)
Stok Penggunaan stok per liter
1. Makro NH4NO3 1650 10x 1/10x200=20
KNO3 1900
KH2PO4 170
MgSO4.7H2O 370
2. Mikro A MnSO4.4H2O 22,3 100x 1/100x500=5
ZnSO4. H2O 8,6
H3BO3 6.2
3. Mikro B KI 0,83 100x 1/100x500=5
Na2MoO4.2H2O 0,25
CuSO4.5H2O 0,025
CoCl2.6H2O 0,025
4. BA 2
5. NAA 2
6. Gula (sukrosa)
30000
7. Agar (pure agar)
6000-6500
pH 5,8















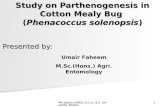


![FB5 Infektion i knogle.PPT [Kompatibilitetstilstand]odont.au.dk/fileadmin/ · ¾Efter necrosis pulpa Lokal infektion Apikal parodontitis Apikal parodontitis (AP) er en inflammation](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5d4a4d2788c99313138b6be5/fb5-infektion-i-kompatibilitetstilstandodontaudkfileadmin-efter-necrosis.jpg)
