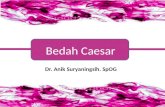Basic sciene bedah
-
Upload
debbie-takaliuang -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
Transcript of Basic sciene bedah
Tugas Bedah
Nama : Desy Purnamasari Kalembu
NIM : 11.2013.097
CoAss Bedah RSUD KOJA Jakarta Utara
1. Jelaskan mengenai kebutuhan cairan dan elektrolit dewasa maupun anak?
Pada orang sehat asupan dan pengeluaran air seimbang. Bila terjadi gangguan
keseimbangan maka mungkin diperlukan koreksi dengan nutrisi parenteral.
Asupan air dan makanan rata-rata adalah sekitar 2000 ml, dan kira-kira 200 ml air
metabolik berasal dari metabolisme nutrien di dalam tubuh. Air dieksresikan dalam urin dan
melalui penguapan yang tidak disadari. Jumlah eksresi urin sekitar 1300 ml/hari, sedangkan
melalui penguapan yang tidak disadari (insensible evaporation) sekitar 900 ml/hari.
Maka pada pasien yang tidak dapat memperoleh makanan melalui oral memerlukan
volume infus per hari yang setara dengan kehilangan air dari tubuh per hari, yaitu :
Dengan perhitungan yang lebih akurat lagi dapat dicari :
volume urin normal : 0,5-1 cc/kg/jam
Air metabolisme : Dewasa : 5 cc/kg/hari, anak 12-14 th : 5-6 cc/kg/hari, 7-11 th :
6-7 cc/kg/hari, balita : 8 cc/kg/hari
Insensible water loss IWL : Dewasa : 15 cc/kg/hari, Anak : 30-usia(th) cc/kg
hari. Jika ada kenaikan suhu : IWL + 200
Kebutuhan air dan elektrolit per hari
Pada orang dewasa :
Air : 25-40 ml/kg/hr
Kebutuhan homeostatis Kalium : 20-30 mEq/kg/hr2
Na : 2 mEq/kg/hr3
K : 1 mEq/kg/hr3
Pada anak dan bayi :
Air : 0-10 kg : 100 ml/kg/hr
10-20 kg : 1000 ml/kg + 50 ml/kg diatas 10 kg/hr
> 20 kg : 1500 ml/kg + 20 ml/kg diatas 20 kg/hr
Na : 3 Meq/kg/hr2
K : 2,5 Meq/kg/hr2
Faktor-faktor modifikasi kebutuhan cairan
Kebutuhan ekstra / meningkat pada :
Demam ( 12% tiap kenaikan suhu 1C )
Hiperventilasi
Suhu lingkungan tinggi
Aktivitas ekstrim
Setiap kehilangan abnormal ( ex: diare, poliuri, dll )
Kebutuhan menurun pada :
Hipotermi ( 12% tiap penurunan suhu 1C )
Kelembaban sangat tinggi
Oligouri atau anuria
Aktivitas menurun / tidak beraktivitas
Retensi cairan ( ex: gagal jantung, gagal ginjal, dll )
Gangguan keseimbangan cairan
Kehilangan cairan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan yang mengakibatkan
dehidrasi, misalnya pada keadaan gastroenteritis, demam tinggi, pembedahan, luka bakar, dan
penyakit lain yang menyebabkan input dan output tidak seimbang.
Dehidrasi
Adalah keadaan dimana kurangnya cairan tubuh dari jumlah normal akibat kehilangan cairan,
asupan yang tidak mencukupi atau kombinasi keduanya.
Dehidrasi dibedakan atas :
Dehidrasi hipotonik
o Kadar Na < 130 mmol/L
o Osmolaritas < 275 mOsm/L
o Letargi, kadang-kadang kejang
Dehidrasi isotonik
o Na dan osmolaritas serum normal
Dehidrasi hipertonik
o Na > 150 mmol/L
o Osmolaritas > 295 mOsm/L
o Haus, iritabel, bila Na > 165 mmol/L dapat terjadi kejang
Keadaan lain yang mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit yaitu :
Gastroenteritis, DHF, Difteri, Tifoid, Hiperemesis gravidarum, Sectio caesar, Histerektomi,
Kistektomi, Apendektomi, Splenektomi, Gastrektomi, Reseksi usus, Perdarahan intraoperatif,
Ketoasidosis Diabetikum.
Terapi cairan ialah tindakan untuk memelihara, mengganti cairan tubuh dalam batas-batas
fisiologis dengan cairan infus kristaloid (elektrolit) atau koloid (plasma ekspander) secara
intravena.
Terapi cairan ini dilakukan pada pasien-pasien dengan keadaan-keadaan seperti yang sudah
djelaskan sebelumnya. Selain itu kuhususnya dalam pembedahan dengan anestesia yang
memerlukan puasa sebelum dan sesudah pembedahan, maka terapi cairan tersebut berfungsi
untuk mengganti defisit cairan saat puasa sebelum dan sesudah pembedahan, mengganti
kebutuhan rutin saat pembedahan, mengganti perdarahan yang terjadi, dan mengganti cairan
yang pindah ke rongga ketiga.
I. Terapi cairan resusitasi
Terapi cairan resusitasi ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh atau
ekspansi cepat dari cairan intravaskuler untuk memperbaiki perfusi jaringan. Misalnya pada
keadaan syok dan luka bakar.
Terapi cairan resusitasi dapat dilakukan dengan pemberian infus Normal Saline (NS), Ringer
Asetat (RA), atau Ringer laktat (RL) sebanyak 20 ml/kg selama 30-60 menit. Pada syok
hemoragik bisa diberikan 2-3 l dalam 10 menit.
Larutan plasma ekspander dapat diberikan pada luka bakar, peningkatan sirkulasi kapiler seperti
MCI, syok kardiogenik, hemoragik atau syok septik. Koloid dapat berupa gelatin (hemaksel,
gelafunin, gelafusin), polimer dextrose (dextran 40, dextran 70), atau turunan kanji (haes,
ekspafusin)
Jika syok terjadi :
Berikan segera oksigen
Berikan cairan infus isotonic RA/RL atau NS
Jika respon tidak membaik, dosis dapat diulangi
Pada luka bakar :
24 jam pertama :
2-4 ml RL/RA per kg tiap % luka bakar
1/2 dosis diberikan 8 jam pertama, 1/2 dosis berikut 16 jam kemudian
Sesuaikan dosis infus untuk menjaga urin 30-50 ml/jam pada dewasa
Jika respon membaik, turunkan laju infus secara bertahap
Pertimbangan dalam resusitasi cairan :
1. Medikasi harus diberikan secara iv selama resusitasi
2. Perubahan Na dapat menyebabkan hiponatremi yang serius. Na serum harus dimonitor,
terutama pada pemberian infus dalam volume besar.
3. Transfusi diberikan bila hematokrit < 30
4. Insulin infus diberikan bila kadar gula darah > 200 mg%
5. Histamin H2-blocker dan antacid sebaiknya diberikan untuk menjaga pH lambung 7,0
II. Terapi cairan rumatan
Terapi rumatan bertujuan memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi. Diberikan dengan
kecepatan 80 ml/jam. Untuk anak gunakan rumus 4:2:1, yaitu :
4 ml/kg/jam untuk 10 kg pertama
2 ml/kg/jam untuk 10 kg kedua
1 ml/kg/jam tambahan untuk sisa berat badan
Terapi rumatan dapat diberikan infus cairan elektrolit dengan kandungan karbohidrat atau infus
yang hanya mengandung karbohidrat saja. Larutan elektrolit yang juga mengendung karbohidrat
adalah larutan KA-EN, dextran + saline, Ringer's dextrose, dll. Sedangkan larutan rumatan yang
mengandung hanya karbohidrat adalah dextrose 5%. Tetapi cairan tanpa elektrolit cepat keluar
dari sirkulasi dan mengisi ruang antar sel sehingga dextrose tidak berperan dalam hipovolemik.
Dalam terapi rumatan cairan keseimbangan kalium perlu diperhatikan karena seperti sudah
dijelaskan kadar berlebihan atau kekurangan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya.
Umumnya infus konvensional RL atau NS tidak mampu mensuplai kalium sesuai kebutuhan
harian. Infus KA-EN dapat mensuplai kalium sesuai kebutuhan harian.
Pada pembedahan akan menyebabkan cairan pindah ke ruang ketiga, ke ruang peritoneum, ke
luar tubuh. Untuk menggantinya tergantung besar kecilnya pembedahan, yaitu :
6-8 ml/kg untuk bedah besar
4-6 ml/kg untuk bedah sedang
2-4 ml/kg untuk bedah kecil
2. Jelaskan tentang perdarahan (menurut ATLS dan bagaimana penatalaksanaannya)?
Tabel 1. Klasifikasi Perdarahan ATLS
Kelas Rata-rata
Kehilangan
Darah (mL)
Volume
Darah (%)
Tanda dan Gejala Umum Kebutuhan
Resusitasi
I < 750 < 15 Tidak ada perubahan denyut
jantung, pernafasan dan tekanan
darah
Tidak ada
II 750 – 1500 15 – 30 Takikardi dan takipnoe; tekanan Biasanya larutan
darah sistolik mungkin hanya
menurun sedikit; sedikit pnoe;
tekanan darah sistolik mungkin
hanya menurun sedikit;
pengurangan
pengurangan output urin (20-30
mL/jam)
kristaloid tunggal,
namun beberapa
pasien mungkin
membutuhkan
transfusi darah
III 1500 – 2000 30 – 40 Takikardi dan takipnoe yang
jelas, ekstremitas dingin dengan
pengisian-kembali kapiler
terlambat secara
signifikan,menurunnya tekanan
darah sistolik, menurunnya
status mental,
menurunnya output urin (5-15
mL/jam)
Seringnya
membutuhkan
transfusi darah
IV > 2000 > 40 Takikardia jelas, tekanan darah
sistolik yang menurun secara
signifikan, kulit dingin dan
pucat, mental status yang
menurun dengan
hebat,output urin yang tak
berarti
Perdarahan yang
membahayakan-jiwa
membutuhkan
transfusi segera
I. Primary Survey
Selama primary survey, keadaan yang mengancam nyawa harus dikenali, dan
resusitasinya dilakukan pada saat itu juga.
a. Airway, menjaga airway dengan kontrol servical (cervical spine control)
Yang pertama dinilai adalah kelancara jalan nafas. Meliputi pemeriksaan adanya
obstruksi jalan nafas (karena benda asing, fraktur tulang wajahfraktur mandibular atau
maksila, fraktur laring atau trakea). Pada penderita yang dapa berbicara, dapat dianggap
bahwa jalan nafas bersih, walaupun demikian penilaian ulang airway tetap dilakukan.
Membebaskan airway dapat dimulai dengan chin lift atau jaw thrust. Pada pasien dengan
GCS ≤ 8 biasanya memerlukan pemasangan airway definitif. Selama memeriksa dan
memperbaiki airway, tidak boleh dilakukan ekstensi, fleksi, atau rotasi leher. Kecurigaan
fraktur servical, harus dipakai alat imobilisasi (collar neck).
b. Breathing, menjaga pernapasan dengan ventilasi
Ventilasi yang baik meliputi fungsi yg baik dari paru, dinding dada dan
diafragma. Inspeksi dan palpasi dapat memperlihatkan kelainan dinding dada yang
mungkin mengganggu ventilasi, perkusi dilakukan untuk menilai adanya udara atau darah
dalam rongga pleura, dan auskultasi dilakukan untuk memastikan masuknya udara ke
dalam paru. Perlukaan yg mengakibatkan gangguan ventilasi yg berat adalah tension
pneumo-thorax, flail chest dengan kontusio paru dan open pneumothorax.
c. Circulation, dengan control perdarahan (hemorrhage control)
i. Volume darah dan cardiac output. Keadaan hipotensi harus dianggap disebabkan
oleh hipovolemia, samapi terbukti sebaliknya. Maka diperlukan penilaian yang
cepat dari status hemodinamik penderita. 3 temua klnis mengenai keadaan
hemodinamik, yakni tingkat kesadaran, warna kulit yang pucat keabu-abuan pada
wajah dan kulit ekstremitas yang pucat, dan nadi yang cepat dan kecil (nadi yang
tidak teratur merupakan tanda gangguan jantung). Tidak ditemukannya pulsai arteri
besar merupakan pertanda diperlukannya resusitasi segera.
ii. Perdarahan.
d. Disability, dengan status neurologis
Penilaian yang dilakukan adalah menilai kesadaran, ukuran dan reaksi pupil,
tanda-tanda lateralisasi dan tingkat (level) cedera spinal. Penilaian dengan GSC (Glasgow
coma scale) dapat meramal outcome penderita. Penrununa kesadaran menuntut dilakukan
reevaluasi terhadap keadaan oksigen, ventilasi, dan perfusi.
e. Exposure/environmental control : buka baju penderita, tetapi cegah hipotermia
Pasien harus dibuka keseluruhan pakaiannya untuk memeriksa dan evaluasi
penderita dan tetap menjaga suhu tubuh pasien. Diberikan selimuti agar tidak hipotermia
dan diberikan cairan kristaloid intra-vena yang sudah di hangatkan.
II. Secondary Survey
Riwayat AMPLE (alergi, medikasi (obat ynag diminum saat ini), past
illness/pregnancy, last meal, event/environment yang berhubungan dengan
kejadian.
Pemeriksaan fisik meliputi, kepala, maksilo-fasial, vertebra servical dan leher,
toraks, abdomen, perineum.rektum/vagina, muskulo-skeletal, dan neurologis
3. Jelaskan mengenai definisi syok dan macam-macam syok.
Syok adalah suatu keadaan gawat yang terjadi jika sistem kardiovaskuler (jantung dan
pembuluh darah) tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dalam jumlah yang
memadai. Syok biasanya berhubungan dengan tekanan darah rendah dan kematian sel
maupun jaringan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kematian apabila tidak segera
ditangani.
Syok hipovolemik
Merupakan kondisi medis atau bedah dimana terjadi kehilangan cairan dengan cepat
yang berakhir pada kegagalan beberapa organ, disebabkan oleh volume sirkulasi
yang tidak adekuat. Sering syok hipovolemik sebagai akibat dari kehilangan darah
yang cepat (syok hemoragik). Penyebab tersering syok hemoragik adalah trauma
tembus, pendarahan gastrointestinal, rupturnya aorta abdominal.Syok hipovolemik
dapat merupakan akibat dari kehilangan cairan yang signifikan (selain darah).
Syok kardiogenik
Merupakan akibat dari kegagalan fungsi pompa jantung yang mengakibatkan curah
jantung menjadi berkurang atau berhenti sama sekali. Syok ini dapat didiagnosa
dengan adanya tanda-tanda syok yang disertai dengan adanya penyakit jantung,
seperti infark miokard yang luas, gangguan irama jantung, atau adanya emboli paru.
Syok septik
Suatu keadaan dimana tekanan darah turun sampai pada tingkat yang
membahayakan yang diakibatkan oleh adanya infeksi . hal ini disebabkan adanya
racun yang dihasilkan oleh bakteri dan akibat sitokinesis. Racun yang dikeluarkan
oleh bakteri dapat mengakibatkan kerusakan jaringan dan menganggu peredaran
darah. infeksi sistemik yang biasanya terjadi yaitu o,eh kuman gram negative yang
menyebabkan kolaps kardiovaskular. Endotoksin bakteri gram negative ini
menyebabkan vasodilatasi kapilar dan terbukanya hubungan pintas arteriovena
perifer. Selain itu terjadi pula vasodilatasi perifer yang menyebabkan hipovolemia
relative, dan terjadi juga peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan
hilangnya cairan intravascular ke interstisial yang terlihat sebagai udem.
Syok anafilaktik
Merupakan syok yang diakibatkan oleh suatu reaksi alergi yang bisa disebabkan oleh
makanan, obat, bahan kimia maupun gigitan serangga. Kondisi ini dapat
menyebabkan kematian. Jika seseorang sensitive terhadap suatu antigen lalu terjadi
kontak lagi terhadap antigen itu maka akan timbul reaksi hipersensitivitas. Antigen
tersebut terikat pada permukaan sel mast kemudian terjadi degranulasi, pengeluaran
histamine serta zat vasoaktif lain. Hal tersebut menyebabkan peningkatan
permeabilitas dan dilatasi kapiler secara menyeluruh.pada syok anafilatik bisa terjadi
bronkospasme yang menurunkan ventilasi.
4. Jelaskan mengenai keseimbangan asam dan basa.
Alkalosis Metabolic
Definisi alkalosis metabolik adalah suatu keadaan dimana darah dalam keadaan basa
karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu
banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode
muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung
(seperti yang kadang-kadang dilakukan di rumah sakit, terutama setelah pembedahan perut).
Pada kasus yang jarang, alkalosis metabolik terjadi pada seseorang yang mengkonsumsi
terlalu banyak basa dari bahan-bahan seperti soda bikarbonat. Selain itu, alkalosis metabolik
dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak
mempengaruhi kemampuan ginjal dalam mengendalikan keseimbangan asam basa darah.
Penyebab utama akalosis metabolic penggunaan diuretik (tiazid, furosemid, asam etakrinat),
kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung, kelenjar adrenal yang terlalu
aktif (sindroma Cushing atau akibat penggunaan kortikosteroid).
Gejala alkalosis metabolik dapat menyebabkan iritabilitas (mudah tersinggung), otot
berkedut dan kejang otot; atau tanpa gejala sama sekali. Bila terjadi alkalosis yang berat,
dapat terjadi kontraksi (pengerutan) dan spasme (kejang) otot yang berkepanjangan (tetani).
Diagnosa dilakukan pemeriksaan darah arteri untuk menunjukkan darah dalam keadaan
basa. Pengobatan biasanya alkalosis metabolik diatasi dengan pemberian cairan dan
elektrolit (natrium dan kalium) . Pada kasus yang berat, diberikan amonium klorida secara
intravena.
Alkalosis Respiratorik
Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan dimana darah menjadi basa karena
pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbondioksida dalam
darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang
menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbondioksida yang dikeluarkan dari aliran darah.
Penyebab hiperventilasi yang paling sering ditemukan adalah kecemasan. Penyebab lain dari
alkalosis respiratorik adalah rasa nyeri, sirosis hati, kadar oksigen darah yang rendah,
demam, overdosis aspirin.
Gejala alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat
menyebabkan rasa gatal disekitar bibir dan wajah. Jika keadaannya makin memburuk, bisa
terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran.
Diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pengukuran kadar karbondioksida dalam
darah arteri. pH darah juga sering meningkat. Pengobatan biasanya satu-satunya
pengobatan yang dibutuhkan adalah memperlambat pernafasan. Jika penyebabnya adalah
kecemasan, memperlambat pernafasan bisa meredakan penyakit ini. Jika penyebabnya
adalah rasa nyeri, diberikan obat pereda nyeri. Menghembuskan nafas dalam kantung kertas
(bukan kantung plastik) bisa membantu meningkatkan kadar karbondioksida setelah
penderita menghirup kembali karbondioksida yang dihembuskannya. Pilihan lainnya adalah
mengajarkan penderita untuk menahan nafasnya selama mungkin, kemudian menarik nafas
dangkal dan menahan kembali nafasnya selama mungkin. Hal ini dilakukan berulang dalam
satu rangkaian sebanyak 6-10 kali. Jika kadar karbondioksida meningkat, gejala
hiperventilasi akan membaik, sehingga mengurangi kecemasan penderita dan menghentikan
serangan alkalosis respiratorik.
Asidosis Metabolik
Pengertian asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan, yang
ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman
melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Seiring dengan
menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha
tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah
karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut
dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih. Tetapi kedua mekanisme
tersebut bisa terlampaui jika tubuh terus menerus menghasilkan terlalu banyak asam,
sehingga terjadi asidosis berat dan berakhir dengan keadaan koma.
Penyebab asidosis metabolik dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok utama
yaitu (1) jumlah asam dalam tubuh dapat meningkat jika mengkonsumsi suatu asam atau
suatu bahan yang diubah menjadi asam. Sebagian besar bahan yang menyebabkan
asidosis bila dimakan dianggap beracun. Contohnya adalah metanol (alkohol kayu) dan
zat anti beku (etilen glikol). Overdosis aspirin pun dapat menyebabkan asidosis
metabolic. (2) tubuh dapat menghasilkan asam yang lebih banyak melalui metabolisme.
Tubuh dapat menghasilkan asam yang berlebihan sebagai suatu akibat dari beberapa
penyakit, salah satu diantaranya adalah diabetes melitus tipe I. Jika diabetes tidak
terkendali dengan baik, tubuh akan memecah lemak dan menghasilkan asam yang disebut
keton. Asam yang berlebihan juga ditemukan pada syok stadium lanjut, dimana asam
laktat dibentuk dari metabolisme gula. (3) asidosis metabolik bisa terjadi jika ginjal tidak
mampu untuk membuang asam dalam jumlah yang semestinya. Bahkan jumlah asam
yang normalpun bisa menyebabkan asidosis jika ginjal tidak berfungsi secara normal.
Kelainan fungsi ginjal ini dikenal sebagai asidosis tubulus renalis, yang bisa terjadi pada
penderita gagal ginjal atau penderita kelainan yang mempengaruhi kemampuan ginjal
untuk membuang asam. Penyebab utama dari asidois metabolic adalah gagal ginjal.
Penyebab lain seperti asidosis tubulus renalis (kelainan bentuk ginjal), ketoasidosis
diabetikum, asidosis laktat (bertambahnya asam laktat), bahan beracun (seperti etilen
glikol, overdosis salisilat, metanol, paraldehid, asetazolamid atau amonium klorida),
kehilangan basa (misalnya bikarbonat) melalui saluran pencernaan karena diare, leostomi
atau kolostomi.
Gejala asidosis metabolik ringan bisa tidak menimbulkan gejala, namun biasanya
penderita merasakan mual, muntah dan kelelahan. Pernafasan menjadi lebih dalam atau
sedikit lebih cepat, namun kebanyakan penderita tidak memperhatikan hal ini. Sejalan
dengan memburuknya asidosis, penderita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa,
rasa mengantuk, semakin mual dan mengalami kebingungan. Bila asidosis semakin
memburuk, tekanan darah dapat turun, menyebabkan syok, koma dan kematian.
Diagnosis asidosis biasanya ditegakkan berdasarkan hasil pengukuran pH darah
yang diambil dari darah arteri (arteri radialis di pergelangan tangan). Darah arteri
digunakan sebagai contoh karena darah vena tidak akurat untuk mengukur pH darah.
Untuk mengetahui penyebabnya, dilakukan pengukuran kadar karbon dioksida dan
bikarbonat dalam darah. Mungkin diperlukan pemeriksaan tambahan untuk membantu
menentukan penyebabnya. Misalnya kadar gula darah yang tinggi dan adanya keton
dalam urin biasanya menunjukkan suatu diabetes yang tak terkendali. Adanya bahan
toksik dalam darah menunjukkan bahwa asidosis metabolik yang terjadi disebabkan oleh
keracunan atau overdosis. Kadang-kadang dilakukan pemeriksaan air kemih secara
mikroskopis dan pengukuran pH air kemih.
Pengobatan asidosis metabolik tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh,
diabetes dikendalikan dengan insulin atau keracunan diatasi dengan membuang bahan
racun tersebut dari dalam darah. Kadang-kadang perlu dilakukan dialisa untuk mengobati
overdosis atau keracunan yang berat. Asidosis metabolik juga bisa diobati secara
langsung. Bila terjadi asidosis ringan, yang diperlukan hanya cairan intravena dan
pengobatan terhadap penyebabnya. Bila terjadi asidosis berat, diberikan bikarbonat
mungkin secara intravena; tetapi bikarbonat hanya memberikan kesembuhan sementara
dan dapat membahayakan.
Asidosis Respiratorik
Pengertian Asidosis Respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena
penumpukan karbondioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang
buruk atau pernafasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernafasan mengendalikan
jumlah karbondioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul
karbondioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Tingginya kadar
karbondioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernafasan, sehingga
pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam.
Penyebab asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan
karbondioksida secara adekuat. Hal ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit berat yang
mempengaruhi paru- paru, seperti emfisema, ronkitis kronis, pneumonia berat, edema
pulmoner dan asma. Selain itu, seseorang dapat mengalami asidosis respiratorik akibat
narkotika dan obat tidur yang kuat, yang menekan pernafasan. Asidosis respiratorik dapat
juga terjadi bila penyakit-penyakit dari saraf atau otot dada menyebabkan gangguan
terhadap mekanisme pernafasan.
Gejala pertama berupa sakit kepala dan rasa mengantuk. Jika keadaannya
memburuk, rasa mengantuk akan berlanjut menjadi stupor (penurunan kesadaran) dan
koma. Stupor dan koma dapat terjadi dalam beberapa saat jika pernafasan terhenti atau
jika pernafasan sangat terganggu, atau setelah berjam-jam jika pernafasan tidak terlalu
terganggu. Ginjal berusaha untuk mengkompensasi asidosis dengan menahan bikarbonat,
namun proses ini memerlukan waktu beberapa jam bahkan beberapa hari.
Diagnose biasanya diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan pH darah
dan pengukuran karbondioksida dari darah arteri. Pengobatan asidosis respiratorik
bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru. Obat-obatan untuk memperbaiki
pernafasan bisa diberikan kepada penderita penyakit paru- paru seperti asma dan
emfisema. Pada penderita yang mengalami gangguan pernafasan yang berat, mungkin
perlu diberikan pernafasan buatan dengan bantuan ventilator mekanik.
5. Jelaskan mengenai minor set.
A. Instrumen Dengan Fungsi Memotong
1. Pisau Scalpel + Pegangan
Scalpel merupakan mata pisau kecil yang digunakan bersama pegangannya. Alat ini
bermanfaat dalam menginsisi kulit dan memotong jaringan secara tajam. Selain itu, alat ini juga
berguna untuk mengangkat jaringan/benda asing dari bagian dalam kulit. Setiap pisau scalpel
memiliki dua ujung yang berbeda, yang satu berujung tajam sebagai bagian pemotong dan yang
lainnya berujung tumpul berlubang sebagai tempat menempelnya pegangan scalpel. Cara
pemasangannya: pegang area tumpul pisau dengan needle-holder dan hubungkan lubang pada
area tersebut pada lidah pegangan sampai terkunci (terdengar bunyi). Cara pelepasan: pegang
ujung pisau dengan needle-holder dan lepaskan dari lidah pegangan, kemudian buang di tempat
sampah. Pegangan scalpel yang sering digunakan adalah yang berukuran 3 yang dapat digunakan
bersama pisau scalpel dalam ukuran beragam. Sedangkan pisau scalpel yang sering digunakan
adalah yang berukuran no.15. Ukuran no.11 digunakan untuk insisi abses dan hematoma
perianal. Pegangan scalpel digunakan seperti pulpen dengan kontrol maksimal pada waktu
pemotongan dilakukan. Dalam praktek keseharian, pegangan scalpel biasanya diabaikan
sehingga hanya memakai pisau scalpel. Hal ini bisa diterima dengan pertimbangan pisaunya
masih dalam keadaan steril (paket baru) dan harus digunakan dengan pengontrolan yang baik
agar tidak menimbulkan kerusakan jaringan sewaktu memotong.
2. Gunting
Pada dasarnya gunting mengkombinasikan antara aksi mengiris dan mencukur. Mencukur
membutuhkan aksi tekanan halus yang saling bertentangan antara ibu jari dan anak jari lainnya.
Gerakan mencukur ini biasanya dilakukan oleh tangan dominan yang bersifat tidak disadari dan
berdasarkan insting. Sebaiknya gunakan ibu jari dan jari manis pada kedua lubang gunting. Hal
ini akan menyebabkan jari telunjuk menyokong instrumen pada waktu memotong sehingga kita
dapat memotong dengan tepat. Selain itu, penggunaan ibu jari dan jari telunjuk pada lubang
gunting biasanya pengontrolannya berkurang. Jenis-jenis gunting berdasarkan objek kerjanya,
yakni gunting jaringan (bedah), gunting benang, gunting perban dan gunting iris.
a. Gunting Jaringan (bedah)
Gunting jaringan (bedah) terdiri atas dua bentuk. Pertama, berbentuk ujung tumpul dan
berbentuk ujung bengkok. Gunting dengan ujung tumpul digunakan untuk membentuk bidang
jaringan atau jaringan yang lembut, yang juga dapat dipotong secara tajam. Gunting dengan
ujung bengkok dibuat oleh ahli pada logam datar dengan cermat. Pemotongan dengan gunting ini
dilakukan pada kasus lipoma atau kista. Biasanya dilakukan dengan cara mengusuri garis batas
lesi dengan gunting. Harus dipastikan kalau pemotongan dilakukan jangan melewati batas lesi
karena dapat menyebabkan kerusakan.
b. Gunting Benang (dressing scissors)
Gunting benang didesain untuk menggunting benang. Gunting ini berbentuk lurus dan
berujung tajam. Gunakan hanya untuk menggunting benang, tidak untuk jaringan. Gunting ini
juga digunakan saat mengangkat benang pada luka yang sudah kering dengan tehnik selipan dan
sebaiknya pemotongan benang menggunakan bagian ujung gunting. Hati-hati dalam pemotongan
jahitan. Jika ujung gunting menonjol keluar jahitan, terdapat resiko memotong struktur lainnya.
c. Gunting Perban
Gunting perban merupakan gunting berujung sudut dengan ujung yang tumpul. Gunting
ini memiliki kepala kecil pada ujungnya yang bermanfaat untuk memudahkan dalam memotong
perban. Jenis gunting ini terdiri atas knowles dan lister. Bagian dasar gunting ini lebih panjang
dan digunakan sangat mudah dalam pemotongan perban. Ujung tumpulnya didesain untuk
mencegah kecelakaan saat remove perban dilakukan. Selain untuk membentuk dan memotong
perban sesaat sebelum menutup luka, gunting ini juga aman digunakan untuk memotong perban
saat perban telah ditempatkan di atas luka. (wikipedia)
d. Gunting Iris
Gunting iris merupakan gunting dengan ujung yang tajam dan berukuran kecil sekitar 3-4
inchi. Biasanya digunakan dalam pembedahan ophtalmicus khususnya iris. Dalam bedah minor,
gunting iris digunakan untuk memotong benang oleh karena ujungnya yang cukup kecil untuk
menyelip saat remove benang dilakukan. (dictionary online)
B. Instrumen Dengan Fungsi Menggenggam
3. Pinset Anatomi
Pinset Anatomi memiliki ujung tumpul halus. Secara umum, pinset digunakan oleh ibu
jari dan dua atau tiga anak jari lainnya dalam satu tangan. Tekanan pegas muncul saat jari-jari
tersebut saling menekan ke arah yang berlawanan dan menghasilkan kemampuan menggenggam.
Alat ini dapat menggenggam objek atau jaringan kecil dengan cepat dan mudah, serta
memindahkan dan mengeluarkan jaringan dengan tekanan yang beragam. Pinset Anatomi ini
juga digunakan saat jahitan dilakukan, berupa eksplorasi jaringan dan membentuk pola jahitan
tanpa melibatkan jari. (wikipedia)
4. Pinset Chirurgis
Pinset Chirurgis biasanya memiliki susunan gigi 1x2 (dua gigi pada satu bidang). Pinset
bergigi ini digunakan pada jaringan; harus dengan perhitungan tepat, oleh karena dapat merusak
jaringan jika dibandingkan dengan pinset anatomi (dapat digunakan dengan genggaman halus).
Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan pinset anatomi yakni untuk membentuk pola jahitan,
meremove jahitan, dan fungsi-fungsi lainnya.(wikipedia)
5. Klem Jaringan
Klem jaringan berbentuk seperti penjepit dengan dua pegas yang saling berhubungan
pada ujung kakinya. Ukuran dan bentuk alat ini bervariasi, ada yang panjang dan adapula yang
pendek serta ada yang bergigi dan ada yang tidak. Alat ini bermanfaat untuk memegang jaringan
dengan tepat. Biasanya dipegang oleh tangan dominan, sedangkan tangan yang lain melakukan
pemotongan, atau menjahit. Cara pemegangannya: klem dipegang dalam keadaan relaks seperti
memegang pulpen dengan posisi di tengah tangan. Banyak orang yang memegang klem ini
dengan salah, yang memaksa lengan dalam posisi pronasi penuh dan menyebabkan tangan
menjadi tegang. Dalam penggunaannya, hati-hati merusak jaringan. Pegang klem selembut
mungkin, usahakan genggam jaringan sedalam batas yang seharusnya. Klem jaringan bergigi
memiliki gigi kecil pada ujungnya yang digunakan untuk memegang jaringan dengan kuat dan
dengan pengontrolan yang akurat. Hati-hati, kekikukan pada saat menggunakan alat ini dapat
merusak jaringan. Kemudian, klem tidak bergigi juga memiliki resiko merusak jaringan jika
jepitan dibiarkan terlalu lama, karena klem ini memiliki tekanan yang kuat dalam menggenggam
jaringan.
C. Instrumen Dengan Fungsi Menghentikan Perdarahan
6. Klem Arteri
Pada prinsipnya, klem arteri bermanfaat untuk menghentikan perdarahan pembuluh darah
kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak
dibutuhkan. Secara umum, klem arteri dan needle-holder memiliki bentuk yang sama.
Perbedaannya pada struktur jepitan (gambar 2), dimana klem arteri, struktur jepitannya berupa
galur paralel pada permukaannya dan ukuran panjang pola jepitannya sampai handle agak lebih
panjang dibanding needle-holder. Alat ini juga tersedia dalam dua bentuk yakni bentuk lurus dan
bengkok (mosquito). Namun, bentuk bengkok (mosquito) lebih cocok digunakan pada bedah
minor.
Cara penggunaan: klem arteri memiliki ratchet pada handlenya. Ratchet inilah yang
menyebabkan posisi klem arteri dalam keadaan terututup (terkunci). Ratchet umumnya memiliki
tiga derajat, dimana pada saat penutupan jangan langsung menggunakan derajat akhir karena
akan mengikat secara otomatis dan sulit untuk dilepaskan. Pelepasan klem dilakukan dengan
cara pertama harus ditekan ke dalam handlenya, kemudian dipisahkan handlenya sambil
membuka keduanya. Sebaiknya gunakan ibu jari dan jari manis karena hal ini akan menyebabkan
jari telunjuk mendukung instrumen bekerja sehingga dapat memposisikan jepitan dengan tepat.
Jepitan klem arteri berbentuk halus dengan galur lintang paralel yang membentuk chanel
lingkaran saat instrumen ditutup. Jepitan ini berukuran relatif panjang terhadap handled yang
memungkinkan genggaman jaringan lebih halus tanpa pengrusakan. Jepitan dengan ujung
bengkok (mosquito) berfungsi untuk membantu pengikatan pembuluh darah. Jangan
menggunakan klem ini untuk menjahit, oleh karena struktur jepitannya tidak mendukung dalam
memegang needle.
D. Instrumen Dengan Fungsi Menjahit
7. Needle Holder
Needle holder bermanfaat untuk memegang needle saat insersi jahitan dilakukan. Secara
keseluruhan antara needle holder dan klem arteri berbentuk sama. Handled dan ujung jepitannya
bisa berbentuk lurus ataupun bengkok. Namun, yang paling penting adalah perbedaan pada
struktur jepitannya (gambar 2). Struktur jepitan needle holder berbentuk criss-cross di
permukaannya dan memiliki ukuran handled yang lebih panjang dari jepitannya, untuk tahanan
yang kuat dalam menggenggam needle. Oleh karena itu, jangan menggenggam jaringan dengan
needle holder karena akan menyebabkan kerusakan jaringan secara serius.
Cara penggunaan: cara menutup dan melepas sama dengan metode ratchet yang telah
dipaparkan pada penggunaan klem arteri di atas. Needle digenggam pada jarak 2/3 dari ujung
berlubang needle, dan berada pada ujung jepitan needle-holder. Hal ini akan memudahkan
tusukan jaringan pada saat jahitan dilakukan. Selain itu, pemegangan needle pada area dekat
dengan engsel needle holder akan menyebabkan needle menekuk. Kemudian, belokkan needle
sedikit ke arah depan pada jepitan instrumen karena akan disesuaikan dengan arah alami tangan
ketika insersi dilakukan dan tangan akan terasa lebih nyaman. Kegagalan dalam membelokkan
needle ini juga akan menyebabkan needle menekuk.
Tehnik menjahit: jaga jari manis dan ibu jari menetap pada lubang handle saat menjahit
dilakukan yang membatasi pergerakan tangan dan lengan. Pegang needle holder dengan telapak
tangan akan memberikan pengontrolan yang baik. Secara konstan, jangan mengeluarkan jari dari
lubang handled karena dapat merusak ritme menjahit. Pertimbangkan pergunakan ibu jari pada
lubang handled yang menetap, namun manipulasi lubang lainnya dengan jari manis dan
kelingking.
Gambar 2. Perbedaan Struktur Jepitan Antara Klem Jaringan, Klem arteri dan Needle Holder
8. Benang Bedah
Benang bedah dapat bersifat absorbable dan non-absorbable. Benang yang absorbable
biasanya digunakan untuk jaringan lapisan dalam, mengikat pembuluh darah dan kadang
digunakan pada bedah minor. Benang non-absorbable biasanya digunakan untuk jaringan
tertentu dan harus diremove. Selain itu, benang bedah ada juga yang bersifat alami dan sintetis.
Benang tersebut dapat berupa monofilamen (Ethilon atau prolene) atau jalinan (black silk).
Umumnya luka pada bedah minor ditutup dengan menggunakan benang non-absorbable. Namun,
jahitan subkutikuler harus menggunakan jenis benang yang absorbable.
Black silk adalah benang jalinan non-absorbable alami yang paling banyak digunakan.
Meskipun demikian, benang ini dapat menimbulkan reaksi jaringan, dan menghasilkan luka yang
agak besar. Jenis benang ini harus dihindari, karena saat ini telah banyak benang sintetis
alternatif yang memberikan hasil yang lebih baik. Luka pada kulit kepala yang berbatas
merupakan pengecualian, oleh karena penggunaan jenis benang ini lebih memuaskan.
Benang non-abosrbable sintetis terdiri atas prolene dan ethilon (nama dagang). Benang
ini berbentuk monofilamen yang merupakan benang terbaik. Jenis benang ini cukup halus dan
luwes dan menghasilkan sedikit reaksi jaringan. Namun, jenis benang ini lebih sulit diikat dari
silk sehingga sering menyebabkan jahitan terbuka. Masalah ini dapat diselesaikan dengan
menggunakan tehnik khusus seperti menggulung benang saat jahitan dilakukan atau mengikat
benang dengan menambah lilitan. Prolene (monofilamen polypropylene) dapat meningkatkan
keamanan jahitan dan lebih mudah diremove dibandingkan dengan Ethilon (monofilamen
polyamide).
Catgut merupakan contoh terbaik dalam kelompok benang absorbable alami. Jenis
benang ini merupakan monofilamen biologi yang dibuat dari usus domba dan sapi. Terdapat dua
macam catgut, plain catgut dan chromic catgut. Plain catgut memiliki kekuatan selama 7-10 hari.
Sedangkan chromic catgut memiliki kekuatan selama 28 hari. Namun, kedua jenis benang ini
dapat menghasilkan reaksi jaringan.
Benang absorbable sintetis terdiri atas vicryl (polygactin) dan Dexon (polyclycalic acid)
yang merupakan benang multifilamen. Benang ini berukuran lebih panjang dari catgut dan
memiliki sedikit reaksi jaringan. Penggunaan utamanya adalah untuk jahitan subkutikuler yang
tidak perlu diremove. Selain itu, juga dapat digunakan untuk jahitan dalam pada penutupan luka
dan mengikat pembuluh darah (hemostasis).
Terdapat dua sistem dalam mengatur penebalan benang, yakni dengan sistem metrik dan
sistem tradisional. Penomoran sistem metrik sesuai dengan diameter benang dalam per-sepuluh
milimeter. Misalnya, benang dengan ukuran 2 berarti memiliki diameter 0.2 mm. Sistem
tradisional kurang rasional namun banyak yang menggunakannya. Ketebalan benang disebutkan
menggunakan nilai nol misalnya 3/0, 4/0, 6/0 dan seterusnya. Paling besar nilainya, ketebalannya
semakin kecil. 6/0 merupakan nomor dengan diameter paling halus yang tebalnya seperti rambut,
digunakan pada wajah dan anak-anak. 3/0 adalah ukuran yang paling tebal yang biasa digunakan
pada sebagian besar bedah minor. Khususnya untuk kulit yang keras (kulit bahu). 4/0 merupakan
nilai pertengahan yang juga sering digunakan.
Dalam suatu paket jahitan, terdapat semua informasi mengenai benang dan needlenya
secara lengkap di cover paketnya. Setiap paket jahitan memiliki dua bagian luar, pertama yang
terbuat dari kertas kuat yang mengikat pada cover transaparan. Paket jahitan ini dijamin dalam
keadaan steril sampai covernya terbuka. Oleh karena itu, saat membuka paket, simpan ke dalam
wadah steril. Bagian kedua yakni amplop yang terbuat dari kertas perak yang dibasahi pada satu
sisinya. Basahan ini memudahkan paket jahitan dipisahkan dari kertas tersebut. Kemudian
dengan menggunakan needle-holder, angkat needle tersebut dari lilitannya dan luruskan secara
hati-hati. Kemudian, gunakan untuk tindakan penjahitan.
Rekomendasi bahan jahitan yang dapat digunakan adalah monofilamen prolene atau
Ethilon 1,5 metrik (4/0) untuk jahitan interuptus pada semua bagian. Monofilamen prolene atau
ethilon 2 metrik (3/0) untuk jahitan subkutikuler non-absorbable. Juga dapat digunakan untuk
jahitan interuptus pada kulit yang keras misalnya pada bahu. Vicryl 2 metrik (3/0) digunakan
pada jahitan subkutikuler yang absorbable dan jahitan dalam hemostasis. Vicryl 1,5 metrik
(4/0) digunakan untuk jahitan subkutikuler jaringan halus atau jahitan dalam. Prolene atau
Ethilon 0,7 (6/0) untuk jahitan halus pada muka dan pada anak-anak.
9. Needle bedah
Saat ini bentuk needle bedah yang digunakan oleh sebagian besar orang adalah jenis
atraumatik yang terdiri atas sebuah lubang pada ujungnya yang merupakan tempat insersi
benang. Benang akan mengikuti jalur needle tanpa menimbulkan kerusakan jaringan (trauma).
Pada needle model lama memiliki mata dan loop pada benangnya sehingga dapat menimbulkan
trauma. Needle memiliki bagian dasar yang sama, meskipun bentuknya beragam. Setiap bagian
memiliki ujung, yakni bagian body dan bagian lubang tempat insersi benang. Sebagian besar
needle berbentuk kurva dengan ukuran ¼, 5/8, ½ dan 3/8 lingkaran. Hal ini menyebabkan needle
memiliki range untuk bertemu dengan jahitan lainnya yang dibutuhkan. Ada juga bentuk needle
yang lurus namun jarang digunakan pada bedah minor. Needle yang berbentuk setengah
lingkaran datar digunakan untuk memudahkan penggunaannya dengan needle holder.
10. Macam-macam Jahitan Luka
Jenis jahitan dalam pembedahan banyak sekali. Dikenal beberapa jahitan sederhana, yaitu
jahitan terputus, jahitan kontinu, dan jahitan intradermal.
Jahitan Terputus (Simple Inerrupted Suture)
Terbanyak digunakan karena sederhana dan mudah. Tiap jahitan disimpul sendiri. Dapat
dilakukan pada kulit atau bagian tubuh lain, dan cocok untuk daerah yang banyak bergerak
karena tiap jahitan saling menunjang satu dengan lain. Digunakan juga untuk jahitan situasi.Cara
jahitan terputus dibuat dengan jarak kira-kira 1 cm antar jahitan. Keuntungan jahitan ini adalah
bila benang putus, hanya satu tempat yang terbuka, dan bila terjadi infeksi luka, cukup dibuka
jahitan di tempat yang terinfeksi. Akan tetapi, dibutuhkan waktu lebih lama untuk
mengerjakannya.
Gambar 2. Interrupted over and over suture.
Jahitan Matras
- Jahitan Matras Horizontal
Jahitan dengan melakukan penusukan seperti simpul, sebelum disimpul dilanjutkan
dengan penusukan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan pertama. Memberikan hasil jahitan yang
kuat.
Gambar 3. Interrupted horizontal mattress suture
- Jahitan Matras Vertikal
Jahitan dengan menjahit secara mendalam di bawah luka kemudian dilanjutkan dengan
menjahit tepi-tepi luka. Biasanya menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena
didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini.
Gambar 4. Interrupted vertical mattress suture
Jahitan Matras Modifikasi
Modifikasi dari matras horizontal tetapi menjahit daerah luka seberangnya pada daerah
subkutannya.
Gambar 5. Interrupted semi-mattress suture
Jahitan Kontinu
Simpul hanya pada ujung-ujung jahitan, jadi hanya dua simpul. Bila salah satu simpul
terbuka, maka jahitan akan terbuka seluruhnya. Jahitan ini jarang dipakai untuk menjahit kulit.
Jahitan Jelujur Sederhana (Continous Over and Over)
Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjelujur baju. Biasanya menghasilkan hasil
kosmetik yang baik, tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat yang longgar.
Gambar 6. Continuous over and over sutures
Jahitan Jelujur Feston (Interlocking Suture)
Jahitan kontinyu dengan mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya, biasa sering dipakai
pada jahitan peritoneum. Merupakan variasi jahitan jelujur biasa.
Gambar 7. Ford suture pattern
Jahitan Intradermal
Memberikan hasil kosmetik yang paling bagus (hanya berupa satu garis saja). Dilakukan
jahitan jelujur pada jaringan lemak tepat di bawah dermis.
Gambar 8. Continuous intracutaneous
6. Jelaskan mengenai macam – macam teknik anestesi.
Secara umum obat bius atau istilah medisnya anestesi ini dibedakan menjadi tiga
golongan yaitu anestesi lokal, regional, dan umum.
1. Anestesi Lokal
Anestesi lokal adalah tindakan pemberian obat yang mampu menghambat
konduksi saraf (terutama nyeri) secara reversibel pada bagian tubuh yang spesifik. Pada
anestesi umum, rasa nyeri hilang bersamaan dengan hilangnya kesadaran penderita.
Sedangkan pada anestesi lokal (sering juga diistilahkan dengan analgesia lokal),
kesadaran penderita tetap utuh dan rasa nyeri yang hilang bersifat setempat (lokal).
Pembiusan atau anestesi lokal biasa dimanfaatkan untuk banyak hal. Misalnya, sulam
bibir, sulam alis, dan liposuction, kegiatan sosial seperti sirkumsisi (sunatan), mencabut
gigi berlubang, hingga merawat luka terbuka yang disertai tindakan penjahitan. Anestesi
lokal bersifat ringan dan biasanya digunakan untuk tindakan yang hanya perlu waktu
singkat. Oleh karena efek mati rasa yang didapat hanya mampu dipertahankan selama
kurun waktu sekitar 30 menit seusai injeksi, bila lebih dari itu, maka akan diperlukan
injeksi tambahan untuk melanjutkan tindakan tanpa rasa nyeri.
2. Anestesi Regional
Anestesi regional biasanya dimanfaatkan untuk kasus bedah yang pasiennya perlu
dalam kondisi sadar untuk meminimalisasi efek samping operasi yang lebih besar, bila
pasien tak sadar. Misalnya, pada persalinan Caesar, operasi usus buntu, operasi pada
lengan dan tungkai. Caranya dengan menginjeksikan obat-obatan bius pada bagian utama
pengantar register rasa nyeri ke otak yaitu saraf utama yang ada di dalam tulang
belakang. Sehingga, obat anestesi mampu menghentikan impuls saraf di area itu. Sensasi
nyeri yang ditimbulkan organ-organ melalui sistem saraf tadi lalu terhambat dan tak
dapat diregister sebagai sensasi nyeri di otak. Dan sifat
anestesi atau efek mati rasa akan lebih luas dan lama dibanding anestesi lokal. Pada kasus
bedah, bisa membuat mati rasa dari perut ke bawah. Namun, oleh karena tidak
mempengaruhi hingga ke susunan saraf pusat atau otak, maka pasien yang sudah di
anestesi regional masih bisa sadar dan mampu berkomunikasi, walaupun tidak merasakan
nyeri di daerah yang sedang dioperasi.
3. Anestesi Umum
Anestesi umum (general anestesi) atau bius total disebut juga dengan nama
narkose umum (NU). Anestesi umum adalah meniadakan nyeri secara sentral disertai
hilangnya kesadaran yang bersifat reversibel. Anestesi umum biasanya dimanfaatkan
untuk tindakan operasi besar yang memerlukan ketenangan pasien dan waktu pengerjaan
lebih panjang, misalnya pada kasus bedah jantung, pengangkatan batu empedu, bedah
rekonstruksi tulang, dan lain-lain. Cara kerja anestesi umum selain menghilangkan rasa
nyeri, menghilangkan kesadaran, dan membuat amnesia, juga merelaksasi seluruh otot.
Maka, selama penggunaan anestesi juga diperlukan alat bantu nafas, selain deteksi
jantung untuk meminimalisasi kegagalan organ vital melakukan fungsinya selama
operasi dilakukan. Untuk menentukan prognosis ASA (American Society of
Anesthesiologists) membuat klasifikasi berdasarkan status fisik pasien pra anestesi yang
membagi pasien kedalam 5 kelompok atau kategori sebagai berikut:
ASA 1, yaitu pasien dalam keadaan sehat yang memerlukan operasi.
ASA 2, yaitu pasien dengan kelainan sistemik ringan sampai sedang baik karena
penyakit bedah maupun penyakit lainnya. Contohnya pasien batu ureter dengan
hipertensi sedang terkontrol, atau pasien apendisitis akut dengan lekositosis dan
febris.
ASA 3, yaitu pasien dengan gangguan atau penyakit sistemik berat yang
diaktibatkan karena berbagai penyebab. Contohnya pasien apendisitis perforasi
dengan septi semia, atau pasien ileus obstruksi dengan iskemia miokardium.
ASA 4, yaitu pasien dengan kelainan sistemik berat yang secara langsung
mengancam kehiduannya.
ASA 5, yaitu pasien tidak diharapkan hidup setelah 24 jam walaupun dioperasi
atau tidak. Contohnya pasien tua dengan perdarahan basis krani dan syok
hemoragik karena ruptura hepatik. Klasifikasi ASA juga dipakai pada
pembedahan darurat dengan mencantumkan tanda darurat (E = emergency),
misalnya ASA 1 E atau III E.
Stadium anestesi dibagi dalam 4 yaitu;
Stadium I (stadium induksi atau eksitasi volunter), dimulai dari pemberian agen
anestesi sampai menimbulkan hilangnya kesadaran. Rasa takut dapat
meningkatkan frekuensi nafas dan pulsus,
dilatasi pupil, dapat terjadi urinasi dan defekasi.
Stadium II (stadium eksitasi involunter), dimulai dari hilangnya kesadaran
sampai permulaan stadium pembedahan. Pada stadium II terjadi eksitasi dan
gerakan yang tidak menurut kehendak, pernafasan tidak teratur, inkontinensia
urin, muntah, midriasis, hipertensi, dan takikardia. Stadium III
(pembedahan/operasi), terbagi dalam 3 bagian yaitu; Plane I yang ditandai dengan
pernafasan yang teratur dan terhentinya anggota gerak. Tipe pernafasan thoraco-
abdominal, refleks pedal masih ada, bola mata bergerak-gerak, palpebra,
konjuctiva dan kornea terdepresi.
Plane II, ditandai dengan respirasi thoraco-abdominal dan bola mata ventro
medial semua otot mengalami relaksasi kecuali otot perut. Plane III, ditandai
dengan respirasi regular, abdominal, bola mata kembali ke tengah dan otot perut
relaksasi.
Stadium IV (paralisis medulla oblongata atau overdosis),ditandai dengan
paralisis otot dada, pulsus cepat dan pupil dilatasi. Bola mata menunjukkan
gambaran seperti mata ikan karena terhentinya sekresi lakrimal.
7. Jelaskan tentang berbagai macam tumor kulit dan jaringan di bawahnya!
Klasifikasi tumor :
- Epithelial
Benigna : papiloma (kulit dan mukosa), adenoma (berasal dari
kelenjar) dan kista
Maligna : karsinoma
- Jaringan ikat
Benigna : fibroma, lipoma (terdiri dari jaringan lemak), kondroma
(berasal dari jaringan tulang rawan)
Maligna : sarkoma
- Vaskuler
Benigna : angioma
Maligna : angiosarkoma
- Muskuler
Benigna : mioma
Maligna : miosarkoma
- Neurogen
Benigna : neurinoma (terdiri atas jaringan saraf), glioma (terdiri atas
jaringan otak)
- Mixed tumor
- Tumor kompleks : terdiri atas bermacam – macam jaringan (teratoma).
8. Jelaskan mengenai berbagai macam transfusi dan bagaimana memberi transfusi!
Darah lengkap (whole blood)
Darah lengkap mempunyai komponen utama yaitu eritrosit, darah lengkap juga
mempunyai kandungan trombosit dan faktor pembekuan labil (V, VIII). Volume darah
sesuai kantong darah yang dipakai yaitu antara lain 250 ml, 350 ml, 450 ml. Dapat bertahan
dalam suhu 4°±2°C. Darah lengkap berguna untuk meningkatkan jumlah eritrosit dan
plasma secara bersamaan. Hb meningkat 0,9±0,12 g/dl dan Ht meningkat 3-4 % post
transfusi 450 ml darah lengkap. Tranfusi darah lengkap hanya untuk mengatasi perdarahan
akut dan masif, meningkatkan dan mempertahankan proses pembekuan. Darah lengkap
diberikan dengan golongan ABO dan Rh yang diketahui. Dosis pada pediatrik rata-rata 20
ml/kg, diikuti dengan volume yang diperlukan untuk stabilisasi.
Indikasi :
1. Penggantian volume pada pasien dengan syok hemoragi, trauma atau luka bakar
2. Pasien dengan perdarahan masif dan telah kehilangan lebih dari 25% dari volume
darah total.
Rumus kebutuhan whole blood
6 x ∆Hb (Hb normal -Hb pasien) x BB
Ket :
Hb normal : Hb yang diharapkan atau Hb normal
Hb pasien : Hb pasien saat ini
Sel darah merah
Packed red cell
Packed red cell diperoleh dari pemisahan atau pengeluaran plasma secara tertutup
atau septik sedemikian rupa sehingga hematokrit menjadi 70-80%. Volume tergantung
kantong darah yang dipakai yaitu 150-300 ml. Suhu simpan 4°±2°C. Lama simpan darah
24 jam dengan sistem terbuka.(3)
Packed cells merupakan komponen yang terdiri dari eritrosit yang telah
dipekatkan dengan memisahkan komponen-komponen yang lain. Packed cells banyak
dipakai dalam pengobatan anemia terutama talasemia, anemia aplastik, leukemia dan
anemia karena keganasan lainnya. Pemberian transfusi bertujuan untuk memperbaiki
oksigenasi jaringan dan alat-alat tubuh. Biasanya tercapai bila kadar Hb sudah di atas 8 g
%.
Untuk menaikkan kadar Hb sebanyak 1 gr/dl diperlukan PRC 4 ml/kgBB atau 1
unit dapat menaikkan kadar hematokrit 3-5 %. Diberikan selama 2 sampai 4 jam dengan
kecepatan 1-2 mL/menit, dengan golongan darah ABO dan Rh yang diketahui.
Kebutuhan darah (ml) :
3 x ∆Hb (Hb normal -Hb pasien) x BB
Ket :
Hb normal : Hb yang diharapkan atau Hb normal
Hb pasien : Hb pasien saat ini
Tujuan transfusi PRC adalah untuk menaikkan Hb pasien tanpa menaikkan volume darah
secara nyata. Keuntungan menggunakan PRC dibandingkan dengan darah jenuh adalah:
1. Mengurangi kemungkinan penularan penyakit
2. Mengurangi kemungkinan reaksi imunologis
3. Volume darah yang diberikan lebih sedikit sehingga
kemungkinan overload berkurang
4. Komponen darah lainnya dapat diberikan pada pasien lain.
Indikasi: :
1. Kehilangan darah >20% dan volume darah lebih dari 1000 ml.
2. Hemoglobin <8 gr/dl.
3. Hemoglobin <10 gr/dl dengan penyakit-penyakit utama : (misalnya empisema,
atau penyakit jantung iskemik)
4. Hemoglobin <12 gr/dl dan tergantung pada ventilator.
Frozen Wash Concentrated Red Blood Cells (Sel Darah Merah Pekat Beku yang
Dicuci)
Diberikan untuk penderita yang mempunyai antibodi terhadap sel darah merah
yang menetap.
Washed red cell
Washed red cell diperoleh dengan mencuci packed red cell 2-3 kali dengan
saline, sisa plasma terbuang habis. Berguna untuk penderita yang tak bisa diberi
human plasma. Kelemahan washed red cell yaitu bahaya infeksi sekunder yang
terjadi selama proses serta masa simpan yang pendek (4-6 jam). Washed red cell
dipakai dalam pengobatan aquired hemolytic anemia dan exchange transfusion.(3) Untuk penderita yang alergi terhadap protein plasma
Darah merah pekat miskin leukosit
Kandungan utama eritrosit, suhu simpan 4°±2°C, berguna untuk
meningkatkan jumlah eritrosit pada pasien yang sering memerlukan transfusi.
Manfaat komponen darah ini untuk mengurangi reaksi panas dan alergi.(6)
White Blood Cells (WBC atau leukosit)
Komponen ini terdiri dari darah lengkap dengan isi seperti PRC, plasma dihilangkan 80 % ,
biasanya tersedia dalam volume 150 ml. Dalam pemberian perlu diketahui golongan darah ABO
dan sistem Rh. Apabila diresepkan berikan dipenhidramin. Berikan antipiretik, karena komponen
ini bisa menyebabkan demam dan dingin. Untuk pencegahan infeksi, berikan tranfusi dan
disambung dengan antibiotik.
Indikasi :
Pasien sepsis yang tidak berespon dengan antibiotik (khususnya untuk pasien dengan kultur
darah positif, demam persisten /38,3° C dan granulositopenia).
Suspensi trombosit
Pemberian trombosit seringkali diperlukan pada kasus perdarahan yang disebabkan oleh
kekurangan trombosit. Pemberian trombosit yang berulang-ulang dapat menyebabkan
pembentukan thrombocyte antibody pada penderita. (3) Transfusi trombosit terbukti bermanfaat
menghentikan perdarahan karena trombositopenia. Komponen trombosit mempunyai masa
simpan sampai dengan 3 hari.(2)
Indikasi pemberian komponen trombosit ialah :
1. Setiap perdarahan spontan atau suatu operasi besar dengan jumlah trombositnya kurang dari
50.000/mm3. Misalnya perdarahan pada trombocytopenic purpura, leukemia, anemia aplastik,
demam berdarah, DIC dan aplasia sumsum tulang karena pemberian sitostatika terhadap tumor
ganas.
2. Splenektomi pada hipersplenisme penderita talasemia maupun hipertensi portal juga memerlukan
pemberian suspensi trombosit prabedah.
Rumus Transfusi Trombosit
BB x 1/13 x 0.3
Macam sediaan:
1. Platelet Rich Plasma (plasma kaya trombosit)
Platelet Rich Plasma dibuat dengan cara pemisahan plasma dari darah segar. Penyimpanan 34°C
sebaiknya 24 jam.
2. Platelet Concentrate (trombosit pekat)
Kandungan utama yaitu trombosit, volume 50 ml dengan suhu simpan 20°±2°C. Berguna untuk
meningkatkan jumlah trombosit. Peningkatan post transfusi pada dewasa rata-rata 5.000-
10.000/ul. Efek samping berupa urtikaria, menggigil, demam, alloimunisasi Antigen trombosit
donor.(6)
Dibuat dengan cara melakukan pemusingan (centrifugasi) lagi pada Platelet Rich Plasma,
sehingga diperoleh endapan yang merupakan pletelet concentrate dan kemudian memisahkannya
dari plasma yang diatas yang berupa Platelet Poor Plasma. Masa simpan ± 48-72 jam.(3)
Plasma
Plasma darah bermanfaat untuk memperbaiki volume dari sirkulasi darah (hypovolemia, luka
bakar), menggantikan protein yang terbuang seperti albumin pada nephrotic syndrom dan
cirhosis hepatis, menggantikan dan memperbaiki jumlah faktor-faktor tertentu dari plasma
seperti globulin.(3)
Macam sediaan plasma adalah:
1. Plasma cair
Diperoleh dengan memisahkan plasma dari whole blood pada pembuatan packed red cell.
2. Plasma kering (lyoplylized plasma)
Diperoleh dengan mengeringkan plasma beku dan lebih tahan lama (3 tahun).
3. Fresh Frozen Plasma
Dibuat dengan cara pemisahan plasma dari darah segar dan langsung dibekukan pada suhu -
60°C. Pemakaian yang paling baik untuk menghentikan perdarahan (hemostasis).(3)
Kandungan utama berupa plasma dan faktor pembekuan, dengan volume 150-220 ml. Suhu
simpan -18°C atau lebih rendah dengan lama simpan 1 tahun. Berguna untuk meningkatkan
faktor pembekuan bila faktor pembekuan pekat/kriopresipitat tidak ada. Ditransfusikan dalam
waktu 6 jam setelah dicairkan. Fresh frozen plasma (FFP) mengandung semua protein plasma
(faktor pembekuan), terutama faktor V dan VII. FFP biasa diberikan setelah transfusi darah
masif, setelah terapi warfarin dan koagulopati pada penyakit hepar. Setiap unit FFP biasanya
dapat menaikan masing-masing kadar faktor pembekuan sebesar 2-3% pada orang dewasa. Sama
dengan PRC, saat hendak diberikan pada pasien perlu dihangatkan terlebih dahulu sesuai suhu
tubuh.
Pemberian dilakukan secara cepat, pada pemberian FFP dalam jumlah besar diperlukan koreksi
adanya hypokalsemia, karena asam sitrat dalam FFP mengikat kalsium. Perlu dilakukan
pencocokan golongan darah ABO dan system Rh.
Efek samping berupa urtikaria, menggigil, demam, hipervolemia.
Indikasi :
– Mengganti defisiensi faktor IX (hemofilia B)
– Neutralisasi hemostasis setelah terapi warfarin bila terdapat perdarahan yang mengancam
nyawa.
– Adanya perdarahan dengan parameter koagulasi yang abnormal setelah transfusi massif
– Pasien dengan penyakit hati dan mengalami defisiensi faktor pembekuan
4. Cryopresipitate
Komponen utama yang terdapat di dalamnya adalah faktor VIII, faktor pembekuan XIII, faktor
Von Willbrand, fibrinogen. Penggunaannya ialah untuk menghentikan perdarahan karena
kurangnya faktor VIII di dalam darah penderita hemofili A.
Cara pemberian ialah dengan menyuntikkan intravena langsung, tidak melalui tetesan infus,
pemberian segera setelah komponen mencair, sebab komponen ini tidak tahan pada suhu
kamar. (2)
Suhu simpan -18°C atau lebih rendah dengan lama simpan 1 tahun, ditransfusikan dalam waktu 6
jam setelah dicairkan. Efek samping berupa demam, alergi. Satu kantong (30 ml) mengadung 75-
80 unit faktor VIII, 150-200 mg fibrinogen, faktor von wilebrand, faktor XIII
Indikasi :
– Hemophilia A
– Perdarahan akibat gangguan faktor koagulasi
– Penyakit von wilebrand
Rumus Kebutuhan Cryopresipitate :
0.5x ∆Hb (Hb normal -Hb pasien) x BB
5. Albumin
Dibuat dari plasma, setelah gamma globulin, AHF dan fibrinogen dipisahkan dari plasma.
Kemurnian 96-98%. Dalam pemakaian diencerkan sampai menjadi cairan 5% atau 20% 100 ml
albumin 20% mempunyai tekanan osmotik sama dengan 400 ml plasma biasa
Rumus Kebutuhan Albumin
∆ albumin x BB x 0.8
9. Jelaskan berbagai macam jenis luka dan tahap penyembuhan luka!
Jenis-jenis luka digolongkan berdasarkan :
Berdasarkan sifat kejadian, dibagi menjadi 2, yaitu luka disengaja (luka terkena radiasi atau
bedah) dan luka tidak disengaja (luka terkena trauma).
Luka tidak disengaja dibagi menjadi 2, yaitu :
- Luka tertutup : luka dimana jaringan yang ada pada permukaan tidak rusak
(kesleo, terkilir, patah tulang, dsb).
- Luka terbuka : luka dimana kulit atau selaput jaringan rusak, kerusakan terjadi
karena kesengajaan (operasi) maupun ketidaksengajaan (kecelakaan).
Berdasarkan penyebabnya, di bagi menjadi :
- . Luka mekanik (cara luka didapat dan luas kulit yang terkena)
- Luka insisi (Incised wound), terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam.
Luka dibuat secara sengaja, misal yang terjadi akibat pembedahan.
- Luka bersih (aseptik) biasanya tertutup oleh sutura setelah seluruh pembuluh
darah yang luka diikat (ligasi).
- Luka memar (Contusion Wound), adalah luka yang tidak disengaja terjadi akibat
benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikkan oleh: cedera pada jaringan
lunak, perdarahan dan bengkak, namun kulit tetap utuh. Pada luka tertutup, kulit
terlihat memar.
- Luka lecet (Abraded Wound), terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain
yang biasanya dengan benda yang tidak tajam.
- Luka tusuk (Punctured Wound), luka ini dibuat oleh benda yang tajam yang
memasuki kulit dan jaringan di bawahnya. Luka punktur yang disengaja dibuat
oleh jarum pada saat injeksi. Luka tusuk/ punktur yang tidak disengaja terjadi
pada kasus: paku yang menusuk alas kaki bila paku tersebut terinjak, luka akibat
peluru atau pisau yang masuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil.
- Luka gores (Lacerated Wound), terjadi bila kulit tersobek secara kasar. Ini terjadi
secara tidak disengaja, biasanya disebabkan oleh kecelakaan akibat benda yang
tajam seperti oleh kaca atau oleh kawat. Pada kasus kebidanan: robeknya
perineum karena kelahiran bayi.
- Luka tembus/luka tembak (Penetrating Wound), yaitu luka yang menembus organ
tubuh biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi pada bagian
ujung biasanya lukanya akan melebar, bagian tepi luka kehitaman.
- Luka bakar (Combustio), luka yang terjadi karena jaringan tubuh terbakar.
- Luka gigitan (Morcum Wound), luka gigitan yang tidak jelas bentuknya pada
bagian luka.
- Luka non mekanik : luka akibat zat kimia, termik, radiasi atau serangan listrik.
Berdasarkan tingkat kontaminasi
- Clean Wounds (luka bersih), yaitu luka bedah takterinfeksi yang mana tidak
terjadi proses peradangan (inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan,
pencernaan, genital dan urinari tidak terjadi. Luka bersih biasanya menghasilkan
luka yang tertutup, jika diperlukan dimasukkan drainase tertutup. Kemungkinan
terjadinya infeksi luka sekitar 1% – 5%.
- Clean-contamined Wounds (luka bersih terkontaminasi), merupakan luka
pembedahan dimana saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam
kondisi terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya
infeksi luka adalah 3% – 11%.
- Contamined Wounds (luka terkontaminasi), termasuk luka terbuka, fresh, luka
akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau
kontaminasi dari saluran cerna. Pada kategori ini juga termasuk insisi akut,
inflamasi nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10% – 17%.
- Dirty or Infected Wounds (luka kotor atau infeksi), yaitu terdapatnya
mikroorganisme pada luka.
Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka
- Stadium I : Luka Superfisial (Non-Blanching Erithema) : yaitu luka yang terjadi
pada lapisan epidermis kulit.
- Stadium II : Luka “Partial Thickness” : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan
epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya
tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.
- Stadium III : Luka “Full Thickness” : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi
kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah
tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan
epidermis, dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis
sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.
- Stadium IV : Luka “Full Thickness” yang telah mencapai lapisan otot, tendon
dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas.
Berdasarkan waktu penyembuhan luka
- Luka akut : yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep
penyembuhan yang telah disepakati.
- Luka kronis : yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan,
dapat karena faktor eksogen dan endogen.
Wound Healing
Wound healing atau penyembuhan luka adalah suatu proses alami, baik secara selular
maupun biokimia, yang dilakukan oleh tubuh untuk regenerasi jaringan dermis atau epidermis
sebagai respon atas suatu jejas atau injuri.
Proses ini secara garis besar terdiri dari 3 fase yang merupakan suatu urut-urutan tertentu
dan dalam perjalanannya dapat saling tumpang tindih. Jika fase-fase ini tidak berjalan
sebagaimana harusnya, maka luka tidak akan sembuh. Luka mungkin menjadi luka kronis seperti
venous ulcer atau skar patologis seperti keloid. Fase-fase tersebut adalah:
FASE INFLAMASI
Fase inflamasi ditandai dengan terjadinya pembekuan darah (clotting) untuk
mempertahankan hemostasis, pelepasan bermacam-macam faktor untuk menarik sel-sel
yang akan memfagosit debris, bakteri, dan jaringan yang rusak, serta pelepasan faktor
yang akan memulai proliferasi jaringan.
Ketika jaringan terluka, maka darah akan kontak dengan kolagen. Hal ini memacu
platelet untuk mensekresi faktor-faktor inflamasi. Platelet atau dikenal juga dengan
trombosit, juga mengekspresi glikoprotein pada membran sel sehingga platelet tersebut
dapat menempel satu sama lain, beragregasi, dan membentuk massa.
Platelet adalah sel yang paling banyak terdapat segera setelah suatu luka terjadi.
Platelet kemudian akan melepaskan faktor-faktor lainnya seperti protein ECM, sitokin,
growth factor yang mempercepat pembelahan sel, dan faktor proinflamasi (serotonin,
bradikinin, prostaglandin, prostasiklin, tromboksan, dan histamine) yang meningkatkan
proliferasi dan migrasi sel ke daerah luka serta menyebabkan peningkatan permeabilitas.
Segera setelah pembuluh darah berdilatasi, membran sel yang ruptur akan
melepaskan tromboksan dan prostaglandin yang menyebabkan pembuluh darah
berkontraksi untuk mencegah kehilangan darah sekaligus mengumpulkan faktor-faktor
dan sel inflamasi lainnya. Vasokonstriksi ini berlangsung selama 5–10 menit, kemudian
diikuti dengan vasodilatasi yang terjadi karena pelepasan histamin. Dengan terjadinya
vasodilatasi maka akan terjadi ekstravasasi protein. Hal ini menyebabkan tekanan
osmolar ekstravaskular meningkat dan air tertarik ke ekstravaskular sehingga jaringan
menjadi edematous. Vasodilatasi ini juga memfasilitasi leukosit dari pembuluh darah
untuk mencapai lokasi luka.
Setelah 1 jam luka terjadi, polymorphonuclear (PMNs) sampai pada lokasi luka
dan menjadi sel predominan hingga 3 hari selanjutnya. PMNs tertarik ke lokasi luka
karena adanya fibronektin, growth factors, neuropeptida, dan kinin. Netrofil akan
memfagositosis debris dan bakteri, membunuh bakteri dengan cara melepaskan radikal
bebas, membersihkan luka dari jaringan mati dengan mensekresi protease. Setelah
netrofil menyelesaikan tugasnya, ia akan mengalami apoptosis dan didegradasi oleh
makrofag. Leukosit lainnya yang memasuki lokasi luka adalah sel T-helper yang
mensekresi sitokin. Sitokin menyebabkan sel T-helper membelah lebih banyak lagi
sehingga terjadi proses inflamasi, vasodilatasi, dan peningkatan permeabilitas kapiler
lebih hebat. Sel T-helper juga akan meningkatkan aktivitas makrofag.
Makrofag akan menggantikan peran PMNs sebagai sel predominan. Platelet dan
faktor-faktor lainnya menarik monosit dari pembuluh darah. Ketika monosit mencapai
lokasi luka, maka ia akan dimatangkan menjadi makrofag. Peran makrofag adalah:
- Memfagositosis bakteri dan jaringan yang rusak dengan melepaskan protease.
- Melepaskan growth factors dan sitokin yang kemudian menarik sel-sel yang
berperan dalam fase proliferasi ke lokasi luka.
- Memproduksi faktor yang menginduksi dan mempercepat angiogenesis
- Memstimulasi sel-sel yang berperan dalam proses re-epitelisasi luka, membuat
jaringan granulasi, dan menyusun matriks ekstraselular.
Fase inflamasi sangat penting dalam proses penyembuhan luka karena berperan
melawan infeksi pada awal terjadinya luka serta memulai fase proliferasi. Walaupun
begitu, inflamasi dapat terus berlangsung hingga terjadi kerusakan jaringan yang kronis.
FASE PROLIFERASI
Fase proliferasi dari penyembuhan luka dimulai kira-kira 2–3 hari setelah
terjadinya luka, dan ditandai dengan adanya fibroblas di sekitar luka. Pada fase ini terjadi
angiogenesis. Angiogenesis disebut juga sebagai neovaskularisasi, yaitu proses
pembentukan pembuluh darah baru. Karena aktivitas fibroblas dan epitelial
membutuhkan oksigen, angiogenesis adalah hal yang penting sekali dalam langkah-
langkah penyembuhan luka. Jaringan dimana pembentukan pembuluh darah baru terjadi,
biasanya terlihat berwarna merah (eritem) karena terbentuknya kapiler-kapiler di daerah
itu.
Seiring dengan terjadinya proliferasi fibroblas, populasi sel keratinosit dan
endothelial serta produksi faktor-faktor pertumbuhan akan bertambah. Hal ini
menstimulasi sel-sel proliferasi dan migrasi sel-sel endotelial ke daerah luka sehingga
terjadi angiogenesis. Pembuluh darah yang baru terbentuk ini mengawali peningkatan
jumlah fibroblas ke daerah luka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan untuk
memproduksi plasminogen activator dan collagenase.
Setelah pembentukan jaringan cukup adekuat, migrasi dan proliferasi sel-sel
endotelial menurun, dan sel yang berlebih akan mati dalam dengan proses apoptosis.
Seiring dengan angiogenesis, fibroblas mulai terkumpul di dalam luka. Fibroblas
mulai memasuki daerah luka 2 – 5 hari setelah fase inflamasi luka berakhir, dan
jumlahnya mencapai puncak pada 1 – 2 minggu setelah terjadinya luka. Pada akhir
minggu pertama, fibroblas adalah sel utama dalam luka. Fibroplasia berakhir 2 sampai 4
minggu setelah luka terjadi.
Pada 2 – 3 hari setelah terjadinya luka, fibroblas berproliferasi dan bermigrasi,
sehingga nantinya menjadi sel utama yang menjadi matrix kolagen di dalam area luka.
Fibroblas dari jaringan normal bermigrasi ke dalam area luka. Awalnya fibroblas
menggunakan benang fibrin pada fase inflamasi untuk bermigrasi, melekat ke fibronectin.
Lalu fibroblas mengendapkan substansi dasar ke dalam area luka yang selanjutnya akan
ditempati oleh kolagen.
Salah satu peranan penting dari fibroblas adalah menghasilkan kolagen. Fibroblas
mulai menghasilkan kolagen pada hari ke-2 sampai hari ke-3 setelah terjadinya luka, dan
mencapai kadar puncak pada minggu ke-1 hingga minggu ke-3. Produksi kolagen terus
berlanjut secara cepat hingga 2 sampai 4 minggu.
Deposisi kolagen sangatlah penting mengingat kolagen berperan dalam
peningkatan kekuatan luka, sebelum jumlahnya menurun, satu-satunya yang membuat
luka dapat berdekatan satu sama lain adalah fibrin – fibronectin clot, yang tidak terlalu
kuat untuk menahan suatu luka karena trauma.
Formasi dari jaringan granulasi pada suatu luka terbuka menyebabkan terjadinya
fase reepitelisasi, seperti halnya sel epitel bermigrasi melintasi jaringan yang baru untuk
membentuk suatu barier diantara luka dan lingkunagn sekitar. Basal keratinosit dari tepi
luka dan lapisan dermal, seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan glandula sebacea
adalah sel yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya fase epitelisasi pada
penyembuhan luka. Mereka tumbuh dalam bentuk lembaran, melintasi luka dan
berproliferasi pada tepi luka, dan berhenti bergerak ketika bertemu di tengah luka.
Dengan demikian onset dari migrasi ini bervariasi dan mungkin terjadi sehari
setelah luka terjadi. Sel pada tepi luka berproliferasi pada hari ke dua dan ke tiga setelah
luka untuk kelangsungan proses migrasi sel. Jika membran basalis tidak rusak, sel epitel
digantikan dalam 3 hari oleh bagian-bagian dari membran basalis dan sel yang
bermigrasi dari stratum basalis, dengan cara yang sama pada kulit yang tidak mengalami
luka.
Namun bagaimanapun, jika membran basalis di sekitar luka mengalami
kerusakan, reepitelisasi pasti terjadi di sekitar tepi luka dan dari lapisan kulit seperti
folikel rambut, kelenjar keringat dan kelenjar sebacea yang melintasi dermis yang
berhubungan dengan keratinosit yang hidup. Jika luka yang terjadi sangat dalam,
kemungkinan besar lapisan kulit juga akan mengalami kerusakan, sehingga migrasi sel
hanya akan terjadi pada tepi luka.
Sekitar 1 minggu setelah terjadinya penyembuhan luka, firoblas berdiferensiasi
menjadi myofibroblas dan luka mulai menyusut. Pada luka yang dalam puncak
penyusutan terjadi dalam 5 – 15 hari setelah terjadinya luka. penyusutan dapat berakhir
dalam beberapa minggu, dan berlanjut bahkan setelah luka mengalami re-epitelisasi. Jika
pengerutan berlanjut terlalu lama, hal ini akan menuju pada kerusakan dan malfungsi.
Pengerutan terjadi untuk mengurangi bentuk yang berlebihan dari penyembuhan
luka. Luka yang besar akan menjadi 40 – 80 % lebih kecil setelah terjadinya pengerutan.
Kecepatan pengerutan dalam penyembuhan luka terjadi 0.75 mm per hari, tergantung
pada seberapa besar jaringan luka yang hilang. Penyusutan biasaya tidak terjadi secara
simetris, namun kebanyakan penyembuhan luka memiliki aksis pengerutan yang dapat
dimasuki lembaran - lembaran sel kolagen.
Pada awalnya, pengerutan terjadi tanpa keterlibatan myofibroblas. Fibroblas baru
distimulasi oleh growth factor yang akan berdiferensiasi menjadi myofibroblas.
Myofibroblas yang mirip sel otot polos bertanggung jawab pada kontraksi. Myofibroblas
mengandung aktin yang serupa ditemukan di dalam sel otot polos.
FASE MATURASI DAN REMODELLING
Saat kadar produksi dan degradasi kolagen mencapai keseimbangan, maka
mulailah fase maturasi dari penyembuhan jaringan luka. Fase ini dapat berlangsung
hingga 1 tahun lamanya atau lebih, tergantung dari ukuran luka dan metode penutupan
luka yang dipakai. Selama proses maturasi, kolagen tipe III yang banyak berperan saat
fase proliferasi akan menurun kadarnya secara bertahap, digantikan dengan kolagen tipe I
yang lebih kuat. Serat-serat kolagen ini akan disusun, dirangkai, dan dirapikan sepanjang
garis luka.
Kekuatan susunan kolagen akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu.
Setelah 3 bulan, rata-rata kekuatan jaringan ini mencapai 50% dari kekuatan jaringan
normal, dan akan terus bertambah hingga maksimal 80% dari kekuatan jaringan normal.
Lama kelamaan aktivitas pada lokasi luka berkurang, sehingga luka pun menjadi tidak
eritematous karena pembuluh darah yang tidak lagi dibutuhkan untuk kelangsungan
proses penyembuhan luka akan dihilangkan secara apoptosis.
Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penyembuhan
Faktor-faktor ini secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok yaitu faktor lokal
dan faktor sistemik. Faktor lokal meliputi besarnya luka, jenis jaringan yang mengalami
luka, lokasi, bersih dan kotornya luka (kontaminasi) serta kecepatan penatalaksanaannya.
Faktor sistemik meliputi keadaan umum penderita beserta kelainan kronik sebelumya
yang telah diderita, keadaan gizi, penyakit sistem imun dan lain sebagainya. Tabel
dibawah ini menerangkan faktor-faktor yang berperan dalam penyembuhan luka.
10. Jelaskan macam-macam jahitan dan jenis benang!
Jenis jahitan dalam pembedahan banyak sekali. Dikenal beberapa jahitan sederhana, yaitu
jahitan terputus, jahitan kontinu, dan jahitan intradermal.
Jahitan Terputus (Simple Inerrupted Suture)
Terbanyak digunakan karena sederhana dan mudah. Tiap jahitan disimpul sendiri. Dapat
dilakukan pada kulit atau bagian tubuh lain, dan cocok untuk daerah yang banyak bergerak
karena tiap jahitan saling menunjang satu dengan lain. Digunakan juga untuk jahitan situasi.Cara
jahitan terputus dibuat dengan jarak kira-kira 1 cm antar jahitan. Keuntungan jahitan ini adalah
bila benang putus, hanya satu tempat yang terbuka, dan bila terjadi infeksi luka, cukup dibuka
jahitan di tempat yang terinfeksi. Akan tetapi, dibutuhkan waktu lebih lama untuk
mengerjakannya.
Gambar 2. Interrupted over and over suture.
Jahitan Matras
- Jahitan Matras Horizontal
Jahitan dengan melakukan penusukan seperti simpul, sebelum disimpul dilanjutkan
dengan penusukan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan pertama. Memberikan hasil jahitan yang
kuat.
Gambar 3. Interrupted horizontal mattress suture
- Jahitan Matras Vertikal
Jahitan dengan menjahit secara mendalam di bawah luka kemudian dilanjutkan dengan
menjahit tepi-tepi luka. Biasanya menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena
didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini.
Gambar 4. Interrupted vertical mattress suture
Jahitan Matras Modifikasi
Modifikasi dari matras horizontal tetapi menjahit daerah luka seberangnya pada daerah
subkutannya.
Gambar 5. Interrupted semi-mattress suture
Jahitan Kontinu
Simpul hanya pada ujung-ujung jahitan, jadi hanya dua simpul. Bila salah satu simpul
terbuka, maka jahitan akan terbuka seluruhnya. Jahitan ini jarang dipakai untuk menjahit kulit.
Jahitan Jelujur Sederhana (Continous Over and Over)
Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjelujur baju. Biasanya menghasilkan hasil
kosmetik yang baik, tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat yang longgar.
Gambar 6. Continuous over and over sutures
Jahitan Jelujur Feston (Interlocking Suture)
Jahitan kontinyu dengan mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya, biasa sering dipakai
pada jahitan peritoneum. Merupakan variasi jahitan jelujur biasa.
Gambar 7. Ford suture pattern
Jahitan Intradermal
Memberikan hasil kosmetik yang paling bagus (hanya berupa satu garis saja). Dilakukan
jahitan jelujur pada jaringan lemak tepat di bawah dermis.
Gambar 8. Continuous intracutaneous
11. Jelaskan definisi dan tindakan asepsis antisepsis!
Asepsis dan teknik antiseptis merupakan upaya yang digunakan untuk menggambarkan upaya kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Tujuan dari tehnik ini untuk membasmi jumlah mikroorganisme pada permukaan hidung (kulit dan jaringan) obyek mati (alat-alat bedah dan barang-barang lainnya)
- Anti sepsis adalah proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput lendir/ jaringan tubuh langsung dengan menggunakan bahan antimikrobial antiseptik.
- Aseptik adalah keadaan bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya melalui teknik aseptik. Teknik aseptik/asepsis adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemungkinan besar akan mengakibatkan infeksi. Tindakan asepsis ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme yang terdapat pada permukaan benda hidup atau benda mati. Tindakan ini meliputi antisepis, desinfeksi, dan sterilisasi. Untuk itu, diperlukan perlakuan khusus pada alat dan bahan operasi, lapangan operasi, operator,dan asisten sebagai pelaksana.
- Antisepsis adalah upaya pencegahan infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Bahan yang digunakan disebut antiseptik. Antiseptik adalah bahan yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan kuman, ada yang bersifat sporosidal (membunuh spora) dan non sporosidal, digunakan pada jaringan hidup khusus,yaitu kulit dan selaput lendir.
- Antiseptik harus dibedakan dengan obat seperti antibiotik yang dapat membunuh mikroorganisme di dalam tubuh atau dengan desinfektan yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat pada benda mati.
Perlu diperhatikan adanya reaksi atau riwayat alergi terhadap iodium. Jenis antiseptik yang sering digunakan adalah alkhol 70 %, povidon iodin, chlorhexidine gluconate dan triklosan.
Kriteria pemilihan antiseptik :
- Aksi yang luas (menghambat mikroorganisme secara luas (gram positif, negatif, Tb, Fungi, Endospora)
- Efektivitas- Kecepatan aktivitas awal- Efek residu : aksi yang lama setelah pemakaian untuk merendam pertumbuhan
kuman- Tidak mengakibatkan alergi- Efektif sekali pakai, tidak perlu diulang.
Contoh antiseptik :
- alkohol (60%-90%),- setrimd / klorheksidin glukonat (2%-4%) ex: hibiscrub, hibitane - klorheksidin glukonat 2% ect..- Mikroorganisme adalah agen penyebab infeksi termasuk bakteri, virus, fungi,
parasit
pencegahan infeksi bakteri dibagi 3 yaitu :
- Vegetatif- Mikobakteria ex: tuberkolosis- Endospora (sulit dibunuh disebabkan lapisan pelindungnya)
Sterilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme pada benda mati/ instrumen dengan cara uap air panas, tekanan tinggi (otoklaf), panas kering (oven), sterilan kimia atau radiasi.
Densifektan tingkat tinggi (DTT): tindakan untuk menghilangkan semua mikroorganisme kecuali endospora bakteri pada benda mati dengan cara merebus dan mengukus penggunaan densifektan kimiawi.
Desinfektan : bahan kimia yang membunuh/ menginaktivasi mikroorganisme
ex: - klorin pemutih 0,5 % untuk dikontaminasi permukaan yang lebar
- klorin 0,1% untuk DTT kimia
- Glutaraldehida 2% bisa digunakan DTT kimia/ sterilisasi kimia
- Fenol / klorin
Dekontaminasi : membuat obyek mati lebih aman ditangani saat sebelum dibersihkan (menginaktifasi) serta menurunkan HBV.
Dekomentanasi: direndam dalam bahan klorin selama 10 menit 0,5%.
Teknik Tindakan Aseptik
- Tindakan yang dilakukan adalah dengan mengusapkan cairan antiseptik pada lapangan operasi dan sekitarnya. Untuk memperluas permukaan steril maka dilakukan drepping, yaitu pemakaian duk bolong steril.
- Prinsipnya adalah mengusap kulit dari mulai daerah yang lebih bersih ke daerah yang paling kotor dengan tidak mengusap daerah yang telah diusap sebelumnya.





























































![02 Bedah I [Diagnosa Kelainan Bedah Orthopedi] 2](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cf9805550346d033950bd7/02-bedah-i-diagnosa-kelainan-bedah-orthopedi-2.jpg)