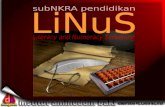Bahan Ajar Utk Fk - Resum Kuliah Pak Machli
-
Upload
aya-soraya -
Category
Documents
-
view
79 -
download
0
description
Transcript of Bahan Ajar Utk Fk - Resum Kuliah Pak Machli
RESUME BAHAN AJAR UTK FK UNLAM
ASPEK HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN
Machli Riyadi,SH.,MH *
Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dari para dokter maupun bagi para dokter yang memberikan pelayanan kesehatan, sehingga tuntutan akan kebutuhan perangkat hukum dalam bidang praktik kedokteran selangkah lebih maju. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mengimbangi kemajuan pola pikir dan tingginya kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam kontrak terapeutik.
Pada asasnya hubungan hukum antara dokter dan pasien ini bertumpu pada dua macam hak asasi manusia yang dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) dan hak atas informasi (the right to information). Kedua hak dasar tersebut bertolak dari hak atas perawatan kesehatan (the right to health care) yang merupakan hak asasi individu (individual human rights). Dokumen internasional yang menjamin kedua hak tersebut adalah The Universal Declaration of Human Right tahun 1948, dan The United Nations International Covenant on Civil and Political right tahun 1966.
Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan suatu profesi yang sangat terhomat dalam pandangan masyarakat. Karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah hubungan hukum keperdataan yang bersipat Innspaning verbentennis (upaya maksimal) dan terikat dalam kontrak terapeutik. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat dan iradat Allah, kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kedokteran atau Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan resiko medik, dan resiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak di luar profesi kedokteran sebagai perbuatan melawan hukum dan atau medical malpractice.
Adapun unsur Standar Profesi Kedokteran yang dikemukakan dalam rumusan Leenen adalah :
1. Berbuat secara teliti/seksama (zorgvulding handelen) dikaitkan dengan culpa/kelalaian, bila seorang dokter yang bertindak onvoorzichteg, tidak teliti, tidak berhati-hati maka ia memenuhi unsur kelalaian ; bila ia sangat tidak berhati ia memenuhi culpa lata.
2. Sesuai ukuran ilmu medik (volgens de medische standaard).
3. Kemampuan rata-rata (average) dibanding kategori keahlian medik yang sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie).
4. Situasi dan kondisi yang sama (gelijke omstandigheden).
5. Sarana upaya (middelen) yang sebanding/proporsional (= azas proporsionalitas). (met middelen die in redelijke verhoudingstaan) dengan tutjuan konkret tindakan/perbuatan medik tersebut (tot het concreet handelingsdoel).
Berkaitan dengan profesi kedokteran ini, belakangan marak diberitakan dalam mass media nasional, baik melalui media elektronika maupun media cetak, bahwa banyak ditemui praktek-praktek malpraktik yang dilakukan kalangan dokter Indonesia. Bahkan menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat tercatat kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktik di Indonesia walau sebagian besar tidak sampai ke meja hijau. Pemberitaan semacam ini telah menimbulkan keresahan atau paling tidak kekhawatiran kalangan dokter, karena profesi dokter ini bagaikan makan buah simalakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati. Tidak menolong dinyatakan salah menurut hukum, ditolong beresiko dituntut pasien atau keluarganya jika tidak sesuai dengan harapannya.
Machmud Syahrul. 2007.Aspek Hukum Dalam Medical Malpactice.Varia Peradilan No.264. Jakarta : IKAHI. Hal.53
Fred Ameln, 1991. Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta. Grafikatama Jaya. Hal 87.
Dari sudut hukum perdata, malpraktik kedokteran terjadi apabila perlakuan salah yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi pelayanan medis pada pasien menimbulkan kerugian perdata. Hal ini terkadang bersamaan dengan akibat yang menjadi unsur tindak pidana tertentu. Unsur adanya kerugian kesehatan fisik, jiwa, maupun nyawa pasien akibat dari salah perlakuan oleh dokter merupakan unsur esensial malpraktik kedokteran dari sudut hukum perdata termasuk hukum pidana. Dengan timbulnya akibat kerugian perdata bagi pasien itulah dasar terbentuknya pertanggungjawaban hukum perdata bagi dokter terhadap kerugian yang timbul.
Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek sumber daya kesehatan terdiri dari sarana kesehatan ( antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktik dokter ) dan tenaga kesehatan (antara lain : dokter, perawat, bidan, apoteker). Sedangkan aspek upaya kesehatan, salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran.
Salah satu bagian dari pemeliharaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan, dalam pelayanan kesehatan ini, lebih difokuskan pada pelayanan kesehatan individu dengan tentunya tidak melupakan pelayanan kesehatan masyarakat.
Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan yang dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah, yaitu kaidah-kaidah medik, hukum dan non hukum ( moral ( etik ), kesopanan, kesusilaan ).
Asas Hukum Kesehatan
Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Bellefroid dalam Mertokusumo, 1986: 32). Sedangkan menurut Eikema Hommes asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.
Di dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas :
Sa science et sa conscience ya ilmunya dan ya hati nuraninya, maksud dari pernyataan asas ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada pengaturan hak hak dokter, dimana dokter berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.
Agroti Salus Lex Suprema keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.
Deminimis noncurat lex hukum tidak mencampuri hal- hal yang sepele. Hal ini berkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien maka hukum tidak akan menuntut.
Res Ipsa liquitur . faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasus-kasus mal praktik dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas.
Asas-asas ini mendasari berlakunya peraturan atau ketentuan yang konkret.
Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan pada asasnya hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).
INDIKATOR MALPRAKTIK MEDIK PADA KONTRAK TERAPEUTIK
Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien
Hubungan hukum dokter-pasien terbentuk karena kesepakatan. Kesepakatan dalam kontrak teraupetik terbentuk pada saat pasien memberikan persetujuan (informed consent) pada dokter untuk melakukan tindakan medis setelah dokter memberikan penjelasan pada pasien. Logika hukumnya, dokter yang berpraktik telah melakukan penawaran umum (openbare aanbod) dalam memberikan jasa pelayanan medis bagi syarat pertama dari terbentuknya kesepakatan. Pada dasarnya, pasien yang datang menghadap untuk dilayani dokter merupakan wujud dari penerimaan penawaran tersebut. Akan tetapi, karena adanya kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan maka penjelasan dokter harus dianggap masih dalam rangka penawaran, atau penegasan penawaran. Menurut hukum, kesepakatan terjadi bila ada penawaran oleh satu pihak dan penawaran tersebut diterima atau disetujui oleh pihak lain. Dalam hal ini, kesepakatan adalah sumber perikatan hukum sebagaimana tertuang pasal 1233 KUHPerdata.
Menghadapnya pasien kepada doket merupakan wujud dari suatu kehendak agar dirinya diberi pelayanan medis sesuai dengan keperluan menurut standar profesi kedokteran dan standar prosedur yang berlaku. Kemudian dokter mengambil langkah pemeriksaan. Langkah pertama yang dilakukan dokter menanyai pasien kemudian memberikan penjelasan secara lengkap dalam pasal 45 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang dianggap suatu penegasan dari openbare aanbod dokter. Disini ada kewajiban moral atau etika dokter untuk melakukan langkah-langkah pada pasien yang datang menghadapnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Setelah diberikan penjelasan, pasien memberikan persetujuan secara diam atau tegas pada dokter untuk dilakukan tindakan medis. Dari sudut hukum, transaksi teraupetik diletakkan pada persetujuan pasien, sedangkan dokter berada pada pihak yang mengadakan openbare aanbod.
Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan ini dokter adalah orang sehat yang juga pakar dalam bidang kedokteran dan pasien adalah orang yang awam mengenai penyakitnya.
Dalam hubungan medik ini kedudukan dokter dan pasien adalah kedudukan yang tidak seimbang. Pasien karena keawamannya akan menyerahkan kepada dokter tentang penyembuhan penyakitnya, dan pasien diharapkan patuh menjalankan semua nasihat dari dokter dan memberikan persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh dokter.
Selain itu dalam hubungan medik ini, dasar dari hubungan antara dokter pasien adalah atas dasar kepercayaan dari pasien atas kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritannya.
Pasien percaya bahwa dokter akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakitnya, tanpa adanya kepercayaan dari pasien yang melandasi hubungan medik, maka akan sia-sia upaya dari dokter menyembuhkan pasien. Sehingga hubungan medik ini dikatakan hubungan atas dasar kepercayaan.
Terdapat pula hubungan yang paternalistik antara dokter dan pasien, dianggap bahwa dokter akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan pasien, seperti seorang bapak yang baik yang akan berbuat untuk kepentingan anaknya. Pasien diharapkan akan bertindak sebagai anak yang patuh dan percaya bahwa dokter akan bertindak sebagai bapak yang baik.
Pola hubungan diatas yaitu antara orang sehat dan orang sakit, pakar awam, kepercayaan dan paternalistik, menempatkan kedudukan yang tidak seimbang antara dokter dan pasien.
Pada setiap hubungan antara dokter dan pasien, terjadi interaksi yaitu hubungan timbal balik dan dalam interaksi sosial itu terjadi kontak dan komunikasi antara pasien dan dokter. Dokter berperan sebagai penyembuh dan pasien berperan sebagai orang yang membutuhkan bantuan penyembuhan.
Seperti diketahui ciri dari kaidah-kaidah moral, adalah tekanan pada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, tanpa membicarakan tentang hak seseorang terhadap pihak yang lainnya. Maka dalam hubungan sosial ini, hanya terdapat kewajiban dokter dan kewajiban pasien.
Kewajiban dokter secara umum, antara lain dokter mempunyai kewajiban untuk menjalankan pekerjaan menurut ukuran yang tertinggi. Selain itu, dokter yang dalam melakukan pekerjaan dipengaruhi oleh keuntungan pribadi adalah perbuatan yang tidak baik.
Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik. Hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban dokter. Keadaan itu menempatkan kedudukan dokter pasien pada kedudukan yang sama dan sederajat.
Hubungan dokter pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan. Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Terdapat hubungan antara dua subyek hukum yang ada di dalam lingkungan hukum perdata. Layaknya hubungan pemberian jasa, maka terdapat hak dan kewajiban pemberi jasa yang menjadi hak dan keajiban yang timbal balik dari penerima jasa.
Hubungan hukum dokter pasien adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (verbintenis). Dasar dari perikatan yang terbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Adapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasien, selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang sama, karena dokter dalam melakukan pekerjaannya selalu berlandaskan kepada apa yang dikenal sebagai standar profesi dokter, yaitu pedoman dokter untuk menjalankan profesinya dengan baik.
Hubungan hukum seperti itu dilandasi pada kepercayaan (saling percaya) antara kedua belah pihak. Hubungan saling percaya (confidential) ini disebutkan dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Walaupun bagi kedua belah pihak kesembuhan merupakan tujuan akhir dari kontrak terapeutik atau perjanjian penyembuhan tetapi bukan objek kewajiban dokter yang dapat dituntut oleh pasien. Perikatan hukum dokter pasien termasuk suatu jenis perikatan hukum yang disebut inspanningsverbintenis atau perikatan usaha. Artinya, suatu bentuk perikatan yang isi prestasinya adalah salah satu pihak maka harus berbuat sesuatu secara maksimal dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya kepada pihak lain. Kewajiban pokok seorang dokter terhadap pasiennya adalah inspanning, yakni suatu usaha keras dari dokter tersebut yang harus dijalankan dan yang diperlukan untuk behoud dan menyembuhkan kesehatan dari pasien. Ukuran sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya bagi dokter dalam hubungan hukum dokter pasien adalah standar profesi medis, standar prosedur, dan prinsip-prinsip umum profesional kedokteran. Hasil dari perlakuan penyembuhan, pemulihan, atau pemeliharaan kesehatan pasien tidak menjadi kewajiban hukum bagi dokter, melainkan suatu kewajiban moral belaka dan akibatnya bukan sanksi hukum tetapi sanksi moral dan sosial.
Doktrin Hukum kesehatan menentukan ada dua bentuk perikatan dilihat dari prestasi yang harus diberikan, yaitu perikatan ikhtiar ( inspanning verbintenis ) dan perikatan hasil ( resultaat verbntenis ). Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan adalah ikhtiar yaitu upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil, maka prestasi yang harus diberikan berupa hasil tertentu.
Pada hubungan hukum dokter pasien, maka hampir semuanya terbentuk perikatan ikhtiar, jarang sekali dokter berjanji memberikan hasil tertentu, sebab setiap tindakan medik, sekecil apapun tindakan medik itu selalu menimbulkan resiko, yang kadang-kadang tidak dapat diprediksi sedikitpun.
Pada perikatan hasil, jelas prestasinya dapat diukur berupa hasil tertentu, sedangkan pada perikatan ikhtiar, maka prestasi yang diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin, yang jelas tidak dapat diukur.
Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum dokter pasien berada dalam suatu perikatan hukum (verbintenis). Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain.
Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (Pasal 1313 jo 1234 BW yang disebut prestasi. Jadi, berdasarkan pasal itu ada tiga macam prestasi. Untuk memenuhi prestasi yang ada pada dasarnya adalah pelaksanaan suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat perikatan hukum (pada perikatan hukum timbal balik).
Di samping melahirkan hak dan kewajiban para pihak, hubungan hukum dokter pasien juga membentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing. Bagi pihak dokter, prestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu in casu tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditunjukkan bagi kepentingan kesehatan pasien adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian dokter pasien (kontrak terapeutik) yang dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebut sebagai Kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undnag-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Ukuran perlakuan berbuat sesuatu secara maksimal dan dengan sebaik-baiknya atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan didasarkan pada standar profesi medis dan standar prosedur. dalam Pasal 50 jo 51 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ukuran itu disebutkan dengan istilah standar profesi dan standar prosedur operasional Sementara dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut disebut sebagai standar pelayanan kedokteran atau dokter gigi, yang isinya dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan pasal 44 ayat (2). Standar pelayanan kedokteran atau dokter gigi yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri pasal 44 ayat (3) Undang-undang tersebut.
Dari sudut perdata, malpraktik kedokteran terjadi apabila perlakuan salah yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi pelayanan medis pada pasien menimbulkan kerugian perdata. Hal ini terkadang bersamaan dengan akibat yang menjadi unsur tindak pidana tertentu. Unsur adanya kerugian kesehatan fisik, jiwa, maupun nyawa pasien akibat dari salah perlakuan oleh dokter merupakan unsur esensial malpraktik kedokteran dari sudut hukum perdata termasuk hukum pidana. Dengan timbulnya akibat kerugian perdata bagi pasien itulah dasar terbentuknya pertanggungjawaban hukum perdata bagi dokter terhadap kerugian yang timbul.
Dilihat dari sumber lahirnya perikatan, ada dua kelompok perikatan hukum. Kelompok yang satu ialah perikatan-perikatan yang disebabkan oleh suatu kesepakatan (Pasal 1313 1315 BW) dan yang lainnya oleh Pasal 1352 1380 KUHPerdata. Hubungan hukum dokter pasien berada dalam kedua jenis perikatan hukum tersebut. Pelanggaran kewajiban hukum dokter dalam perikatan hukum karena kesepakatan (kontrak terapeutik) membawa suatu keadaan wanprestasi. Pelanggaran hukum dokter atas kewajiban hukum dokter karena Undang-Undang membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiged daad, Pasal 1365 BW).
Pelanggaran suatu kewajiban hukum dapat pula terjadi karena Undang-Undang yang disebut zaakwaarneming (Pasal 1354 BW). Zaakwaarneming berupa melakukan sesuatu dengan diam-diam dan secara sukarela bagi kepentingan orang lain tanpa persetujuannya dan tanpa sepengetahuannya menimbulkan suatu kewajiban pelaksanaan dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan tanggung jawab terhadap akibat yang timbul apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan sesuatu tersebut. Keadaan wanprestasi, onrechtmatig daad, maupun pelanggaran kewajiban dalam zaakwarneming dalam hubungan hukum dokter pasien membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter terhadap kerugian yang timbul.
Pedoman Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Dunia profesi kedokteran Indonesia telah memiliki satu pedoman perilaku profesi dokter dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, yaitu Sumpah Dokter,Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Peraturan Perundang-undangan, berikut beberapa ketentuan yang wajib dilaksanakan dan diperhatikan oleh seorang dokter sebelum dia melaksanakan praktik yaitu :
Pendaftaran dan Izin Praktik
Seorang dokter/dokter gigi yang telah lulus pendidikan dokter dari lembaga yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia , sebelum melakukan praktek kedokterannya wajib melakukan sumpah kedokteran dan memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku untuk 5 tahunan dapat diregistrasi ulang setiap 1 tahun. Sebelum melakukan praktik kedokterannya maka dokter tersebut wajib memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat praktek kedokteran dilaksanakan. Surat izin dokter ini hanya diberikan untuk paling banyak 3 tempat praktik serta wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran.
Kemudian bagi dokter yang telah berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.
Standar Profesi Medis
Standar profesi medis adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
Yang dimaksudkan dengan kemampuan minimal adalah kemampuan rata-rata dari keilmuan seorang dokter/dokter gigi, Dokter dapat dipersalahkan apabila dia tahu bahwa penyakit pasien diluar batas kemampuannya dan dia tidak merujuk kepada dokter spesialis yang kompeten terhadap penyakit pasien.
Menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik dan benar, terutama dalam proses tindakan medik dari semua petugas kesehatan. Akibat kelalaian yang dilakukan dokter sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, maka pasien berhak untuk memperoleh ganti rugi.
Pengaturan tentang standar profesi yang ada masih terbatas pada bidang spesialisasi tertentu, sebagai contoh misalnya, standar profesi di bidang keahlian Anestesiologi yang disusun oleh Sub Direktorat Penunjang Medik, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik bersama dengan Ikatan Profesi (Ikatan Dokter Ahli Anestesiaologi yang disingkat dengan sebutan IDSAI).
Standar Pelayanan Medik dan Standar Prosedur Operasional
Selain dokter harus mematuhi standar profesi medik seperti diuraikan di atas, maka dokter diharuskan pula memenuhi standar pelayanan medik dan standar prosedur operasional.
Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan, bahwa dokter yang menyelenggarakan praktek kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan dokter/medik yang akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Standar pelayanan tersebut dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. Standar pelayanan medik adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
Standar pelayanan medik ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengawasan praktik dokter, pembinaan serta upaya peningkatan mutu pelayanan medis di Indonesia yang efektif dan efisien. Selain itu dimaksudkan juga untuk melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan yang tidak wajar dari masyarakat luas. Juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan praktik-praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran. Standar pelayanan medik ini dapat dijadikan tolok ukur mutu pelayanan tenaga kesehatan, dimaksudkan pula agar para tenaga medis seragam dalam memberikan diagnosa, dan setiap diagnosa harus memenuhi kriteria minimal yang terdapat dalam standar pelayanan medis dan standar pelayanan RS tersebut. Standar pelayanan medik ini juga dapat difungsikan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan apabila terjadi sengketa.
Unsur-Unsur Malpraktik Medik
Meski berita yang membahas mengenai malpraktek medik atau kelalaian medik begitu marak, namun, jarang yang memaparkan pengertian mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, untuk memberikan pengertian yang lebih baik, penulis terlebih dahulu memaparkan beberapa pengertian malpraktek medik atau kelalaian medik.
M. Jusuf Hanafiah, memberikan pengertian tentang malpraktek medik yaitu kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian disini ialah sikap kurang hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik.
Lebih jauh lagi, M. Jusuf Hanafiah, berpendapat bahwa kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum De minimis noncurat lex yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata), serius dan kriminal.
Kemudian J. Guwandi, mengatakan bahwa malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis. Sebenarnya istilah malpraktek tidak hanya terjadi pada profesi kedokteran saja. Namun entah mengapa, ternyata dimana-mana, bahkan di luar negeri, istilah malpraktek selalu pertama-tama dikaitkan kepada profesi medis.
Ada beberapa penulis yang mengatakan bahwa sukar untuk mengadakan pembedaan antara negligence dan malpractice. Menurut pendapat mereka, lebih baik malpractice dianggap sinonim saja dengan professional negligence. Memang di dalam literatur, penggunaan kedua istilah itu sering dipakai secara bergantian seolah-olah artinya sama. Malpractice is a term which is increasingly widely used as a synonym for medical negligence (Mason-McCall Smith, 339).
Berbeda dengan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, J. Guwandi,. tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan malpraktek lebih baik dianggap sinonim dengan kelalaian. Menurutnya, malpraktek tidaklah sama dengan kelalaian. Kelalaian memang termasuk dalam arti malpraktek, tetapi di dalam malpraktek tidak selalu terdapat unsur kelalaian.
Sedangkan menurut Fred Ameln, seorang dokter melakukan malpraktek apabila ia melakukan suatu tindakan medik yang salah (wrong-doing) atau ia tidak atau tidak cukup mengurus pengobatan/perawatan pasien (neglect the patient by giving not or not enough care to the patient).
Malpraktek mempunyai pengertian yang lebih luas daripada kelalaian. Karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktek pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (intentional, dolus, onzettelijk) dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat adanya suatu motif (mens rea, guilty mind). Sedangkan arti kelalaian lebih berintikan ketidaksengajaan (culpa), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang timbul memang bukanlah menjadi tujuannya.
Dari beberapa pengertian dan pendapat dari para ahli hukum kedokteran di atas, terlihat adanya perbedaan dalam melihat pengertian dari malpraktek dan kelalaian dalam profesi kedokteran. Namun terlepas apakah malpraktek medik dan kelalaian medik merupakan suatu pengertian yang sama atau berbeda, penulis berpendapat bahwa pada intinya pengertian-pengertian tersebut di atas adalah sama. Yaitu kesalahan dokter dalam melakukan tindakan medik terhadap pasiennya, sengaja atau tidak sengaja tindakan medik tersebut dilakukan oleh sang dokter tersebut.
Namun ada baiknya pengertian malpraktek medik dan kelalaian medik di Indonesia diseragamkan dan diatur secara jelas serta tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis. Terlepas apakah nantinya akan dibedakan antara pengertian malpraktek medik dan kelalaian medik, atau menjadi satu pengertian tanpa pembedaan.
Pengaturan ini sangatlah penting guna terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter serta untuk menjamin rasa keadilan. Para dokter tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hukum profesinya, sedangkan pasien tidak dapat sembarangan menggugat dokter yang menanganinya. Terlebih apabila terlihat jelas bahwa tindakan medik yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan telah memenuhi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Standar Profesi Kedokteran yang berlaku.
Dari beberapa dipinisi/pengertian dari para pakar hukum kesehatan yang termuat diatas, penulis juga berpendapat bahwa dokter dapat dikatakan melakukan malpraktek apabila dokter kurang menguasai ilmu kedokteran yang berlaku umum, memberikan pelayanan dibawah standar, melakukan kelalaian berat, atau melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.:
Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka ia hanya telah melakukan malpraktek etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian, maka penggugat harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut:
Adanya kewajiban dokter terhadap pasien yang tidak dilaksanakan,
Dokter melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipakai,
Penggugat menderita kerugian,
Dan kerugian tersebut disebabkan tindakan di bawah standar.
* Mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum FH UNAIR
Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM
Machli riyadi,SH.,MH *
Pendahuluan
Kesehatan adalah keadaaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Pasal 1 poin 1 UU No 36/2009 tentang Kesehatan), karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya.1,2 Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (Human Development Index)3,4,5,6
Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut :
a. Instrumen Internasional
1. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
2. Pasal 6 dan 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
3. Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)
4. Pasal 5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).
5. Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Womens Convention).
6. Pasal 1 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT).
7. Pasal 24 Convention on the Rights of the Child (Childrens Convention, or CRC)
b. Instrumen Nasional
1. Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.
2. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. pasal 4 jo ppasal 5 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Dengan melihat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya tiap gangguan, intervensi atau ketidak-adilan, ketidak-acuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidak-sehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidak-adilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia.2, 7-15
Hak Atas Kesehatan
Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.16,17 Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :
a. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.
dapat diketahui bahwa hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.9,18
Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula
Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hubungan tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini :
Lingkaran kanan bawah dari lingkaran hubungan antara HAM dan Kesehatan merupakan akibat tidak terpenuhi atau gagalnya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, lingkaran atas erat kaitannya dengan hak atas kesehatan yang terlanggar oleh praktik-praktik kekerasan, yang menjadi bagian dari pelanggaran hak sipil dan politik. Untuk lingkaran kiri bawah menggambarkan hubungan antara HAM dan Kesehatan yang terjadi akibat kondisi masyarakat yang rentan.16
Sementara itu juga terdapat beberapa aspek yang tidak dapat diarahkan secara sendiri dalam hubungan antara Negara dan Individu. Secara khusus, kesehatan yang baik tidaklah dapat dijamin oleh Negara, dan tidak juga Negara menyediakan perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena itu, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat atau beresiko, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesehatan seseorang. Sehingga, Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.14,15,18
Isu Pokok Hak Atas Kesehatan
Pengertian kesehatan sangat luas dan merupakan konsep yang subjektif, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor-faktor geografis, budaya dan sosio-ekonomi. Oleh karena itu sulit untuk menentukan tentang apa saja yang termasuk ke dalam hak atas kesehatan. Untuk itu para ahli, aktivis dan badan-badan PBB mencoba membuat rincian mengenai core content hak atas kesehatan. Core content terdiri dari seperangkat unsur-unsur yang harus dijamin oleh negara dalam keadaan apapun, tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, yang terdiri dari :
1. Perawatan kesehatan :
a. Perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana;
b. Imunisasi;
c. Tindakan yang layak untuk penyakit-penyakit biasa (common disease) dan kecelakaan;
d. Penyediaan obat-obatan yang pokok (essential drugs).
2. Prakondisi dasar untuk kesehatan :
a. Pendidikan untuk menangani masalah kesehatan termasuk metode-metode untuk mencegah dan mengedalikannya;
b. Promosi penyediaan makanan dan nutrisi yang tepat;
c. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.
Jika melihat hubungan antara kesehatan dan HAM, kategorisasi unsur-unsur di atas belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan. Untuk itu faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan yang termasuk dalam hak-hak asasi manusia yang lain, tidak perlu ditambahkan ke dalam hak atas kesehatan.14-16,19
Sementara itu dalam komentar umum No 14 tentang hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau sesuai bunyi pasal 12 ayat (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) memberikan contoh umum dan spesifik berbagai langkah-langkah yang muncul dari adanya definisi yang luas dari hak atas kesehatan dalam pasal 12 ayat (1) sehingga dapat dapat menggambarkan isi dari hak atas tersebut, yaitu :
a. Hak ibu, Hak anak dan kesehatan reproduksi.
- mengurangi angka kematian bayi dan anak di bawah usia 5 tahun;
- pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi;
- akses terhadap Keluarga Berencana (KB);
- perawatan sebelum dan sesudah melahirkan;
- pelayanan gawat darurat dalam bidang obstetri (kebidanan);
- akses dan sumber daya yang dibutuhkan sehubungan dengan kesehatan reproduksi.
b. Hak atas lingkungan alam dan tempat kerja yang sehat dan aman.
- Tindakan preventif terhadap kecelakaan kerja dan penyakit;
- Air minum yang sehat dan aman serta sanitasi dasar;
- Pencegahan dan menurunkan kerentanan masyarakat dari substansi yang membahayakan seperti radiasi, zat kimia berbahaya, kondisi lingkungan yang membahayakan;
- Industri yang higienis;
- Lingkungan kerja yang sehat dan higienis;
- Perumahan yang sehat dan memadai;
- Persediaan makanan dan nutrisi yang cukup;
- Tidak mendorong penyalahgunaan alkohol, tembakau, obat-obatan dan substansi yang berbahaya lainnya.
c. Hak pencegahan, penanggulangan dan pemeriksaan penyakit.
- Pencegahan dan penanggulangan serta pengawasan penyakit epidemik dan endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan;
- Pembentukan program pencegahan dan pendidikan bagi tingkah laku yang berkaitan dengan kesehatan seperti penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS, penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi;
- Promosi menenai faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan, misalnya lingkungan yang aman, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan keseteraan gender;
- Hak atas perawatan;
- Bantuan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat;
- Pengendalian penyakit dengan menyediakan teknologi, menggunakan dan meningkatkan ketahanan epidemi serta imunisasi.
d. Hak atas fasilitas kesehatan, barang dan jasa.
- Menjamin adanya pelayanan medis yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik fisik maupun mental;
- Penyediaan obat-obatan yang esensial;
- Pengobatan atau perawatan mental yang tepat;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan seperti organisasi bidang kesehatan, sistem asuransi, secara khusus partisipasi dalam keputusan politik di level komunitas tertentu dan negara.
e. Topik khusus dan penerapan yang lebih luas.
- Non diskriminasi dan perlakuan yang sama;
- Perspektif gender
- Kesehatan anak dan remaja, orang tua, penyandang cacat dan masyarakat adat.
Untuk itu badan kesehatan dunia (WHO) telah membuat indikator-indikator kesehatan untuk menilai pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan hak atas kesehatan tersebut. Indonesia juga terikat dengan komitmen tersebut dan hal tersebut telah diadopsi dengan menetapkan 50 indikator kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2010.6,18
Implementasi Hak Atas Kesehatan Dalam Konteks HAM
Dalam upaya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip :
1. Ketersediaan pelayanan kesehatan, dimana negara diharuskan memiiki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk;
2. Aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu :tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik, terjangkau secara ekonomi dan akses informasi untuk mencari, menerima dan atau menyebarkan informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan.
3. Penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.
4. Kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi memadai.
Sementara itu dalam kerangka 3 bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Menghormati hak atas kesehatan
Dalam konteks ini hal yang menjadi perhatian utama bagi negara adalah tindakan atau kebijakan apa yang tidak akan dilakukan atau apa yang akan dihindari. Negara wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif pada kesehatan, antara lain : menghindari kebijakan limitasi akses pelayanan kesehatan, menghindari diskriminasi, tidak menyembunyikan atau misrepresentasikan informasi kesehatan yang penting, tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehatan, tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman, tidak mendistribusikan obat yang tidak aman.
b. Melindungi hak atas kesehatan
Kewajiban utama negara adalah melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan serta panduan untuk melindungi : tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. Mengontrol dan mengatur pemasaran, pendistribusian substansi yang berbahaya bagi kesehatan seperti tembakau, alkohol dan lain-lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional yang diketahu berbahaya bagi kesehatan.
c. Memenuhi hak atas kesehatan
Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan (should do) oleh pemerintah seperti menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, informasi dan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan, pelayanan pra kondisi kesehatan serta
faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti : kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk bekerja, hak anak untuk mendapatkan. identitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, eksploitasi, kejatahan seksual yang berdampak pada kesehatan.
Dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan negara harus mengambil langkah-langkah baik secara individual, bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak atas kesehatan sebagaimana mandat dari pasal 2 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR).9, 14-19
Disadari bahwa perlu kesungguhan dari negara serta partisipasi semua pihak baik itu masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat untuk dapat senantiasa meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi sehingga hak atas kesehatan dapat terpenuhi yang secara tidak langsung akan berdampak positif dalam pembangunan masyarakat Indonesia.
* Mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum FH UNAIR
KEPUSTAKAAN
1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Wahid S. Kesehatan sebagai hak asasi manusia. Seminar dan Lokakarya Kesehatan dan hak asasi manusia, Jakarta;19-20 Maret 2003.
3. Departemen Kesehatan RI. Sistim kesehatan nasional (SKN), 2004.
4. Moelok FA. Hak untuk hidup sehat (paradigma sehat). Seminar dan Lokakarya Kesehatan dan hak asasi manusia, Jakarta;19-20 Maret 2003.
5. Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2001; Menuju Indonesia Sehat 2010, Jakarta 2002.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1202/MENKES/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Penetapan Pedoman Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat.
7. Universal Declaration of Human Right, 1948. www.unhchr.ch/udhr/index.htm
8. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966. www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
9. International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR), 1966. www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
10. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 1965. www.ohchr.org/english/law/cerd.htm
11. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Womens Convention), 1979. www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
12. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT), 1984. www.ohchr.org/english/law/cat.htm
13. Convention on the Rights of the Child (Childrens Convention, or CRC), 1989. www.ohchr.org/english/law/crc.htm
14. Asher J. The right to health : A resource manual for NGOs. Amersfoort, The Netherlands: Printing B.V ;2004.
15. WHO. Human rights, health and poverty reduction strategies. Health and human rights publication series;Issue No 5, April 2005.
16. WHO. 25 Question and answer on health and human rights. Health and human rights publication series;issue N0 1, July 2002.
17. Lubis F. Kesehatan dan hak asasi manusia, perspektif Indonesia. Seminar dan Lokakarya Kesehatan dan hak asasi manusia, Jakarta;19-20 Maret 2003.
18. United Nations Economimic and Social ouncil, Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000). The rights tothe highest attainable standart of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Geneva, United Nations, 2000.
19. Rizki R. Beberapa catatan tentang hak atas kesehatan. Seminar dan Lokakarya Kesehatan dan hak asasi manusia, Jakarta;19-20 Maret 2003.